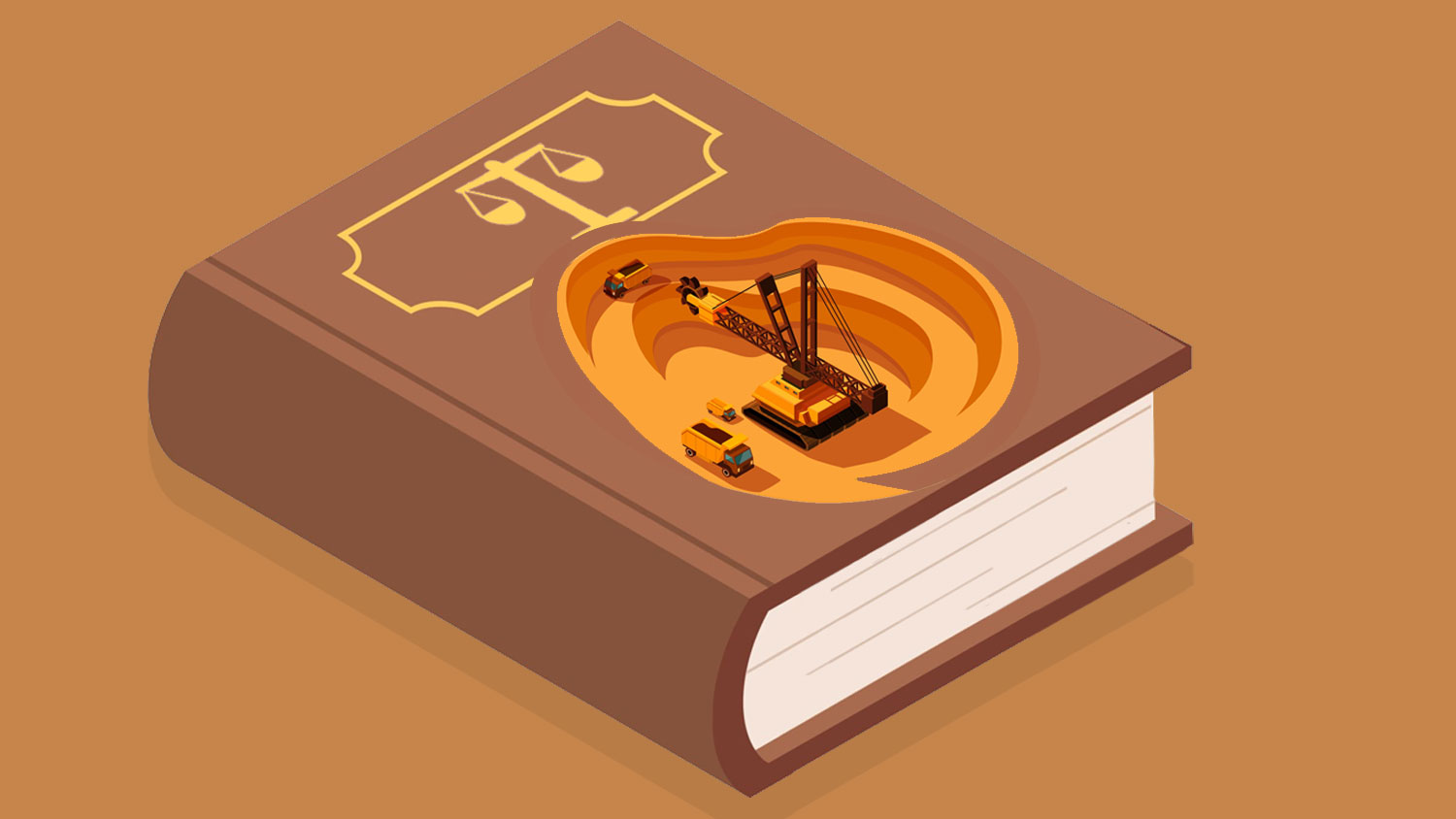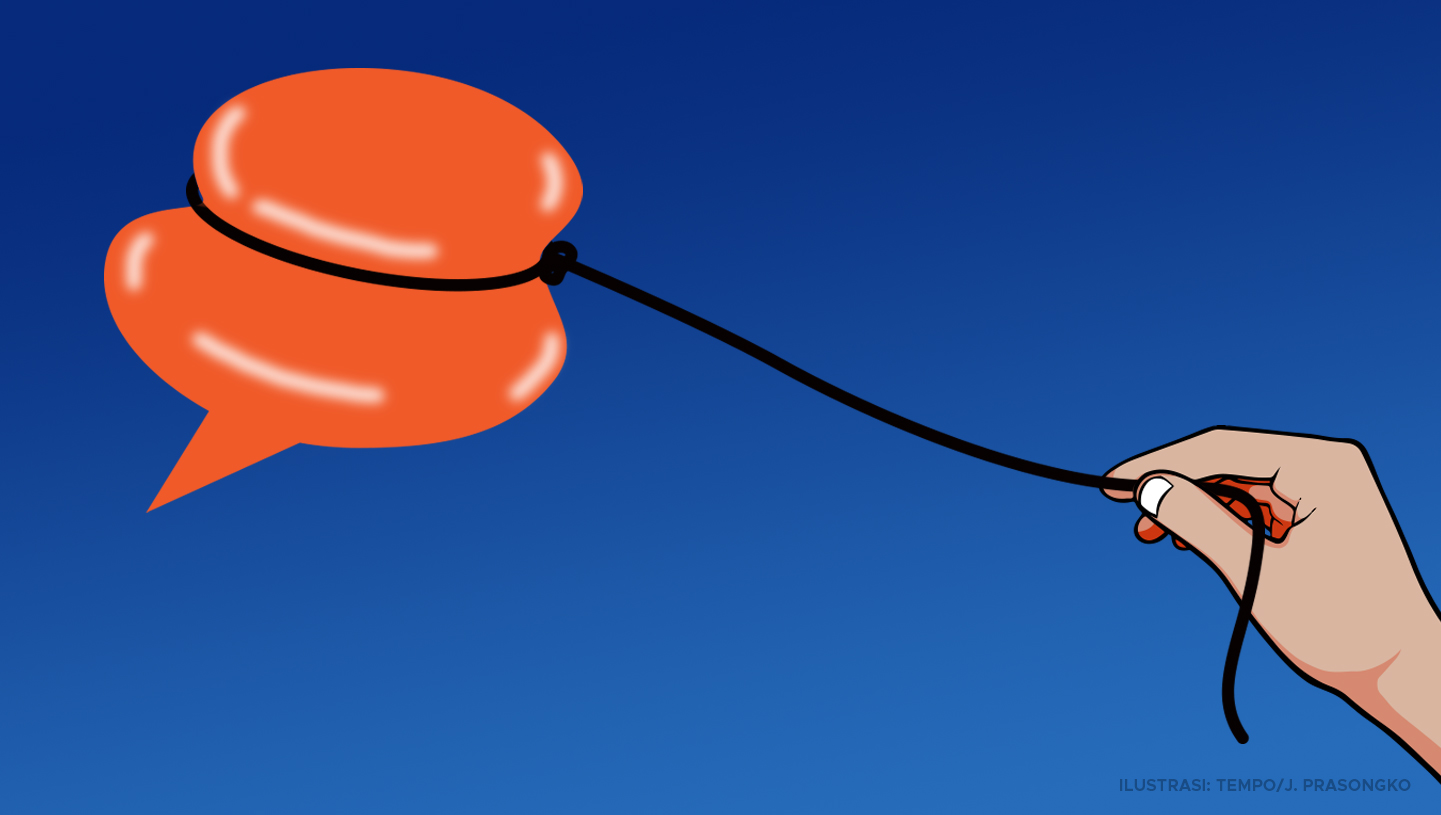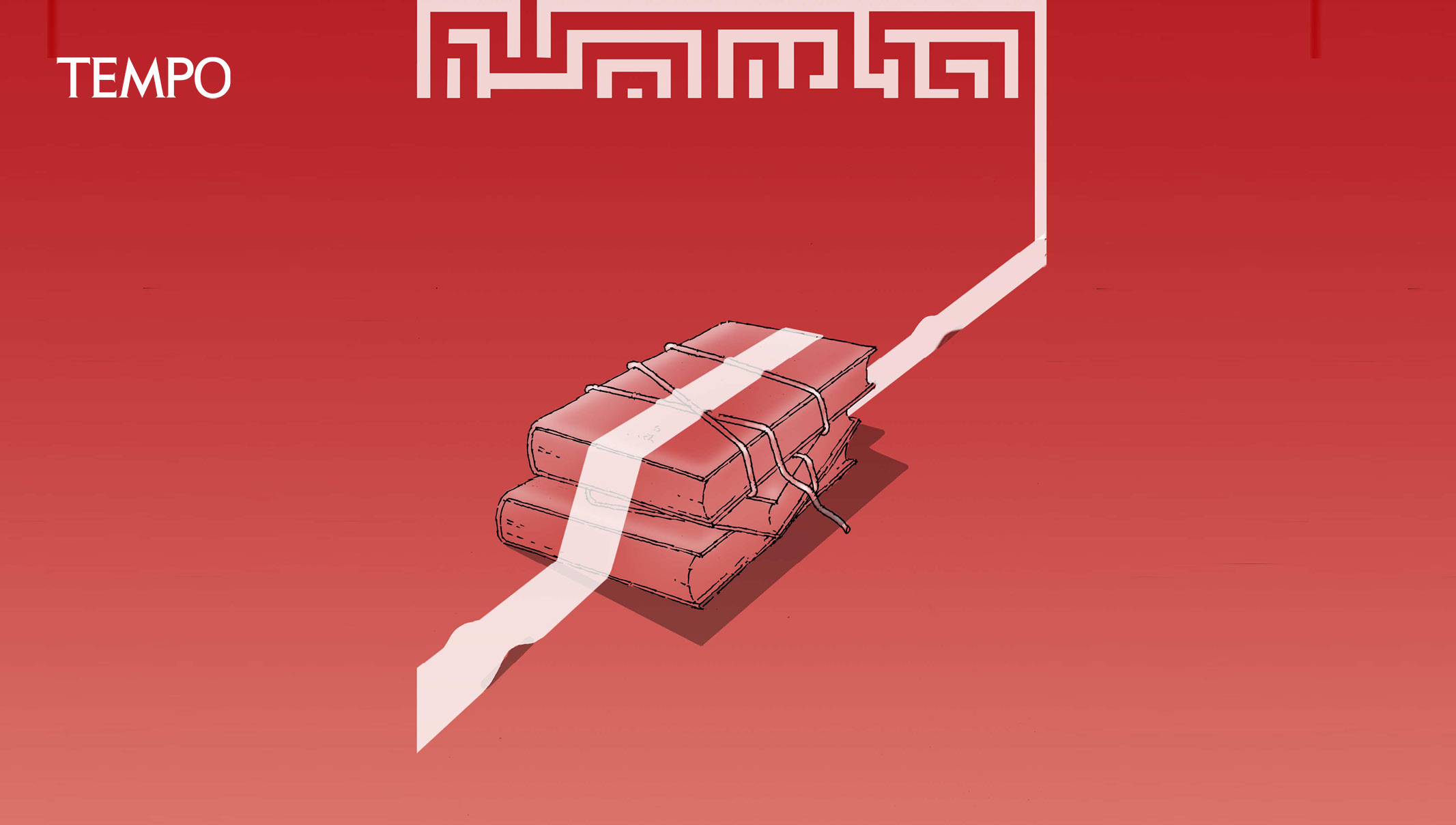DI negara-negara sedang berkembang yang kurang demokratis, biasanya ketertutupan politik sering menjelma ke dalam sistem ekonomi yang tidak terbuka. Akses terhadap sumber- sumber ekonomi potensial dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi yang terbatas, yang kemudian bermuara pada sistem penguasaan pasar yang monopoli. Pintu pasar menjadi tertutup, terbatas untuk segelintir orang yang mempunyai akses politik dalam sistem yang tertutup ini. Akibatnya, partisipasi ekonomi tidak meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Struktur pasar yang tergiring ke arah monopoli akan distortif dan mengakibatkan terjadinya inefisiensi, kolusi politik yang tidak perlu, dan mengurangi kemanfaatan sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat luas. Di Indonesia, praktek monopoli masih terus berlangsung dengan berbagai alasan, meskipun beberapa pasar untuk komoditi tertentu sudah mulai dibuka. Struktur pasar yang ada masih belum bebas dari praktek monopoli yang menguntungkan segelintir pelaku ekonomi, tapi sangat merugikan masyarakat. Meskipun demikian, deregulasi terus digulirkan sebagai bukti bahwa Pemerintah atau otoritas ekonomi semakin responsif terhadap pentingnya kebijakan yang rasional. Mekanisme pasar yang efektif ingin dikembalikan ke tengah-tengah sistem ekonomi sebagai penggerak pembangunan sehingga sasaran pertumbuhan, target ekspor, dan perbaikan ekonmi bisa dicapai. Sayangnya, peraturan pragmatis dan rasional yang digelar tersebut tidak bergulir secara otomatis karena distorsi yang sudah berlangsung cukup lama. Di lapangan, masalahnya lain lagi karena banyaknya gangguan kelompok kepentingan, sikap patronase politik, dan maraknya perburuan rente yang tidak rasional. Itu berarti, deregulasi dan rasionalisasi ekonomi tetap akan berhadapan dengan berbagai kendala-kendala yang sifatnya politis maupun birokratis. Di sektor-sektor tertentu atau di daerah masih dijumpai birokrasi yang berbelit-belit. Misalnya, untuk membentuk usaha kecil yang formal masih harus melewati puluhan meja birokrasi. Kondisi seperti ini menjadi hambatan yang pada gilirannya akan menghabiskan ''energi'' para pengusaha secara sia-sia dan mengarah pada kefrustrasian. Sementara itu, di luar birokrasi, sistem ekonomi dan struktur pasar terlihat tidak mencerminkan pola keadilan komutatif yang wajar. Sebab, adanya peran dan tekanan yang besar dari berbagai kelompok kepentingan. Kaitan yang erat antara struktur pasar dan pola patronase politik sangat jelas terlihat. Struktur yang seperti ini menjadikan usaha-usaha besar konglomerasi yang ada tidak berpijak pada kekuatannya sendiri. Kelemahan ini bersifat sangat mendasar dan struktural, hingga usaha konglomerasi kita tumbuh tidak efisien. Kredit macet yang sangat besar hanya merupakan satu muara dari kelemahan tersebut. Pola penguasaan produksi dan pasar secara monopoli atau oligopoli pada industri-industri hulu merupakan kendala amat serius bagi sistem perekonomian kita. Bahkan, monopoli tersebut secara de facto dibenarkan terjadi dari hulu sampai hilir, suatu hal yang tidak rasional jika kita ingin membangun sistem ekonomi yang efisien. Jika struktur pasar dibiarkan berlangsung distortif, jangan diharapkan proses produksi yang efisien dan daya saing yang kuat akan terciptakan. Ada beberapa konsekuensi penting dan dampak negatif yang terjadi jika monopoli di industri hulu ini masih dibiarkan seperti itu. Pertama, penguasaan pasar secara monopoli akan menghasilkan bias dan distorsi sehingga mengarah pada inefisiensi produksi. Struktur pasar seperti ini tidak bisa dikontrol secara rasional oleh pesaing-pesaing lainnya. Juga, tidak ada dasar pembenaran teoretis-rasional terhadap pola penguasaan struktur pasar monopoli seperti ini, kecuali dilihat dari kepentingan yang terlibat dalam hubungan patronase politik yang kurang terbuka. Kedua, monopoli menghilangkan kemungkinan tercapainya kondisi pareto optimal di dalam sistem ekonomi masyarakat. Yang bekerja keras dan kreatif tidak memperoleh imbalan seperti yang dilakukannya, sedangkan yang mempunyai akses terhadap kolusi dan patronase politik memperoleh imbalan secara berlebihan, meskipun tidak produktif. Fakta ini cenderung menciptakan kondisi yang tidak mendorong perkembangan dunia wiraswasta, dan kreativitas ekonomi masyarakat. Ketiga, jika industri hulu terus dikuasai secara monopoli, totalitas mekanisme ekonomi akan dikontrol oleh pelaku tunggal tersebut, dan harga tidak terbentuk secara wajar. Pembenaran monopoli di industri hulu secara de facto sangat mengganggu target-target pencapaian ekspor nasional di masa mendatang. Industri di hilirnya pasti akan tertular menjadi tidak efisien, sebab sumber bahan bakunya di hulu terperangkap ke dalam struktur pasar yang monopolis. Akibat selanjutnya, tidak akan tercapai kondisi keunggulan komparatif tangguh. Daya saing pun kemudian bisa terancam. Jika penekanan harga terpaksa dilakukan, buruh akan menjadi korban langsung diberlakukannya sistem seperti ini, khususnya dalam bentuk tekanan terhadap upah. Keempat, jika struktur ini dibenarkan berlanjut, maka nuansa perburuan rente akan semakin subur. Pembonceng gratis (free rider), khususnya pengusaha-pengusaha katrolan, akan semakin banyak bermunculan dan mengganggu sistem ekonomi. Perburuan rente akan semakin semarak sejalan dengan semakin menguatnya patronase politik dan menemukan momentumnya yang tepat dalam sistem politik dan ekonomi yang tertutup. Karena itu, perubahan terhadap struktur pasar sangat perlu dilakukan, agar pasar lebih terbuka dan lebih banyak pelaku ekonomi bisa berpartisipasi. Pencapaian sasaran rasional dari kebijakan deregulasi sangat tergantung sejauh mana struktur pasar yang monopolis ini bisa diubah, dan dibebaskan dari cengkeraman kelompok kepentingan dan patronase politiknya. *)Penulis adalah peneliti di LP3ES
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini