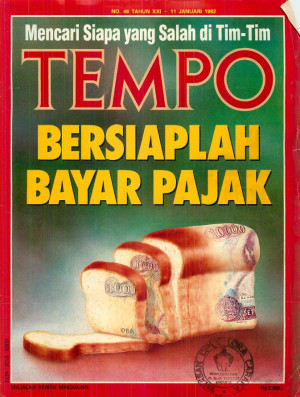PAJAK adalah ongkos peradaban. Kita keluar dari sebuah museum, berjalan dengan siul yang aman, dan tahu: tidak banyak hal di dunia ini yang gratis, dan kian lama yang tidak gratis itu kian mahal. Museum itu tidak akan berdiri, rasa aman itu tak akan timbul, dan kita mungkin akan tidak senang pergi ke sana bila tidak ada hal-hal yang diurus secara publik: penelitian benda-benda kuno, perawatan peninggalan sejarah, jalan ke tempat museum itu, penjagaan polisi, dan mahkamah yang bekerja menjaga tertib hukum. Semua adalah anasir peradaban manusia, yang perlu diteruskan -- dan perlu biaya. Dan biaya itu hanya ditutup dengan perpajakan. "Pajak adalah ongkos peradaban", dan tiba-tiba kita ingat siapa yang mengatakan itu: seorang hakim agung Amerika, Oliver Wendell Holmes. Tapi pajak juga sumber kebrengsekan, tiba-tiba kita merasa bisa dan perlu membantah. Pajak bisa menyebabkan kesewenang-wenangan. Dengan pajak warga negara membiayai para legislator di parlemen -- para politikus itu -- dan dengan pajak pula warga negara membayar gaji para pejabat, para birokrat, mereka yang di Indonesia sering disebut sebagai "penguasa". Dan apa hasilnya? Para legislator dan para pejabat dan para birokrat menghasilkan aturan-aturan, yang kadangkala dengan asumsi bahwa mereka mahatahu apa yang baik dan apa yang buruk bagi masyarakat, dan dengan anggapan warga negara kurang-lebih sama seperti anak-anak yang perlu selalu dibimbing. Di Singapura, ada larangan menjual permen karet. Di Indonesia, ada larangan (antara lain) membaca buku Pramudya Ananta Toer. Di AS, ada larangan (atau usaha untuk melarang) wanita memilih untuk apa yang akan dilakukannya dengan kandungannya. Di hadapan aturan-aturan macam itu, siapa yang hidup di akhir abad ke-20 ini tahu, bagaimana semangat membikin regulasi ditampik di mana-mana. Hasilnya meragukan dan harga yang dibayar untuk itu -- tidak selalu berarti uang -- terlampau besar. Coba baca ramalan Norman Macrae dalam The Economist di akhir tahun 1991. Menurut dia, penswastaan besar-besaran -- dengan kata lain: pembebasan dari urusan penguasa dan birokrat -- akan terjadi kelak. Di suatu masa nanti bahkan penjara akan diurus swasta, yang dibiayai para entrepreneur, dan bukan birokrat, yang ternyata tidak punya cukup insentif untuk mencegah mereka jadi residivis. Para entrepreneur pengelola bui nantinya akan dapat bayaran lebih bila para napi di sel-sel mereka tidak jadi bromocorah yang bikin onar lagi. Bahkan di sekitar tahun 2010, tulis Macrae, untuk menentukan siapa yang bakal mengurus kota secara lebih baik, orang tidak akan memilih para calon partai untuk jadi wali kota. Yang akan dipilih adalah perusahaan multinasional mana yang servisnya akan lebih beres. Kita tak tahu, benarkah ramalan itu akan terbukti. Yang pasti, semangat antibirokrat inilah yang mendasari rasa enggan dan kekecewaan warga negara kepada pajak. Sebab di mana adilnya ketentuan, bahwa kita harus membayar dari keringat kita sementara itu hidup kita dibikin ruwet oleh orang-orang yang makan gaji dari uang kita itu? Di AS, pajak dibayar buat membiayai sejumlah regulasi. Setiap tahun, untuk itu, pemerintah membelanjakan uang sebesar tiga sampai enam milyar dolar setahun. Tapi hasilnya malah membuat pertumbuhan perusahaan yang harus mengikuti regulasi itu -- di bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan -- menjadi seret: sebelum masa banyak regulasi di tahun 70-an, pertumbuhan bisa sampai 2%. Setelah banyak aturan, menjadi 0,4%. Sementara itu, betapa sedikit perbaikan di tempat-tempat yang akan diselamatkan oleh aturan-aturan pemerintah itu. "Pajak adalah ongkos peradaban". Ini diucapkan oleh seorang Amerika, dengan harapan bahwa peradaban terjamin dengan undang-undang yang baik, pelayanan kepada masyarakat yang layak, perlakuan kepada manusia yang patut. Ketika seorang demonstran ditembak di tahun 1966, Penyair Taufiq Ismail menulis sajak, mengingatkan bahwa peluru yang ditembakkan itu adalah hasil "pembayar pajak negeri ini". Ia memang saat itu terdengar seperti penyair Amerika, karena Amerika Serikat memang bermula dari perkara pajak: Revolusi Amerika dimulai ketika Penjajah Inggris mau mengenakan pajak kepada para warga di koloni di Barat itu, tanpa memberi mereka hak untuk ikut menentukan. Tapi 30 tahun kemudian, di Indonesia juga, apa yang dikatakan Taufiq Ismail tetap berlaku -- dan makin sah karena justru kini, bukan di tahun 1966, pajak diterapkan dengan serius. Tapi barangkali Taufiq Ismail tetap salah? Barangkali, dalam kesadaran Indonesia -- yang biasanya harus dianggap lain dari Amerika -- pajak adalah semacam upeti kepada para pejabat? Barangkali yang berkuasa memang lebih tahu -- dan kita bayari -- untuk mengadakan larangan ini dan itu, dan menindak ini dan itu? Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini