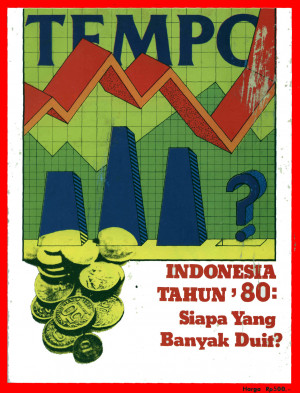SEJAK Februari 1934 ketika "triumvirate" Sukarno-Hatta-Syahrir
dibuang Belanda, suasana perjuangan politik menjadi kerut kalau
bukan kecut. Gubernur Jenderal De Jonge mau secepatnya
melumpuhkan sayap radikal nonkooperatif dari para pejuang
kemerdekaan. 'Alasan di atas segala alasan kita adalah perlunya
menegakkan keamanan dan ketertiban ....,' katanya.
Setelah itu ia pun mendendangkan 'lagu biasa' dari setiap
penguasa, yaitu memperketat penjagaan terhadap semua gerakan
politik yang dicurigai, dengan penyusupan polisi rahasia ke
mana-mana.
Gebrakan De Jonge, yang pada mulanya ragu itu temyata hasilnya
amat efektif. Dalam tekanan yang bertubi-tubi itu partai-partai
radikal ambruk. Partindo, partainya Sukarno secara resmi
dibubarkan oleh Sartono tahun 1936. PNI-Barunya Syahrir-Hatta
pun susut lalu mati sejak saat para penganjur mereka ditangkap,
meskipun tak pernah secara formal dibubarkan. Termasuk koran
mereka Daulat Rakyat. Di penjara Glodok Hatta sempat heran apa
sebab Daulat Rakyat tak bisa terbit lagi ....
Ditantang oleh kiprah De Jonge, pada akhirnya gerakan politik
nasional mengembangkan sikap dan warna perjuangan yang agak
lain. Perubahan warna tersebut nampak dalam pembentukan Parindra
tahun 1935 yang diketuai Raden Sutomo. Parindra dan Gerindo
kemudian merupakan dua partai terkemuka yang penampilannya dapat
dikatakan kooperatif, santun, hati-hati serta pendiam.
Ancaman pembuangan tetap membayangi setiap kelompok yang berani
terang-terangan menentang pemerintah. Satu-satunya lembaga yang
bebas dari sensor pemerintah, yaitu sisa tempat untuk berpolitik
tinggal Dewan Rakyat (Volksraad).
Simbolik dari perubahan warna perjuangan politik nampak dalam
apa yang terkenal dengan 'Petisi Sutarjo' yang disampaikan pada
tanggal 15 Juli 1936. Petisi tersebut dengan lembut memohon
kepada pemerintah agar 'diselenggarakan pertemuan yang setara
antara pihak Belanda dengan wakil Indonesia, untuk membicarakan
bersama rencana terperinci tentang otonomi Indonesia.'
Toh, usul yang disorongkan oleh enam orang penanda-tangan petisi
tersebut yang dengan hormat mengajukan permohonan pada
Pemerintah Tinggi dan Staten General 'Soepaja soekalah
menolong', pada akhirnya ditolak. Hal ini menimbulkan kekecewaan
besar di kalangan para pejuang kemerdekaan.
Kekecewaan demi kekecewaan menumpuk. Tuntutan kemerdekaan dengan
halus atau kasar ternyata tak 'menginsyafkan' Belanda. Dalam
keadaan putus-asa semacam ini maka salah satu hiburan di
kalangan para pejuang adalah pada meletusnya Perang Pasifik. Di
kalangan rakyat kebanyakan semakin santer bertiup nubuatan 'nabi
Jawa' Joyoboyo yang sejak lama mereka tunggu kebenarannya. Yaitu
bakal datangnya bangsa kuning dari arah utara yang akan mengusir
Belanda dari bumi Nusantara.
Sementara itu 'tiga serangkai' bersunyi-sunyi di pengasingan.
Sukarno di Flores kemudian pindah ke Bengkulu. Dalam
kesunyiannya ia banyak mengisi waktu mempelajari soal keagamaan.
Khususnya sejarah dan aliran dalam pemikiran theologi Islam.
Demi mencari kecocokan pandangan. Sedangkan Hatta sibuk antara
lain dengan sistematik filsafat Yunani. Syahrir yang bersama
Hatta dapat bagian Digul dan Banda Neira lebih tertarik pada
renungan kebudayaan. Lewat refleksi personalnya ia menyelami
masalah hubungan antara vitalitas kebudayaan Barat dan
kelambanan kebudayaan Timur. Suasana retraite yang reflektif
semacam ini memberikan kesempatan untuk merenungi aspek
spiritual-kultural yang dalam keadaan biasa mungkin tak
tersentuh.
Dalam suasana vacum, kecewa dan sunyi seperti itulah berlangsung
'Polemik Kebudayaan' yang terkenal (1935, 1936 dan 1939).
Masalah kebudayaan dilontarkan jauh melintasi jangkauan politik
saat itu. Apabila perjuangan politik kandas, 'polemik'
menembusnya dan menempatkan perjuangan di seberang penjajahan.
Pada saat para pejuang politik terkurung tanpa daya, muncul
isyarat lain yang dilontarkan dalam polemik berupa semangat yang
tegar dan optimisme yang tak tertahankan.
Pendekar muda usia (27 tahun) asal Sumatera yang bergelar Sutan
Takdir Alisyahbana menggebrak panggung budaya dengan pilihan
yang tegas-lugas. "Perantauannya" ke Barat menyentakkan
kesadarannya ke masa depan. Masa depan budaya Indonesia harus
terarah ke Barat. Unsur-unsur dinamis budaya Barat khususnya
ilmu dan teknik harus dikejar. Kesatuan budaya nasional adalah
ciptaan khas abad 20, milik semangat waja generasi muda.
Provinsialisme adalah jahiliah. Budaya Timur yang mementingkan
harmoni alam adalah lemah dan statis. Pendidikan hendaknya
menyadarkan generasi muda pada nilai-nilai individualisme,
intelektualisme, egoisme dan materialisme. 'Dengar, dengarlah
tempik kegirangan memenuhi udara! Itulah generasi baru yang
tiada tertahan menuju ke puncak.. dan seterusnya. Gaung suara
Takdir beserta dengan segala soal yang ditimbulkannya terus
bergema di sepanjang tahun kehidupan republik ini.
Adapun Syahrir di Banda Neira yang sepi, mengeluh: 'Aku, boleh
jadi terlalu abstrak bagi bangsaku. Teramat jauh dari alam pikir
mereka, terlalu 'Barat'. Dan mereka juga bagiku terlampau lamban
.... kaum intelektual kita lebih dekat ke Amerika, Eropa
daripada Borobudur atau Mahabarata.
Keluhan ini boleh jadi merupakan simbolik frustrasi intelektual
tahun 30-an. Dan sebagaimana gaung suara Takdir yang masih dapat
kita dengar hari ini, begitu pula keluhan Syahrir. Simbolik
frustrasi kaum intelektual kita hari ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini