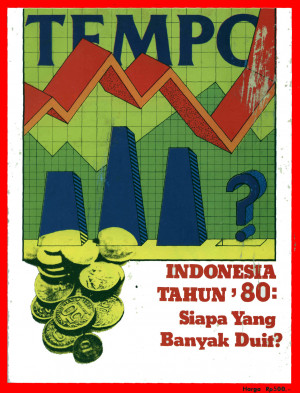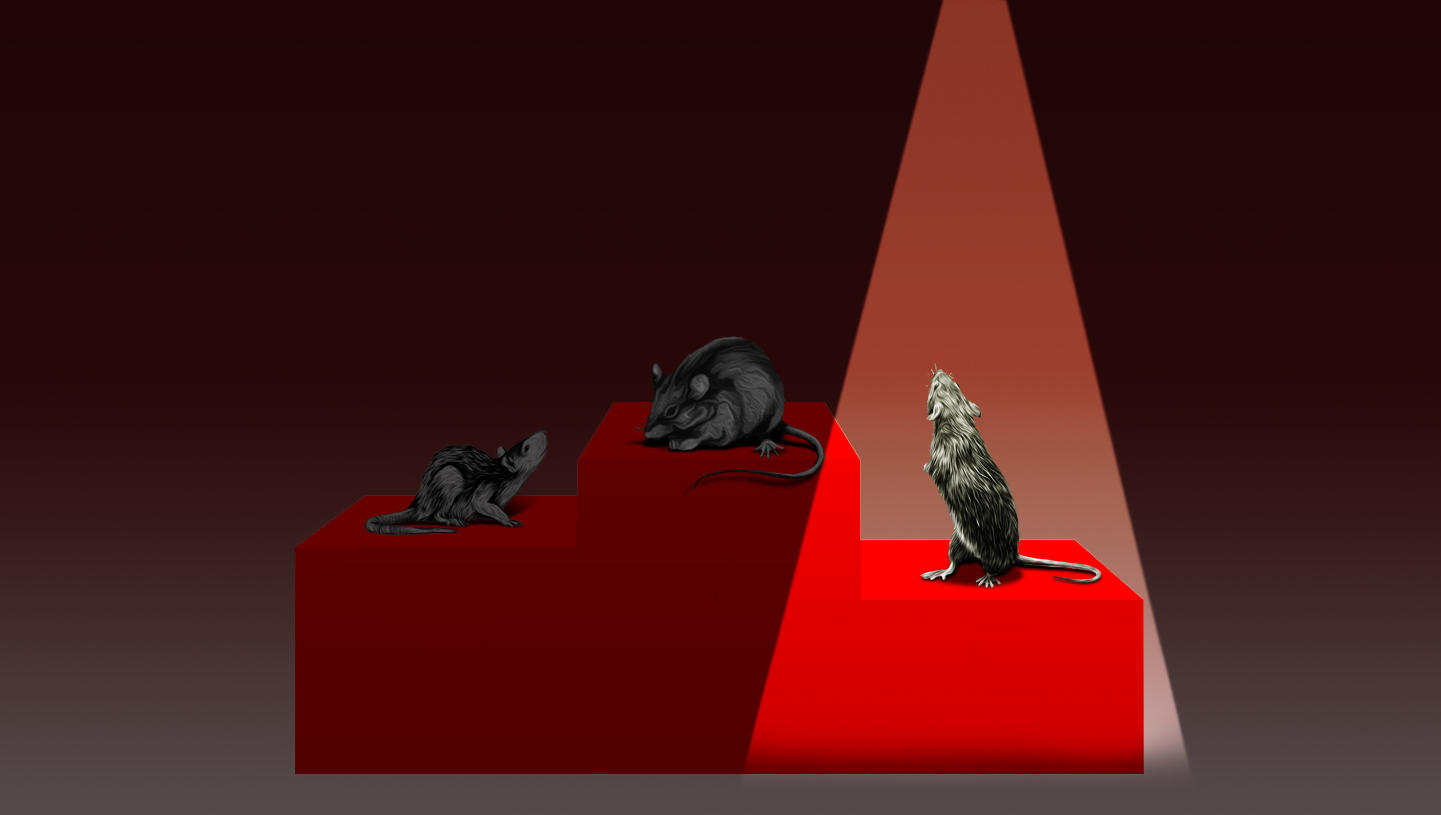BUAT keluarga buruh-petani yang mengandalkan pembagian ikatan
panenan, bawon, pada waktu musim menuai, keputusan sang pemilik
sawah pada satu hari untuk menebaskan saja panenan sawahnya
merupakan hari yang gelap gulita. Bagi mereka, dengan sekali
renggut rezeki makan mereka begitu saja lenyap.
Bagi keluarga petani gurem yang mengandalkan hidupnya yang serba
kekurangan itu dari hasil tanahnya yang cuma sebesar beberapa
kedok itu, keputusan sang penguasa untuk menggusur mereka karena
mereka mengerjakan tanah perkebunan secara tidak sah merupakan
hari kiamat. Bagi mereka, dengan sekali tebas putuslah sudah
kepala.
Bagi keluarga nelayan tradisional kecil yang mengandalkan
rezekinya pada hasil tangkapan mereka yang sporadis itu,
hadirnya armada pukat harimau yang mendapat berbagai dekking itu
merupakan pukulan gelombang yang tak tertanggulangi lagi. Bagi
mereka, dengan sekali sempyokan ombak rezeki mereka telah lenyap
ke dasar lautan.
Bagi, bagi, bagi .... seakan tak ada habisnya duka cerita jutaan
keluarga rakyat-kecil sejak berabad-abad.
Buat jutaan orang yang mengalami kesialan seperti itu dapatlah
dibayangkan mereka masih akan sempat bertemu dan berurusan
dengan lembaga-lembaga di masyarakat beserta segala perangkat
hierarki birokrasinya? Untuk mendengarkan penjelasan tentang
bimas, kredit bank rakyat, pembatasan kelahiran, gunanya
Puskesmas, pentingnya koran masuk desa dan seribu satu
penerangan lainnya lagi?
Mereka yang mesti menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer
tetapi gawat yang mesti mereka jawab pada hari itu juga, bahkan
menit itu juga. Pertanyaan seperti ke mana mesti mencari
panenan, ke mana mesti mengerjakan tanah, ke mana mesti mencari
ikan dan udang.
Dan bila untuk membayangkan bertemu dengan orangorang yang
menghiasi perangkat birokrasi pelembagaan desa mereka saja sudah
susah, bagaimana mesti dibayangkan daya jangkau "orang-orang
sial" itu dengan orang-orang yang terletak dalam radius
jangkauan yang lebih jauh atau tinggi lagi. Bagi rakyat banyak
yang miskin itu mungkin sekali orang-orang yang berada di balik
atau di atas desa mereka mereka taruh saja dalam satu kategori:
orang gede. Barangkali bukan kebetulan bila orang desa Jawa
menyebut siapa saja itu priyantun -- bentuk halus dari kata
priyayi ....
Dari sudut posisi rakyat kecil yang miskin yang terjepit itu,
yang cakrawalanya hanya sejauh periuk nasi mereka yang kosong
yang bertengger di atas tungku yang tidak berasap, juga para
ahli ilmu-sosial adalah "orang-orang gede", priyantun-priyantun,
yang tempatnya adalah nun jauh di sana di balik cakrawala. Bagi
orang yang hidup dalam kemiskinan "struktural" itu, mereka sudah
lama menyesuaikan dengan apa yang disebut oleh Oscar Lewis (Five
Families La Vida, The Children of Sanchez) the culture of
poverty budaya kemelaratan.
Dalam keadaan begitu mereka telah lama menyesuaikan dengan
orientasi nilai kemelaratan yang mempunyai aturan dan dinamika
sendiri. Maka bagi mereka, apa yang terjadi di balik cakrawala
mereka -- termasuk apa yang diomongkan orang-orang di balik
cakrawala itu -- adalah hal-hal yang pantas dikhayalkan saja --
saking jauhnya letak itu semua dari mereka.
Mengingat itu semua alangkah kikuk posisi organisasi ilmiawan
sosial seperti HIPIS menyelenggarakan satu seminar ilmiah
tentang jalur pemerataan dan kemiskinan struktural.
Kikuk karena tema seperti ini adalah satu tema yang "panas" dan
peka. Tema seperti ini akan bisa sekaligus membangkitkan
tuntutan dan tuduhan. Tuntutan akan kualitas compassion atau
simpati para pujangga ilmu-sosial itu terhadap persoalan dan
"aktor pendukung" kemiskinan stuktural itu. Ini adalah tuntutan
yang pagi-pagi sudah berbau kecurigaan terhadap kemampuan para
pujangga ilmu-sosial yang klas-menengah itu untuk menanggapi
kemiskinan dengan simpati yang murni.
Kecurigaan ini kemudian bisa meningkat pada keputusan bahwa para
pujangga itu, sebagai layaknya anggota klas menengah kota, yang
terpeluk ketat oleh gaya hidup kota, tidak akan mungkin mampu
peka terhadap persoalan kemiskinan. Ini akan bisa membawa kepada
tuduhan bahwa kalau toh para warga klas-menengah kota yang
berpredikat ahli ilmu-sosial itu mulai menaruh perhatian pada
soal-soal kemiskinan maka itu adalah sekedar basa-basi,
lip-service atau suatu pic-nic ke dunia miskin.
Dan lebih berat lagi bila tuduhan itu meningkat sebagai tuduhan
yang membayangkan seminar seperti ini adalah keinginan warga
klas-menengah kota itu untuk menjadikan kemiskinan sebagai satu
commodity, satu barang dagangan untuk dijajakan pada forum
pembiayaan internasional. Jadi semacam "paket pengemisan" untuk
dijual berkeliling pada suatu konsorsium penelitian ilmiah.
Tuntutan yang berikut adalah tuntutan terhadap kualitas
kemampuan para pujangga ilmu-sosial kita secara profesional
menghayati kemiskinan struktural itu. Sudahkah para pujangga itu
menguasai metodologi dan mengembangkan teori yang cukup jitu,
halus dan tepat untuk dapat menggarap kemiskinan struktural
kita? Dan bukan sekedar pengetrapan secara membabi-buta
metodologi dan teori para superstar ilmu-sosial asing? ....
Tuntutan dan bahkan tuduhan seperti tersebut di atas adalah sah
meskipun mungkin tidak selalu adil, fair. Kesahan itu terletak
pada kenyataan kemiskinan struktural itu yang sudah ada selama
berabad dan tak kunjung teratasi. Serta juga pada kenyataan
bahwa posisi para ilmiawan, para pujangga kita, adalah posisi
elite dalam masyarakat kita yang berpretensi Pancasila ini.
Mungkin ini jauh hari sudah disadari oleh para anggota HIPIS.
Sebab bila tidak, bagaimana menjelaskan sikap keterbukaan HIPIS
untuk merangkul sebanyak mungkin unsur non-HIPIS dan
non-akademik dalam pembahasan-pembahasan itu? Dari sudut ini
keputusan HIPIS untuk memilih tema yang begitu "panas" dan peka
adalah satu keberanian yang patut dihargai.
Tapi sembari menghargai itu baiklah peringatan Soedjatmoko bahwa
agaknya banyak dari teori ilmu-sosial, teori ekonomi dan
ideologi politik yang dianggap mapan, established, dewasa ini
terbukti tidak mampu menunjukkan jalan keluar bagi kemiskinan
struktural di negara-negara berkembang, direnungkan ....
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini