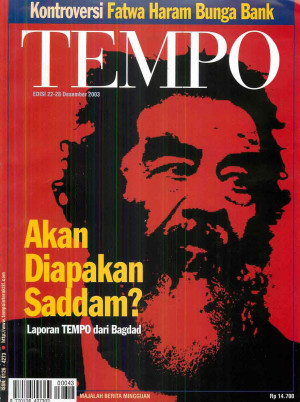Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setiap Desember adalah menunggu. Malam akan habis, kalender dirobek, dan dini hari dicegat pertanyaan yang setengah tertelan: "Apa yang akan datang? Siapa yang bakal datang?"
Mungkin sebab itu setiap Desember berada di ambang advent. Orang Kristen membatasinya sebagai masa empat pekan menjelang Natal. Pengertian ini konon datang dari abad ke-12, dari bahasa Latin adventus, yang berasal dari kata kerja advenire, yang secara harfiah berarti "datang ke". Advent: kedatangan sesuatu yang penting dan ditunggu.
Sesuatu yang penting dan ditunggu, sesuatu yang belum jelas apa, mungkin sesuatu yang mustahil, sebuah mukjizat, tapi mungkin juga sebuah bencana.... Setiap Desember adalah awal orang meniti buih di selat yang gelap yang terkadang rusuh. Di seberang, hanya beberapa langkah lagi, ter- bentang kurun waktu di mana harapan bisa memukau tapi juga bisa lancung. Kini kita gamang. Terutama karena kita telah sering harus bersandar pada kepercayaan yang patah. Yang kita punyai hanya beberapa bekas kekerasan, rasa terkecoh oleh impian, rasa cemas.
The evil and armed draw near...
And the houses smell of our fear.
Saya ingat kalimat itu: "Makin dekat juga yang keji dan bersenjata…/Dan rumah-rumah mengendus ketakutan kita." W.H. Auden menuliskannya melalui sebuah Desember yang juga waswas, di antara akhir 1941 dan pertengahan 1942, sebagai baris-baris dalam For the Time Being: A Christmas Oratorio, puisi Natal yang panjang yang dibuka dengan "Advent," bagian pertama.
Waktu itu perang masih membelah bumi. Tak seorang pun yang tahu dapatkah Hitler (dan "yang keji dan bersenjata") akhirnya dikalahkan. Tapi puisi itu tak hanya berpusar pada titik yang kelam. Oratorio itu digubah se- telah Auden kembali memeluk iman yang pernah ditinggalkannya. For the Time Being mengandung harapan Nasrani: ada kabar baik bahwa mukjizat bisa terjadi. Yesus dilahirkan dan malam itu terbit bintang yang jernih di atas Bethlehem.
Bintang di kejauhan itu seakan-akan menggamit, ketika, dalam kata-kata Auden, kita "hanya samar-samar tahu, apa gerangan kita dan kenapa kita di sini." Dan "untuk menemukan bagaimana jadi manusia saat ini," itulah alasan kita mengikutinya. "To discover to be human now/Is the reason we follow this star."
Tapi justru di situlah terasa bahwa kita berjalan di lorong sengsara: untuk tahu bagaimana "jadi manusia," kita ternyata harus menunggu sesuatu yang praktis mustahil—bintang yang jernih itu, benda langit yang menandai saat ketika Yang Suci masuk merasuk ke dalam hidup sehari-hari dan Yang Kekal menjelma ke dalam yang temporal.
Lorong sengsara itu—mungkin Buddhisme berbicara lebih jelas tentang hal ini—tak kunjung berakhir. Juga setelah berpuluh-puluh Desember lewat. Tiap kali kita harus menempuh lagi suasana seperti yang terpantul dari pelbagai puisi Auden: sebuah suasana "Audenesque", seperti disebut oleh Graham Greene pada tahun 1930-an: kemurungan yang makin akrab.
Kemurungan "Audenesque" adalah warna dunia yang ditinggalkan sesuatu—dan "sesuatu" itu sangat berarti. Sebuah sajak Auden yang terkenal, bagian dari Twelve Songs, bergumam dengan nada getir yang ditahan:
Stop semua jam, putuskan telepun
Bujuk anjing untuk diam, beri dia tulang yang ranum
Bisukan piano, dan dengan genderang mendesah
Kita keluarkan jenazah; silakan mereka yang bertakziah.
Mungkin selalu ada saat seperti itu, ketika kita seakan-akan ingin berhenti dari hari, dan membiarkan datang "mereka yang bertakziah," the mourners.
Takziah untuk siapa? Siapa jenazah di hari kemarin, kini, dan esok? Kita tak perlu tahu. Sebab yang mati, yang hancur, yang hilang, begitu banyak. Bahkan tak akan jadi ganjil jika kita sendiri telah terdaftar di pemakaman. Maka biarkan di langit kapal terbang membentuk huruf berita kematian dan polisi lalu-lintas memasang kaus-tangan hitam. Bintang-bintang kini tak dikehendaki—kata bait terakhir sajak itu—maka padamkan. For nothing now can ever come to any good.
"Sebab kini tak ada yang akan bisa baik." Putus asa itu lengkap, atau nyaris lengkap....
Pada bulan Desember 1939, Auden ada di sebuah bioskop di satu bagian Manhattan, New York, di mana penduduk hampir semuanya berbahasa Jerman. Sebuah film berita tentang invasi Hitler ke Polandia diputar. Sesuatu mengguncang Auden sore itu: ketika di layar tampak deretan orang Polandia yang ditahan, penonton berteriak, "Bunuh mereka! Bunuh mereka!"
Tak ada yang berpura-pura. Tak ada yang malu untuk "tak beradab". Beberapa tahun kemudian Auden mengingat pengalaman itu: "Aku bertanya-tanya pada diri sendiri, waktu itu, mengapa aku bereaksi menentang sikap ingkar kepada tiap nilai humanistis ini."
Apa haknya untuk mengecam? Atas dasar apa ia bisa menuntut para penonton di bioskop di Manhattan itu agar mereka tak dengan bengis meminta orang lain dibantai? Apa alasannya untuk menegaskan bahwa yang membakar dunia dengan kebencian tak boleh dianggap pahlawan dan yang dizalimi tak boleh merasa berhak menyembelih?
Auden tak bisa menjawab. Di ambang putus asa, ketika ia merasa "nothing now can ever come to any good," ia kembali ke dalam iman yang dikenalnya di masa kanak. Ia bersedia lari melintasi gurun panjang ke arah bintang di Bethlehem itu.
Di kandang tempat Kelahiran itu terjadi, ia ingat bahwa di sanalah, buat pertama kali dalam hidup, tiap hal muncul sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang layak disapa. Tiap hal jadi sebuah "Engkau" (You), bukan sekadar obyek (It) yang dengan gampang dibungkam:
Remembering the stable where for once in our lives
Everything became a You and nothing was an It.
Betapa dalam dan menakjubkan momen itu, ketika Yang Suci masuk merasuk ke dalam hidup sehari-hari dan Yang Kekal menempuh laku temporal, "the Eternal do a temporal act."
Tapi bersamaan dengan itu, momen itu sebetulnya juga bukan sesuatu yang sama sekali mustahil: ketika "tiap hal" jadi "sebuah Engkau", ketika itulah kita menyambut tulus yang-lain di luar diri kita. Dan kita ingin menemaninya. Inilah sebuah epiphaneia: ketika "tiap hal" tampil sebagai "Engkau", di situlah terjadi manifestasi diri Yang Ilahi, Kasih, Yang Kekal, Yang Suci—hingga kita pun tak hendak memasung dan merusaknya.
Seorang sufi seperti Ibn 'Arabi akan menyebut momen itu sebagai tajalli (kadang-kadang juga fayd atau "pancaran"). Ia akan berbicara tentang "pancaran yang mahakudus" dan "napas kasih sayang" yang diembuskan Yang Mutlak, hingga dari tiada terbitlah ada.
Tapi dengan pandangan itu, dunia tampak berubah. Dan tak semua orang bersenang hati. Herodes, raja yang menitahkan agar semua bayi hari itu dibunuh—untuk menangkal Sang Bayi Yesus turun ke dunia—punya argumen yang membenarkan tindakan preventif itu.
Auden menggambarkan Herodes sebagai orang yang berpikir panjang—atau lebih tepat, orang yang ingin mempertahankan kehidupan yang rasional, sosial, dan praktis: bila tiap hal jadi "sebuah Engkau", bagaimana dunia tak akan kacau? Bila Kasih tak takut akan anarki ("Love does not fear substantial anarchy," kata orang-orang arif yang datang ke kandang sapi di Bethlehem itu), apa jadinya tatanan sosial?
Herodes melihat betapa berbahayanya bila "kehormatan Ilahi" diberikan kepada tiap hal: "cerek teh dari perak, liang cetek dalam tanah, nama-nama pada peta, hewan piaraan, kincir angin yang runtuh...." Raja itu ingin menjaga tata yang tertib.
Ia tak mau pengetahuan jadi kalang-kabut karena, ketika rasio hilang, yang ada hanya "sebuah kekacauan pandangan-pandangan subyektif." Ia menyukai "Hukum yang Rasional." Dunia subyektif merisaukannya. Apa jadinya bila kebutuhan menyembah Tuhan tersalur dalam jalur yang tak dapat disosialisasi, dan cerita pahlawan seluruhnya "ditulis dalam bahasa yang privat"? Kehidupan bersama yang ditopang konsensus akan runtuh. Aturan tak akan bisa berlaku secara universal. Hukum akan jadi sendi yang tak pasti. Ketika hidup diperlakukan sebagai ekspresi "napas kasih sayang," akan mampukah kita memberi keadilan, dalam arti hukuman? "Keadilan akan di- gantikan oleh Belas Kasihan...," kata Herodes dengan masygul, "dan akan lenyap semua rasa takut pada pembalasan."
Tapi apa yang akan kita pilih? Ini Desember 2003 yang dibayangi teror, perang, statemen-statemen keras. Juga suara galak yang pasti bahwa pembalasan lebih efektif ketimbang belas kasihan, lebih tertib, sebab balas-membalas membentuk simetri. Berbareng dengan itu, benci telah jadi tugas politik. Ia tak lagi perkara pribadi, ia ada dalam barisan yang rapi, berderap. Tak aneh, sebab bahkan menyembah Tuhan juga telah kehilangan bahasa yang privat.
Tentu, Auden tak bisa memilih argumen Herodes. Ia telah tahu apa artinya Kelahiran itu, ketika tiap hal jadi sebuah "Engkau". Baginya dunia tak lagi tersusun dari "mereka" yang seragam yang bisa diatur sepenuhnya dari sebuah ruang kontrol. Kasih telah turun, dan, seperti dikatakan para orang arif yang datang ke Bethlehem, Kasih membutuhkan "sebuah kelainan yang dapat bilang Aku"—an Otherness that can say I.
Berarti hidup adalah bangunan subyektif yang berbeda-beda. Kita tak akan bisa mengutamakan tata yang tertib. Kita tak akan bisa hidup hanya dengan iman yang dibariskan dalam alur yang siap dan aman. Tuhan justru dicari dalam the Kingdom of Anxiety, "Kerajaan Kecemasan". Di situ, mungkin iman adalah seperti iman Kierkegaard: sebuah lompatan yang berani, sendiri. Setelah malam Kelahiran itu lewat, dan hari jadi siang, "sang sukma harus menanggungkan sebuah sunyi yang tak mendukung ataupun menentang keyakinannya bahwa kehendak Tuhan akan jadi."
Dengan kata lain, itulah iman dalam ketidakpastian, di jalan yang rancu. Juga ketika kita hidup dengan bekas-bekas kekerasan dan begitu gentar hingga "rumah-rumah mengendus ketakutan kita." Maka, sehabis Desember, bisa saja kita kembali gagal mencintai semua saudara kita. Tapi kita tahu, kita tak bisa memimpikan kerajaan yang sempurna tempat kita lari mengungsi. Justru impian itu "sebagian hukuman kita."
Sebaliknya, "kuitansi yang harus dibayar, perabot yang harus direparasi, kata-kata ganjil yang harus dihafal"—semua yang sepele, yang belum selesai—bisa punya arti bila kita ingat bahwa hidup dan cinta bisa menakjubkan: ketika Yang Suci merasuk ke dalam yang sehari-hari dan Yang Kekal di tengah yang temporal. Seorang Herodes tak akan paham. Tapi itu dasar kita untuk bersyukur, untuk tak mengutuk. Dan dari sana kita pun akan bisa "mengakui kekalahan kita tapi tanpa patah harap."
Sebab semua masyarakat dan zaman adalah detail yang akan lewat.
Jakarta, 22 Desember 2003
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo