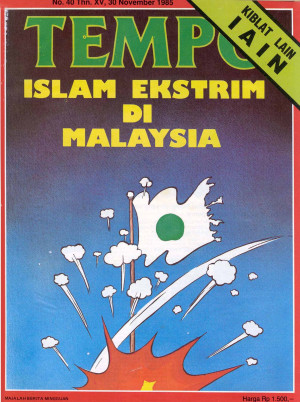HARI sore, Saminem dan Tirah sudah ngider menari, mengitari petak arena di depan jajaran penabuh gamelan: para niyaga. Keduanya sibuk meliuk-liuk mengikuti gending puspawarna, irama dasar pembuka setiap pesta rakyat, tayuban. Istilah pesta rakyat sebenarnya penamaan yang salah kaprah. Karena tayuban adalah pesta yang dirancang dan dibiayai yang punya kerja. Bahkan pesta yang merupakan ajang bagi sisi paling telanjang, paling jujur apa adanya, dari budaya dan peri laku para pemuka desa. Dari gending pangkur iromo telu sampai godril, semuanya ditabuh untuk diabdikan kepada selera para pemuka. Meningkat hot-nya irama tergantung perkembangan selera pemuka yang dipercaya membimbing suasana, dan ialah pemegang sampur. Sedang rakyat jelata cukup ngider di pinggir arena. Tayuban ialah acara menari bersama antara para lelaki perkasa. Untuk aksen, kembang, dan pencipta suasana, dua, tiga sampai lima penari wanita menuntun jalannya irama. Satu saja dari para wanita penari itu yang primadona. Sisanya adalah pendamping, istilah sopannya untul adalah sebutan populernya. Saminem dan Tirah adalah untul. Keduanya pemain, keduanya menari dan menyanyi, tapi lagu dan gendingnya hanya terbatas pada porsi seorang pelengkap penderita belaka. Saminem dan Tirah dalam penggung arena memang diberi gincu ber-celak, bahkan selendang (sampur) yang mereka kenakan pun dari cinde, berkain batik corak parang rusak. Tetapi mutu penampilan keduanya tetap dijaga, agar obvious bagi semua bahwa mereka adalah untul. Karena itu, dari sekelebatan pun segera ketahuan, Saminem atau Tirah bukan sang primadona. Untul boleh centil, tetapi harus bodoh atau membodoh. Untul boleh cantik, tapi jangan mencoba menyamai apalagi menyaingi sang primadona. Dalam akar budaya warisan nenek moyang semacam tayuban ini tercermin nuansa hubungan antara abdi dan ndoro, supremasi dan subordinasi. Biarpun dibungkus sebutan apa pun, aturan mana pun, nuansa itu jelas terasa. Primadona tempat merujuk Untul Saminem dan Untul Tirah adalah Mbakyu Darmi. Tetapi sejak menjadi primadona, Darmi yang Desa Ngrajek asal nenek moyangnya itu mesti mencari legitimasi sakral untuk mengganjal kedudukannya. Ia harus berbau-bau, biar sedikit, trahing kusumo rembesing madu, keturunan puspa rembesan madu. Karena itu, Mbakyu Darmi pun berpelengkap nama Darminingrum. Maka, dalam hubungan untulprimadona, perlakuan jadi berbeda. Saminem dan Tirah, bila hendak manggung, cukup dijemput motor - bahkan dulu sepeda. Darminingrum mesti disongsong mobil - sekurang-kurangnya Colt mini. Saminem dan Tirah harus sudah siap bersolek sejak jam delapan sore. Darminingrum hanya akan siap jam sembilan malam. Feodalisme kampungan ini mengambil bentuk yang pas dengan penjenjangan perlakuan di tingkat masyarakat desa. Seorang primadona boleh menetapkan hampir sekehendaknya (at her full discretion) jatah kenikmatan atau kemudahan bagi untul-nya. Berapa lama untul boleh duduk, kapan harus beranjak menari lagi, sepenuhnya dikomando oleh kedip matanya. Anehnya, para untul cukup bahagia dengan peran pendamping ini. Tampaknya tidak pernah terbayangkan bagi untul untuk menikmati kebebasan berprakarsa, misalnya dalam memilih cengkok gending atau ukel yang sesuai dengan cita rasanya. Tidak pernah ada untul yang punya nyali untuk berbeda dari sang primadona. Sebagai pendamping, mereka tahu diri. Sebagai untul, mereka toh hanya menumpang hidup. Tidak pernah bowo uler kambang yang cantik itu dinyanyikan seorang untul. Apalagi menembangkannya sambil duduk di pangkuan seorang pemuka desa, hak prerogatif sang primadona. Karena lagu istimewa itu tidak dapat dilepaskan dari budaya leladi milik sang primadona. Bagian untul ialah peran pinggiran. Bila penari penyerta yang ramai-ramai ngider sekeliling arena turut mabuk, untul-lah sasaran penampung gendeng mereka. Saminem harus siap dituding-tuding, bahkar-dicolek pemabuk yang menari di ekstrem kiri arena. Tirah bagian menahan sempoyongan pemabuk di ekstrem kanan. Biar terkadang mabuk juga, penari pemegang sampur yang tengah tidak pernah tergolong ekstrem kiri, kanan, atau lainnya. Paling-paling bila minum araknya terlalu banyak, ia hanya akan terkapar di tengah arena. Dan hanya akan jadi momongan sang primadona. Ia tidak dituding-tuding. Hanya diangkat ramai-ramai dengan sukacita. Dibaringkan di tempat tidur utama. Sampai esok, si pemain tengah akan bangkit kembali. Menjalankan fungsi dan tugas pokoknya seperti sedia kala. Manakala tiba saat penari tengah mabuk tanpa menanggung beban sorakan itu, sampai pulalah klimaks acara tayuban. Selesai sudah tugas paling berat sang primadona. Tinggal untul menampung sisa-sisa para teler di sekelilingnya, yang kini leluasa berimprovisasi menari, menyanyi, menghabiskan sisa tenaga menjelang fajar. Tugas untul selanjutnya: menampung uang receh yang berserakan ke dalam baki. Atau menghitung dua tiga lembar ribuan yang dengan gemas diselipkan ke dadanya oleh penggemar yang tahu diri. Bukan primadona ukuran teman mainnya. Cukup untul saja, untuk menyalurkan drama manusianya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini