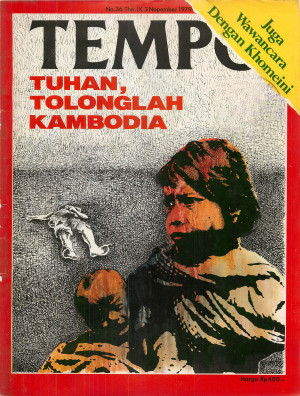PADA sebuah bukit hijau di dataran tinggi Peloponnesus, ada
sebuah monumen. Bukan tugu. Bukan bangunan. Tapi sebuah tulisan,
terdiri dari tiga huruf: oxi.
Kata itu berarti "tidak". Tiga huruf itu telah berada di sana
selama 30 tahun lebih, dalam kesunyian semenanjung yang liar
itu. 30 tahun lebih -- sejak tentara Nazi menduduki Yunani, dan
para partisan bertahan, menyerukan kemerdekaan, seraya
menatahkan kata oxi di antara pohon-pohon.
Yunani kemudian bebas. Tapi dalam sejarahnya lalu datang
sejumlah perwira yang kemudian terkenal dengan sebutan "para
kolonel". Mereka mengambil alih kekuasaan. Yunani jadi
kediktaturan, kali ini oleh anak kandungnya sendiri. Dan di
negeri tempat lahirnya demokrasi itu demokrasi pun dianggap
asing, hendak dihapus, seperti juga mereka mencoba menghapus
kata oxi di dataran tinggi Peloponnesus.
Namun tiga huruf itu tetap saja: cat yang mengapurnya kemudian
terkelupas oleh hujan, terusir oleh matahari. Kata "tidak" itu
begitu keras rupanya bertahan. Itulah "monumen yang paling indah
memperingati harga diri manusia," tulis Oriana Fallaci dalam
bukunya yang telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa, Intervista
con la storia (Wawancara Dengan Sejarah).
Kita tahu kemudian kenapa wartawan wanita terkenal itu
berpendapat demikian. Bukunya dipersembahkan kepada ibunya,
Tosca, "dan kepada semua mereka yang tidak menyukai kekuasaan."
Isinya 14 hasil wawancara dengan tokoh-tokoh dunia yang
mencerminkan sejarah masa kini: ada Henry Kissinger, ada
Jenderal Vietnam Utara Giap. Ada Golda Meir, ada Yasir Arafat.
Ada Indira Gandhi, ada Ali Bhutto. Ada Shah Iran Riza Pahlavi
yang polisi rahasianya konon sering menyiksa orang, ada pula
seorang penyair Yunani yang disiksa "para kolonel" dan menulis
puisi dengan darah.
Tak berarti Fallaci mencoba menarik tokoh yang saling bermusuhan
itu ke dalam dialog. Ia bukan mak comblang untuk kerukunan
dunia. Fallaci tidak netral. Jurnalismenya bukan jurnalisme
putih yang mau berimbang, tak mau memihak, melainkan suatu
ledakan sikap pendirian, juga prasangka dan kemarahan. "Aku tak
merasa diriku sebagai perekam dingin dari yang kulihat dan
kudengar," katanya, dalam pengantar Intervista con la storia. Ia
mendatangi tokoh-tokoh yang diwawancarai dengan seribu rasa
marah, "seribu pertanyaan yang telah menyerang diriku sebelum
menyerang mereka."
Sungguh khas ia memakai kata "menyerang". Ada sesuatu yang galak
pada dirinya. Interviewnya adalah semacam duel, bila yang
dihadapinya bukan tokoh tempat ia menyampaikan kagum. Taktik
pertanyaannya adalah provokasi. Ia ingin mencongkel subyeknya
sampai marah, hingga dari mulutnya keluar kata-kata yang tak
berkedok.
Namun taktik itu bukan sesuatu yang hanya dipakainya. Kita bisa
bayangkan ia ngomong keras seperti wanita dalam film Itali,
menyemprot-nyemprot, tapi kali ini karena satu hal: Fallaci
membenci kekuasaan. Ia ingin meludahinya "Apakah itu datang dari
penguasa yang lalim atau seorang presiden yang dipilih .... aku
melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tak human dan
menjijikkan," begitu ia berkata.
Karena itulah ia melihat tiga huruf di bukit Peloponncsus itu
sebagai sebuah monumen. Sebab itulah ia pernah mendatangi
Kissinger, dan kemudian September yang lalu mendatangi Ayatullah
Khomeini: seorang pemimpin yang dielu-elukan rakyat tapi juga
seorang pemegang kekuasaan yang hampir mutlak. Fallaci juga dulu
mewawancarai Shah Iran dan menutup interviewnya dengan berkata,
"Anda menakutkan saya, Baginda."
Mungkin ia anarkis 75%. Tapi mungkin ia hanya saksi yang tajam
sejarah kita sekarang: ketika manusia makin sadar akan harga
diri dan haknya, tapi sementara itu tetap banyak mulut yang
diinjak agar jangan bilang "tidak". Oriana Fallaci telah bertemu
dengan Alexandros Panagoulis. Dialah penyair yang ditahan,
disiksa dan menulis sajak di penara dengan tetesan darahnya.
Dialah penyair yang digebuk, disetrum, digantung, dikerangkeng
dalam sel paling sempit, dan dalam usia muda keluar ke bumi
dengan wajah seorang tua. "Hari itu ia punya wajah seorang Jesus
yang disalibkan sepuluh kali," tulis Fallaci seperti seorang ibu
yang gementar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini