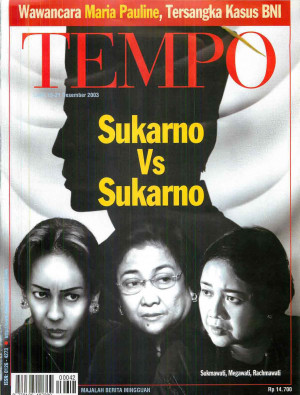Membicarakan upaya pemberantasan korupsi hanya terasa sedikit lebih berarti jika menampilkan sosok Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Ketika pada 3 Juli 2001 ia diberitakan wafat saat menunaikan ibadah umrah, mayoritas rakyat Indonesia merasa sangat kehilangan. Kepergiannya menorehkan rasa pedih yang dalam bagi banyak orang. Bahkan ada laki-laki yang terisak di pinggir jalan, tak jauh dari rumah tempat jenazah Lopa disemayamkan.
Jarang sekali masyarakat Indonesia—dari berbagai lapisan dan usia—merasa terpukul karena kematian seorang pejabat. Tapi itulah yang terjadi saat Lopa meninggal. Dan mungkin karena harapan akan keberhasilan menumpas korupsi begitu tinggi, bersama kematian Lopa, harapan itu pun langsung pupus. Orang-orang jadi apatis. Padahal Lopa sendiri belum sempat membersihkan negeri ini dari praktek korupsi-kolusi-nepotisme (KKN). Ia baru merintis ke arah sana, menyiapkan beberapa berkas investigasi dan menyebutkan sejumlah nama koruptor yang akan segera disidik.
Sepeninggal Lopa, banyak yang merasa yakin bahwa Indonesia tidak akan segera mendapat penggantinya. Selama dua tahun terakhir ini, kita pun tidak punya alasan untuk berharap banyak pada upaya pemberantasan KKN. Kita bahkan sudah tidak sabar menyaksikan perilaku orang-orang yang berkompromi dengan KKN, dan kehilangan kepercayaan kepada pemimpin yang ragu-ragu memberantas KKN. Kita seperti terperangkap dalam kondisi yang suram memuakkan.
Kondisi itu tidak menjadi lebih baik ketika pekan lalu DPR memilih lima dari sepuluh orang calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama Taufiequrachman Ruki, yang terpilih sebagai Ketua KPK (dia memperoleh 43 dari 44 suara di DPR), hampir tidak bergema di telinga banyak orang. Selain kurang dikenal di luar lingkungannya (kepolisian), prestasinya yang biasa-biasa saja membuat khalayak bertanya, mengapa DPR menjatuhkan pilihan pada tokoh ini. Keteguhan hati dan keberanian tidak pula memancar dari kepribadiannya. Ciri-ciri serupa mewarnai pribadi keempat wakilnya. Dengan wewenang KPK yang luar biasa—bisa menahan siapa saja, bisa mengusut siapa pun tanpa melibatkan polisi ataupun jaksa, bisa memproses kasus-kasus korupsi di pengadilan antikorupsi—kapasitas mereka terlihat kecil di bawah payung KPK yang tampak terlalu besar.
Jelaslah, KPK itu sebuah superbody. Yang dikhawatirkan ialah seperangkat wewenang yang hebat-hebat itu akan tidak bermanfaat karena tidak digunakan. Mengapa? Bisa karena personel KPK tidak mampu atau tidak cukup bersih ataupun tidak cukup berani untuk menerapkannya. Hal-hal seperti ini harus dikembalikan kepada anggota DPR yang ternyata tidak cukup berani untuk memilih seorang pendekar pemberani sebagai pemimpin KPK. Buktinya, mereka tidak memilih Bambang Widjojanto, Marsillam Simanjuntak, atau Muhammad Yamin.
Reformasi, harus diakui, telah berhasil memperbarui, menyempurnakan, dan memberdayakan lembaga-lembaga negara. Sayangnya, kehadiran lembaga-lembaga itu tidak menjamin bahwa pemberantasan KKN bisa terlaksana. Berbekal pemahaman seperti ini, masyarakat yang kecewa dengan pilihan DPR kelak tidak perlu terperanjat bila KPK berkiprah hanya sebagai pelengkap penggembira—sekadar melayani kepentingan elite, dan tidak terpanggil untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.
Jangan lupa, negeri ini selalu tampil sebagai pengecualian bagi setiap solusi baku yang efektif berlaku di negara lain. Sementara di Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia, lembaga mahasakti seperti KPK cukup efektif memberantas korupsi, di sini belum tentu bisa begitu. Selagi ciri pengecualian ini masih sangat dominan, keberhasilan memberantas korupsi akan lebih ditentukan oleh personalia pemimpin KPK daripada wewenang hebat yang disandang lembaga itu. Karena itu pula kita lagi-lagi teringat pada almarhum Baharuddin Lopa, pada keteladanan, integritas, dan keberaniannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini