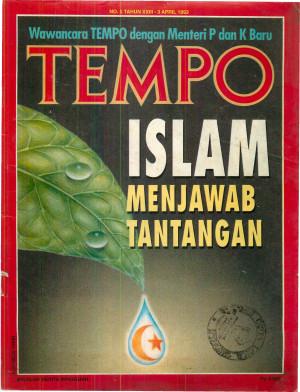TEMAN saya, Zulharman, kemarin berangkat. Dalam peristilahan Zulharman ia tidak meninggal dunia: ia sekadar naik kereta terakhir. Keberangkatan Zul juga bukan karena penyakit. Dalam kata-kata Zul tidak ada istilah ''penyakit''. Zul memang kadang- kadang sakit hati, tapi tidak pernah berpenyakit. Saya menduga dia sakit hati ketika saya minta diri untuk meneruskan studi: sampai tiga kali saya minta pamit. Dua kali pertama ditolak dengan air matanya. Ketiga kalinya ia berdiam mengia. Dia juga sakit hati karena tidak mengerti mengapa Orde Baru menutup HARIAN KAMI, suatu koran Orde Baru ''dalam''. Zul tidak paham politik praktis sampai embus napasnya terakhir. Konstruksi jiwa Zulharman tidak dibuat untuk ''realpolitik''. Dalam ketidakpahamannya itu Zul memutuskan untuk mengangkat intuisi jiwa pejuangnya menjadi panglima. Itu sebabnya mengapa ia bertempur terus, jauh setelah jaket kuning digantung di kapstok. Zul bukan dari generasi saya. Ia datang dari generasi sebelum 1966. Saya pertama kali ketemu Zul pada tahun 1964: Mubes Nasakom Penterapan Penpres 1/1964 Tentang Perfilman Nasional. Adalah tipikal bahwa orang selalu bertemu dengan Zul dalam suatu arena pergerakan. Dalam arena itu saya pertama kali dikenalkan pada Asrul Sani, Malidar, Hadis, Harmoko, Misbach, dan sejumlah orang ''nekat'' lainnya yang berani maju ke muka untuk menyetop mesin giling poros nasionalis-komunis. Di situ saya mengerti bahwa orang itu akan selalu ''nekat'' kalau tidak lagi melihat alternatif. Ketika itu kami tidak melihat alternatif dan siap melawan secara terbuka stoomwals progresif-revolusioner yang bergerak di bawah panji-panji merah PKI. Di situ juga saya mulai bermimpi bahwa kalau umur panjang, saya ingin pandai menulis seperti Asrul berpidato. Goenawan Mohamad, yang baru saja diteror pelarangan Manifes Kebudayaan, menyusun pamflet Strategi Penyederhanaan Medan di suatu tempat dekat Pasar Cikini. Wiratmo Soekito berfalsafah dan membayar warung kopi untuk kita semua. Dari Los Pijet di Senen sampai Warteg Pabrik Angin di Jalan Minangkabau, warung-warung kecil dikonversi menjadi sidang- sidang seminarium. Dari Mao sampai Proust, dari Milosz sampai Proudhon dan kaum Jacobin hingga Kardelj, Oscar Lange serta Rosa Luxenburg, Yevtushenko dan Brodsky. Begitu konteks keadaan ketika saya pertama kali bertemu dengan Zul. Ia mengantar saya bermimpi, akan tetapi terlalu aktivistik untuk betah mendengarkan misalnya bahwa revolusi perpetual Mao bukan sekadar revisi terhadap Marxisme-Leninisme, melainkan puncak kecongkakan rekayasa sosial. Zulharman juga mengajarkan bagaimana membikin jembatan antara kelompok yang cita-citanya sama, tapi canggung menjalin aliansi. Buat Zul, pergerakan adalah segala-galanya. Inspirasi dari Zul telah menggerakkan saya untuk mempertemukan Harry Tjan dengan Subchan Z.E. Pertemuan itu pada waktunya melahirkan suatu aliansi besar yang kemudian memuntahkan massa rakyat ke jalan-jalan protokol di kota-kota seantero Jawa. Buat Zul, dalam perbandingan dengan pergerakan, orang seperti kita kecil artinya. Sikap hidup hiper-positif, antusiasme yang menular ke mana-mana, tawanya yang gampang tumpah, dan energi yang gemuruh deras mengalir entah di mana hulunya betapa mudahnya Zul memimpin kita. Rumahnya terbuka 24 jam buat siapa pun yang mengetuk pintu. Tiada orang yang lebih lapar daripada bujangan pukul 3 pagi, atau pukul 4 sore. Dan pada pukul 3 pagi atau pukul 4 sore Cuni siap menghidangkan makanan di meja, dengan senyum geli sedikit. Di rumah Zul dan Cuni, bukan hanya setiap hari open house, tapi setiap hari ada pula sahur pukul 3 pagi. Saya diam-diam menduga bahwa Cuni agak ketawa geli dalam hatinya menyaksikan sepak terjang suami dan teman-teman suaminya. Di lain pihak, kita para bujangan masing-masing berangan-angan: kalau nanti kawin, moga- moga dapat istri seperti Cuni. Kesayangan pada Cuni lambat laun tumbuh menjadi kekaguman kita semua akan kekuatan sanubarinya, akan kekukuhan batinnya. Luar biasa teladan dua orang ini bagi kita semua. Saya jumpa Zul terakhir di RSCM. Dia terbaring, seluruh tubuhnya berwarna kuning dalu. Dia peluk saya erat-erat sambil menangis. Semua orang yang hatinya baik mudah menangis. Buat orang seperti itu tiada hal yang perlu disembunyikan, termasuk emosinya. Kami bicara tentang rumahnya di Kebon Kacang, tentang kesatuan aksi, tentang analisis zaman sekarang, zaman kemarin, zaman besok. Kami bicara seakan-akan waktu berhenti dan menonton dua sahabat berbincang. Waktu berhenti hanya kalau orang bicara tentang soal yang lebih besar dari dirinya. Pada saat itu sebagian dari diri saya melepas keluar dari tubuh dan berdiri di samping kiri waktu. Saya coba berbisik: pembicaraan ini dari waktu dan tempat yang lainkah? Kalau memang demikian, kalau ini memang skenario dari masa silam, mengapa hati saya tenggelam dalam perasaan solider yang begitu kuat? Dan mengapa lengan waktu berpeluk seperti dalam salat? Ketika pamit saya menciumnya sekali lagi. Saya pesan agar dia tidak mengalah. ''Jangan kau khawatir, No! Kereta ini tak kan kulepas! Aku merasa begitu nikmat kalau teman-teman datang berbincang seperti ini hatiku sedih kalau kau pergi, sedangkan aku harus diam berbaring!'' Pada saat itu tanpa diketahui satu pun orang, Zul memberikan warisannya kepada saya, kepada teman- temannya yang ditinggalkan di peron stasiun: kesan bahwa tiada yang lebih nikmat daripada berpeduli pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Terima kasih, Zul! Bolehkah tulisan ini kuturunkan?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini