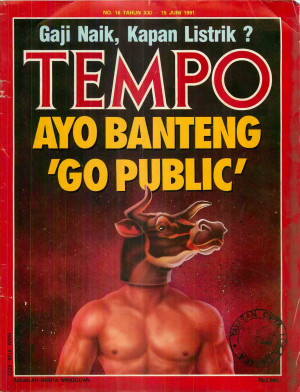Inilah pesantren pertama di Indonesia dengan metode dan sikap pendidikan modern. 15 ribu alumnusnya berprestasi di berbagai bidang Ulang tahun Gontor ke-64. PADA mulanya adalah soal bahasa. Kongres umat Islam di Surabaya, 1920-an, menuntut agar yang mewakili umat Islam Indonesia pada pertemuan umat Islam sedunia di Mekah, adalah orang yang mampu berbahasa Inggris dan Arab. Tapi itu tak mudah, meski dalam pertemuan itu hadir tokoh nasional seperti Haji Omar Said Cokroaminoto, K.H. Mas Mansur, H. Agus Salim, dan A.M. Sangaji. Akhirnya dicapai kompromi, ditunjuk dua orang wakil: Cokroaminoto yang mampu berbahasa Inggris, dan Mas Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah, yang fasih berbahasa Arab. Peristiwa inilah yang mengilhami Ahmad Sahal, salah seorang pemuda yang hadir dalam kongres, untuk mendirikan pondok pesantren yang bisa melahirkan manusia berakhlak tinggi dan sekaligus menguasai pengetahuan umum lewat bahasa Inggris dan pengetahuan agama Islam lewat bahasa Arab. Keinginan itu terlaksana pada 9 Oktober 1926. Persisnya, seusai peringatan Maulud Nabi Muhammad. Ketika itu Ahmad Sahal dengan dua orang adiknya- Zainuddin Fananie dan Imam Zarkasyi- mengumumkan bahwa Pondok Gontor, yang tadinya tidak berjalan, dihidupkan kembali dengan nama baru Pondok Pesantren Darussalam, yang artinya pondok tempat mencari kedamaian. Pondok inilah yang kemudian dikenal sebagai Pondok Modern Gontor. Bila pada 3 Juni sampai 20 Juli 1991 ini, pesantren yang terletak 12 km tenggara Ponorogo, Jawa Timur, itu ramai dikunjungi para alumnusnya, di situ memang ada peringatan 8 windu atau 64 tahun usia Pondok. Sebyah acara akbar, lebih dari sebulan, dengan biaya tak kecil pula, sekitar Rp 516 juta. Tapi tema peringatan cukup terdengar rendah hati: mawas diri. Suasana di Gontor memang aneh buat ukuran lembaga pendidikan di Indonesia. Coba saja, sejak berdiri 64 tahun lalu itu, tak satu pun dialog dengan bahasa Indonesia terdengar di sini. Para santri bergurau dengan bahasa Inggris, berdiskusi dengan bahasa Arab. Hanya di ruang tamunya, di pondok seluas sekitar 6,5 ha ini, bahasa Indonesia boleh digunakan tanpa ada sanksi. Hasilnya, sebuah anekdot yang diceritakan oleh Kafrawi Ridwan, bekas Sekjen Departemen Agama, yang kini jadi pemimpin redaksi majalah Amanah. Pada 1979, tuturnya, Sekjen Rabithah Islam yang berpusat di Mekah berkunjung ke Indonesia. Di Gontor ia berpidato, dengan bahasa Arab tentu. Dan para santri, dalam acara tanya jawab, menanggapi pidato tamunya dengan baik- mereka paham benar isi pidato tersebut. Di IAIN Surabaya, Sekjen Rabithah Islam itu pun memberikan ceramah, dan para mahasiswa susah menanggapinya, karena salah menangkap pidato dalam bahasa Arab itu. Itu bukan kesombongan Kafrawi, 57 tahun, yang alumni Gontor dan sekarang menjadi "rektor" bekas sekolahnya itu. Itu adalah contoh, bagaimana sebenarnya pujian terhadap Pondok Darussalam itu bukan omong kosong. Sebab, seperti diakui oleh Nurcholish Madjid, santri Gontor pada 1955-1960, pada Sri Raharti dari TEMPO, metode pendidikan bahasa di Gontor sungguh berhasil. Memang, sebagaimana diniatkan oleh para pendirinya, dan kemudian menjadi salah satu barometer kemodernan Gontor, keluaran Gontor pintar berbahasa Arab lebih dari lulusan IAIN, dan jauh pintar berbahasa Inggris lebih dari lulusan SMA. Herannya, metode pendidikan bahasa itu tak disontek oleh pendidikan umum di negeri ini, yang dikeluhkan sangat buruk. Karena bahasa itu juga pada 1957 pemerintah Mesir mengakui mutu tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor, pendidikan setingkat SMA, yang didirikan K.H. Imam Zarkasyi pada 1936. Tamatan KMI bisa diterima langsung di Universitas Al Azhar, Kairo. Sebenarnya, KMI bukanlah ide orisinil Gontor. Model sekolah itu pertama kalinya diperkenalkan di Indonesia oleh Prof. H. Mahmud Yunus di Padang, pada 1931. Yakni sepulang Mahmud dari belajar jadi guru di Darul Ulum, Kairo, Mesir. Ke KMI Padang yang meniru sistem Darul Ulum inilah Imam Zarkasyi diutus kakaknya untuk mempelajari sistem dan falsafah pendidikannya. Itulah awal sejarah Gontor mengapa berkiblat pada pemikiran para pembaru, misalnya Syeikh Muhammad Abduh dan Rasid Ridha. Di bidang fikih, Pondok Gontor memang sudah meninggalkan kitab-kitab kuning seperti Fathul Qarib, yang biasa diajarkan dengan sistem sorogan dan weton di berbagai pesantren tradisional. Di sini dipelajarkan kitab yang jarang digunakan di pesantren, antara lain Bidayatul Mujtahid, karya besar Ibnu Rusyd, seorang fukaha muslim yang hidup di abad ke-12. Fukaha "komentator Aristoteles" ini menulis bukunya dengan pendekatan komparatif, perbandingan mazhab. Ini mencerminkan bahwa Gontor memiliki "semangat berdiri di atas semua golongan". Semua mazhab diajarkan pada santri, agar para siswa tak picik horison wawasannya. "Soal apakah mereka memilih salah satu mazhab atau tidak, itu terserah," kata Hamam Dja'far, alumni Gontor yang mendirikan Pesantren Pabelan di Magelang, Jawa Tengah, pada R. Fadjri dari TEMPO. Gontor memang tak memihak, dan menjaga kebebasan berpikir. Lihat saja, semangat pembaruannya mengingatkan orang pada Muhammadiyah. Tapi di masjid Jamik, yang merupakan titik sentral Pesantren Gontor, ada beduk. Bahkan, dalam salat subuh, imamnya kadang-kadang membaca kunut. Beduk dan kunut, bukankah ini ciri Nahdlatul Ulama? Dan dari pesta peringatan kini, orang bisa bilang, pembaruan di Gontor tak berhenti jadi sejarah. Hampir tiap malam ratusan penduduk desa tumplek di lapangan sepak bola di depan kompleks Pondok. Ini tentu saja mengundang datangnya para pedagang kacang, es, bakso, mainan anak-anak, dan lain-lain. Enam tahun lalu, di zaman K.H. Imam Zarkasyi masih hidup, pemandangan seperti ini tentulah mustahil. Waktu itu peraturan di Gontor sangatlah keras: para santri dilarang berkumpul di kampung, dan warga kampung pun, yang tak ada sangkut pautnya dengan Pondok harap dimaafkan, tak juga bisa bertandang seenaknya ke Pondok. Bila seorang santri kepergok bermain di kampung, ia akan dikenai hukuman. Bahkan, kata Nurcholish Madjid, ia bisa dikeluarkan dengan alasan melanggar disiplin. Maka, kritik waktu itu adalah, Gontor jadi menara gading di tengah masyarakat yang memerlukan obor pengetahuan. Kritik itu baru hilang sejak Gontor dipimpin oleh K.H. Shoiman Lukman Hakim, K.H. Abdullah Syukri, dan K.H. Hasan Abdullah Sahal- trio generasi kedua, putra-putra para pendiri. Diputuskan, Pondok Gontor menyatu ke dalam masyarakat lingkungannya. Sarana untuk itu pun diadakan: sebuah jembatan senilai Rp 15 juta yang menghubungkan pondok dan kampung sekitarnya dibangun. Melalui jembatan inilah, penduduk setiap malam berlalu-lalang menuju lapangan bola menyaksikan hiburan berupa layar tancap, band, reog, drama, atau pergelaran wayang kulit. Karena acara sulit yang ditemukan di pondok-pondok pesantren tradisional itulah, ditambah metode pendidikannya yang menjaga berpikir bebas, seorang pastor yang berkunjung menjuluki Darussalam sebagai Pondok Modern Gontor- nama yang kemudian lebih melekat daripada nama aslinya. Memang dalam beberapa tahun ini, hubungan antara Gontor dan masyarakat sekitarnya bisa disebut sebagai simbiose mutualistis- saling menguntungkan. Umpama saja, pihak Gontor meminjamkan pupuk pada para petani yang berada di radius 5 km dari pondok, dengan perjanjian: jika panen penduduk harus menjual gabahnya kepada pondok sesuai dengan harga pasar. "Jadi, tiap tahun kami tidak kekurangan beras," kata Kiai Abdullah Syukri, 48 tahun, salah seorang dari trio baru tadi. Dari kerja sama itu pihak Pondok bisa membeli corong dan pengeras suara dan sarana masjid yang lain. Dan sekali setahun, diundanglah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk mengadakan khitanan masal untuk masyarakat sekitar pondok. Syahdan, zaman emansipasi pun akhirnya menyentuh Gontor, meski terlambat. Dulu, pernah Nurcholish Madjid mengusulkan pada K.H. Imam Zarkasyi untuk mendirikan pesantren putri digabung dengan pesantren putra. Tapi usul itu ditolak oleh sang kiai. Barulah satu tahun belakangan ini dibangun pesantren putri, tapi tempatnya 100 km arah barat Kota Ngawi. "Pondok pria harus jauh dari pondok putri," pesan K.H. Imam Zarkasyi semasa hidupnya. Inilah salah satu tanda, modernisasi di Gontor tidak macet. Kini Gontor tidak hanya memiliki ribuan alumni yang berprestasi di masyarakat, tapi juga memiliki kekayaan yang membuatnya tetap mandiri. Sejumlah usaha kini dikelola Pondok. Ada percetakan, penggilingan padi, apotek, polikliknik, koperasi, sawah, dan perkebunan. Dari koperasi siswa, misalnya, tahun lalu diperoleh keuntungan Rp 116 juta. Dari kantin diperoleh keuntungan Rp 64 juta. Kini cita-cita almarhum K.H. Imam Zarkasyi- ingin mendirikan seribu pondok modern seperti Gontor- terlaksana sudah. Meski belum seribu, sudah berdiri 52 pondok dengan sistem Gontor oleh alumnus Gontor. Alumnus dari sistem pendidikan yang awalnya merupakan peleburan dari empat lembaga pendidikan ternama di dunia. Yakni di Afrika (Al Azhar benteng Islam yang kukuh dan wakafnya yang luas, dan Shanggit yang dermawan yang memberikan pendidikan gratis) dan di India ( Aligarhnya Sayyid Ahmad Khan yang dicap "kebarat-baratan," dan Shantiniketannya Rabindranath Tagore yang damai dan sederhana). Jadi, apa sumbangan Gontor bagi dunia Islam Indonesia khususnya, dan masyarakat luas umumnya? Para alumnusnya itulah. Selain kepintaran berbahasa ("Hadiin Rifai, Direktur Sepatu Bata itu, mondar-mandir ke luar negeri dengan kepintaran berbahasa Inggris yang diperolehnya dari Gontor," tutur Kafrawi), paling penting adalah sikap berpikir terbuka alumnusnya. "Kebebasan berpikir, lebih toleran," itulah, menurut Nurcholish, bekal berharga yang dimiliki bekas santri Gontor, untuk disumbangkan ke masyarakat. Inilah contoh modernisasi tanpa menimbulkan guncangan. Sebab, Pondok Modern yang baru setahun lalu berlistrik dari PLN, dan baru setengah tahun lalu punya telepon, tetap mempertahankan kelembagaan kiai. Meski kata para pengritiknya, ajaran spiritual Islamnya di sini kurang kental. Tapi dengan bekal kemampuan berbahasa Arab dan Inggris, bukankah itu bisa dipelajari sendiri oleh santrinya? Julizar Kasiri, Sitti Nurbaiti, dan Zed Abidien (Surabaya)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini