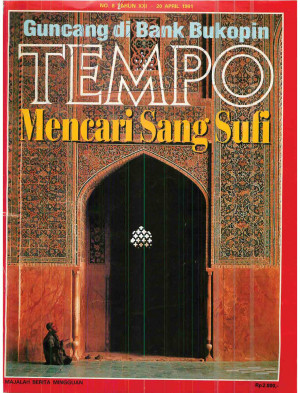Seratusan WNI dari Aceh mendarat di Malaysia, dan minta diterima sebagai pengungsi. Menurut Menlu Alatas, mereka imigran gelap biasa. PERDEBATAN soal imigran gelap asal Indonesia pekan ini kembali mewarnai koran-koran Malaysia. Yang dipersoalkan: pendaratan sejumlah warga negara Indonesia asal Aceh di Pulau Pinang, daerah utara Semenanjung Malaysia itu. "Kami masih belum bisa memastikan motif mereka memasuki negara ini secara haram," komentar Deputi Menteri Dalam Negeri Malaysia, Megat Junid. Sudah hampir satu bulan rombongan pendatang itu mendekam di karantina kantor imigrasi Pulau Pinang. Jumlah yang datang pada 15 Maret itu, menurut laporan wartawan TEMPO di Malaysia, ada 52 orang (16 di antaranya wanita, dan 11 anak-anak). Disusul 32 orang pada 4 April. Dua rombongan asal Aceh itu mendarat di Teluk Bahang (Pulau Pinang), dengan menggunakan sebuah tongkang nelayan. Karena datang pada dini hari, mereka dicurigai penduduk setempat yang kemudian melapor ke polisi. Tiga jam kemudian, polisi datang menginterogasi mereka. Tapi tak lama, polisi menyerahkannya pada imigrasi. Alasannya, mereka datang untuk minta perlindungan sebagai pengungsi. "Kalau kami dipulangkan, kami pasti akan dibunuh," tutur sebuah sumber imigrasi, mengutip alasan mereka. Tentu saja pihak imigrasi kebingungan karena selama ini tak satu pun ada pendatang asal Indonesia yang meminta status seperti itu. Kebingungan imigrasi bertambah, ketika pada 7 April datang laporan baru: ada 28 orang lagi pendatang dari Aceh mendarat di pantai Kuala Kedah, Negara Bagian Kedah dengan alasan sama. Jumlah keseluruhan, menurut sumber imigrasi Malaysia, ada 112 orang. Pada mulanya, imigrasi tak mau menerima alasan pendatang. "Itu alasan yang dicari-cari agar bisa diizinkan tinggal di Malaysia." Namun, orang-orang itu terus bersikeras, dan bertekad lebih baik mati di Malaysia daripada pulang. Malah menurut sumber TEMPO di kantor imigrasi itu, para pendatang sudah mengontak kantor PBB urusan pengungsi (UNHCR), untuk mendapatkan status pengungsi. Segera saja pihak imigrasi Malaysia menelepon Konsulat RI Pulau Pinang, memberi tahu permintaan yang dianggap aneh itu. "Sebagai negara bukan penanda tangan Konvensi Jenewa, sebenarnya kami tak ada kewajiban memberi tahu. Tapi, sebagai negara sahabat yang punya hubungan istimewa, kami merasa itu suatu kewajiban moral," tutur sumber TEMPO di kantor imigrasi Malaysia. Cerita pendatang Aceh itu kemudian cepat meluas. Apalagi setelah Reuters dan koran setempat memberitakan. Reaksi pro dan kontra tentang status mereka bermunculan. Organisasi Wisma Putera menganggap pendaratan tanpa izin itu sebagai "imigran gelap". Sebaliknya, dua organisasi lain -- Angkatan Belia Islam Malaysia dan Persatuan Kebangsaan Mahasiswa Islam -- justru meminta agar orang Aceh itu diakui sebagai pengungsi. Pemerintah Malaysia sendiri menjadi serba kikuk. "Untuk bisa memastikan apakah mereka pengungsi politik atau ekonomi, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan screening pada mereka," ujar seorang pejabat. Megat Junid sendiri, yang kementeriannya membawahi imigrasi, polisi, dan penjara, lebih tegas sikapnya: "Kami tak mau terlibat urusan dalam negeri negara sahabat," katanya, seperti dikutip Berita Harian dan The Star. Bahwa mereka tak diusir, katanya, semata karena pertimbangan kemanusiaan. "Apalagi di antara mereka ada wanita dan kanak-kanak yang datang secara aman." Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Soenarso Djajusman, menyatakan siap memberi bantuan jika pemerintah Malaysia berkeinginan untuk mendeportasikan pendatang dari Aceh itu. "Saya sudah menghubungi Jakarta, dan Jakarta setuju," katanya. Senin pekan lalu, hasil pembicaraan disampaikan pada Kementerian Luar Negeri Malaysia. Menyinggung permintaan status pengungsi seperti yang diinginkan pendatang Aceh itu, Soenarso tak mau menjawab. "Itu adalah hak penuh pemerintah Malaysia untuk menentukannya." Sten Bronee, Kepala Kantor UNHCR Kuala Lumpur, membenarkan bahwa yang berhak menentukan status adalah negeri mana orang itu minta perlindungan. Tugas kami melindungi dan memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka yang melarikan diri dari negaranya, karena korban konflik dan pelanggaran hak asasi manusia," katanya. Dalam kasus orang Aceh itu, UNHCR hanya bisa memberi saran pada pemerintah Malaysia, kalau mau mendeportasi, "hendaknya setelah statusnya jelas, bukan pengungsi politik," kata Bronee. Diakui oleh Bronee, ihwal pendatang Aceh itu sudah ia bicarakan dengan pemerintah Malaysia. Namun, ia menolak memberi tahu hasil pembicaraan itu, "karena kami telah berjanji tak akan membeberkannya terlebih dulu pada pers," katanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, kepada TEMPO menyatakan, Deplu kini tengah mengupayakan perundingan dengan pemerintah Malaysia. Menurut Alatas, jumlah pendatang Aceh itu hanya 83 orang, yang datang dua gelombang. "Mereka itu illegal immigrants, masalah penyeberangan biasa. Saya yakin, masalahnya bisa diselesaikan lewat saluran diplomatik." Mengalirnya pendatang asal Aceh ke Malaysia, menurut Alatas, bukan gejala baru. "Orang Aceh yang menyeberang ke Penang itu sudah bertahun-tahun. Polanya sama, hanya sekarang masalahnya diperbesar oleh beberapa pihak." Alatas tak menyangkal adanya interpretasi yang mengaitkan masalah ini dengan kekacauan di Aceh. "Tapi faktanya, mereka adalah penyeberang tanpa izin. Dan dulu pun sering terjadi," katanya. Ihwal jumlahnya yang cukup besar, Ali Alatas juga tak kaget, karena sejak dulu pun, katanya, jumlah penyeberang asal Aceh sudah banyak. "Pembicaraan dengan Malaysia masih berlangsung, belum ada spesifikasi. Dalam beberapa waktu lagi barangkali akan jelas masalahnya." Alatas berjanji masalah itu akan diselesaikan secara bilateral dengan sebaik-baiknya ARM, Liston P. Siregar (Jakarta), Ekram H. Attamimi (Kuala Lumpur)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini