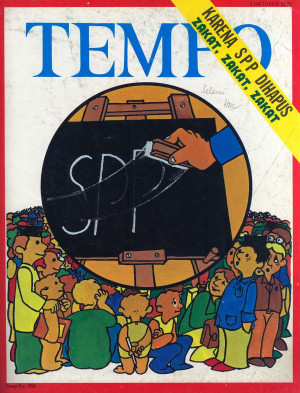SEBUAH oplet tua yang dihadang serombongan pelajar di Lapangan
Banteng, Jakarta, ditulisi kapur: SPP Gila. Beberapa di
antaranya berteriak: "SPP, Surat Pemerasan Pendidikan".
Sementara Prof. Bachtiar Rifai, waktu itu Dirjen Pendidikan
(sekarang ketua LIPI) memberikan alasan berlakunya SPP, karena
anggaran biaya pendidikan tidak memadai. "Orang tua terpaksa
menjadi sapi perahan", katanya. Itu terjadi di tahun 1971,
lahirnya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)
Lima tahun kemudian, 16 Agustus 1976 di depan sidang DPR,
Presiden dalam pidato kenegaraannya antara lain memutuskan
menghapuskan SPP, untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD yang
akan berlaku mulai tahun depan."Ini langkah kecil, tapi punya
arti besar", ucap Presiden. Kecil, karena beban orang tua baru
sebagian kecil yang dapat diringankan. Besar karena keputusan
itu merupakan langkah menuju ke arah pelaksanaan UUD pasal 31:
setiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal itu,
demikian Presiden, telah memberi isyarat bahwa dalam jangka
panjang negaralah yang harus menyediakan pendidikan secara
cuma-cuma kepada warganegaranya. "Tapi itu belum mungkin
terwujud seluruhnya sekarang. Kita akan mengarah ke sana",
tambah Presiden lagi.
Bagi banyak orang, keputusan Presiden yang datangnya seperti
mendadak itu memang cukup mengejutkan. Dan sekaligus
menggembirakan fihak orang tua tentunya. Sebab selama hampir 6
tahun dengan SPP, peraturan yang mewajibkan fihak orang tua
turut menyumbangkan uang untuk pendidikan anak-anaknya itu,
hampir selalu ricuh. Padahal, ketika Menteri Mashuri pertama
kali memperkenalkan peraturan itu jelas tak bermaksud buruk.
Katanya SPP yang disusun berdasarkan aas keadilan itu, selain
dimaksudkan untuk menggalang partisipasi yang harmonis antara
komponen penanggung jawab pendidikan, yaitu orang tua,
masyarakat dan pemerintah, juga dimaksudkan untuk melindungi
orang tua murid dari pelbagai macam pungutan yang sangat
memberatkan pada waktu penerimaan murid baru. Justru di saat
para orang tua murid berada dalam posisi yang amat lemah: perlu
bangku sekolah buat anak-anaknya.
Betulkah lantas orang tua murid terhindar dari pemerasan?
Mengambil contoh Jakarta, nampaknya maksud baik pemerintah itu
hampir tak pernah mencapai sasarannya. Aas keadilan,
keseimbangan dan perataan, sering terasa tak adil. Sebab kadang
terdapat anak orang tua yang berpenghasilan rendah dengan anak
orang tua yang berpenghasilan tinggi, membayar SPP yang sama
jumlahnya. Juga timbul kericuhan, siapa dan bagaimana mengontrol
pendapatan orang tua murid? Kelemahan seperti itu tak jarang
hanya mengundang "oknum" guru untuk menambah penghasilannya.
Sementara orang tua ramai-ramai berusaha menghindarkan bayar
SPP.
Hampir setiap tahun ajaran baru, soal SPP ini tetap tak pernah
selesai. Karena itu barangkali, dua tahun lalu, Menteri P & K
Sjarif Thajeb melakukan penyempurnaan SPP. Dengan optimis
menteri ini menyebutkan kelebihan dari SPP yang disempurnakannya
dibanding dengan SPP lama. SPP yang mulai berlaku pada tahun
pelajaran 1975 itu katanya diterapkan prinsip flate rate:
besarnya pungutan untuk semua wajib bayar pada satu atau semua
sekolah dalam satu daerah disamakan. Variasi tarif yang terbagi
dalam kategori yang ditetapkan potongan 50% sampai kepada yang
bebas SPP, dimaksudkan untuk memberi keringanan kepada wajib
bayar yang tidak atau kurang mampu. Tak lupa dicantumkan
larangan keras bagi sekolah untuk melakukan pungutan lain di
luar SPP. Kemudian bersamaan dengan keluarnya SPP baru,
pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk pembemtukan Badan
Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Tugasnya, antara lain
mengusahakan bantuan masyarakat baik berupa benda, uang, maupun
jasa dengan tidak menambah beban wajib bayar.
Namun dalam pelaksanaannya SPP baru itu tetap masih mengundang
penyempurnaan lagi. Peraturan hasil keputusan Menteri P & K,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan itu toh nyatanya tak
praktis. Sekolah mengeluh, karena hasil SPP mesti disetor dulu
ke bank, susah untuk diambil lagi untuk keperluan sekolah. Itu
saja sudah melahirkan lagi keputusan. Menteri P & K yang baru,
berisi pemberian wewenang penuh kepada Kepala Sekolah SD untuk
menggunakan bagian SPP sebesar 50% (yang lain, berdasarkan
peraturannya, 30O untuk Kesejahteraan Personil Sekolah, 10%
masing-masing untuk pos Perbaikan Sarana dan Kegiatan, dan
Supervisi dan Pengelolaan SPP) untuk pos Penyelenggaraan
Sekolah, tanpa menyetorkan dulu ke Bank. Penyempurnaan itu
berlaku untuk tahun pelajaran 1976 ini.
SPP nampaknya memang lebih banyak merepotkan ketimbang membantu
kelancaran pendidikan. Selain menambah beban orang tua dan guru
-- karena harus mengurus SPP, sebenarnya biaya yang diperoleh
dari pos ini pun "tak ada sepersepuluhnya dari seluruh biaya
pendidikan", ujar Prof Dr. Setijadi, Ketua Badan Pengembangan
dan Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (BP3 K). Karena itu
keputusan Presiden untuk menghapus SPP kelas 1 sampai dengan
kelas 3 SD, menurut Setijadi, pengaruhnya terhadap biaya
pendidikan tak akan terlalu besar. Diperkirakan akibat
penghapusan itu, uang yang hilang berjumlah Rp 3 milyar lebih,
yang berasal dari kira-kira 60% murid SD tersebut.
Namun Setijadi mengakui: Jumlah uang SPP itu walaupun kecil,
bagi sekolah-sekolah yang bersangkutan memiliki arti yang sangat
besar. Bukan saja untuk pos Penyelenggaraan Sekolah, misalnya
keperluan sehari-hari yang mendadak seperti kapur atau genting
bocor. Tapi di beberapa daerah misalnya Jakarta SPP bagi guru
merupakan salah satu sumber tambahan penghasilan. "Sangat besar
artinya buat guru-guru itu", ujar Setijadi "tapi saya kira
pemerintah tidak akan sembarang menghapus SPP, kalau belum
difikirkan penggantinya". Belum secara jelas disebutkan,
bagaimana bentuk pengganti SPP yang bakal hilang itu. Namun
Setijadi menunjuk bagian pidato Presiden yang menyebutkan bakal
adanya perbaikan gaji pegawai negeri mulai tahun depan. "Ada
kenaikan gaji guru dan tambahan biaya operasionil", katanya.
Sementara Basyuni Suryamihardja, Ketua PGRI, juga mengharapkan
agar gaji guru dinaikkan. "Karena dengan SPP, pada prinsipnya
PGRI tidak setuju guru dapat bantuan dari orang tua", katanya.
Ketua PGRI itu dari dulu kurang setuju dengan SPP. "Kalau memang
ingin mendemokrasikan tanggung jawab pendidikan pada masyarakat,
Pajak Pendidikan semacam pajak radio misalnya, lebih baik dari
pada SPP", ujar Basyuni. Dan bentuk pajak pendidikan ini
nampaknya disokong oleh banyak kalangaa, seperti Ki Suratman,
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Mohamad Said dari Taman Siswa dan
Sayuti Melik, anggota DPR. Tapi kongkritnya bagaimana? "Belum
ada konsep, baru gagasan saja", ujar Basyuni.
TENTU saja belum pasti, apakah setelah SPP hapus semua, maka
biaya pendidikan dari masyarakat akan dilahirkan dalam bentuk
pajak pendidikan. Yang jelas seperti yang dikatakan Presiden,
keputusan menghapus SPP itu akan dapat mendorong pelaksanaan
kewajiban belajar. "Karena orang tua yang tidak mampu bayar SPP
telah dapat kita singkirkan sebagian", katanya. Itu pun dengan
pembangunan SD-SD Inpres dan perbaikan ribuan gedung sekolah,
pada akhir Pelita II nanti pemerintah baru mentargetkan sekitar
85% anak usia SD yang bisa tertampung. Karena memang akibat
penghapusan SPP itu, pengaruhnya terhadap kenaikan jumlah anak
yang masuk sekolah SD tak terlalu besar. Setijadi menaksir
hanya akan ada kenaikan, 1 sampai 2%. "Penghapusan SPP itu tidak
semata-mata dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah anak yang
masuk sekolah SD, tapi bagaimana agar mereka yang sudah di
bangku SD bisa menyelesaikan pelajarannya sampai tamat", ujar
Setijadi. Angka putus-sekolah di tingkat sekolah ini, memang
bukan main besarnya. Hanya kira-kira 40% yang berhasil
menyelesaikan sekolahnya sampai kelas VI SD. Selebihnya putus di
tengah jalan. Padahal, demikian Setijadi, sampai saat ini
diperkirakan sudah 90% anak usia SD yang pernah mengecap bangku
sekolah. Namun tak sedikit yang keluar lagi dengan bermacam
alasan, terutama di desa. Seperti bekerja dengan orang tuanya,
atau memang tidak kuat bayar SPP. Jumlah golongan yang terakhir
itu belum ada data penelitian. Namun yang pasti angka putus
sekolah yang tertinggi terdapat pada anak-anak kelas IV SD.
Lebih dari 15% berguguran di kelas ini.
Memang di daerah pedesaan, selain angka putus sekolah tinggi,
SPP meskipun sudah disempurnakan oleh Menteri P & K, hampir tak
bermanfaat. Bukan saja dari fihak orang tua itu tidak bisa
diharapkan terkumpul uang buat biaya pendidikan, tapi bagi fhak
guru pun hanya menambah beban pekerjaan saja. Di samping ekses
buruk yang sering terjadi di sekitar penggunaan uang SPP.
Menurut Waryo Sukanda, Ketua I PGRI Jawa Barat, SPP di daerah
menjadi beban guru. SPP yang mesti disetor pada waktunya, karena
banyak orang tua yang menunggak, untuk menutupinya terpaksa
gaji guru dipotong. Uang yang disetor ke Kabupaten, susah turun
kembali. Padahal kegiatan administrasi sekolah harus berjalan
tiap hari. Untuk itu guru terpaksa iuran untuk menutupi ongkos
sehari-hari sekolah. "Karena itu SPP pos Kesejahteraan Personil
Sekolah tidak bisa diharapkan", ujar Waryo, "dan ada atau tidak
ada SPP bagi daerah sama saja".
Di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah murid SD yang tertampung
sebanyak 218 ribu lebih (tidak tertampung menurut data tahun
1975 sebanyak 200 ribu lebih) SPP di desa rata-rata Rp 25
(duapuluh lima rupiah). "Rata-rata karena faktor ekonomi lemah",
ujar drs Syahruddin, Wakil Kepala Dinas P & K Propinsi NTB.
Kebanyakan orang tua murid bekerja sebagai petani penggarap yang
jarang punya uang kontan. "Apalagi kalau dibebani lagi dengan
pungutan semacam PMI, beli buku atau baju pramuka", ucap
Syahruddin lagi. Dan ekonomi lemah itu masih ditambah oleh sikap
masyarakat di sana yang pesimis terhadap hasil sekolah dan masa
depan anaknya. "Biar anak saya jadi petani saja membantu saya di
sawah. Kalau sekolah juga, kalau tamat belum tentu dapat
pekerjaan di kantor", ujar Amaq Munirah, petani penggarap miskin
dan buta huruf. Amaq punya tiga anak, yang kecil 9 tahun. Hanya
anak tertua yang pernah sekolah sampai kelas 2 SD. Amaq dan
banyak orang tua di daerah yang banyak memasukkan anak-anak ke
sekolah Madrasah itu, tak tahu SPP.
Di Sulawesi Tengah, faktor yang serupa berpengaruh terhadap SPP.
Sejak jatuhnya harga kopra dan kayu, penghidupan di daerah ini,
lesu. Di beberapa kabupaten, Donggala misamya SPP yang tadinya
Rp 200 karena seret ditagih, turun jadi Rp 100. Di Bada,
Kabupaten Poso, SPP yang asalnya Rp 150 turun jadi hanya Rp 50.
Dan tidak jarang walaupun menurut peraturannya SPP harus dibayar
dengan uang -- banyak orang tua yang membayar SPP dengan telur,
ayam atau ubi, yang tak mudah dijual. Sementara tagihan terhadap
orang tua yang menunggak banyak berakibat psikologis bagi
anak-anaknya. Bila tiga kali saja dilakukan penagihan,
"anak-anak akan jadi takut sekolah" ujar Abubakar Makarau,
Kepala Dinas P & K Sulteng. Di daerah ini bahkan pernah kejadian
ada uang SPP yang terpakai untuk kepentingan tugas rutin camat.
Dan menurut pembantu TEMPO di sana, Bupati Banggai dengan
mempergunakan uang SPP telah melakukan kontrak untuk membeli 200
set gambar peraga dengan harga Rp 20 ribu. Padahal di Surabaya
atau Ujung Pandang misalnya, barang yang sama bisa dibeli dengan
harga Rp 4 ribu. Sehingga uang Rp 4 juta yang dikumpulkan dengan
susah payah dari fihak orang tua, habis sama sekali.
Di Sumatera Utara, penyelewengan uang SPP juga terjadi. Jaksa
Mohamad N Pane di Kabupaten Asahan sejak pertengahan Agustus
kemarin, memulai tugasnya memeriksa uang SPP di 15 Kecamatan
itu yang nyangkut di 4 pos: wali murid, guru-guru kelas, Kepala
SD dan Dinas P & K Kecamatan. Menurut koresponden TEMPO di
Medan, uang SPP itu telah digunakan untuk kepentingan
pribadi-pribadi yang duduk di pos-pos itu. Dengan janji akan
dibayar dengan pemotongan gaji bulan berikutnya. Tapi ternyata
tak lunas juga hingga tak dapat disetor ke bank. Dana sebesar
lebih Rp 5 juta itu jadi beku. Kabarnya kasus Asahan itu
menyebabkan banyak guru dengan diam-diam agak berat hati juga
bila SPP dihapuskan. Beberapa sumber menunjukkan, ada guru yang
menggunakan uang SPP untuk beli Honda atau bikin betul rumah.
Di samping yang jahil-jahil terhadap uang SPP, masih banyak juga
pengajar yang mau berkorban. "Di Kalimantan Timur antara
tenaga yang keluar dengan hasilnya tak sebanding", ujar drs
Abibaswan Hanafie, Asisten I pada Dinas P & K Kaltim. Sehingga
menurut drs Serta Tarigan, Kepala Kanwil P & K disana, SPP di
daerahnya praktis tak jalan. Sehingga penghapusan SPP, praktis
tidak ada pengaruhnya. Lagi pula bagi daerah, SPP memaksa guru
untuk bekerja di luar bidangnya. Seperti yang kejadian di daerah
Yogyakarta, karena tidak menguasai soal pembukuan, pegurusan
SPP menjadi acak-acakan. Sehingga salah-salah nama baik guru
yang bersangkutan bisa jatuh. Menurut S. Haripoernomo, Kepala SD
Lempuyangan II, guru menerima Rp 3 ribu setiap triwulannya. Itu
pun kalau bayaran dari orang tua murid jalannya lancar. Kalau
tidak, untuk memenuhi kewajiban setor itu, guru nombok dulu
dari kantong sendiri.
Lagi lagi di Irian Jaya. Di sana, selain SD negeri yang swasta
pun ternyata dikenakan SPP, misalnya di Kabupaten Jayapura. Tapi
Rp 15 juta yang diharapkan datang, ternyata cuma terkumpul Rp 3
juta per tahunnya. "Itu pun pemungutannya seret", ujar
Kisdiparno Kepala Sekolah. Namun begitu, SPP menurut M. Tegai,
Kepala Dinas P & K Kabupaten Jayapura, tetap diperlukan. "Tapi
kalaupun dihapus, perlu ditingkatkan kerjasama antara guru dan
BP3", ucap Tegai.
Tapi bisakah dengan penghapusan SPP, BP3 dimanfaatkan untuk
menambah dana pendidikan? Di beberapa daerah badan yang
tujuannya antara lain memang mengusahakan bantuan dari
masyarakat berupa benda, uang maupun jasa itu, ada yang
berhasil. Di Pulau Nias misalnya badan itu sudah berhasil
membangun gedung SD dengan cara menyediakan tanah, kayu atau
batu kerikil. Di Sukajadi, Bandung, BP3 setempat berhasil
menambah lokal sekolah, membuat sumur dengan mengumpulkan
donatur yang tidak mengikat. Namun tentu saja usaha yang telah
dijalankan oleh badan tersebut belum menjamin dana bakal masuk
secara rutin. Bahkan, selain belum semua sekolah berhasil
membentuk BP3, kordinator tingkat propinsi yang seharusnya
menurut peraturan sudah terbentuk Oktober tahun lalu, kebanyakan
daerah belum memilikinya. "Di tingkat sekolah saja sudah sulit
bergerak, apa lagi tingkat propinsi", ujar sebuah sumber di
Jakarta mengenai BP3 di daerahnya. Pernah ada sebuah sekolah
yang ingin mendirikan CV. Tapi ditolak Kanwil. "Sebab, memangnya
sekolah mau disuruh dagang", ucap sumber tersebut. Kebanyakan
sekolah di Jakarta BP3-nya aktif dalam kegiatan pertunjukan
amal, misalnya pemutaran film. "Tapi apa kegiatan itu bisa
dilakukan tiap bulan sehingga dana bisa dipungut secara rutin?
"Kadang-kadang untuk sebuah pertunjukan amal, terpaksa kita
giring murid-murid sendiri buat menontonnya", tambah sumber itu.
Di tengah macetnya pelaksanaan SPP dan BP3, keputusan Presiden
untuk menghapus SPP itu, selain disambut oleh banyak fihak, ada
juga yang keberatan. Jakarta misalnya. Dengan adanya SPP saja
kota itu mengalami defisit sampai 500. Maka dengan hapusnya SPP
kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, diperkirakan setiap tahunnya
Jakarta akan kehilangan Rp 1 milyar. "Kalau anggota DPR,
masyarakat dan pers bertepuk tangan menanggapi hal itu, maka
saya hanya bisa urut dada", ujar Ali Sadikin. Gubernur yang satu
ini, memang sudah sejak awal tahun bahkan minta agar
diperkenankan bikin SPP khusus untuk daerahnya. Tapi ditolak
oleh Pusat.
Dengan hapusnya SPP, kecuali ucapan Presiden yang menyinggung
kenaikan gaji tahun depan, belum jelas benar dengan apa
pemerintah akan mengganti dan yang hilang itu. Menteri Sjarif
Thajeb sendiri mengakui, akibat penghapusan itu, daerah
kekurangan pendapatan. Namun, katanya, itu tidak banyak dan bisa
ditampung dengan anggaran daerah. Lagi pula, menurut menteri
itu, P & K memiliki saldo SPP tahun lalu, beberapa milyar
rupiah, yang bisa dibagikan: 50 untuk kegiatan SPP, 30% untuk
gaji guru dan 10% untuk survei dan kegiatan lain. Sementara
team untuk mencari usaha penanggulangan akibat hapusnya SPP itu
segera dibentuk. Di depan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR,
Menteri ada juga menyebutkan kemungkinan merubah komposisi
prosentase SPP. Artinya kelak bisa saja bagian untuk guru (SPP
sekarang bagiannya 30%) diperbesar. Atau sebaliknya?
Namun segera Ali Sadikin mengeritik Menteri Sjarif Thajeb.
"Mestinya ketika Presiden bilang dalam pidato 16 Agustus bahwa
SPP akan dihapus, Menteri sudah memikirkan apa yang bakal
terjadi", ujar Ali. "Ini bukan prosedur kerja yang baik. Ini mah
ilmu komandan". Dan Gubernur menyebutkan keheranannya. "Yang
hapus mereka, yang tanggung risikonya kok Kepala Daerah"
katanya, "yang benar saja, kehilangan Rp 1 milyar karena
hapusnya SPP kok masuk APBD. Kenapa tidak masuk dalam APBN?"
Kesal gara-gara SPP, Gubernur Ali Sadikin yang bakal habis masa
jabatannya tahun depan itu, langsung kirim surat ke Menteri P &
K, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Katanya,
Pemerintah Pusatlah yang mesti menutup defisit biaya pendidikan
di daerahnya. "Saya mau ngomong tentang kekurangan ini, karena
saya butuh. Saya tidak mau menanggungnya", ujar Ali tegas. Ali
Sadikin memang berpendapat, sekolah tak mungkin gratis sekarang
ini (lihat box ).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini