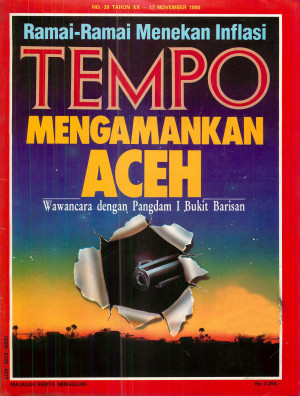INI mungkin hanya bisa dijumpai di Pasar Lhokseumawe. Harga-harga barang kebutuhan pokok yang dijajakan di sana bisa berubah-ubah secara mendadak. Pada hari-hari tertentu pada pagi hari, harga-harga di pasar mendadak bisa melejit. Ikan kembung, misalnya, yang biasa dijual Rp 1.500/kg, tiba-tiba naik menjadi Rp 3.000/kg. Itu terjadi bila para penghuni kompleks permukiman industri yang merebak di sekitar Lhokseumawe datang berbelanja. Para pedagang kontan menaikkan harga dagangannya. Harga-harga yang mahal itu akan kembali normal setelah matahari mulai meninggi. Maka, seperti yang diungkapkan Bupati Aceh Utara H. Ramli Ridwan, tak heran kalau kebanyakan warga di daerahnya lebih suka ke pasar pada siang atau sore hari -- seusai penghuni kompleks berbelanja ria. Warga yang mendiami sejumlah kompleks permukiman di kawasan industri itu memang sering dituding sebagai "perusak harga pasaran" bagi masyarakat di sekitar Lhokseumawe. Penghasilan para pekerja di sektor industri memang jauh lebih besar daripada penduduk lokal, yang hanya mengandalkan dari sektor pertanian. Bahkan ada pekerja sektor industri yang mendapat gaji dengan perhitungan mata uang asing. Akibatnya, para pemilik toko di Lhokseumawe jadi terbiasa menggunakan standar harga sesuai dengan kantung para penghuni kompleks industri tadi. Tentu saja harga jual tadi tak dapat dijangkau oleh penduduk lokal. "Mungkin, ini salah satu faktor yang menyebabkan warga Lhokseumawe tak suka melihat kehadiran pendatang yang bermukim di kompleks industri," tutur seorang mahasiswa di Medan yang berasal dari Lhokseumawe. Di sekitar Lhokseumawe memang berdiri sejumlah industri raksasa yang mulai tumbuh sejak awal 1970-an. Seperti PT Arun (industri pertambangan gas alam cair), Mobil Oil Indonesia Inc. (pertambangan minyak), PT Aceh ASEAN Fertilizer (pupuk), PT Pupuk Iskandar Muda (pupuk), dan PT Kertas Kraft Aceh (industri kertas semen). Kalau dihitung-hitung, total investasi dari kelima industri raksasa itu kini sudah mencapai puluhan milyar dolar. Sedangkan tenaga kerja yang diserap lebih dari 6.000 orang. Maka, seperti yang diungkapkan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan, 75-% kehidupan Aceh bergantung pada Aceh Utara, tempat bercokolnya sejumlah proyek vital tadi. Maka, untuk banyak masyarakat Aceh, Lhokseumawe -- ibu kota Kabupaten Aceh Utara -- mendapat julukan kota "sejuta harapan". Seperti semut yang mengerubungi gula, para pencari kerja berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru di Aceh -- bahkan ada yang dari luar Provinsi Aceh -- "menyerbu" Lhokseumawe. Bupati Aceh Utara H. Ramli Ridwan menjelaskan, tumbuhnya industri di kawasannya membawa dampak "perubahan yang mendadak" buat penduduknya. Maklum, sebelumnya masyarakat di sana dikenal sebagai masyarakat agraris. Kini mereka "dipaksa" hidup dalam suasana yang industrialis, yang serba wah. Padahal, kondisi masyarakat di sana tak siap. Bagaimana ketaksiapan masyarakat di sana barangkali bisa dilihat dari hasil penelitian di Lhokseumawe pada 1967 oleh pakar sosiologi Bahrein T. Sugihen, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Salah satu temuannya yang mengagetkan: masyarakat di sana ternyata banyak yang belum pernah melihat lembaran uang Rp 10.000. Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun itu, taraf kehidupan ekonomi masyarakat di sana memang masih rendah. Bahkan sekolah teknik tingkat menengah saja, pada pertengahan tahun 1970-an itu, tak ada di kawasan Kabupaten Aceh Utara. Akibatnya, para kontraktor di sana terpaksa mendatangkan tenaga kerja dari luar Aceh. Kesenjangan memang tampak semakin mencolok. Seperti pemakaian air dan listrik oleh kompleks industri dianggap terlalu melimpah ruah -- boleh jadi memang untuk memenuhi kebutuhan proses produksi. Rata-rata pemakaian air buat keperluan industri besar itu mencapai lebih dari 70 ribu meter kubik per hari. Sedangkan kapasitas listrik yang dimiliki total hampir mencapai 250 megawatt. Sebaliknya, masyarakat di sekitar sana sebagian besar masih belum bisa memanfaatkan kehadiran PLN. Begitu juga PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tampaknya masih kewalahan untuk melayani permintaan air bersih buat warga setempat. Dengan keterbatasan dan kesenjangan seperti itu, sosok Lhokseumawe mendadak berubah wujud menjadi "metropolis" untuk memenuhi kebutuhan para industrialis. Sebuah kota yang tiba-tiba semuanya harus serba gemerlapan. Dan gaya hidup konsumtif pun hinggap dan pelan-pelan mulai merebak di sana. Sejumlah pasar swalayan bermunculan. Kehidupan malam pun di sana menjadi semakin semarak. Seperti pada suatu malam di akhir Oktober 1990 silam, kendati hujan mengguyur lebat, diskotek di Hotel Lido Graha tetap sarat dikunjungi peminatnya yang getol berjoget. Juga "warung remang-remang" seperti kedai "Molek" yang menyediakan minuman keras dan teman kencan tampak dipadati pelanggan-pelanggan hidung belang. Tingkat kejahatan juga tiba-tiba melonjak drastis. Pada 1987, misalnya, terdapat 134 kasus pencurian dengan pemberatan. Tahun lalu angka kejahatan serupa naik menjadi hampir empat kali lipat: 400 kasus. Juga soal penganiayaan, tiga tahun yang lalu dijumpai ada 95 kasus. Pada tahun silam, kasus itu meningkat hampir dua kali: lebih dari 197 kasus. Di kota berpenduduk 150.000-an orang ini, berbaur juga para pencari kerja (yang belum tentu penganggur), yang ditaksir jumlahnya mencapai 35.000 orang. "Berarti sekitar 70 persen dari seluruh pencari kerja di Aceh, yang jumlahnya hampir 50 ribu orang," kata Soemardi, staf Kanwil Departemen Tenaga Kerja Aceh. Dari jumlah para pencari kerja tadi, hanya sekitar 3.000 yang mengantungi ijazah sarjana. Sisanya sebagian besar adalah lulusan SLTA atau yang setingkat. Tak cuma Lhokseumawe yang berubah wujud. Kota-kota sepanjang pesisir timur dan utara Aceh lainnya juga ikut bersolek. Sederet industri menengah lainnya ikut menjamur. Apalagi di wilayah ini ada jalan raya mulus yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Jalan inilah yang menjadi urat nadi perekonomian Aceh. Memang sejak semula skenario pembangunan di Aceh direncanakan terbagi dua, yaitu zone industri di belahan utara dan timur Provinsi Aceh, dan zone pertanian dikembangkan di belahan barat, tengah, dan selatan Provinsi Aceh. Namun, para pencari kerja di Aceh tampaknya lebih melirik pada zone industri. Akibatnya, sekitar 65% dari penduduk Aceh yang jumlahnya lebih dari 3 juta jiwa itu berdiam di pesisir utara dan timur. Sedangkan sisanya tersebar di tempat lainnya. Maka, kepadatan penduduk di zone industri mencapai 105 jiwa/km2, dan di zone pertanian 29 jiwa/km2. Ironisnya, pertanian di Aceh justru banyak dihasilkan di kawasan zone yang semula dikembangkan untuk industri (TEMPO, 30 Juni 1990). "Produsen beras terbesar di Aceh adalah di Kabupaten Aceh Utara," kata Muzakir Ismail, staf Bappeda Aceh. Maka, ketimpangan itulah yang membuat wajah Aceh kini menjadi buram. Banyak yang mengaitkan munculnya tindak kekerasan oleh sekelompok orang di sana akhir-akhir ini, yang kemudian oleh aparat keamanan disebut Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), disebabkan faktor kesenjangan sosial tadi. Hal itu sebenarnya sudah diduga oleh Ibrahim Hasan, 14 tahun yang silam, tatkala ia menyusun laporan penelitiannya yang berjudul "Siasat dan Kebijaksanaan Perencanaan Pembangunan di Aceh". Ketika itu Ibrahim menyimpulkan bahwa ketakseimbangan ini otomatis mempengaruhi kestabilan masyarakat, kehidupan politik, dan ketahanan masyarakat. Apa yang pernah dikhawatirkan itu kini terjadi. Entah kebetulan atau tidak, "ramalan" Ibrahim tadi terbukti benar justru ketika ia menjabat Gubernur Aceh. Akar persoalan dari gejolak sosial yang belakangan muncul di Aceh ini, menurut Ibrahim Alfian, dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, karena terlambatnya pemerintah dalam mengantisipasi pendidikan kejuruan di sana. "Sekolah politeknik mestinya sudah didirikan sebelum pabrik LNG Arun dibangun," katanya. Pada kenyataannya, sekolah politeknik baru berdiri tiga tahun yang silam di Lhokseumawe. "Ini sudah terlambat," ujarnya lagi. Maksud Ibrahim jelas. Memang ada benang merah antara permintaan tenaga kerja di sektor industri dan tingkat pendidikan. Tenaga kerja yang berasal dari Aceh tampaknya tak siap mengisi sektor industri yang tumbuh di daerahnya. Dan industrialis tak peduli, maka jalan pintas yang diambil adalah mendatangkan tenaga kerja dari luar provinsi. Pendidikan (termasuk sarananya) di Aceh memang sempat mengkhawatirkan. Prof. Dr. Ali Hasjmy, Gubernur Aceh (1957-1964), adalah orang yang mencoba memperbaiki ketimpangan ini. Tatkala memimpin provinsi yang mendapat status "Daerah Istimewa" pada 1959 itu, ia dihadapkan kenyataan bahwa hanya ada tiga SMA di Provinsi Aceh. Sedangkan Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, yang ketika itu baru berdiri, hanya memiliki satu fakultas ekonomi dengan 200 mahasiswa. Maka, salah satu programnya ketika itu adalah memprioritaskan pembangunan sarana pendidikan. Beleidnya itu diteruskan oleh sejumlah gubernur penggantinya. Hasilnya memang cukup menakjubkan. Kini, di Aceh sudah berdiri 4.100-an SD dan SMP, serta 196 SMA. Sedangkan perguruan tingginya ada delapan buah dengan total mahasiswa sekitar 8.000 orang. Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dan siswa di Aceh itu, ternyata, tak menjamin angkatan kerja di sana siap pakai. Soalnya, "Kualitas pendidikan yang ada sangat mencemaskan," kata Hasjmy. Bagaimana tidak, banyak sekolah di sana tak diimbangi dengan penyediaan guru yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya. Dan yang lebih memalukan, menurut Hasjmy, guru untuk mengajarkan bahasa Aceh pun hampir tak ada. Mungkin rendahnya kualitas angkatan kerja setempat itulah yang menyebabkan masih banyak tenaga kerja luar yang didatangkan. Dan tampaknya itu bisa menyebabkan kecemburuan dan ketidakpuasan. Lebih-lebih bila ada yang mengipas. Barangkali, karena melihat pengalaman itu, Gubernur Ibrahim Hasan mengambil jalan pintas. Pada 1986, tak lama setelah dilantik menjadi Gubernur Aceh, ia membentuk Yayasan Malem Putra dan mengumpulkan dana Rp 300 juta. Sebagian berasal dari sumbangan tokoh-tokoh dan pengusaha Aceh, antara lain Bustanil Arifin, Ibrahim Risjad, dan A.R. Ramly. Kini, dengan uang itu, sudah 300 pelajar Aceh berbakat yang dikirim untuk belajar ke Universitas Indonesia di Jakarta dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Tentu, di pundak merekalah Aceh kini menaruh sebagian harapannya. Ahmed K. Soeriawidjaja, Irwan E. Siregar, dan Mukhlizardy Mukhtar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini