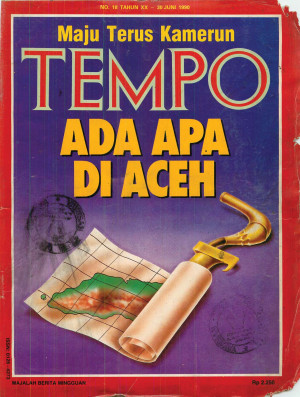ACEH, daerah istimewa RI di ujung barat laut Pulau Sumatera, sudah lama memendam suatu riwayat yang panjang, orang bi- lang, itulah kawasan kaya yang mudah tersulut api ketidakpuasan dan tak jarang meletup menjadi kerusuhan. Kini kerusuhan itu marak lagi dengan munculnya sekelompok orang bersenjata, yang menebar teror berdarah. Adalah Cottage Surya Aceh di Desa Hagu Barat Laut, Lhokseumawe, yang tak urung menjadi ajang kerusuhan. Dini hari di akhir bulan Agustus hampir dua tahun silam, sebuah ledakan keras terdengar dari kompleks penginapan yang memiliki 20 kamar tidur itu. Dua bangunan cottage pun porak-poranda: langit-langitnya jebol, dua AC remuk, dan sebuah lubang menganga di serambi kamar. Pasangan Wandi dan Lili lari terbirit-birit dari salah satu kamar yang meledak. Mereka menjerit-jerit minta tolong. Saat yang sama, Indra dan Vera lintang-pukang meloloskan diri dari kamar sebelah, dengan pakaian "ala kadarnya". Untung ledakan itu tak sampai menelan korban. Bukan rahasia lagi, di "gubuk" ber-AC itulah para pasangan yang bukan muhrim sering melepaskan hasrat masing-masing. Suatu praktek yang diharamkan oleh penduduk sekitar. Siapa pelaku pengeboman belum lagi terungkap. Polisi hanya me- nemukan kabel yang menjulur 40 meter. Satu ujung ada dekat dinding tembok yang hancur, ujung yang lain bersembunyi di bawah pohon mangga, di pinggir kuburan. Di situ dijumpai pula dua buah batere 6 volt, kaus tangan, dan detonator. Jauh sebelumnya hampir semua instansi pemerintah di Lhokseumawe menerima surat kaleng. Isinya, memprotes kehadiran Cottage Surya Aceh, yang dituding sebagai sarang pelacuran. Pemda sendiri, ketika itu, meminta agar pemilik cottage menutup usahanya, untuk sementara waktu, tapi tak digubris. Aparat keamanan di Lhokseumawe kembali disibukkan dengan keributan baru 10 Maret 1989 lalu. Sekitar 8.000 massa mengobrak-abrik arena oriental Sirkus Indonesia di Lapangan Hirak, di Desa Simpang Empat. "Bakar! Bakar! Bakar . . . !" teriak mereka. Mula-mula massa menjebol dinding arena pertunjukan dan melempar batu ke panggung. Lantas, entah siapa yang menyulutnya, tiba-tiba sebuah truk milik rombongan sirkus terbakar. Juga dua mobil pikap mereka remuk. Huru-hara bermula dari pertengkaran Yahya, 25 tahun, dengan penjaga loket. Pemuda setempat yang bertubuh gempal itu kesal lantaran merasa tak dilayani ketika mau membeli karcis. Dia bahkan merasa dituding sebagai calo. Tuduhan itu dibalas dengan bogem mentah oleh Yahya. Perkelahian terjadi. Penjualan karcis terhenti. Massa, yang antre dan berdesak -desak, mulai mendorong-dorong pagar besi hingga roboh. Keributan baru usai setelah tiga peleton polisi dikerahkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, syukur. Letupan itu hanya gara-gara tak sabar antre karcis? Rasanya tidak. Kehadiran sirkus itu sebelumnya telah membuat tokoh-tokoh masyarakat Desa Simpang Empat berani Lewat kantor Wali Kota Lhokseumawe mereka menuntut agar sirkus itu tak menggelar keramaian pada setiap Kamis malam. Tapi kurang diindahkan. Para pemuka masyarakat juga mengecam cara rombongan sirkus mengundang pengunjung Loud speaker dari arena pertunjukan berkoar keras di tengah suara azan Masjid Baiturrahim, 100 meter dari lokasi sirkus. Pakaian para artis sirkus yang minim ikut jadi gara-gara. Alhasil, pengunjung yang meluber di sekitar arena sirkus seperti menyimpan sikap yang mendua: rasa ingin tahu dan penolakan. Masih di Lhokseumawe, pada 20 Mei 1989, api marak di tempat rekreasi Air Terjun Blang Kolam, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Timur, 22 km dari Lhokseumawe. Panggung hiburan, pos penjaga- an, kios-kios, dan gubuk-gubuk habis dibakar penduduk. Padahal, tempat rekreasi itu baru dua bulan direnovasi menelan Rp 20 juta. Puncak keberangan terjadi ketika penduduk memergoki Meunasa Meucat, gadis setempat, sedang bercintaan dengan seorang pemuda di salah satu gubuk. Keduanya dihajar ramai-ramai sampai babak belur. Soal zina memang jadi perkara peka di Aceh. Sampai-sampai Aji, pemuda 20-an tahun, dan beberapa kawannya, menggerebek kantor Polsek di Idi Cut, juga di Aceh Timur. Gara-garanya, Aji tak senang melihat Sersan Dua Faisal, anggota Polsek itu membawa seorang wanita yang bukan muhrimnya ke markas polisi, di satu sore awal 1988. Faisal pun diseret keluar dan digebuk ramai-ramai. Si perempuan, yang dikenal sebagai wanita nakal, ikut kena gampar pula. Usai "menggarap" pasangan ilegal tadi, para pemuda itu pun kabur. Tapi rupanya, Aji telah dikenali oleh korban. Esoknya dia dipanggil ke kepolisian. Aji pun datang, diiringi puluhan pemuda yang berteriak-teriak, "Bebaskan Aji!" Untung, datang Kapten Nurdin, Danramil setempat. oleh Nurdin, pertikaian Aji- Faisal didamaikan. Aji diwajibkan membayar ganti rugi Rp 25 ribu. Keduanya setuju. Namun, rupanya, perkara itu masih berbuntut. Beberapa bulan kemudian, dua orang polisi tiba-tiba saja menghajar Aji yang sedang berjualan makanan kecil dan minuman. Esoknya, Aji bersama 30-an pemuda mendatangi kantor Polsek. Kebetulan di jalan mereka berpapasan dengan Letnan Dua Pol. Sujasmin, Kapolsek Idi Cut. Tanpa tanya ini-itu, Sujasmin pun dikepung lalu dihujani pukulan dan tendangan. Untung, dia lolos. Para pengeroyok itu pun mengejar ke kantor Polsek. Sampai di depan markas polisi itu, massa pengeroyok berkembang menjadi sekitar 300 orang. Aksi kekerasan itu berlanjut, mereka menyerbu kantor polisi dan membakarnya, setelah sebelumnya membebaskan beber- apa orang tahanan. Kekerasan dalam versi yang unik sempat pula "dipentaskan" oleh pengikut Tengku Bantaqiah, tokoh yang oleh Majelis Ulama Aceh dianggap menyebarkan ajaran sesat. Aksi "kaum" Bantaqiah itu muncul pada bulan Mei 1987 di dua tempat: Sigli (di Kabupaten Aceh Piddie) dan Meulaboh (Aceh Barat). Aksi mereka khas: dengan mengerahkan sejumlah orang berjubah putih atau hitam, bersorban, dan membawa pedang atau tombak. Di Sigli, aksi itu diikuti sekitar 25 orang. Mereka bergerak selepas subuh, dari Desa Busu, Kecamatan Mutiara, ke Sigli menempuh jarak 12 km. Sepanjang perjalanan mereka meneriakkan takbir, "Allahu Akbar...." Mereka pun menyebarkan selebaran yang isinya seruan untuk membasmi kebatilan dan menegakkan Islam. Kelompok bergerak tanpa hambatan sampai ke Kota Sigli. Sampai di depan Kantor Kodim sejumlah petugas menghadangnya. Tapi mereka terus merangsek maju kendati tembakan peringatan telah dilepaskan. Gerak maju baru bisa ditahan setelah datang bantuan dua regu polisi. Mereka pun dilucuti tanpa perlawanan. Namun, kelompok yang beraksi di Meulaboh lebih beringas. Di situ aksi dilakukan oleh lima pemuda berjubah hitam dan bersorban serba hitam, di bawah pimpinan Sabirin A.R. Usai salat subuh, Sabirin merampas mikrofon dari tangan penceramah yang tengah berpidato di masjid kampung Kota Padang. Lantas, ia berpidato mengajak umat Islam memerangi kemaksiatan. Ajakan yang diserukan dengan cara sangar itu tak mendapat sambutan. Maka, kelima pemuda itu bergegas ke Masjid Nurul Huda dua kilometer dari sana, sambil mengarak bendera merah berlambang bulan-bintang, pedang bersilang, dan Quran. Bendera itu kemudian dikerek di halaman Nurul Huda. Sampai pukul 09.00, tak ada yang berani mengusik mereka. Merasa menang angin mereka pun membawa bendera itu ke jalan raya. Nah, keributan terjadi. Kelima pemuda itu terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Sabirin tertembak, dan akhirnya meninggal di rumah sakit umum Meulaboh. Adakah hubungan antara Bantaqiyah dan Aceh Merdeka? "Tidak," kata Tengku Banta akhir tahun lalu. Dia mengaku pernah dihubungi oleh utusan "Aceh Merdeka", tapi menolak. "Saya sebenarnya bukan orang yang anti-Pancasila atau UUD '45," ujarnya. Hanya saja, dia merasa kesal karena sikap MUI Aceh yang suka salah paham. "Saya tak pernah bermaksud menyebar ajaran sesat," ujar laki-laki 56 tahun jebolan kelas III madrasah itu. Banta memang pernah dikenal sebagai penceramah yang "berani" karena pidatonya suka meledak-ledak. Tak heran jika sebagian muridnya lalu jadi beringas, dan membuat aksi "jubah hitam" dan "jubah putih" di Meulaboh dan Sigli. Tengku Banta kini memilih putar haluan. Dia hidup sebagai petani kopi di desa terpencil Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong, Aceh Barat. Bahkan dia bersedia duduk menjadi salah satu penasihat Golkar Beutong. "Dia tak mau menghasut lagi pengikutnya untuk bikin huru-hara," ujar Kapolres Aceh Barat, Letnan Kolonel Pol. Syafri D.M. Sebagian pengamat beranggapan, aksi-aksi yang suka meletup-letup di beberapa wilayah Aceh itu boleh diilhami oleh aksi DI/TII Aceh pimpinan Tengku Daud Beureueh pada 1953. Ketika itu mereka kecewa karena Provinsi Aceh dilebur dalam Provinsi Sumatera Utara, dan statusnya turun menjadi karesidenan. "Itu ditentang keras oleh orang Aceh," kata Letnan Kolonel (Purn.) Hasan Saleh, 69 tahun, bekas Menteri Urusan Perang DI/TII Aceh. Kemerosotan status Aceh itu memang dirasakan cukup menyakitkan. Sebab, sebelumnya, Daud Beureueh sempat pula menjabat sebagai gubernur militer, kepala daerah sekaligus pemimpin militer yang menguasai wilayah Aceh-Langkat-Tanah Karo. Keruan saja, Daud bersikeras agar Aceh tetap dalam status provinsi dengan otonomi yang memadai. Ini diterjemahkan sebagai niat untuk memberontak. Maka, atas perintah Jakarta, sepasukan tentara menggeledah rumah Daud Beureueh, dan beberapa tokoh lain, dengan dalih mencari senjata. "Penggeledahan terhadap rumah pejuang '45 itu tentu saja dianggap penghinaan oleh orang Aceh," kata Hasan Saleh. Maka, pecahlah gerakan DI/TII Aceh itu. Perlawanan DI/TII mulai surut setelah pemerintah pusat bersedia berkompromi dengan menjanjikan Aceh sebagai Daerah Istimewa, yang direalisasikan pada 25 Mei 1959. Namun, ketika itu, masih perlu waktu untuk mengajak Ayah Daud, begitu almarhum dipanggil, turun gunung. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat itu rupanya masih diwarisi oleh bekas anak buah Daud Beureueh, antara lain Hasan Tiro, yang mencoba mengobarkan perlawanan lewat gerakan Aceh Merdekanya. Tapi gerakannya tak mengakar seperti yang dimpimpin Daud. "Aceh Merdeka tak akan pernah mendapat dukungan karena tak berpijak pada jalur Islam," kata H. Hasan Aly, bekas Perdana Menteri DI/TII Aceh. Hasan Aly, kini 74 tahun, menilai gerakan separatis dengan napas Islam sekalipun kini tak lagi relevan. "Perkembangan Islam di Aceh sekarang bagus," ujarnya. Lantas, dia melihat aksi teror bersenjata seperti yang terjadi di Aceh Timur sekarang ini, "Lebih cocok disebut gerakan kriminal, bukan politis". Putut Tri Husodo (Jakarta) dan Wahyu Muryadi (Aceh)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini