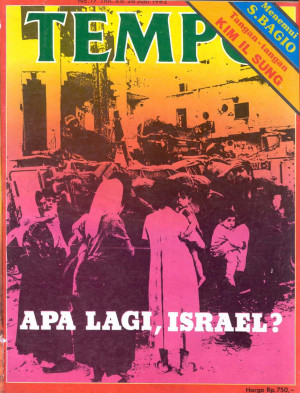MUDAH-mudahan tidak akan ada lagi kasus seperti yang menyangkut
Cut Satariah . Perempuan Aceh ini, tanggal 14 Desember 1976
dicerai suaminya: si suami mengucapkan talaq di depan Kepala
Kampung Blok Sawah, Sigli, Aceh Utara, di depan para saksi. Tapi
agar sesuai dengan UU Perkawinan, ia kemudian mengajukan gugatan
perceraian ke Pengadilan Agama di Sigli.
Tapi Pengadilan Agama, dalam sidang 26 Juli 1977, menolak
permohonan cerainya. Padahal bukan saja talaq telah dijatuhkan.
Masa iddah pun, yang menurut ketentuan agama berjangka 3 bulan
10 hari, sudah lewat -- dan tak ada ketentuan hakim agar mereka
menikah lagi.
Karena itu Rasyidin, si suami, naik banding ke Mahkamah Syariah
Provinsi. Dan di situlah, 6 Desember 1977, Mahkamah Provinsi
membatalkan keputusan bawahannya -- seraya memerintahkan membuka
sidang "guna menyaksikan perceraian" mereka.
Tapi Cut Satariah, entah siapa yang menunjukkan jalan, naik ke
Mahkamah Agung (MA). Dan MA pun, 15 Maret 1979, ganti
membatalkan keputusan Mahkamah Provinsi.
Puyeng, bukan? Cut Satariah sendiri terbengong-bengong. Secara
resmi, katanya, ia masih istri Rasyidin. Tapi ia insaf juga,
menurut agama ia sudah lama bukan istrinya. Dan nasibnya tidak
berubah. Sebab, kata Rasyidin: "Saya akan tetap mengakui putusan
Mahkamah Syariah "
Nah. Kasus itulah agaknya yang oleh seorang anggota DPR, Sjufri
H. Tanjung dari F-PP, dikemukakannya dalam himbauannya sekitar
MA, seperti dimuat Kompas 14 Juni. Yakni agar di MA ada "hakim
agung yang benar-benar paham hukum Islam", minimal dua orang.
Maklum pengangkatan 30 hakim agung sudah akan dilaksanakan dalam
waktu dekat: diharap bulan Juli DPR sudah selesai menggodok para
calon mereka. Tapi jawaban dari pihak MA membikin kaget si
anggota DPR. Busthanul Arifin SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan
Peradilan Agama (singkatannya: Tuada Uldilag), dalam siaran
persnya hanya sehari kemudian mernyebut pernyataan Sjufri
sebagai "menunjukkan pengetahuan yang dangkal dari yang
bersangkutan sendiri, baik mengenai hukum Islam maupun hukum
pada umumnya."
Sjufri terkejut. Ia kemudian mengakui, kepada TEMPO, di MA
memang ada seorang ahli agama Islam, yang dikatakannya 'hebat'
-- yakni Busthanul sendiri -- "walaupun ia tidak mampu
memanfaatkan keahliannya." Katanya, lalu: "Usul saya itu
sebenarnya untuk membantu Pak Busthanul, bukan untuk
menikamnya." Tambahan lagi, kata lulusan Fakultas Tarbiah IAIN
Sumatera Utara itu, "adanya hakim yang tahu hukum Islam itu
sebenarnya keinginan seluruh umat Islam."
Tapi masalah 'dualisme' peradilan di Indonesia, yang menyangkut
hukum agama, bukan baru kali ini saja muncul. Pengajuan perkara
Cut Satariah sendiri ke MA merupakan salah satu contoh: bukan
Mahkamah Syariah Provinsi Aceh yang menyalurkan permintaan
kasasi, melainkan Satariah sendiri. Pengadilan agama seolah tak
mengakui MA sebagai atasan.
Bahkan Direktur (waktu itu) Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama, H. Ichtijanto SA, SH, menyatakan bahwa keputusan
pengadilan agama tingkat banding bersifat final. Di samping
memang belum ada undang-undang organik yang mengatur upaya
kasasi untuk peradilan agama, juga kata Ichtijanto, dalam
suratnya 1 Mei 1978 kepada ketua pengadilan agama tingkat I dan
banding seluruh Indonesia, "karena hingga kini belum ada hakim
agung bidang agama di Mahkamah Agung" (TEMPO, 14 April 1979).
"Tapi itu dulu," kata H. Muchtar Zarkasyi SH, pengganti H.
Ichtijanto, kepada TEMPO. Muchtar berbicara di sela-sela rapat
kerja bersama MA dengan Departemen Agama dan pengadilan tinggi
agama seluruh Indonesia, di Jakarta, 18-19 bulan ini. Raker
bersama itu sendiri, yang bermaksud terutama untuk meningkatkan
pembinaan badan peradilan agama dalam hubungannya dengan MA,
merupakan bukti kerjasama. Ini bahkan sudah yang kedua kalinya
-yang pertama 29 Mei 1981.
Seperti dituturkan Muchtar (40 tahun, lulusan FH-UI, memangku
jabatan sejak 14 April 1981), sejak setahun lalu sebenarnya
sudah jelas peningkatan hubungan antara Departemen Agama dan MA
yang kini di bawah Mudjono SH itu. Misalnya MA meminta tenaga,
dan pihak peradilan agama memberikan dua orang sarjana fakultas
syari'ah. Juga acapkali MA minta bantuan saksi ahli dari
Departemen Agama, H. Wasith Aulawi MA, dalam mengambil putusan.
Dan kemudian raker yang sudah dua kali ini.
Jabatan Busthanul Arifin sendiri (lulusan Sumatera Thawalib
Padang Panjang, madrasah yang didirikan ayab Hamka, sebelum ke
fakultas hukum) di MA, sebagai Tuada Uldilag tadi, menegaskan
fungsi MA dalam "membimbing, mengawasi, meliput dan mengayomi"
peradilan agama, "khususnya di bidang teknis peradilan," seperti
dikatakan Prawoto Gandasubrata SH, Wakil Ketua MA, dalam
sambutan Raker.
Menteri Agama, dalam pidato pengarahannya pada raker kemarin itu
mengharapkan agar hubungan kerja kedua kalangan itu dapat
mempertahankan keyakinan, bahwa hukum syariah "tidak diragukan
sedikit pun penerapannya oleh pihak-pihak pencari keadilan."
Tapi Menteri juga menyebut, bahwa terutama sebelum 1975 hakim
dan aparat peradilan agama terdiri dari mereka yang sebenarnya
tidak memiliki tingkat pendidikan yang benar-benar tinggi dalam
hukum Islam.
Tentu ada maksud perbaikan dalam kesadaran seperti itu.
Khususnya sehubungan dengan kebutuhan pembaruan dalam
pelaksanaan hukum Islam sendiri -- seperti yang sebagian sudah
tertuang dalam UU Perkawinan -- sehubungan dengan munculnya
"generasi baru" dalam kelembagaan hukum Islam. Dan hanya dengan
begitu kasus seperti yang dialami Cut Satariah tidak akan
berulang. Bukan hanya tidak cocoknya keputusan sebuah lembaga
pengadilan dengan keyakinan keagamaan penduduk. Tapi juga
pengertian akan perlindungan hukum agama kepada Satariah
sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini