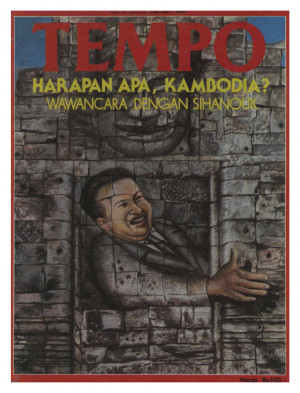INI sebuah kisah perlawanan terhadap feodalisme Mataram. Ki
Ageng Mangir memberontak, mencoba berdiri sama tinggi dengan
rajanya, Panembahan Senapati. Akhirnya dengan tipu muslihat,
pembangkang itu dibunuh.
Sepotong kisah sejarah pada awal berdirinya kerajaan Mataram
itu, yang amat populer bagi sebagian besar orang Jawa, ditulis
kembali dalam bentuk drama oleh sastrawan Pramudya Ananta Toer,
yang bulan lalu telah dibebaskan dari P. Buru.
Pram, yang dikecualikan dari para tahanan politik yang terlibat
G30S/PKI lainnya, diperbolehkan menulis karya-karya sastra di
Buru. Hasilnya: 7 novel dan satu naskah drama.
Kedelapan naskah itu mengambil bahan pokok kejadian sejarah.
"Saya memang lagi senang menulis tentang hal-hal itu,'i katanya
kepada TEMPO di rumahnya. Dan sambungnya: "Tradisi penulisan
Jawa tak berani mengatakan hal sebenarnya. Diambilnya sanepa
(bahasa Jawa, artinya kiasan red). Nah, saya justru ingin
mencoba mengungkap apa sebenarnya yang terjadi." Yang dimaksud
tradisi penulisan Jawa itu, ialah kitab Pararaton dan
Nagarakertagama.
Meski begitu, tetap dia mengharap karya fiksinya itu dipandang
sebagai karya fiksi dan bukan, misalnya, buku sejarah.
Mangir, satu-satunya drama yang dia tulis, menurut Pram hendak
mengungkap bagaimana Panembahan Senapati "dalam melaksanakan
politiknya menempuh segala jalan, bahkan pernah melawan ayah
angkatnya sendiri." Adakah itu merupakan sikap positif atau
negatif? "Dipandang dari kepentingan Mataram, ya dia harus
begitu. Dia berkuasa," jawabnya spontan.
Dan tokoh Mangir menurut Pram adalah contoh, "bagaimana
kelemahan orang itu di bidang seks." Maksudnya banyak orang
runtuh karena tak tahan menghadapi godaan seks.
Yang baru diselesaikan penulisan jilid pertamanya adalah novel
Arok dan Dedes. Pram mengaku tertarik pada kisah ini: bagaimana
mungkin anak jelata bisa naik menjadi bangsawan, dan diterima
oleh para ksatria maupun brahmana." Menurutnya, itu barangkali
karena ada kekuatan yang bersatu yang mendukung Ken Arok. "Kalau
tidak, tentulah dia dianggap bertindali kriminal." Tapi sekali
lagi, Pram ingin bukunya ini hanya dilihat sebagai karya fiksi
dan bukannya kebenaran sejarah.
Sebuah lagi novelnya yang masih mengambil bahan dari sejarah
kerajaan di Jawa, berjudul Mata Pusaran. Pokok ceritanya tentang
keruntuhan Majapahit, karena kalah oleh kerajaan Tiongkok.
Empat novel yang lain merupakan satu rangkaian: Bumi Manusia,
Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Di Atas Lumpur. Ini novel
yang mengambil bahan dari sejarah periode Kebangkitan Nasional.
"Saya katakan periode, dan bukan hanya Kebangkitan Nasional,
karena itu merupakan satu kontinyuitas," tutur Pram.
Sebuah lagi novelnya, Arus Balik, merupakan kisah masuknya
bangsa kulit putih ke Nusantara dan akibat-akibatnya.
Menarik untuk membaca karya mutakhir prosais ini, yang oleh
kritikus sastra H.B. Jassin dinilai sebagai pembaharu gaya
penulisan prosa setelah zaman Pujangga Baru (di samping Idrus).
Tapi agaknya tak mudah. Kedelapan naskah itu sekarang "masih
diperiksa yang berwajib." Pun, kalau misalnya sudah di
kembalikan dan ternyata diizinkan diterbitkan, mungkin masih
membutuhkan waktu untuk terbit.
"Semuanya saya tulis berdasar ingatan yang masih ada," katanya,
menceritakan tiadanya buku-buku referensi yang dibutuhkannya.
"Karena itu membutuhkan revisi," -- satu hal yang katanya tak
pernah dia lakukan dalam karya-karyanya yang lalu.
Montir Radio
Pramudya Ananta Toer lahir di Blora, 6 Februari 1925. Pernah
sekolah montir radio di Surabaya, menjelang Jepang menduduki
Indonesia. Seperti lazimnya pemuda waktu zaman Perang
Kemerdekaan, Pram pun ikut angkat senjata. Juli 1947 tertangkap
Belanda, dipenjara di Bukit Duri, Jakarta sampai Desember 1949.
Seperti juga di Instalasi Rehabilitasi P. Buru beberapa tahun
belakangan ini, waktu itu Pram juga menghabiskan masa tahanannya
dengan menulis.
Hingga tahun 1965 sekitar 15 karya berupa novel, kumpulan cerita
pendek atau drama telah ditulisnya. Di masa menjelang peristiwa
G30S, ketika PKI dan kekuatan politik lain yang dipengaruhinya
memegang kontrol atas media massa, Pramudya terkenal sebagai
tokoh yang garang kepada penulis yang dianggapnya lawan.
Dalam istilahnya sendiri, ia "membabat" -- memotong semak-semak.
Peristiwa Manifes Kebudayaan, 1963, adalah puncaknya. Sejumlah
besar sastrawan Indonesia, antara lain H.B. Jassin, W.S. Rendra
dan Taufiq Ismail, yang berusaha melawan kebekuan sastra yang
dikendalikan partai dan pemerintah, kena "babat" Pram. Mereka
dilarang menulis, kehilangan pekerjaan dan jadi orang yang
tersingkir. Kegagalan G30S menyebabkan Pram yang ganti
tersingkir, untuk 14 tahun.
Adakah kini tulisannya masih juga seperti dulu? Dalam sebuah
pembahasan buku di majalah Mimbar Indonesia, Mei 1960, H.B.
Jassin menulis, bahwa karya-karya Pram periode sesudah tahun
1953 tak begitu disukainya lagi. Bahkan jika dibaca kembali
kini, karya-karya Pram di masa lalu mungkin tak teramat bagus,
tidak sebagus karya-karyanya yang ia tulis di P. Buru itu --
siapa tahu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini