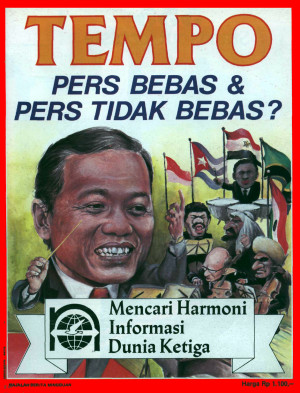INDONESIAN CHINESE IN CRISIS Oleh: Charles A. Coppel Penerbit: Oxford University Press, KualaLumpur, 1983, 236 halaman DR. CHARLES COPPEL, yang kini mengajar dl Universitas Melbourne telah banyak menulis karangan tentang orang Tionghoa di Indonesia, tapi baru kali ini ia sempat menerbitkan sebuah buku. Buku yang berdasarkan disertasinya di Universitas Monash pada 1975 ini, meski sudah diaktualisasikan (terutama bab terakhir mengenai akomodasi Orde Baru), intinya tidak banyak berbeda dengan aslinya. Buku ini membahas politik peranakan dan kebijaksanaan pemerintah Indonesia sebelum dan sesudah G-30-S/PKI, terutama dari tahun 1963 hingga 1968. Walau judul buku ini memberikan kesan seakan-akan mencakup politik Tionghoa secara menyeluruh, yang menonjol ialah politik dan masyarakat peranakan. Gambarannya tentang politik dan aktivitas Tionghoa totok masih jauh dari memuaskan. Salah satu fokus Coppel adalah percaturan politik antara Baperki dan LPKB, dan peranan LPKB setelah terjadinya Gestapu. Buku ini telah berhasil memberikan gambaran terperinci pada periode bergolak itu. Coppel tidak berhenti di situ. Ia bermaksud menumbangkan "teori" yang dikemukakan Prof. Lea Wiliams dalam buku The Future of the Overseas Chinese in Southeast Asia (1966). Williams mengatakan, penyelesaian masalah Tionghoa ialah dengan "asimilasi politik" dalam arti "berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan". Contoh yang diberikan Williams adalah Indonesia di masa Presiden Soekarno masih berkuasa, sebelum Gestapu. Williams berpendapat bahwa asimilasi politik ala Baperki di Indonesia telah menguntungkan golongan Tionghoa, karena dengan ini mereka bisa diterima oleh pribumi. Coppel tidak sependapat dengan "teori" itu. Ia menunjukkan bahwa politik Baperki pada zaman Demokrasi Terpimpin telah mengakibatkan reaksi anti-Tionghoa yang hebat setelah 1965. Baperki sebagai organisasi massa yang dekat dengan Presiden Soekarno dan PKI akhirnya menemui ajalnya dengan lenyapnya kedua aktor Politik itu. Karena Baperki dianggap mewakili Tionghoa, maka orang Tionghoa juga menjadi sasaran kaum militer, partai politik, dan massa anti-PKI dan anti-Soekarno yang muncul setelah Gestapu. Kerusuhan anti-Tionghoa terjadi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penduduk Tionghoa menderita karena kekacauan itu. Apa pesan buku Coppel? Coppel menunjukkan dilema golongan Tionghoa di Indonesia. Kalau tidak berpartisipasi dalam politik, mereka akan dikecam sebagai makhluk yang hanya mau mencari keuntungan. Jika mereka berpolitik, banyak faktor internal dan imternasional yang berada di luar kekuasaan mereka. Akhirnya mereka lebih menjadi obyek daripada aktor yang aktif. Karena itu, Coppel menarik kesimpulan demikian: sebagai minoritas etnis yang kecil, Tlonghoa Indonesla tldak mempunxai banyak pilihan, tapi mesti berusaha menyesuaikan diri dengan pemerintah. Menurut Coppel, selama prasangka Tionghoa dan kepentingan yang bertentangan tetap hadlr, dilema Tlonghoa di Indonesia tidak akan lenyap. Beridentifikasikan dengan golongan yang berkuasa pada suatu waktu tertentu akan membawa bencana kepada minoritas itu ketika golongan berkuasa itu digulingkan. Coppel tidak menganjurkan orang Tionghoa tidak berpartisipasi dalam politik. Yang ia ragukan hanya sejenis partisipasi politik, yaitu "Identiflkasi dengan golongan yang berkuasa", yang menurut dia ialah konsep "asimilasi politik" yang dianjurkan Williams. Baaimana orang Tionghoa bisa keluar dari jalan buntu ini? Apakah dengan cara LPKB dulu? Coppel mengatakan, pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, segolongan elite peranakan, yang anti-PKI dan pro-asimilasi, bersatu dengan kaum militer dan kekuatan politik lain yang anti-PKI dan anti-Soekarno. Adanya orang-orang LPKB itulah yang mempengaruhi para pemimpin Orde Baru, sehingga kampanye anti-Tionghoa yang berkobar-kobar bisa diredakan. Bagaimana sekarang? Apakah ada golongan semacam LPKB-nya Orde Lama? Coppel tidak menjawabnya secara tegas, kecuali menunjuk kepada Bakom yang terdiri dari banyak kelompok. Sebetulnya, minoritas Tionghoa merupakan golongan yang heterogen. Mereka terpecah-belah dalam hal kebudayaan, agama, kelas sosial, dan pandangan politik. Jadi, tidaklah, mungkim bagi mioritas itu hanya beridentifikasikan satu golongan saja. Heterogenitas minoritas itu mungkin akan menghindarkan golongan itu tersisih habis, tapi tidak menjamin keselamatan anggotanya dalam keadaan krisis. Di samping partisipasi politik, keadaan ekonomi Indonesia umumnya dan soal pri dan nonpri khususnya akan turut mempengaruhi intensitas bentrokan kedua golongan itu. Buku ini mengingatkan saya kepada disertasi Mary F. Somers (1965) yang membahas politik peranakan Indonesia sampai pertengahan 1963. Coppel melanjutkan cerita dan pembahasan Somers yang belum selesai. Coppel tidak saja telah mengisi "kesenjangan" yang cukup penting itu, melainkan juga telah menggunakan beberapa bahan yang sukar diperoieh (seperti arsip LPKB) dalam menganalisa politik Indonesia, terutama yang bersangkutan dengan golongan Tionghoa peranakan. Bagi orang yang ingin mempelajari masalah Tlonghoa di Indonesia, buku ini akan membantu. Leo Suryadinata * Pengajar pada Departemen llmu Politik di National University of Singapore.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini