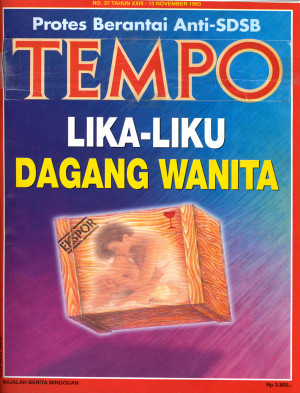APABILA penonton rajin tertawa, terutama di bagian pertama, dalam pentas Aum oleh Teater Mandiri di Gedung Kesenian Jakarta akhir Oktober lalu, itu niscaya mereka menikmati parodi yang kental tentang rakyat dan penguasa. Apalagi sandiwara yang ditulis Putu Wijaya di tahun 1982 ini menggunakan bahasa jalanan, dialek, bahkan kata-kata yang tak ada artinya. Teater Mandiri membekuk akal sehat, menisbikan dan memain-mainkan pengertian tentang kekuasaan. Serombongan orang kampung menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk mengadu kepada bupati mereka. Mula-mula mereka hanya dapat menemui dua orang hansip, penjaga rumah bupati. Baru kemudian mereka, secara kebetulan, dapat menemui bupati yang tengah lari pagi. Tokoh-tokoh itu mengingatkan kita pada tokoh sehari-hari, tapi mereka sungguh edan jahanam karena menjungkirbalikkan setiap kewajaran. Selama 70 menit pertama kita menyaksikan olok-olok, umpatan, dan pelesetan. Pendeknya, pembicaraan main-main antara orang- orang kampung, hansip, dan bupati penuh kejutan dan kegilaan. Percakapan antara mereka bukanlah komunikasi, melainkan serentetan kesalahpahaman. Dan dari sanalah terbit humor. Lihatlah, misalnya, ketika orang-orang kampung itu tengah bersitegang dengan dua orang hansip penjaga rumah bupati, mendadak si bupati muncul dalam pakaian lari pagi. Kontan, si bupati beserta dua hansip itu beromong kosong tentang kebugaran tubuh seraya melakukan gerak senam yang lucu. (''Bangsa yang kuat ditentukan oleh hansip-hansip yang kuat,'' katanya.) Kemudian, orang-orang kampung itu mendesak si bupati mendengarkan pelbagai persoalan mereka, tapi ia merasa tak mendengar sepatah pun pertanyaan dari mereka. Ia pun hanya memaki hansip-hansipnya sungguh sering ia mengumpat ''taik kucing''. Dan panggung sungguh ramai. Ramai oleh kehadiran para pemain yang bergerak ke sana-kemari terutama orang-orang kampung tapi dalam bloking yang terencana rapi. Mereka mengenakan kostum warna-warni, berlapis-lapis, seakan perpanjangan dari tubuh mereka yang ganas. Suara mereka pun berderai-derai, kadang menjerit-jerit, seperti keluar dari jiwa miring dan panas. Lalu, panggung yang ditata Roedjito: menjorok dalam ke arah belakang, seperti jadi ruang berlapis-lapis oleh tirai- tirai berwarna hijau, biru, dan cokelat. Dan masih ada buntalan dan gundukan, yang dapat diseret ke sana-kemari. Adalah Arswendi Nasution (bupati) serta Yanto Kribo dan Edi Pantat (keduanya hansip) yang menghidupkan panggung. Melalui merekalah bahasa jalanan yang kasar dan carut-marut itu jadi hidup, meledak, dan berwarna-warni. Merekalah yang membikin peran penguasa itu mengandung kekonyolan dan ejekan terhadap diri sendiri. Sampai di sini kita boleh mencatat ''filsafat'' lakon ini: bahwa kebajikan tak berada di pihak penguasa maupun di pihak rakyat. Kita menikmati bahasa kotor berseliweran di panggung, bahasa yang hidup dan segar. Mungkin dengan begitu kita meragukan kepastian hidup, yang sering dibentuk dengan bahasa yang ''baik dan benar''. Tetapi ''filsafat'' semacam itu bukanlah tujuan utama. Itu sekadar cara untuk menciptakan kejutan terus-menerus. Bahwa, jika kita menyimpan ingatan pada realitas keseharian (karena ada tokoh-tokoh bupati, hansip, dan rakyat), ingatan itulah yang mau digedor sampai akhir pertunjukan. Dan memang, pada 40 menit bagian kedua (setelah jeda), kesan parodi terhadap kekuasaan itu menghilang perlahan-lahan, digantikan oleh kemuraman dan absurditas sekalipun humor-humor kecil masih tetap jalan. Orang-orang kampung itu, ternyata, mengadu karena mereka telah ditimpa sejumlah keganjilan: ada para lelaki yang hamil, ada manusia bertangan banyak seperti gurita semua itu diwujudkan di panggung. Mereka akhirnya bertanya kepada Tuhan. Tak terjawab, mereka melakukan bunuh diri menusuk diri dengan keris beramai-ramai. Dan di akhir pertunjukan, pak bupati dan hansipnya juga bunting. Maka, yang tersisa buat kita adalah keganjilan, dan itulah agaknya ''inti'' tontonan. Tak ada yang salah dengan tontonan. Tapi, dalam Aum kali ini (pertama kali dipentaskan Teater Mandiri tahun 1982), terlampau besar keinginan untuk menciptakan, terutama, permainan rupa: siluet orang di latar belakang, bendera putih besar yang dikibar-kibarkan, kepala terpenggal yang terayun-ayun, sosok perempuan yang dikerek ke langit-langit, kain amat lebar dibentang-getarkan jadi gelombang. Rasanya, sungguh terlalu banyak gambaran yang mau disampaikan. Apalagi, musik yang digarap Harry Roesli begitu manis dan ingar-bingar, sehingga yang terjadi adalah ''pertandingan'' kata-kata, musik, dan rupa. Karena si sutradara tersihir oleh keramaian yang sudah terkandung dalam naskah? Sutradara itu adalah Yanto Kribo. Seusai pertunjukan saya bertanya, cukupkah sentuhan sutradara baru ini, sehingga pentas Aum memang berbeda de-ngan pentas-pentas yang disutradarai Putu Wijaya. Barangkali ini bukan pertanyaan penting karena dari panggung kita tetap saja digedor oleh keramaian, oleh pelbagai kontras: kontras antara keseharian dan keganjilan, antara yang serius dan yang main-main, antara kegilaan dan kewajaran itulah yang mengingatkan selalu pada kehadiran Putu Wijaya, sejak naskah hingga pemanggungannya. Akibatnya, tidak perlu dipersoalkan lagi, siapa yang jadi sutradara di Teater Mandiri. Nirwan Dewanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini