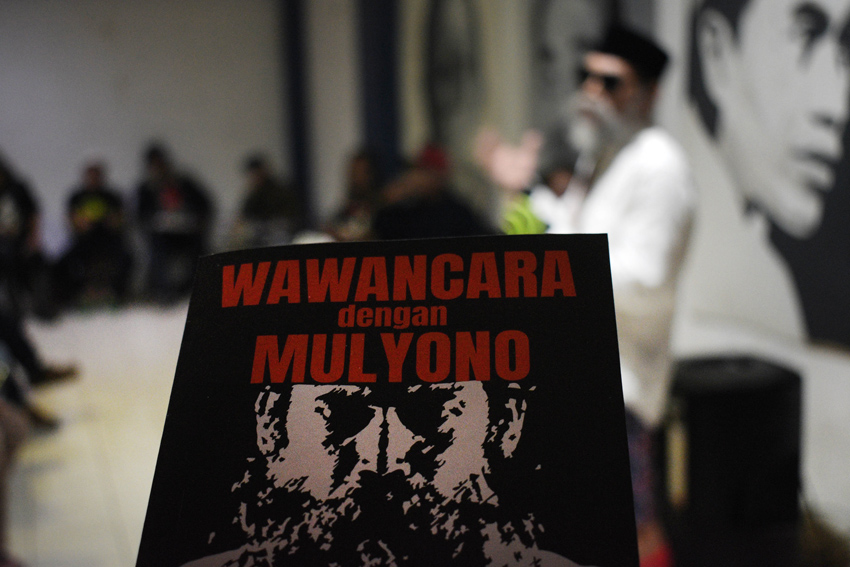Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Judul: Aku Eks-Tapol
Pengarang: Hersri Setiawan. Tebal: 466 + xii
Penerbit: Galang Press, Yogyakarta, 2003
Sejarah Indonesia telah ditulis dengan banyak pergeseran. Sebutlah, misalnya, pergeseran dari kecenderungan Euro-sentrisme ke Indo-sentrisme. Dari sejarah politik ke sejarah sosial. Dari sejarah religio-magis ke sejarah ilmiah. Dari sejarah orang besar menjadi sejarah orang kebanyakan. Dari sejarah pusat kekuasaan menjadi sejarah rakyat pinggiran.
Pergeseran-pergeseran itu menunjukkan adanya perubahan titik tekan dalam penulisan sejarah: dari sejarah yang bertumpu pada narasi besar ke narasi-narasi kecil. Sementara narasi besar sering dimanfaatkan oleh penguasa, narasi kecil dapat memberi kesempatan bersuara bagi orang-orang yang berada di tepian kekuasaan, termasuk mereka yang telah menjadi korban dari kekuasaan itu.
Buku Aku Eks-Tapol, yang berisi kumpulan karangan karya Hersri Setiawan—seorang bekas anggota Lekra yang sempat menjadi tahanan di Pulau Buru—dengan jelas mencerminkan pergeseran-pergeseran itu.
Dalam berbagai kesempatan tatap muka, penulisnya menekankan bahwa buku itu tidak dimaksudkan sebagai karya sejarah, karena ia bukan seorang sejarawan.
Meskipun demikian, sebagai suatu upaya rekonstruksi terhadap masa lalu dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan, buku itu dapat dikatakan sebagai karya sejarah.
Sebagai sebuah karya sejarah, buku ini mengangkat tema-tema narasi kecil yang sifatnya keseharian dan kerakyatan. Khususnya pengalaman sebagai orang biasa yang mendapat stigma "PKI" dan pernah dibuang ke Pulau Buru selama tujuh tahun (1971-1978). Hersri berkali-kali dalam bukunya, secara terbuka, menyebut dirinya sebagai eks tapol, mantan aktivis Lekra, dan eks tapol Buru.
Selanjutnya, melawan pandangan Orde Baru yang menggambarkan para tawanan sebagai orang-orang yang biadab, Hersri justru menunjukkan bahwa tawanan Pulau Buru jauh lebih manusiawi daripada para petugas yang dikirim untuk menjaga mereka. Ia mengkritik berbagai istilah eufemistik yang kerap dipakai para penguasa Pulau Buru ketika itu: "bereskan" yang berarti bunuh, "tefaat" yang berarti pembuangan di Pulau Buru (singkatan dari tempat pemanfaatan), "ciduk" yang berarti penangkapan.
Penulis yakin bahwa kesadaran budaya tidak harus hanya dimiliki oleh kelompok elite, tapi juga merupakan milik setiap warga masyarakat. Ia memaparkan kisah "turba"-nya seniman Lekra untuk mengembangkan kebudayaan dengan cara berdialog langsung dengan rakyat (hlm. 383-408). Hersri menggugat kecenderungan elite, yang mengembangkan kebudayaan yang hanya bertumpu pada wacana elitis semata.
Dalam artikel berjudul Aku Abangan, Hersri menggugat formalitas agama. Suatu ketika ketika SMP, ia diminta mengisi formulir yang salah satunya menanyakan agama yang ia peluk. Hersri kecil menolak mengisi formulir itu. Dialog sengit terjadi antara Hersri dan gurunya. Intinya, Hersri menolak formalisasi agama. Baginya, religiositas seseorang lebih luas daripada kategori-kategori yang telah ditentukan oleh kekuasaan politik.
Di tempat yang lain, Hersri menolak formalisasi bahasa. Itulah sebabnya, dalam mengungkapkan gagasannya, ia bisa dengan mudah melompat dari satu bahasa ke bahasa yang lain.
Upaya penulis untuk keluar dari pakem itu menunjukkan bahwa Hersri sedang menghayati beberapa hal.
Pertama, sebagai manusia bebas, ia tak mau dikungkung oleh berbagai macam konvensi sosial-politik-religius. Kedua, baginya keterpenjaraan fisik tidak harus selalu disertai oleh keterpenjaraan batin. Ketiga, sejarahnya di Pulau Buru menunjukkan bahwa kemenangan selalu ada di pihak korban yang mau bertahan dan terus berjuang. Selain itu, ketidakadilan yang dialami seseorang tidak harus selalu disertai oleh kebencian dan dendam kesumat.
Dengan lancar, Hersri—juga baru saja menerbitkan buku Kamus Gestok dan Negara Madiun?—menceritakan perlakuan semena-mena yang dilakukan penguasa terhadapnya, tanpa diikuti dengan keinginan untuk membenci atau membalas.
Buku yang ditulis dengan bahasa yang jujur dan lugas ini merupakan rekaman atas serpihan-serpihan pengalaman dan gagasan pribadi sang penulis. Namun, secara de facto, Hersri telah mengangkat sisi-sisi penting dari sejarah bangsa ini, khususnya tentang tragedi G30S dan Pulau Buru. Buku ini pada akhirnya memang bukan perjalanan batin penulisnya semata, tapi juga perjalanan nasib sebuah bangsa.
Baskara T. Wardaya S.J.
(Guru Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo