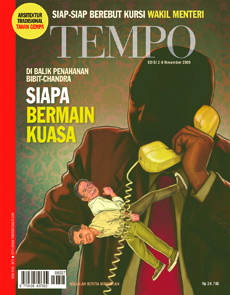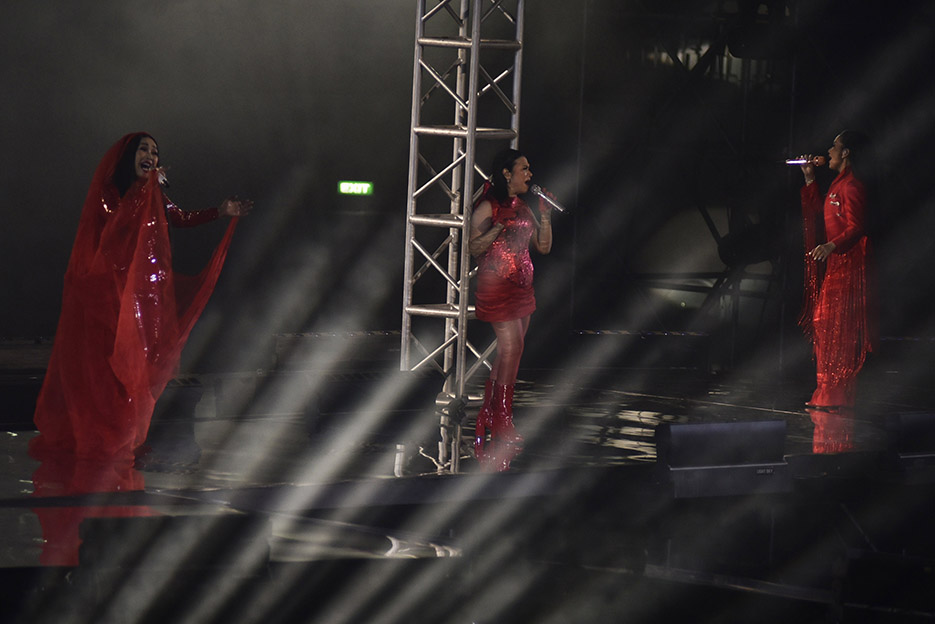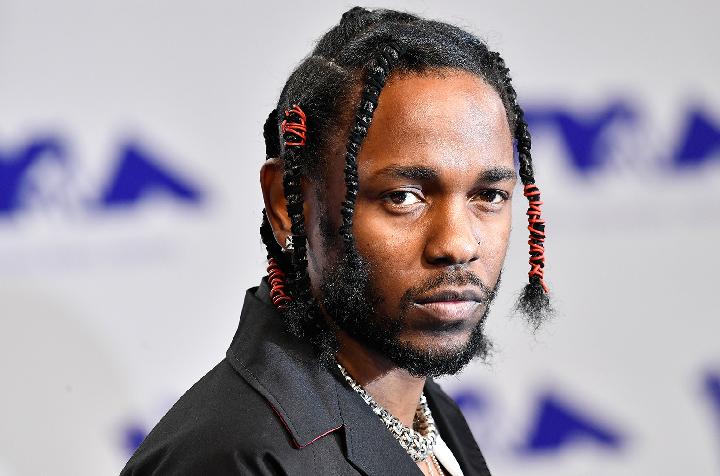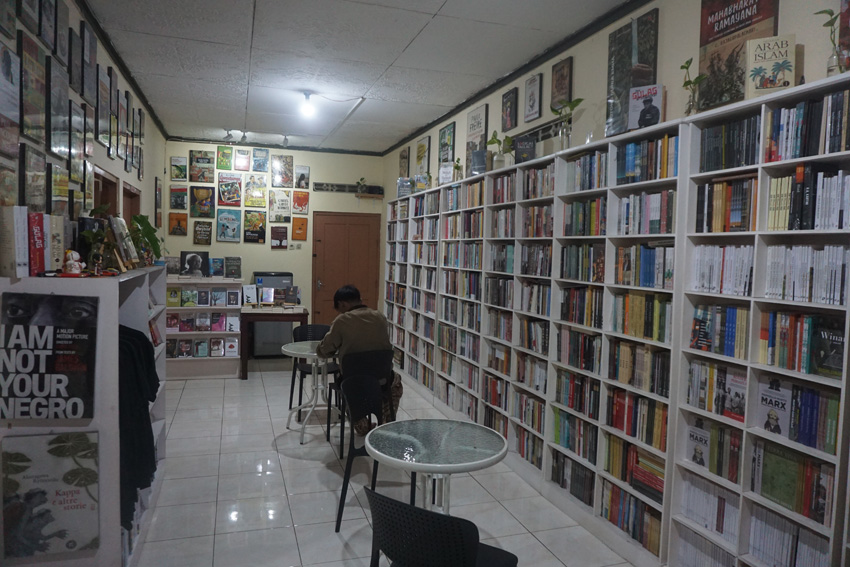Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEBUAH cerita pendek Umar Kayam saya ingat di luar kepala. Satu keluarga kota berlibur ke desa, mengunjungi rumah pembantu rumah tangga. Barulah keluarga ini melihat sosok sebenarnya pembantu itu: tanpa mesin cuci, keran air, kulkas, dan sebagainya. Saya tak ingat apa yang kemudian dilakukan keluarga itu terhadap si pembantu. Yang terkesan ketika membaca cerita pendek itu, penulisnya ingin menggambarkan potret sosial kita: kesenjangan sosial yang ada, dan sering kita tak menangkapnya.
Karya foto Ahmad ”Deny” Salman dalam Pameran Urbantopia di galeri North Art Space, Pasar Seni Ancol, Jakarta, mengingatkan saya pada cerita pendek tersebut. Lima paket karya foto menyajikan tema yang sama dengan cara yang sama: kontras sosial. Di satu sisi adalah kemegahan rumah beserta penghuninya, di sisi lain potret warga sosial yang dalam istilah ekonomi tergolong bekerja di sektor informal. Lima paket karya foto ini mewakili perbedaan ”selera”, tampak dari arsitektur rumah itu; dan lima jenis pekerjaan dalam sektor informal. Sama-sama megah dan mewah, yang satu mencerminkan ketradisionalan, yang lain kemodernan dan postmodern; yang satu menggambarkan cita rasa berkesenian, yang lain asal magrong-magrong. Kemegahan itu dikontraskan dengan sosok penjual minuman botol yang sedang membawa balok es untuk pendingin dagangannya, penjual minyak goreng keliling, penjual barang plastik keliling, penjual jamu gendong, dan penjahit keliling.
Ahmad ”Deny” tak hanya melihat kemegahan itu dari luar (sosok rumah), tapi juga dari dalam (potret keluarga penghuni di salah satu ruang rumah). Sosok pekerja informal itu juga tak dipotret dari ”jauh”; disertakan juga close up dagangannya (barang-barang plastik, kotak penyimpan minuman, botol-botol jamu) atau peranti kerjanya (mesin jahit, gayung minyak goreng). Inilah karya foto protes sosial yang indah dilihat tapi tetap mengabarkan kepincangan sosial yang mengganggu. Dan itu disampaikan dengan pintar: kita tetap diberi ruang untuk berimajinasi tentang hubungan kemegahan dan kemiskinan itu.
Tentulah potret tentang kota tak hanya seperti karya Ahmad ”Deny”. Di samping kota secara fisik (gedung, kesimpangsiuran lalu lintas, mal, dan sebagainya), adalah kota sebagai sesuatu yang abstrak, tentang sisi kejiwaan yang berkaitan dengan hubungan sosial, persoalan pribadi, kerja, upacara, religi, dan sebagainya. Namun sejumlah karya dari 12 fotografer ini terbilang jarang yang menggarap sisi ini. Pada umumnya mereka menampilkan kota yang fisik.
Dari sudut yang fisik ini, John Suryaatmadja terbilang bermata jeli. Ia, misalnya, menyajikan pemandangan yang campur-baur di sebuah kawasan pertokoan yang padat. Kecampurbauran itu akibat bangunan-bangunan menggunakan kaca sehingga terbentuk ruang-ruang transparan. Huruf-huruf, perempuan berjalan, tirai, logo, garis-garis bangunan, aspal jalan menyatu dalam sebuah orkes metropolitan yang simpang-siur (Pix 01). Atau, ia rekam sebuah pemandangan yang ”rancu”, tak jelas mana bawah, mana atas (Pix 02). Tampaknya ia mengarahkan kameranya ke langit-langit teras sebuah bangunan, dan langit-langit itu berbahan kaca. Terbayanglah di langit-langit itu pemandangan terbalik dari sekitar: trotoar yang sibuk, gedung megah di seberang yang angkuh. Atau, John menceritakan ihwal kota dibangun: besi, aspal, bata semen, cat, menyatu membentuk bidang dan ruang. Lalu kaki-kaki melangkah, grafiti (Pix 03).
Lalu karya Sutrisno. Ia potret poster-poster promosi yang sering kita lihat ditempel di tembok. Bukan poster yang masih utuh, melainkan yang sudah sobek-sobek, yang sudah ditumpuki poster lain yang juga sudah ”compang-camping”. Dipisahkan dari lingkungan, poster ”compang-camping” itu membentuk komposisi bidang dan warna yang tak kita lihat sehari-hari. Sutrisno memanfaatkan kodrat fotografi yang menangkap sebatas bidang, menghilangkan yang di luar bidang. Inilah komposisi yang kita temui dan sekaligus abaikan sehari-hari.
Kemudian bandingkan karya John dan Sutrisno dengan, misalnya, karya Kemal Jufri. Fotografer yang merekam kedahsyatan tsunami di Aceh dengan menyajikan foto suasana pantai dengan fokus pohon-pohon kelapa yang tinggal pokok setinggi semeter ini lebih berbicara tentang sesuatu yang ada di balik kesibukan di sudut-sudut kota. Dengan bahan kota, ia bicara tentang manusia, bahkan lebih dari itu: tentang nasib, mungkin.
Di latar depan seorang anak perempuan, sepertinya berjalan di tempat dengan kedua tangan mempertahankan keseimbangan tubuh. Di latar belakang, sosok-sosok anak-anak, orang dewasa melangkah. Jalan yang basah, sosok-sosok yang kuyup; ada guyuran air rupanya. Namun bukan pemandangan basah dan gerak sosok-sosok itu yang terutama terasakan dari karya ini. Bagi saya, dari bidang dua dimensi ini muncul pertanyaan, sebenarnya hidup ini bergerak ke mana. Lihat, tak seluruh bidang seperti berkabut gara-gara guyuran air. Di sisi kiri sesosok lelaki, dengan tas yang berayun di tangan kiri, seolah menatap aktivitas dalam kabut itu. Sesosok lelaki ini sendiri jelas tertangkap kamera, tanpa kabut: seperti ada dua dunia di sini, yang samar-samar dan yang tegas nyata (Summer in Paris 02).
Kemal punya kecenderungan menangkap sesuatu yang tak jelas dari aktivitas hidup sehari-hari. Aktivitas yang absurd, mungkin disebut begitu. Ia arahkan kamera menentang matahari. Ia tangkap orang-orang yang berjalan ke arah depan. Tentu saja, hasilnya adalah sosok-sosok dan bayang-bayang memanjang. Gelap terang bidang dan arah komposisi seolah mengabarkan ada sesuatu muncul nun di sana, dan orang-orang itu berdatangan menyambutnya.
Bahkan potret yang ”biasa” dan jelas, pemandangan di suatu hamparan pasir, mungkin di pinggir sungai, tak sekadar sajian obyek. Ada patung pasir berbentuk perempuan telanjang, kedua kaku ditekuk, kedua tangan berhubungan membentuk ”lingkaran”, jari-jari mengatup di bawah pusar. Lalu gelas kertas teronggok. Dan di bidang atas, di sisi kiri, dua sosok duduk, berselonjor kaki. Bidang gambar disengaja untuk tak menangkap kedua sosok ini sebatas bawah pundak—tak ada kepala di sini. Siapakah makhluk sebenarnya: wanita telanjang terbentuk dari pasir, atau dua sosok ”tak” berkepala itu?
Di samping Kemal adalah Oscar, Davy Linggar, dan Jim Allen Abel. Ketiga fotografer ini pun menyajikan kota yang bukan fisik. Sosok perempuan yang seperti disiksa, logam melingkari leher, dan sesuatu yang tak nyaman di putingnya, serta kepala sebatas mulut ditutupi topi yang tidak biasa. Sadomachoism, bisa jadi demikianlah karya Oscar Motuloh ini. Rasa sakit itu makin terasa karena yang disajikan negatif fotonya. Sedangkan Davy menyuguhkan karya seni instalasi, berbentuk tumpukan kotak kecil disusun seperti pintu dengan kusennya dan tembok yang tak selesai. Di kotak-kotak itulah ia tempel foto-foto. Menurut saya, karya ini kurang mengundang perhatian dibanding pameran Davy beberapa lama lalu di Ark Gallery, Jakarta. Foto-foto kecil yang seharusnya mengundang kita mendekat, keinginan ini ”terhalang” oleh struktur bentuk ”pintu” tadi. Mungkin ini masalah penyajian.
Adalah foto-foto sosok yang memakai kostum yang mencerminkan identitas tertentu: pegawai negeri, polisi, tentara. Yang menjadikan foto sosok ini bagian dari imaji kota adalah kepala mereka yang diganti dengan sulur-suluran hijau untuk pegawai negeri, sekelompok mawar merah untuk polisi, dan bulu-bulu merah unggas untuk tentara—hanya tentara yang masih terlihat mulutnya, yang lain sepenuh kepala diganti. Hubungan itu membentuk sesuatu yang sifatnya adalah kota, dengan asumsi bahwa pemikiran yang kompleks seperti ini adalah pemikiran kota. Kota di sini bukan menunjuk tempat, melainkan konsep pemikiran.
Jadi inikah pameran tentang kota? Saya kira pameran ini, yang juga diikuti oleh Agan Harahap, Hengki Koentjoro, Imelda Mandala, Jay Subijakto, dan Wimo Ambala Bayang—selain yang telah disebutkan—termasuk yang mesti diabaikan temanya, agar kita bisa lebih bebas menikmati tiap karya.
Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo