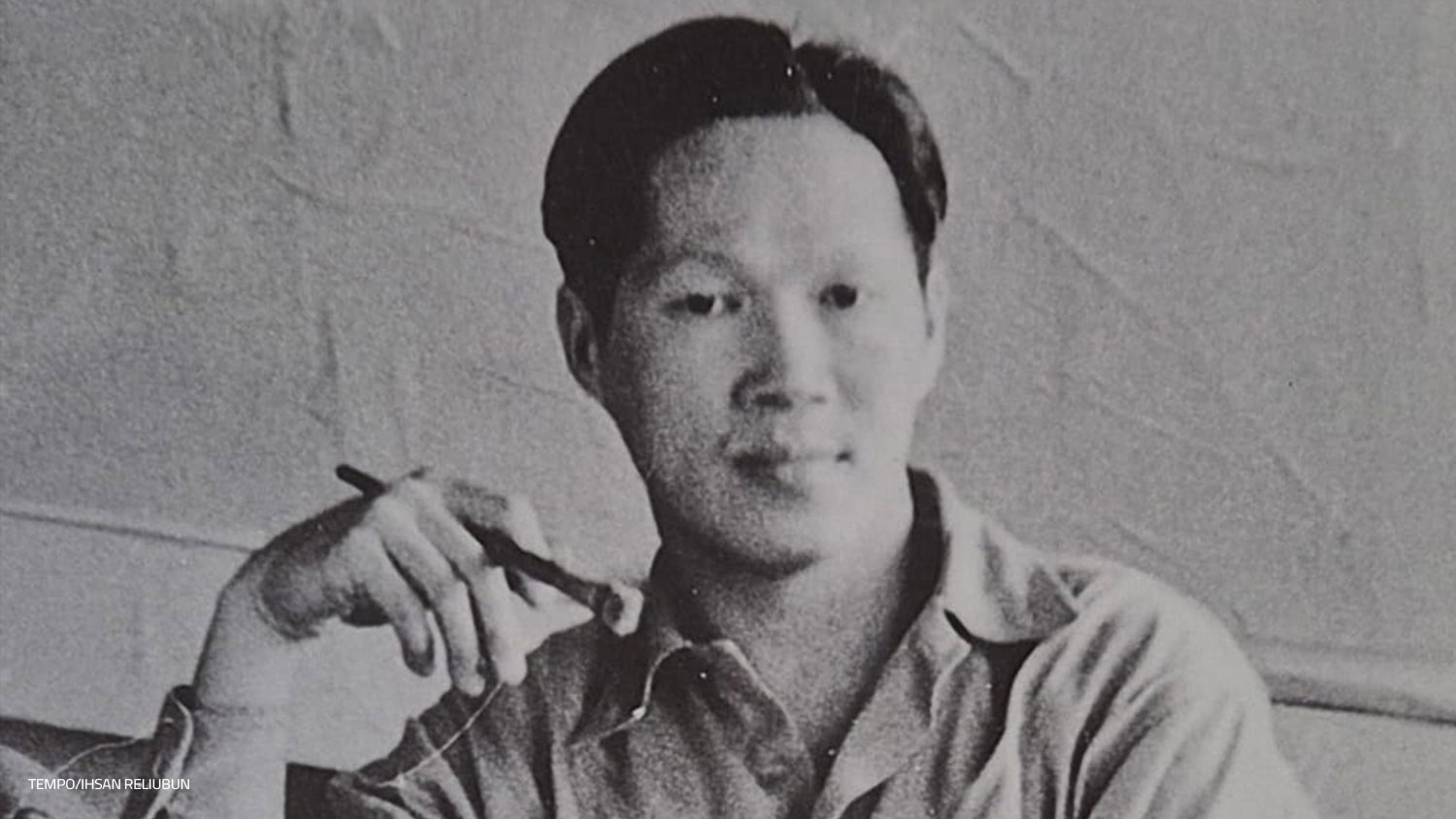Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wahai Angin
Tiuplah angin
Wahai air
Alirkan air
Jiwaku dan ragaku
Bukanlah milikku
CAHWATI Sugiharto, penari asal Solo, bersimpuh bersenandung. Ia seolah-olah memanggil-manggil "sesuatu" memasuki jiwanya, mengundang "sesuatu" mengisi tubuhnya. Bersama tiga performer lain, Agus Margiyato, Retno Sulistyorini, dan Hendra Setiawan, ia lalu menggelar bedcover. Mereka duduk bersila, seolah-olah berada di sebuah kenduri.…
Cahwati menuangkan air dari teko ke gelas. Teko itu sederhana: teko belang hijau-putih yang mudah dijumpai di pasar tradisional. Dia mengucurkan air berulang-ulang dan lamat-lamat—seolah-olah tiap tetes kucuran itu diresapkannya. Tetesan air itu satu-satunya suara di ruangan.
Satu per satu performer itu bergantian berdiri. Mula-mula Hendra Setiawan. Dua langkah, tiga langkah, tubuhnya terhuyung-huyung. Ia menggelimpang. Ia berdiri. Jatuh. Bangun, menggelimpang lagi. Giliran Retno Sulistyorini melangkah.
Penari yang akrab dipanggil Eno itu diam sejenak. Kesadarannya tiba-tiba seperti "diambil". Badannya doyong ke belakang, seakan-akan agak melayang. Tubuhnya memutar-mutar. Ia limbung dan menampilkan gerakan dengan kaki terjengkang.
Lalu Agus Margiyanto. Baru beberapa kaki melangkah, tubuhnya seperti tersedot ke belakang. Tubuh Mbendol—nama panggilan Agus—kemudian berkali-kali menyajikan gerak tertekuk ke belakang. Tubuh Cahwati, dalam posisi duduk, mendadak gemetar. Tergirap-girap, lalu terpelanting ke belakang. Inilah bagian klimaks dan paling mencekam dari Sisyphus karya Melati Suryodarmo.
Selama dua hari di Frankfurt LAB, Melati Suryodarmo menyajikan sebuah karya yang berbicara tentang trance. Melati, yang lama tinggal di Jerman dan belajar di Braunschweig pada tokoh gerak dunia yang dijuluki "grandmother of performance", Marina Abramovi, tertarik pada gagasan membebaskan tubuh dari kerutinan dan mencari asal-muasal inner energy. Ia mengaku terkesan oleh gagasan Antonin Artaud, dramawan Prancis yang dikenal memiliki pemikiran tersendiri tentang tubuh.
Pada 1931, Artaud menyaksikan tari Bali yang dipentaskan di Paris Colonial Exposition (Expo Kolonial Paris). Penari-penari dari Ubud itu kerasukan. Ia terkesima. Sejak itu, Artaud diburu gagasan tentang sesuatu keaktoran yang lain. Ia melahirkan catatan dan diary tentang keaktoran serta tubuh yang membuatnya gila.
Ia mengidamkan suatu keaktoran yang mampu menyerap energi roh-roh yang ada di dalam ruangan. "Dari dulu saya memiliki rasa ingin tahu terhadap gagasan Artaud," kata Melati. Ia mencari teknik atau metode yang dapat membuat tubuh seperti direfleksikan Artaud.
Pada 2013, Melati bertemu dengan seorang kiai di Yogyakarta yang memiliki kemampuan mengundang roh ke dalam tubuh. Tubuh siapa pun bisa dijadikan medium dan roh itu bisa menggerakkan tubuh untuk menari. Melati meminta sang kiai melatih dirinya, Agus Mbendol, Eno, Cahwati, dan Hendra di rumah Butet Kartaredjasa di Yogya dan di rumahnya sendiri di Plesungan, Solo.
"Kami menjadikan tubuh kami sendiri sebagai preparat atau uji coba," ujar Melati. "Tapi saya tak ingin menjadikan tubuh kami sebagai tubuh ritual atau upacara. Yang hendak saya cari adalah situasi ketika tubuh penari kembali ke hal yang paling dasar."
Latihan bersama kiai itu berlangsung intens, lebih dari sepuluh kali. "Latihan selalu diadakan malam hari. Tangan saya seperti merasakan sesuatu. Saya merasa dibawa energi. Itu yang membuat saya jatuh-bangun," kata Hendra. Menurut Hendra, Pak Dwi—nama panggilan sang kiai—hanya memberi stimulasi. "Kami dilepaskan berekspresi gerak apa saja, tapi Pak Dwi menjaga agar kami tak sampai kebablasan." Pengalaman demikian juga dirasakan Agus. "Pak Dwi memberi sugesti bahwa ada 'sesuatu' yang datang. Saya berkonsentrasi. Saya lalu merasakan ada aliran ke tangan dan kaki. Rasa bebas kemudian memasuki diri saya."
Juga Eno. Mulanya ia menikmati desir angin yang menyentuh kulitnya. "Tiba-tiba ada perasaan mau melompat, lari ke mana-mana. Saya berusaha mengontrolnya." Suatu kali, dalam latihan di Solo, datang seorang seniman Korea memainkan kecapi Korea.
Ketika bergerak menyesapkan suara kecapi itu, Eno mengaku matanya menutup sendiri. "Kemudian tubuh saya berputar-putar." Menurut Eno, ia sama sekali tak melawan energi. Ia mengikutinya sembari mengontrol. "Justru nanti bisa muncul gerak radikal bila kita melawan," ujarnya.
Kenangan situasi-situasi latihan saat malam hari itulah yang dimunculkan kembali dalam pementasan Sisyphus di Jerman. Ketika bergerak, baik Eno, Agus, maupun Cahwati, yang adalah penari Jawa, merasa terbebaskan dari teknik tari Jawa. Gerak yang mereka sajikan adalah ingatan-ingatan tubuh ketika berlatih bersama Pak Dwi. "Mereka menghidupkan rekaman-rekaman gerak yang tersimpan dalam memori tubuh ketika latihan," kata Melati.
Struktur pertunjukan Sisyphus sendiri sederhana tapi dalam. Begitu penonton masuk, mulanya kumparan benang merah terhampar di lantai. Di pojok kiri, Eno berdiri menggulung benang di lengannya. Lalu Cahwati bersenandung. Mereka berempat kemudian menyatu dan berlari ke sana-kemari bertubrukan satu sama lain.
Ada bagian mereka mengangkat batu berulang-ulang. Sebuah repetisi. Judul Sisyphus memang mengandaikan mitologi Yunani, Sisyphus, yang ditafsirkan ulang filsuf eksistensialis Albert Camus. Tentang seseorang yang menggelundungkan batu berat naik ke atas bukit, tapi batu itu selalu jatuh, dan dia terus mendorong kembali batu itu tanpa paksaan. Ia mengulang, mengulang kembali, dan selalu bahagia.
Menarik bagaimana pementasan ini bisa lembut mengalir. "Trance" yang disajikan bukan jenis kesurupan liar, melainkan menghasilkan sesuatu yang enak dilihat dan sama sekali tak artifisial. Eno, misalnya. Ketika tubuhnya memutar-mutar, kita tak melihat putaran klise seperti gaya para darwish. Juga ketika punggung Agus berulang kali tertarik ke belakang, membuatnya mundur dan tersungkur. Pun Cahwati. Geraknya pada saat "trance" paling minim, hanya dua menit. Tapi, dalam dua menit itu, dengan rambut panjang terurai, tubuhnya mengigal-igal, seolah-olah kejang terjengkang ke belakang. Dua menit yang sangat kuat.
Suara musik mendukung atmosfer. Musik dihasilkan dari instrumen ciptaan pemusik Wukir Suryadi. Instrumen itu berbentuk gaharu yang panjangnya sekitar 2,5 meter. Bahan string-nya menggunakan kawat jemuran, kawat pancing, dan tali kopling Vespa. Instrumen itu digesek oleh Ikbal S. Lubys, lulusan musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta, menggunakan stik biola.
"Senar instrumen gaharu ini panjang. Kalau senar biasa tak ada," katanya. Instrumen itu mampu menghasilkan bunyi derum dan getar dengan frekuensi rendah. Deramnya kasar, garau, kemretak, kadang runcing. "Suaranya antara bunyi rebab dan cello," ujar Ikbal.
Ekspresi tubuh para performer terasa wajar. Mereka mampu mengesankan bahwa tubuh manusia Jawa mudah terbuka bagi dimensi-dimensi lain. "Sesuatu" bisa datang dan pergi ke dalam tubuh mereka—bisa hilang dan kembali lagi. Tubuh manusia Jawa sehari-hari adalah tubuh yang peka.
"Saya tak mengerti bahasa nyanyian yang dilantunkan, tapi suasananya tertangkap. Suasana shamanisme," kata Natalie Driemyer, dramaturg asal Bremen yang sengaja menonton pertunjukan di Frankfurt ini. Tatkala tubuh para performer kembali tenang dan mereka bersila lagi, dan Cahwati sebagaimana semula menuangkan air, suara gemericik itu sampai kita pulang pun masih membekas.
Seno Joko Suyono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo