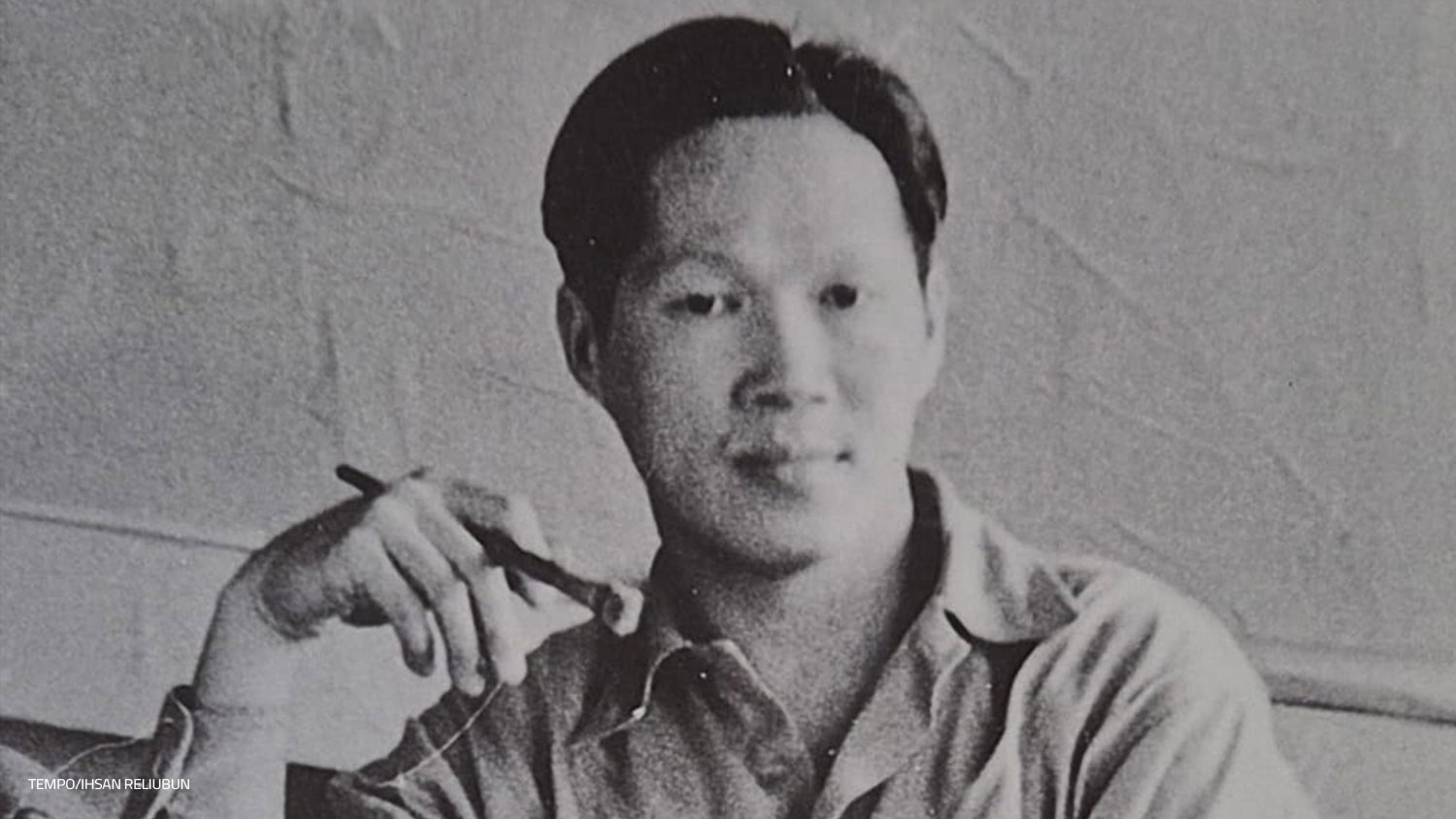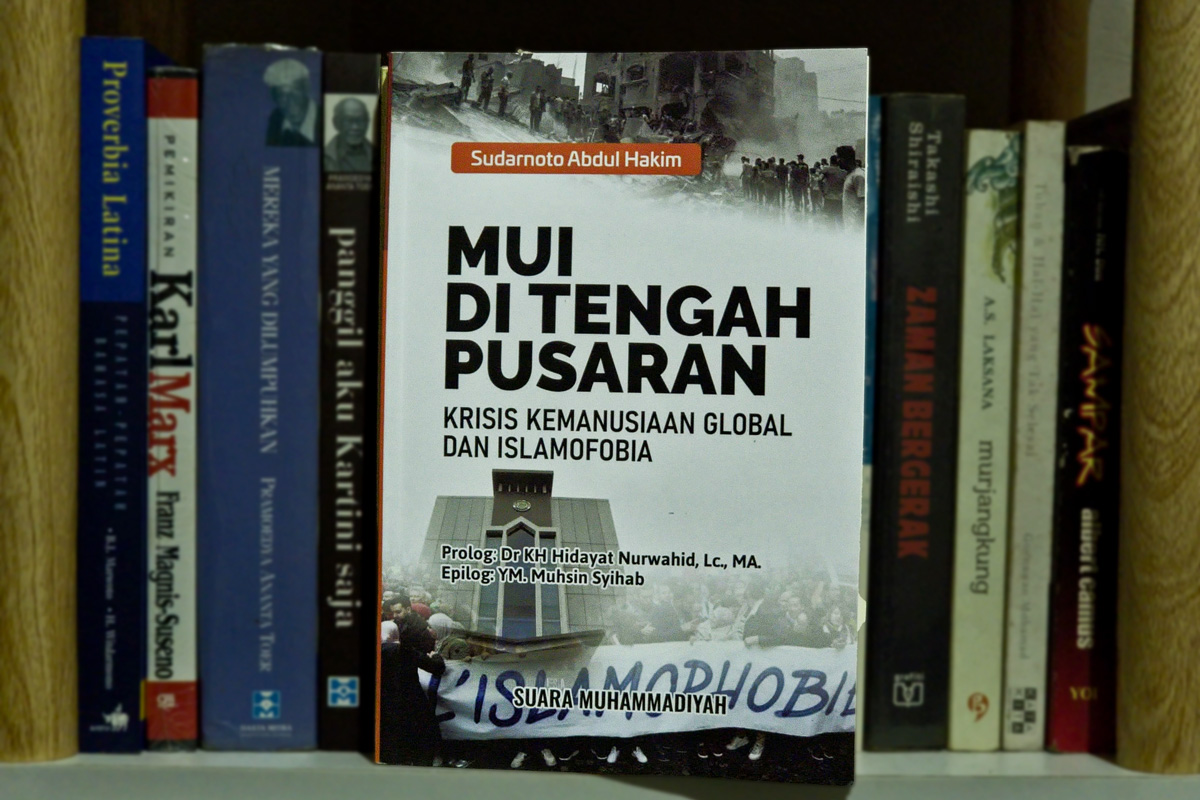Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TUJUH pasang kaki penari remaja Jailolo itu berderap. Berlompatan bagaikan pegas. Hampir satu setengah jam. Mereka bergerak membentuk berbagai formasi. Seperti kelompok ikan di dasar laut, seorang menyisih dari kelompok, memecah, menyebar, mengumpul lagi. Semua dilakukan dengan kaki-kaki yang terus-menerus bouncing, bergetar. Stamina mereka luar biasa. Peluh bercucuran.
Selama dua malam berturut-turut, Cry Jailolo karya Eko Supriyanto mengundang tepuk tangan yang hebat di gedung pertunjukan Mousonturm Frankfurt. Eko tampil dalam program Indonesia LAB. Inilah sebuah tari yang mengandalkan kekuatan otot-otot kaki. Inilah sebuah tari yang kembali kepada kemurnian tubuh. Sederhana. Minimalis. Bertolak dari elemen-elemen tradisi tapi hasilnya kontemporer.
Penonton penasaran. Apalagi ketika menyadari bahwa para penari Eko bukan penari profesional, melainkan anak-anak nelayan Jailolo. Mereka bertanya di manakah letak Halmahera Barat. Di manakah letak Jailolo. Mereka ingin tahu kehidupan beragama di Maluku Utara sekarang. Jailolo termasuk kawasan yang pernah dilanda konflik muslim-Katolik. "Anak-anak itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri perang tersebut," kata Eko. Beberapa penari memiliki pengalaman pahit. "Ada yang lahir dari seorang ibu gila. Ada yang pernah hampir terbunuh tapi kemudian justru dilindungi keluarga Katolik."
Untuk kebutuhan koreografi tarinya, Eko meriset tari-tarian di Jailolo. "Saya mengambil elemen tari Legusalai dari suku Sahu dan Soya-Soya, tarian perang khas Maluku Utara," ujarnya. Menurut Eko, getaran kaki ia ambil dari khazanah tari Legusalai. "Gerakan aslinya disertai tangan melambai-lambai." Dalam koreografinya, Eko lalu menambah tenaga. "Tempo saya cepatkan. Volume gerak saya tambah." Eko melihat ketahanan fisik remaja-remaja Jailolo luar biasa. "Mereka biasa memanjat pohon kelapa mengambil kopra. Bisa 50 pohon kelapa sehari. Bayangkan. Setelah itu, mereka langsung nyemplung ke laut." Bersama mereka, Eko menyelam. Di dalam laut, ia melihat kumpulan-kumpulan menggerombol, menyebar, mengumpul kembali. Itu dijadikannya ide koreografi.
Tapi mula-mula susah mengajak para remaja itu berlatih. Di Jailolo, anak-anak usia 17-21 tahun tak lazim menari. "Tari mereka selalu didominasi anak kecil atau orang tua. Generasi tengah tak ada," kata Eko. Keikutsertaan anak-anak itu berlatih terutama dilarang oleh orang tua mereka. Hampir tiap orang tua di Jailolo menginginkan anak laki-lakinya menjadi tentara atau polisi. Remaja-remaja itu awalnya sampai sembunyi-sembunyi saat latihan. "Ada penari saya yang saat latihan didatangi bapaknya. Ia dijambak dan diseret pulang," ujar Eko.
Tapi, setelah selesai, hasilnya mengejutkan Eko sendiri dan seluruh warga Jailolo. Selama kariernya sebagai koreografer, Eko tidak pernah sesukses sekarang. Ia membuat hat-trick. Selama tiga bulan Cry Jailolo berkeliling sepuluh festival di tiga benua. Dimulai pada Agustus berpentas di Darwin, Australia, mereka kemudian tampil di Hamburg (Jerman)-Groningen (Belanda)-Totori (Jepang)-Adelaide (Australia)-Zurich (Swiss)-Antwerp (Belgia). "Setelah dari Frankfurt, kami main di Düsseldorf, lalu Singapura," kata Eko. Dan, di setiap festival itu, mereka main bukan satu kali, melainkan bisa empat kali. Ada yang bahkan menjadi opening festival. Misalnya di Totori, Adelaide, dan Antwerp.
"Belum pernah terjadi dalam sejarah tari Indonesia ada touring international koreografer sebanyak ini. Sardono saja paling banyak bila ke Eropa hanya tiga kali pentas berturut-turut," ujar Iskandar Loedin, penata lampu Cry Jailolo, yang banyak mengikuti koreografer Indonesia tampil di luar negeri. Dan, hampir di tiap kota itu, sambutannya mengesankan. "Di Hamburg, seusai pentas, penonton sampai menggedruk-gedruk lantai dengan kaki menirukan bunyi kaki anak-anak," kata Iskandar.
Jerman adalah negara yang memiliki sejarah panjang ketertarikan pada budaya Indonesia. Museum-museum di sana, misalnya, banyak memiliki koleksi benda dari Jawa dan Bali. Datanglah Anda ke Museum der Weltkulturen di Frankfurt. Museum ini secara khusus memiliki 9.000 koleksi barang asal Indonesia yang dikumpulkan oleh etnolog, biolog, ornitolog, dan antropolog Jerman dari awal abad ke-20. Terutama koleksi kawasan timur Indonesia, seperti Pulau Seram, Alor, dan Solor (lihat tulisan mengenai Wukir dan Museum der Weltkulturen). "Koleksi benda dari kawasan timur Indonesia di museum kami jumlahnya ribuan, tapi belum diteliti lebih lanjut," ujar Vanessa von Glieczgrki, kurator seksi Asia Tenggara Museum der Weltkulturen.
Pada awal abad ke-20, novelis dan seniman Jerman termasuk yang memelopori seniman dunia mengeksplorasi Bali dan Jawa. Katakanlah Vicki Baum, artis dan penulis, yang menulis buku tentang Bali. Lalu yang tersohor adalah pelukis Walter Spies. Di paviliun Guest Honour Indonesia Frankfurt Book Fair, Anda bisa melihat sebuah buku luks mengenai Walter Spies turut dipajang. Penulisnya adalah John Stowell, peneliti seni dari University of Newcastle, New South Wales, Australia. Format buku itu besar, berisi lukisan Spies saat di Bali. Buku itu beratnya sampai 21 kilogram. Buku tersebut ditempatkan dalam boks kayu. Di Tanah Air sendiri, buku itu dibanderol Rp 55 juta.
Yang banyak belum diketahui adalah dalam sejarah tari modern Jerman ternyata Indonesia memiliki "peranan". "Sejarah tari modern di Jerman diawali ketertarikan tentang tubuh non-Eropa, terutama tubuh Asia. Penari Julius Hans Spiegel pada awal abad ke-20, misalnya. Ia sangat tertarik pada tari Indonesia. Ini banyak yang tidak tahu. Dia dilupakan dalam sejarah tari Jerman," kata Anna Wagner, kurator program Mousonturm yang memilih Eko Supriyanto untuk tampil di Indonesia LAB.
Hans Spiegel adalah sosok yang unik. "Sekitar 1920, dia bersahabat akrab dengan Raden Mas Djojana," ujar Anna. Raden Mas Djojana adalah pangeran asal Yogyakarta yang tinggal di Belanda. Ia banyak mencipta karya tari dan mementaskannya keliling Eropa. Djojana banyak bergaul dengan kalangan seniman Eropa. Pelukis Isaac Israel, misalnya, salah satunya. Djojana banyak dilukis oleh Isaac Israel. Akan halnya Hans Spiegel memiliki kedekatan khusus dengan Djojana. "Spiegel banyak mendapat hadiah dari Djojana berupa topeng dan kostum tari."
Dalam risetnya, Anna menemukan banyak foto Spiegel pada era itu mencoba berpose dan menari seperti penari Jawa. Kadang kostumnya campur aduk. Ia mengenakan sarung Jawa, lalu selempang Thailand, tapi juga kuku-kuku rangda dari Bali. "Gaya Spiegel, yang tertarik pada eksotisme Asia, kemudian mempengaruhi penari seperti Mary Wigman dan Mata Hari," kata Anna. Mata Hari, kita ketahui, adalah penari yang kemudian menjadi mata-mata terkenal.
Eksplorasi Eko di Halmahera yang memperluas khazanah tari kontemporer Indonesia tak hanya berangkat dari idiom Jawa, Bali, atau Padang dianggap Anna Wagner penting. Karena itu, memanfaatkan momentum dipilihnya Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam Frankfurt Book Fair 2015, ia merancang sebuah festival seni khusus yang dinamakan Indonesia LAB. Ini forum yang mempertunjukkan bagaimana pentas tari kontemporer Indonesia masa kini diolah dari pergulatan tubuh dari Jawa, Halmahera, sampai Papua. Selain Eko, yang tampil adalah Melati Suryodarmo dan Jecko Siompo.
Dalam subprogram yang dinamakan Choreographer LAB, Anna juga mempertemukan beberapa penari Indonesia untuk berkolaborasi dengan komposer atau penari Eropa. "Mereka sebelumnya tak saling mengenal. Kami pertemukan agar terjadi semacam blind date." Tujuan Choreographer Lab adalah agar mereka saling berproses untuk mengenal tubuh, lalu proses itu disajikan kepada publik. Hasil akhir tak diutamakan. Mereka yang terlibat adalah Darlane Litaay-Tian Rotteveel, Fitri Setyaningsih-Nicola Mascia, Agus Margiyanto-Ioannis Mandafounis, dan Elia Nurvista-Josh Johnson.
Program Indonesia LAB dirancang jauh oleh Anna Wagner. Pada 2014, ia bekerja di Hans Spiegel Centre Freiburg. Anna mengundang Eko Supriyanto membuat karya tari berdasarkan barang-barang milik Hans Spiegel yang kini disimpan di Museum Munich. Eko menerima tawaran, tapi ia menolak membuat sesuatu yang eksotis tentang Indonesia sebagaimana Spiegel. "Saya tidak ingin terjebak pada eksotisme. Saya malah ingin membuat tari bertolak dari sisi humanis Spiegel, yaitu sosok Spiegel yang bisu dan tuli," ujarnya. Hans Spiegel adalah seorang tunarungu dan tunawicara. "Dia tuli total, tapi dia berusaha mendengarkan gamelan," kata Anna.
Eko ingat, bersama Anna, ia pergi ke Muenchen. "Saya ke Museum Munich untuk menyaksikan topeng-topeng milik Hans Spiegel," ujar Eko. Dia lalu meminta dipertemukan dengan komunitas bisu-tuli di Freiburg. Eko ingin membuat koreografi dengan penari tunarungu seperti Spiegel. Sekitar 120 penyandang tunarungu mengikuti workshop tersebut. Eko juga mengundang Bondan Wrahatnolo, etnomusikolog dari Institut Seni Indonesia Solo, untuk memainkan gamelan. Ia ingin bereksperimen, melihat apakah para penyandang tunarungu itu bisa merasakan getaran gamelan sebagaimana Spiegel. Eko kemudian memutuskan membuat koreografi dengan mereka membawa balon. Ternyata para penyandang tunarungu itu bisa merasakan getaran dari balon.
Diputuskan kemudian pentas berupa tarian tunggal. "Saya ingat, yang terpilih namanya Lua Leiner. Dia orang Basel, Swiss," kata Eko. Eko meminta Lua mengenakan topeng Panji. Tapi, saat memakai topeng, Lua merasa sesak dan hampir tidak bisa melihat. Ia memprotes Eko. "Saya sudah bisu-tuli, sekarang kamu menambah saya buta," ujarnya seperti diingat Eko. Toh, kemudian tarian itu, menurut Eko, menjadi "ajaib". Sebagian besar penonton yang hadir adalah penyandang tunarungu yang membawa balon.
Yang juga menohok di Indonesia LAB adalah kolaborasi Darlane Litaay (Papua) dan Tian Rotteveel (Belanda). Begitu masuk Studio 1 Mousonturm, ruangan kecil dengan kapasitas tak lebih dari 75 penonton, kita melihat Darlane dan Tian bercakap-cakap santai, seolah-olah ini bukan pertunjukan. Darlane mengenakan kaus merah. Rambutnya terurai. Mereka bertukar gerak. Darlane memencet telepon selulernya dan menyuruh Tian bergerak berdasarkan bunyi-bunyian ponselnya. Penonton melihat di antara mereka mulai terjalin keakraban. Tian lalu mengotak-atik meja engineer, memperbesar suara musik techno dari laptopnya. Muncul gemuruh dan psychedelic.
Tiba-tiba Darlane, di tengah suasana "ambience" itu, melepas baju dan celananya. Koreografer lulusan ISI Yogyakarta itu telanjang bulat, yang membuat penonton terperenyak. Darlane lalu hanya mengenakan koteka, yang tak kuasa menutupi bulu-bulu kemaluannya. Lantas ia menunjuk-nunjuk Tian untuk melakukan hal yang sama dengannya. Tian seperti bingung. Menghadap penonton, ia membuka baju dan celananya ikutan telanjang bulat. Lalu Tian memasang koteka. Kotekanya berbeda dengan yang dipakai Darlane. Puncaknya, mereka berdua "kalap". Seperti orang kesurupan, mereka memencet-memencet peralatan engineer suara dan mendorong mejanya ke sana-kemari, menimbulkan bunyi berdebum-debum. Sungguh sesuatu yang tak terduga.
Seusai pementasan, terjadi diskusi menarik. Penonton bertanya dari kota mana Darlane berasal. Apakah kebiasaan koteka suku Dani di Lembah Baliem, bagi Darlane, menjadi identitas dirinya atau hanya sesuatu yang eksotis. Adalah menarik membandingkan pentas Darlane dengan karya Jecko Siompo, In Front of Papua, yang dipentaskan di forum ini juga. Ini karya lama dan pada 2011 pernah dipentaskan di Jerman. "Karya ini membicarakan spesies binatang di Papua dan masih aktual karena makin banyak spesies ikan purba ditemukan di Raja Ampat. Saya sendiri masih ingin membuat karya mengenai biawak lampu. Dulu, saat saya kecil di Jayapura, malam-malam saya sering melihat ada binatang berbintik-bintik cahaya melesat dalam rerimbunan. Tapi, menurut Mama, saya berhalusinasi saja."
Dua karya ini bila kita bandingkan menampilkan pendekatan Papua yang berbeda. Anna Wagner menampik anggapan bahwa ia ingin menyajikan eksotisme Papua bagi publik Jerman. Baginya, Jecko dan Darlane adalah anak muda urban yang melakukan refleksi ulang terhadap tradisi. "Identitas mereka kompleks. Berlapis-lapis. Coba Anda tatap mata tujuh mata anak Jailolo. Terlihat ekspresi individu, bukan?" Jecko sendiri merasa bahwa asal-usulnya berlapis-lapis. "Saya Papua Islam. Kakek saya dari Tidore. Karena itu, saya merasa tak asing melihat karya Eko, Cry Jailolo."
Yang menarik, hal berlapis-lapis demikian juga dirasakan oleh Tian Rotteveel. "Ibu saya masih keturunan Keraton Yogya. Kakek saya serdadu KNIL dan pernah ditawan selama tiga tahun oleh Jepang. Saat Indonesia merdeka, kakek saya memilih ke Belanda membawa ibu saya yang masih berumur enam tahun. Ibu saya sudah tua sekarang, sama sekali tak ingat Indonesia, tak bisa berbahasa Jawa." Di akhir pertunjukannya, Tian membacakan sebuah surat untuk penonton:
"Penonton yang baik,
Kami tidak mengenal Anda, sesungguhnya. Tapi mungkin kita dapat sedikit saling mengenal sekarang. Kami tak tahu apa yang bisa kami bagi dengan Anda. Tapi kami merasa sudah berbagi. Berbagi sesuatu yang universal...."
Di Frankfurt, Oktober ini, kita merasakan kehadiran Indonesia di mana-mana. Di berbagai sudut Frankfurt, dari kafe, perpustakaan, kampus, museum, sampai galeri, para sastrawan Indonesia berdiskusi dan para perupa berpameran. Di Zentralbibliothek, Redha Gaudiamo dan Ari Malibu menyanyikan sajak-sajak Sapardi Djoko Damono. Di Portico, bangunan klasik mirip kapel yang letaknya di tengah jembatan Sungai Frankfurt, ada pameran Ade Darmawan.
Di galeri kafe Frankfurter Kunstverein, yang letaknya di Romersberg, kawasan yang ada sejak zaman Romawi, perupa Joko Avianto membuat instalasi bambu memikat berjudul Big Tree. Joko membawa 1.525 bambu dari Jawa Barat. Bambu-bambu itu kemudian di Frankfurt dibuatnya melengkung-lengkung dan dipasang menutupi hampir separuh sisi muka kafe Frankfurter Kunstverein, kecuali pintu masuk dan jendela-jendelanya. Siapa saja yang lewat di situ pasti terperangah melihat bambu-bambu itu bisa sedemikian plastis. Pelintir-memelintir. "Pemerintah Kota Frankfurt sampai meminta saya memperpanjang pameran. Instalasi saya diminta sampai September tahun depan," kata Joko. Tak jauh dari tempat Joko, Fotografie Forum Frankfurt menggelar pameran bertajuk "Beyond Transisi, Contemporary Indonesian Photography", yang melibatkan di antaranya karya Oscar Motuloh dan Kemal Jufri. Di Haus am Dom, bangunan milik katedral, Rahmayani menggelar pameran.
Di sepanjang Jalan Schaumainkai, jalan di Frankfurt yang terkenal dengan deretan museumnya, aroma Indonesia juga merebak. Di Deutsches Architektur Museum atau Museum Arsitek digelar pameran "Tropicality Revisited" dengan kurator Avianti Armand. Di Weltkulturen Museum, etnomusikolog Philip Yampolski dan Endo Suanda akan membahas cara merekam musik tradisi Indonesia dan ada pementasan musik eksperimen Wukir Suryadi. Di Deutsches Filmmuseum atau Museum Film dan Game, sebuah festival film yang dikoordinasi Slamet Rahardjo akan disajikan. Di situ, film-film seperti Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo, Cahaya dari Timur dari Angga Dwimas Sasongko, dan Sebelum Pagi Terulang Kembali karya Lasja P. Susatyo ditayangkan.
Belum lagi paviliun kehormatan Indonesia sendiri. Di paviliun yang sangat artistik dan luas ini ada sebuah stage berbentuk arena, yang selama Frankfurt Book Fair akan diisi berbagai pementasan, dari topeng Cirebon sampai Betawi. Nuansa seni Indonesia sudah sangat terasa saat Endah Laras melantunkan Suluk Malang Sumirang di Opening Frankfurt Book Fair, 13 Oktober lalu. Lalu Goenawan Mohamad secara mengesankan mendeskripsikan Suluk Malang Sumirang.
Di depan Menteri Kebudayaan dan Media Jerman Monika Grütters, Wali Kota Frankfurt Peter Feldman, Presiden Asosiasi Penerbit dan Toko Buku Jerman Heinrich Riethmüller, Direktur Frankfurt Book Fair Juergen Boss, serta ratusan insan penerbitan dan sastrawan, Goenawan bercerita tentang Malang Sumirang, seorang sufi Jawa yang dibakar oleh sultan tapi tubuhnya tak hangus. Menjelang dimasukkan ke kobaran api, ia meminta kertas dan tinta untuk menulis sajak. Goenawan seolah-olah ingin mengatakan bahwa Indonesia, negeri kepulauan yang tak dikenal ini, memiliki tradisi susastra yang sangat tua.
Dan tradisi tua itu juga yang akan dipercakapkan di paviliun. Di paviliun, misalnya, akan dibahas Babad Diponegoro. Selain pementasan di dalam paviliun, para musikus dan penari kita tampil di arena panggung terbuka Frankfurt Book Fair, yang dinamakan Agora (pasar dalam bahasa Yunani). Tak lupa, Komite Nasional Indonesia mementaskan Gandari, opera tari prestisius karya Tony Prabowo dan Goenawan Mohamad dengan koreografer Su Wen Chi, di Frankfurt LAB, tempat kesenian alternatif yang didirikan penari terkenal William Forshyte dan sekarang didanai oleh Ensemble Modern—kelompok musik papan atas Frankfurt. Pementasan ini diiringi oleh Ensemble Modern Academy.
Forum seperti Indonesia LAB menambah semarak "suasana Indonesia" selama Frankfurt Book Fair. Anna Wagner berharap penonton Jerman mampu menangkap bagaimana para koreografer Indonesia memiliki cara pandang baru dalam melihat tubuh tradisi. "Melati Suryodarmo, misalnya, menggunakan shamanism tapi tidak memandang ke belakang. Ia menghubungkan dengan kondisi kita sebagai manusia modern sehari-hari. Ini menarik karena shamanism selalu menjadi topik yang hangat dalam dunia tari Jerman," kata Anna.
Seno Joko Suyono (Frankfurt)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo