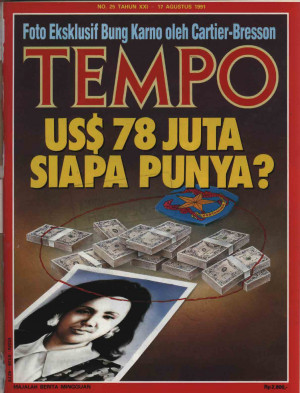Kaum ulama ada kalanya memandang kegiatan bisnis sebagai penghalang jalan ke surga. Wajar bila kemudian nonpri yang kebanjiran rezeki. ISU kesenjangan sosial antara pri dan nonpri masih menggelinding. Di tengah-tengah itu, tampil Kebangkitan Pengusaha Muslim. Ini adalah buku rangkuman berbagai makalah dari "Dialog Bisnis Muktamar Muhammadiyah ke-42" mengenai dikotomi pengusaha lemah-kuat, muslim-nonmuslim. Syukuran atas terbitnya buku yang disunting B. Wiwoho awal bulan lalu itu juga ditandai dengan terbentuknya Yayasan Amanah Umat. Yayasan ini bertugas memobilisasi, mengelola, dan memanfaatkan zakat, infak, dan sedekah. Pada akhir acara, para pengusaha, pejabat, dan hadirin lainnya disodori formulir sumbangan. Malam itu, di Hotel Hilton, terkumpul Rp 300 juta, plus Rp 150 juta yang masuk sebelumnya. Buku itu merangkum 12 makalah. Sebagian penyumbang tulisan yang hadir dalam acara syukuran itu antara lain Dirjen Pajak Mar'ie Muhammad, Menteri Muda Keuangan Nasrudin Sumintapura, Menteri Perdagangan Arifin M. Siregar, Menteri Muda Pertanian Syarifudin Baharsyah, Sekretaris Yayasan Tunas Bangsa Junus Jahja, dan Soetrisno Bachir dari Grup Ika Muda. Inti "Dialog Ekonomi Muhammadiyah" yang tersimpul dari buku itu tampaknya tak bisa dilepaskan dari persoalan pri dan nonpri, minoritas dan mayoritas. Kesenjangan antara mayoritas dan minoritas, menurut para penulis, punya potensi mengundang kecemburuan sosial. Rahimi Sutan, Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah, menilainya sebagai ironi. Islam mengajarkan penganutnya mencari rezeki sebanyak-banyaknya dan menentang kemelaratan. "Kenyataannya masih banyak di antara mereka yang berada dalam kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan," tulisnya. Artinya, potensi ekonomi umat Islam tampak kedodoran, apalagi bila dibandingkan dengan nonpri yang umumnya nonmuslim. Junus Jahya mencatat, dalam sejarah, umat Islam pernah melahirkan saudagar-saudagar besar, seperti Hasyim Ning, Nitisemito, Djohan Djohor, dan Gobel. Namun, kini dunia usaha terpusat ke tangan etnis Cina, baik yang telah WNI maupun yang masih WNA. "Mereka inilah yang ternyata lebih siap menanggapi dan menampung tantangan," tulis Junus Jahja dalam "Etnis Cina Perlu Terobosan Baru". Probosutedjo, dalam "Pengembangan Potensi Bisnis di Lingkungan Muhammadiyah", menaksir sekitar 90% konglomerat di negeri ini adalah nonpri. Para pengusaha pribumi -- yang sebagian besar muslim -- katanya, merupakan pengusaha lemah yang berada di papan bawah kegiatan bisnis. Mereka sering tergilas oleh kelompok konglomerat. Menurut Probo, penyebab terjadinya ketimpangan itu adalah adanya pandangan yang menganggap orang-orang pribumi tak becus berdagang, tak disiplin, susah diajar, dan bodoh. Sebaliknya, pengusaha keturunan Cina telanjur menjadi mitos pengusaha yang lihai. "Cina-Cina di Indonesia yang dapat menjadi konglomerat pada umumnya karena memperoleh kemudahan dari para pejabat untuk mendirikan berbagai usaha, bahkan kemudahan dalam memperoleh proyek serta kemudahan dalam memperoleh kredit dari bank-bank pemerintah," tulis Probo. Probo yakin, apabila para pengusaha pribumi memperoleh kemudahan yang sama, mereka tak akan kalah lihai dengan pengusaha-pengusaha keturunan Cina. Namun, ia tak menutup mata pada kelemahan penduduk pribumi sendiri, terutama pandangan umat Islam terhadap kegiatan bisnis. "Mungkin karena kurangnya perhatian para juru dakwah dan para ulama mengenai keadaan pertumbuhan dunia, terutama dalam bidang ekonomi, maka setiap umat muslim selalu mengutamakan ajaran spiritual yang bertujuan mencapai surga," tulisnya. Menteri Perdagangan Arifin M. Siregar tampak lebih srek dengan pendapat Probo yang terakhir itu. Masyarakat muslim, misalnya, belum siap menyongsong kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang digulirkan Pemerintah. Sejumlah faktor, katanya, membuat mereka terlempar dari persaingan yang semakin ketat. Ada sikap yang lembek dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dunia usaha. "Kegiatan dunia usaha tak hanya terdiri dari keberhasilan yang terus-menerus, tapi sering pula diliputi oleh masalah-masalah sulit yang memerlukan keuletan dan daya cipta," kata Arifin Siregar dalam buku itu. Sebaliknya, Menteri Muda Keuangan Nasrudin Sumintanura tak sepenuhnya menyalahkan pengusaha pribumi. Ia menunjuk kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang penjabaran operasionalnya belum jelas benar. Itu yang kemudian justru memukul pengusaha menengah ke bawah. Untuk mengatasinya, "Peraturan-peraturan yang ada harus baku dan transparan sehingga di samping menutup kemungkinan adanya permainan birokrasi yang tak sehat, juga memberikan kepastian hukum dan kesempatan yang sama kepada masyarakat," katanya. Pemerintah bukannya tak menyadari adanya kesenjangan yang ada. Berbagai usaha telah ditempuh untuk mengatasinya. Misalnya lewat kebijaksanaan perpajakan. Dirjen Pajak Mar'ie Muhammad sadar bahwa peranan pajak sebagai alat redistribusi memang penting. Untuk membantu pengusaha kecil, misalnya, Pemerintah membebaskan mereka dari kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Pengusaha kecil di sini adalah perusahaan yang omzetnya Rp 60 juta ke bawah untuk barang dan Rp 30 juta ke bawah untuk jasa," tulis Mar'ie. Namun, masih menurut Mar'ie, itu belum cukup. Berbagai mekanisme dan kebijaksanaan diperlukan untuk mengatasi masalah pengusaha pri dan nonpri, atau muslim dan nonmuslim. "Apakah tak perlu, misalnya, undang-undang perlindungan dan pengembangan usaha menengah dan kecil?" tulisnya. Priyono B. Sumbogo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini