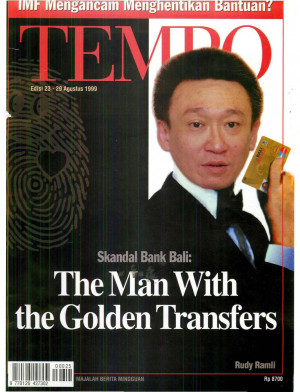BANYAK kalangan menuduh WNI keturunan "Cina" tak lebih dari sekadar economic animal. Mereka, demikian tuduhan itu, tak punya jiwa nasionalis; banyak di antaranya melakukan bisnis dengan cara KKN dengan penguasa yang korup, atau membawa terbang modal ke luar negeri. Mereka tak punya sumbangan apa pun untuk Indonesia.
Benarkah demikian? Menelusuri sejarah panjang Orde Baru, kita akan menemukan bahwa lewat berbagai kebijakan pemerintah, keturunan Tionghoa memang digiring melalui ruang labirin untuk akhirnya hanya bisa bergerak di sektor swasta: pedagangan. Dari KTP yang diberi stigma, pembatasan memasuki perguruan tinggi negeri, hambatan memasuki karir ABRI-PNS dan birokrasi pemerintah, hingga berbagai aksi "penjinakan" lewat politik kebudayaan.
Yang terjadi kemudian adalah, Orde Baru mencabut peranan kaum Tionghoa dari sejarah formal Indonesia, seolah-olah orang Tionghoa tak punya peranan penting apa pun dalam pembentukan nation-state Indonesia. Padahal, sejak awal pembentukan kesadaran nasionalisme hingga zaman pemerintahan Sukarno, banyak di antaranya yang menempati berbagai posisi penting, dari guru, wartawan, tenaga medis, pengurus partai, diplomat, hingga militer dan anggota kabinet.
Siauw Giok Tjhan adalah salah satu di antaranya. Tokoh berpenampilan bersahaja yang lebih suka mengenakan kain dril warna putih ini adalah tokoh besar di kalangan warga keturunan Tionghoa. Sejak awal, ia bukan hanya memperjuangkan golongan Tionghoa, tapi ikut berjuang membela cita-cita Indonesia merdeka. Sejak muda, ia menentang sikap mayoritas orang Tionghoa Indonesia yang berkiblat ke Tiongkok atau pemerintah kolonial Belanda.
Pada 1932, ketika berusia 18 tahun, Siauw Giok Tjhan bekerja sebagai wartawan dan aktif berjuang bagi Indonesia, yang dianggapnya sebagai tanah airnya sendiri. Lantas, pengagum sosok Cipto Mangunkusumo ini terpilih sebagai salah satu pimpinan Partai Sosialis yang kemudian menyebabkannya terpilih sebagai anggota KNIP. Pada zaman Kabinet Amir Sjarifuddin, ia menjabat sebagai anggota pekerja KNIP sekaligus sebagai Menteri Urusan Minoritas. Dalam masa-masa awal Republik, ia berada di tengah-tengah pergaulan penting pusat kekuasaan.
Gagasan Siauw tentang minoritas Tionghoa adalah bahwa warga Tionghoa harus diterima sebagai salah satu suku bangsa Indonesia, tanpa perlu menghilangkan ciri etnisitasnya. Ia memimpikan Indonesia bisa jadi sebuah nation yang pluralistis. Impian itu pada kemudian hari disalurkannya lewat Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), tempat ia menjabat sebagai ketua. Presiden Sukarno dalam sejumlah pidatonya selalu menyebut nama tokoh Tionghoa kelahiran Surabaya ini dengan panggilan akrab "Cak Siauw".
Gagasan Siauw tentang keberadaan minoritas Tionghoa sebagai bagian nation-state Indonesia merupakan bagian dari gagasan besar tentang masyarakat sosialis Indonesia yang harus segera direalisasi. Baperki, di bawah kepemimpinan Siauw, memperkenalkan ide tentang "integrasi" sebagai jalan keluar aksi rasialisme terhadap keturunan Tionghoa. Ide ini mendapat tentangan keras dari kelompok "asimilasionis" yang dikembangkan sejumlah tokoh Tionghoa dari kubu Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) yang didukung sayap kanan Angkatan Darat. Presiden Sukarno menyokong gagasan Siauw. Alhasil, Baperki dan Siauw pun mendapat stigma sebagai kelompok revolusioner kiri.
Saat Sukarno "digulingkan", Siauw ikut digulung. Baperki dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Puluhan sekolah dan universitas yang didirikan Siauw disulap jadi kantor militer dan gedung milik "swasta". Ratusan pendukung Baperki diculik dan "dihilangkan" oleh sejumlah barisan pemuda yang didukung tentara. Siauw agak beruntung. Ia "hanya" wajib masuk hotel perdeo Orde Baru selama 10 tahun, sejak November 1965. Pada September 1975, statusnya diubah jadi tahanan rumah. Meskipun demikian, siksaan, tekanan psikologis. Yang dialaminya selama dalam masa tahanan membuat kesehatannya, terutama matanya, merosot drastis.
Atas bantuan sahabatnya, Adam Malik, pada September 1978 Siauw diizinkan berobat ke Belanda. Sebuah kesempatan yang tak disia-siakan Siauw untuk mengampanyekan kondisi Indonesia.
Ia meninggal pada 20 November 1981, beberapa menit sebelum menyampaikan pidatonya di Universitas Leiden.
Buku ini adalah buku yang perlu dibaca oleh siapa saja yang berminat dengan sejarah Indonesia, khususnya sejarah dan peranan orang Tionghoa, yang digelapkan selama Orde Baru. Kelebihan buku ini—yang ditulis oleh putra Siauw sendiri—adalah karena penulisnya berhasil menjaga jarak dengan "subyek" yang ditulisnya, dan ia juga memperkayanya dengan sejumlah nuansa human interest. Barangkali karena itulah, sang penulis, atas jerih payah karyanya, dianugerahi gelar doktor oleh Universitas Monash, Australia.
Buku penting tentang minoritas Tionghoa ini barangkali lebih tepat sebagai "pengantar besar" bagi buku Lima Zaman karya Siauw Giok Tjhan, yang dilarang pemerintah Orde Baru. Buku ini adalah kisah potret pahit seorang pejuang yang disulap jadi pengkhianat oleh penguasa—yang pada suatu masa berkuasa sepenuhnya atas catatan sejarah.
Stanley J.A. Prasetya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini