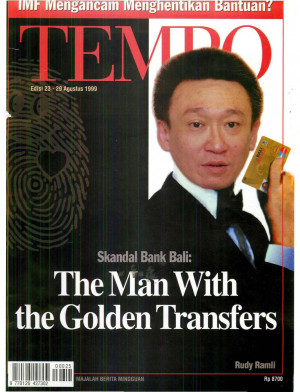| Penulis | : | Martin Aleida | | Penerbit | : | Emansipasi Damar Warga, 1999 |
BUKU karya Sulami bisa dibandingkan, minimal disandingkan, dengan buku Sebelum Prahara karya Rosihan Anwar, atau Catatan Subversif karya Mochtar Lubis, atau Surviving Indonesia's Gulag karya Carmel Budiardjo. Kesamaan semua buku ini adalah tema cerita yang mengisahkan pengalaman penulisnya (semacam catatan harian) di dalam penjara sebagai tahanan atau narapidana politik yang dituduh berbuat makar dan subversi terhadap penguasa (musuh negara). Ada ketidakpastian, kemarahan, kekecewaan karena merasa diperlakukan tidak adil, hak-hak asasi mereka dilanggar, dan mendapat perlakuan yang tidak layak sebagai manusia. Bedanya, jika dua penulis pertama ditahan pada masa Orde Lama di bawah Sukarno, yang belakangan, sebagaimana Sulami, ditahan pada periode Orde Baru di bawah Soeharto. Namun, secara kualitas maupun kuantitas, fenomena tahanan politik harus diakui mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, khususnya setelah G30S-PKI.
Buku yang ditulis oleh Sulami ini—saat itu memiliki jabatan sebagai Wakil Sekjen II Gerwani, yang juga sekaligus korban—adalah bagian dari persoalan sosial-politik yang muncul dan berkembang saat itu, dan imbasnya tetap ada hingga saat ini. Sulami ditahan selama 20 tahun dengan tuduhan melakukan aksi subversi atau makar terhadap negara, tepatnya pada peristiwa G30S-PKI pada 1965, ketika PKI dan seluruh organisasi bawahannya dan simpatisannya dituduh berada di balik peristiwa tersebut. Sebagaimana sudah mulai terbuka lebar, di samping enam perwira tinggi dan satu perwira muda yang mati, ada estimasi sekitar tiga perempat juta orang dibantai dalam suatu pertumpahan darah antikomunis, dan ratusan ribu orang dijebloskan dalam penjara gara-gara dicurigai, difitnah, dan bahkan asal dicomot saja dengan tuduhan terlibat dalam peristiwa G30S. Suasana perang dingin saat itu menyebabkan negara-negara Barat, khususnya AS dan Inggris, terkesan menutup mata terhadap kejadian pembantaian tersebut.
Untuk lebih "produktif" dalam memahami buku ini, ada dua faktor yang saling berkaitan yang bisa diangkat sebagai pijakan awalnya. Pertama berkaitan dengan apa yang disebut sebagai "kebenaran sejarah". Siapa yang paling berhak menentukan catatan sejarah sebagai suatu peristiwa yang salah atau benar? Apa yang menjadi ukuran untuk bisa menentukan autentiknya suatu peristiwa sejarah tertentu? Mungkin tidak terlalu salah jika ada yang mengatakan bahwa sejarah hanyalah catatan buat mereka yang menang. Sebaliknya, mereka yang kalah atau dikalahkan sudah pasti akan tampil dalam bentuknya yang "buruk rupa", atau bahkan tenggelam tanpa orang tahu apa peranan dan jasanya dalam suatu peristiwa. Kalaupun ada, ia tak lebih hanya sebagai pelengkap penderita.
Selanjutnya, yang kedua, dalam dunia politik saat itu, garis batas antara kebaikan dan keburukan, pahlawan dan pengkhianat, hanya seujung rambut. Suatu ketika, seseorang bisa menjadi pejuang kemerdekaan (freedom fighter), tapi dalam seketika juga, ia bisa dianggap sebagai seorang yang subversif atau musuh negara.
Pada faktor pertama, terlihat jelas, sejarah Orde Baru adalah sejarah yang dibuat oleh penguasa, yang menulis teks dan menguasainya sekaligus. Hampir tidak pernah ada, khususnya teks resmi dari pemerintah atau bahkan media massa, yang berbicara tentang penangkapan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan lain terhadap para tahanan politik yang dituduh bertanggung jawab, baik langsung maupun tidak, atas peristiwa G30S-PKI. Sebaliknya, yang tampil ke permukaan adalah pembunuhan terhadap para jenderal, dan kekejaman yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pembunuhan tersebut. Pesannya jelas, periode sebelum lahirnya Orde Baru adalah periode ketika terjadi konflik politik yang tajam, dan bahkan sebagai periode "musibah" bagi rakyat Indonesia. Ada monopoli atau bahkan hegemoni terhadap sejarah yang menggambarkan peristiwa prahara tersebut. Contohnya yang termudah adalah dengan melihat film Pengkhianatan G30S-PKI" yang pada dasarnya merupakan upaya mereproduksi "realitas" atas peristiwa versi resmi negara tersebut.
Padahal, sebagaimana ditulis buku ini, ada "realitas" lain (yang nyatanya memang kalah dalam sejarahnya), yang menggambarkan kekejaman yang dialami para tahanan politik tersebut. Sebagaimana dikutip Sulami, ia membandingkan pengalaman dirinya dan kawan-kawan senasib yang mendapat perlakuan kejam dari aparat militer dengan wajah serdadu-serdadu Jepang yang sedang menghajar pemuda-pemuda pejuang Indonesia, atau dengan peristiwa ketika Belanda menangkapi penganut komunis dan kemudian dibuang ke Boven Digul. Namun, yang belakangan ini kekejamannya masih berdasarkan hukum karena masih memakai surat perintah, tidak ada upaya menjarah, apalagi mengutak-atik keluarganya. Cerita seperti ini—kecuali mungkin hanya sebagai "bisik-bisik" di antara kelompok dalam masyarakat atau ada tercantum dalam beberapa buku atau tulisan wartawan dan kalangan akademisi asing—hampir pasti "absen" dalam khazanah sejarah Indonesia. Dengan demikian, sejarah tidak pernah netral, apalagi obyektif. Ada elemen kepentingan politik dan ada kekuasaan di baliknya. Ada hegemoni atau dominasi yang terkait erat di dalamnya.
Menurut Michael van Langenberg, ada tiga tujuan utama di balik cerita versi resmi G30S-PKI (atau "Gestapu") tersebut. Pertama, sebagai alat propaganda dalam menghancurkan struktur pimpinan PKI dan kader massanya; kedua, sebagai alat peringatan yang tidak main-main kepada mereka yang mencoba melawan elite kekuasaan yang baru; dan ketiga, sebagai alat untuk menciptakan pemutusan sejarah yang dramatis.
Sementara itu, pada faktor yang kedua, istilah subversi atau makar sebagai musuh negara memiliki definisi yang sangat lentur sedemikian rupa sehingga batas-batasnya semakin tidak jelas. Pada masa Orde Baru, ketika pengertian tentang musuh negara, sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Anti-Subversi, bisa sangat luas, semua bentuk kegiatan dan pemikiran apa pun dengan sangat gampang bisa dikategorikan sebagai musuh negara: dari mereka yang dituduh terlibat G30S-PKI, gerakan mahasiswa, orang yang membawa dan membaca buku "terlarang", mereka yang dianggap bermaksud mendirikan negara Islam, hingga kelompok-kelompok separatis seperti GAM, Fretilin, dan OPM. Orang bisa ditahan, dan bahkan tanpa diadili, jika sudah dituduh memiliki pemikiran yang anti-Pancasila, anti-UUD l945, dan anti-RI. Dalam buku ini terlihat jelas, Sulami, yang pernah ikut berjuang dalam perang kemerdekaan di daerah Gunung Lawu hingga Mranggen bersama TNI, tiba-tiba setelah peristiwa G30S-PKI menemukan dirinya sebagai buronan politik yang masuk dalam daftar musuh negara. Dirinya dilihat sebagai orang yang memiliki pandangan politik atau kepercayaan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan negara. Sampai di sini, jelas buat kita, ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang bisa dilihat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara di sini (baca: Orde Baru) telah melakukan kekerasan (violence by action), baik itu bersifat langsung (state-directed) maupun tidak langsung (state-supported). Atau, negara telah gagal, bahkan mengabaikan terjadinya kekerasan terhadap sebagian besar masyarakat (violence by omission) yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab atau kewajiban negara untuk melindungi warganya, menciptakan perasaan aman dan ketenteraman.
Memang benar, orang bisa berkata bahwa buku ini bukan buku sejarah yang "baik" dan "benar", yang tidak jelas metodologinya, tidak ada referensinya, dan sangat subyektif. Namun, itu karena selama ini tidak ada celah, masukan, atau alternatif lain yang boleh hadir di luar "kebenaran sejarah" versi Orde Baru. Ada "kotak pandora" yang tertutup begitu lama, dan setelah sekarang sudah mulai terbuka, ada berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan terhadap kemanusiaan yang sudah dan terus terjadi hingga kini. Dari perspektif HAM, satu nyawa saja, siapa pun dia, sudah merupakan sebuah tragedi, dan selebihnya hanya merupakan catatan statistik. Nunca Mas (Jangan Pernah Terulang Lagi), judul laporan pelanggaran HAM di Argentina selama pemerintahan militer, mungkin adalah kata yang tepat untuk "pesan" di balik kehadiran buku ini.
Nur Iman Sabono