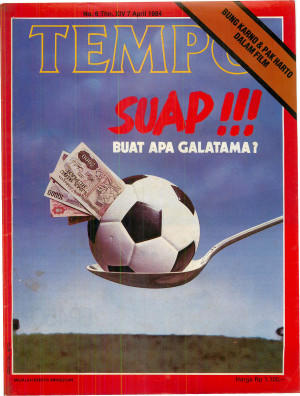MALAM Jumat Pahing itu Letnan Jenderal Ahmad Yani diberondong peluru Cakrabirawa dari belakang. Tubuhnya terbanting ke pintu, disaksikan sendiri oleh putranya dari bawah meja seterika. Piyama sang jenderal bersimbah darah. Jasadnya kemudian diseret ke luar, meninggalkan alur merah memanjang di atas ubin. Istilah Jumat Pahing berasal dari mulut Aidit ketika ia bicara tentang hari H. "Kita tidak boleh terlambat," ujar Ketua PKI itu tak sabar. Soalnya, ada anggota politbiro yang meragukan apakah Dewan Jenderal itu benar ada dan bermaksud melancarkan kup. Rakyat baru mendengar tentang Dewan Jenderal lewat warta berita RRI, Jumat pagi 1 Oktober 1965. Keesokan malamnya, Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto juga lewat RRI - menegaskan bahwa Dewan Jenderal tidak ada. Namun, pada saat itu, Jenderal Nasution mengalami cedera. Enam perwira tinggi - di antaranya Ahmad Yani - dan seorang perwira menengah TNI AD telah gugur dalam rentetan pembunuhan yang paling keji di pentas politik negeri ini. Peristiwa itulah yang direkonstruksikan dalam film Pengkhianatan G-30-S, yang telah disaksikan sendiri oleh Prsiden Soeharto, Januari berselang, di Istana. Komentar Presidn waktu itu antara lain, ". . . banyak yang belum diceritakan . . . karena itu akan dibuat satu film lagi, kelak." Sebagai rekonstruksi, film ini dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan aslinya hingga penyimpangan tidak perlu dikhawatirkan. Tapi untuk pesta kematian di Lubang Buaya, ada komentar "kurang sadis". Ini diutarakan langsung pada Sutradara Arifin C. Noor. Ada juga penonton misalnya yang meragukan peri laku Katrin Panjaitan, putri almarhum Brigadir Jenderal Panjaitan. Secara dramatis, gadis ini digambarkan membarut wajahnya dengan darah ayahnya. Ada pula yang ingin tahu apakah pertanyaan "Adik masih hidup, Sayang?" benar-benar diucapkan Ny. A.H. Nasution kepada anaknya yang tertembak berlumuran darah. Kuat dugaan, film Pengkhianatan akan mendapat sambutan ramai bila diputar pada umum kelak. Hal ini bisa dimengerti, karena antara pemberontakan G-30-S/PKI dan masa kini hanya terentang jarak waktu yang relatif singkat: 20 tahun. Siapa pun dari kita yang pernah mengalaml masa suram itu tidak akan sepenuhnya siap untuk menerima bahwa sejarah adalah sejarah dan film tetap film. Antara keduanya terentang keterbatasan daya ingat manusia, di samping perbedaan visi dan interpretasi. Karena itu, adalah masuk akal sekali bila pembuat film secara ketat membatasi periode sejarah yang di-celluloid-kan itu, yakni hanya pada enam hari genting dalam sejarah Rl, 30 September sampai dengan 5 Oktober 1965. Di mata awam, film ini sebenarnya cukup kaya dengan detail, apalagi setting-nya berpindah-pindah dari Istana Bogor ke rapat-rapat gelap PKI, kemudian ke rumah Pahlawan Revolusi lalu ke Lubang Buaya. Tapi di samping beberapa fakta yang sudah amat kita kenal itu Pengkhianatan juga menampilkan sketsa kerawanan ekonomi masa itu lewat antre dan kemiskinan. Sedangkan kerawanan politik dilukiskan melalui serangan PKI ke sebuah masjid di Jawa Timur, guntingan koran, berita radio, dan komentar-komentar tajam. Poster Bung Karno tak terkecuali menyeruak di sana-sini, dan tulisan Manipol Usdek bertebaran di tembok dan atap rumah. Adapun inti cerita pastilah diketahui orang banyak dan plotnya sederhana, "persis diorama di Lubang Buaya," kata Arifin. Tapi yang terasa mengganggu ialah perpindahan adegan: tidak mulus, sering pula meloncat. Suasana ramai juga memaksa penonton senantiasa awas, karena di samping dua tokoh utama - Bung Karno dan Mayor Jenderal Soeharto masih ada 120 tokoh lain dan 10.000 figuran. Meski ini bukanlah film kolosal karya Arifin yang pertama, mengurus dan menata casting begitu besar memang jauh dan gampang. "Benar-benar gila. Edan!" ucap sang sutradara, mengingat dirinya yang kewalahan. Hal lain yang terasa mengganjel ialah kegagalan mengumandangkan suara asli Bung Karno dalam pidato 17 Agustus 1965. "Rekamannya sudah tidak ada," kata Arifin. Untung, ada Kusno Sujarwadi, pemain watak yang volume suara dan logat Jawanya bisa ditekuk sedemikian rupa hingga pas mewakili suara babe. Adapun pembawa peran presiden pertama Rl tak lain Dr. Umat Kayam, dosen UGM, ahli sosiologi, dan pengarang terkenal. Dia terpilih sesudah seleksi gagal menemukan "Soekarno" di antara sekian banyak orang. Ketika Arifin datang kepada Kayam, yang disebut terakhir ini tidak mungkin lagi mengelak. Tapi syaratnya bukan tidak ada. "Soekarno itu orang hebat. Jangan sampai film ini malah mendiskreditkannya," ujar Kayam, meminta. Tanpa keberatan apa-apa, syarat itu dipenuhi. Lalu cerita selanjutnya? Kayam harus segera berangkat ke Bogor, tanpa sempat mempelajari Bung Karno lebih mendalam, tanpa melihat film dokumenternya atau membaca kembali tulisannya. Dan, tentu saja, tanpa dapat melangsingkan tubuh. Toh sesudah ia didandani, para pelayan Istana Bogor terpana melihat kehadiran "pemimpin besar" itu di tengah-tengah mereka, sampai-sampai ada yang berlinang air mata. Dari mereka, Kayam sempat bertanya bagaimana cara Bung Karno berjalan dan berbicara. Khusus untuk memperlihatkan kepala sulah Bung Karno - yang memang tak diketahui umum -- Kayam terpaksa rela dibotaki. Pengalaman kurang menyenangkan ini tidak membuatnya jera untuk lain kali melakonkan tokoh yang sama, "asal diberi waktu mempersiapkan diri". Amoroso Katamsi, sebaliknya, berkesempatan cukup mempelajari tokoh Mayor Jenderal Soeharto, baik lewat tulisan maupun pengamatan. Letnan Kolonel (L) yang perawakan dan parasnya mirip Presiden itu tidak menyembunyikan rasa bangga diberi kepercayaan memerankan tokoh sentral film ini. Namun, ada juga beban yang menghimpit, terutama karena "gejolak emosional Pak Harto hampir-hampir tidak nampak," hingga sulit dibawakan. Di sampmg itu, ia juga merasa dituntut untuk mewujudkan kepribadian seorang Soeharto, hingga tiap kali diganggu pertanyaan sendiri: "Apakah permainan saya sudah tepat?" Toh pada akhirnya Amoroso yano terhimpit ragu dapat juga berkata, "Ketika berhadapan dengan kamera, saya merasa sebagai Pak Harto, bukan imitasi Pak Harto." Bagaimana dengan Aidit, yang digambarkan merokok terus, tegang terus? Beban mental tidak ada, tapi Syu'bah Asa, wartawan TEMPO, yang berperan sebagai gembong PKI itu merasa aktingnya "kurang meyakinkan". Untuk lebih mengenal Aidit, Syu'bah ngobrol semalam suntuk dengan seseorang, asyik menggali dan meniru lagak sang ketua, hingga ketika tiba saat shooting keesokan harinya, "saya tertidur." Waktu dua tahun untuk menggarap Pengkhianatan dirasakan tidak cukup, khususnya bagi sutradara. Demi kebenaran sejarah, misalnya, Arifin membaca sebanyak mungkin, mewawancarai saksi sejarah, mencari property asli, berfikir dan merenung. Tapi yang terakhir hampir tidak mungkin dilakukan, karena kegiatan ini dianggap membuang biaya tanpa kerja. Padahal, sutradara itu mencita-citakan Pengkhianatan sebagai film pendidikan dan renungan tanpa "menawarkan kebencian". Memang, tema besar selalu merepotkan. Sebagai film cerita, Pengkhianatan berada di bawah Serangan Fajar. Porsi sejarahnya terkesan menuntut terlalu banyak hingga kisahnya tidak mungkin lagi digarap menurut kaidah-kaidah perfilman yang biasa. Akibatnya, film bukan saja tidak menawarkan kebencian, tapi juga tidak menerbitkan rasa haru. Padahal, inilah unsur yang paling berpotensi untuk mengikat kita dengan masa lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini