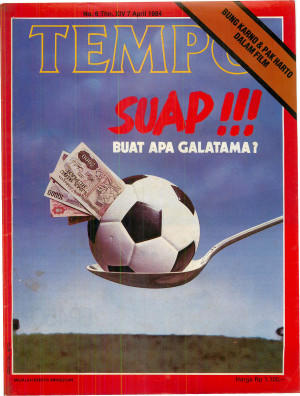KRITIK ISLAM ATAS MARXISME DAN SESAT-PIKIR BARAT LAINNYA oleh: Ali Syari'ati Pengantar: M. Dawam Raharjo Penerbit Mizan, Bandung, 1983 SEBUAH tema besar, juga sebuah kerja besar: dunia tengah mencari pilihan lain di samping kapitalisme dan komunisme. Bung Karno atau Frantz Fannon, Mahatma Gandhi atau teologi pembebasan bahkan kaum Sosialis Demokrat dan Children of God - semuanya melacak dan menawarkan jalan ketiga itu. Islam, tentu saja, tak ketinggalan. Ali Syari'ati, cendekiawan muda Iran itu, termasuk dalam deretan pemikir Islam yang bicara untuk itu. Namanya menjadi tenar setelah revolusi Iran meletus. Syari'ati memang bukan seorang Marx bagi revolusi yang bersejarah itu. Revolusi itu tak bisa dikatakan sebagai hasil pelaksanaan ide-idenya. Ayatullah Khomeini-lah, lebih dari siapa pun juga, tokoh yang menyebabkan revolusi Iran mendapatkan bentuknya seperti sekarang. Tapi Syari'ati, yang terlatih di Sorbonne, Paris, dan penceramah yang menarik, agaknya menonjol dari yang lain-lain karena riwayat hidupnya yang dramatis: ia pernah dipenjarakan rezim Pahlevi, dan ia dianggap mati syahid secara misterius di London, 1977 (meskipun keterangan resmi pemerintahan Syah mengatakan ia meninggal karena serangan jantung). Bagi peminat di luar Iran, tentu Syari'ati lebih tampil karena ia menggunakan acuan yang dikenal. Dari kepustakaannya, ia tampak lebih bisa "omong Barat" ketimbang sejumlah pemikir Iran lain. Dan praktis lewat Barat-lah pikirannya beredar. Bukunya ini juga terjemahan dari bahasa Inggris. Terjemahan Husin Anis al-Habsyi cukup bagus, menunjukkan dengan jelas penerjemahnya memahami inti soal yang dibentangkan Syari'ati. Tapi tentu hasilnya bukan suatu risalah yang mudah dicerna: seperti hampir tiap penerjemah dari bahasa Inggris, Husin Anis harus bergulat dengan khasanah bahasa Indonesia yang tak selamanya cocok untuk peristilahan filsafat berbahasa Barat. Lagi pula, risalah ini berasal dari rangkaian ceramah (yang mungkin sekali, meskipun tak jelas disebutkan, aslinya berbahasa Parsi). Dari sebuah ceramah, umumnya kita hanya mendapatkan pesan-pesan yang efektif, tapi belum tentu suatu analisa yang tekun dan sekaligus jernih. Apalagi sifat dasar buku ini suatu polemik, suatu "kritik". Sifat dasar itu yang tak menampilkan Syari'ati di sini dalam nalar yang tenang dan sistematik. Ia memang memikat. la lebih punya kekayaan yang oleh orang Prancis disebut I'esprit dibanding misalnya dengan Iqbal atau Qutub. Tapi justu itu, setidaknya dalam buku ini, Syari'ati kadang terasa meringkas satu kesimpulan yang sebenarnya perlu argumentasi cukup. Pernyataannya tentang Protestantisme, misalnya. Bukan saja kurang tepat mengelompokkan pelbagai aliran Kristen yang non-Katolik sebagai "suatu ideologi", tapi juga terlampau bersahaja untuk menyebut Protestantisme "mengolah ... moralitas yang cocok dengan kehidupan borjuis." Pertama, orang bisa mengutip Luther, untuk membantah Syari'ati. Luther misalnya pernah menolak saham-saham pertambangan, Kuxen, yang dianggapnya "uang spekulasi". Kedua, orang bisa mengedepankan pemikir Protestan modern seperti Paul Tillich. Ketiga, teori Weber, yang diberi tekanan lebih oleh Sombart, tentang hubungan Protestantisme dan kapitalisme, pada akhirnya tetap meragukan. Tulisan polemis memang belum tentu tulisan yang kukuh, justru karena cenderung untuk berat sebelah. Kritik Syari'ati terhadap Marxisme memang sangat tajam dan umumnya kena. Tapi menghadapkan kutipan Marx dengan Quran, di depan pendengar dan pembaca Muslim, tidaklah fair: derajat keyakinan kita terhadap kedua teks itu sudah berbeda sejak mula. Apalagi Marx di sini digebuk pada sisinya yang paling lemah: pandangannya terhadap agama. Pengaruh materialisme historis dalam pemikiran tentang Dunia Ketiga dengan sendirinya diabaikan. Pengabaian beberapa hal memang sebuah siasat dalam polemik. Itu pula agaknya yang dilakukan Syari'ati terhadap eksistensialisme. Bagus dan mendasar serangannya kepada pemikiran humanistis Sartre, suatu yang juga pernah dilakukan Raymond Aron dalam polemiknya yang termasyhur. Tapi, dalam hal Syari'ati, tentu jadi pertanyaan: cukupkah baginya berbicara tentang eksistensialisme hanya dari Sartre, dan terutama Sartre yang diwakili risalah ringkasnya, I'Existentialisrne est un Humanisme. Kenapa pula ia menyebut Camus "materialistis"? Tapi baiklah diingat, sekali lagi, bahwa buku ini berasal dari ceramah. Ia diarahkan untuk sesederhana mungkin dan seefektif mungkin sebagi kritik. Lagi pula, betapa pun kadang simplistis, pernyataan Syari'ati sering melontarkan percikan kebenaran. Ia memang tak sepenuhnya terang, tapi ia cemerlang. Ungkapannya tentang inti pemikirannya bisa menggugah dan sekaligus orisinil, misalnya ketika ia membandingkan konsep ketuhanan Yunani dan agama Timur: "Risalah agama Timur berdasar pada kenaikan manusia dari bumi ke surga .... " Memang, dalam pendapat seperti itu kita bisa mendapatkan jejak Iqbal, pemikir yang lebih analitis dan sistematis dan lebih dahulu bicara sebelum Syari'ati. Khususnya tafsiran Iqbal yang mengagumkan tentang mutasi Adam dari Firdaus kebumi, yang bukan Kejatuhan seperti konsep Kristen tapi berhubungan dengan kemerdekaan manusia. Bisa dikatakan bahwa pokok pandangan Iqbal dan Syari'ati (dan juga kemudian, katakanlah, Nurcholish Madjid) paralel: manusia sebagai khalifah Tuhan di atas bumi. Yang tak sering disadari ialah bahwa pandangan tentang kemerdekaan manusia itu sesuatu yang sebenarnya kontroversial bagi umumnya pemikiran di Dunia Ketiga. Maka, sangat menarik untuk tahu bagaimana posisi Syari'ati dalam konstelasi pemikiran Islam di Iran sekarang. Pengantar Hamid Agar, dan terutama pengantar Dawam Rahardjo yang amat bagus, mencoba menjawabnya. Sayang, keduanya masih diwarnai oleh usaha "menjaga persatuan" antara Syari'ati dan Khomeini. Maka belum jelas benar bagaimana pemikiran Syari'ati bagi para pemuda Mujahiddin yang kini tersingkir, misalnya. Sebab, siapa tahu, seandainya ia tetap hidup, Syari'ati berada dalam posisi Bani Sadr. Oleh Dawam Rahardjo, Bani Sadr disetujui untuk dianggap sebagai "intelektual Barat yang gagal memahami masyarakatnya sendiri". Agaknya, ini hanya karena Bani Sadr kalah - dan, seperti banyak orang yang kalah dalam pergulatan politik di Dunia Ketiga, ia dapat cap "kurang-memahami-rakyat". Tapi kalau pun benar Bani Sadr bisa disebut "Barat", Syari'ati pun dapat ditudu demikian - di balik pernyataan anti-Baratnya yang berapi-api. Lebih sering menyebut filsuf Barat ketimbang Timur, ia juga dengan bersemangat memuji Darwin. Ia, yang tampaknya beberapa kali dikecam sebagai bukan orang Syiah yang baik, juga siap dengan semangat "menanamkan kontradiksi dan konflik". Demi Tuhan. katanya, 1.000 kali lebih berjasa untuk menaburkan keraguan di antara beberapa orang ini daripada menyebarkan kepastian. "Kita," kata Syari'ati, "700 juta kaum Muslimim mempunyai suatu kepastian yang sedikit pun tidak ada nilainya." Tak pelak lagi: kata-kata yang bagus, tapi juga mengejutkan, dan bisa dicap "membahayakan persatuan umat". Tapi siapa tahu di situ Syari'ati pada titik yang tepat: bila Islam hendak berhasil menawarkan jalan alternatil, benarkah permulaannya dengan menumpuk kepastian berlapis-lapis? Tidakkah awalnya adalah menghidupkan pikiran yang sesua dengan kemerdekaan manusia? Dari sanalah kita berharap akan merasakan rahmat dari perbedaan pendapat. Tentu saja dengan risiko. Tapi kenapa pemikiran yang berasal dari sebuah ajaran yang universal harus takut risiko - termasuk risiko untuk diragukan, digugat, dikritik? Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini