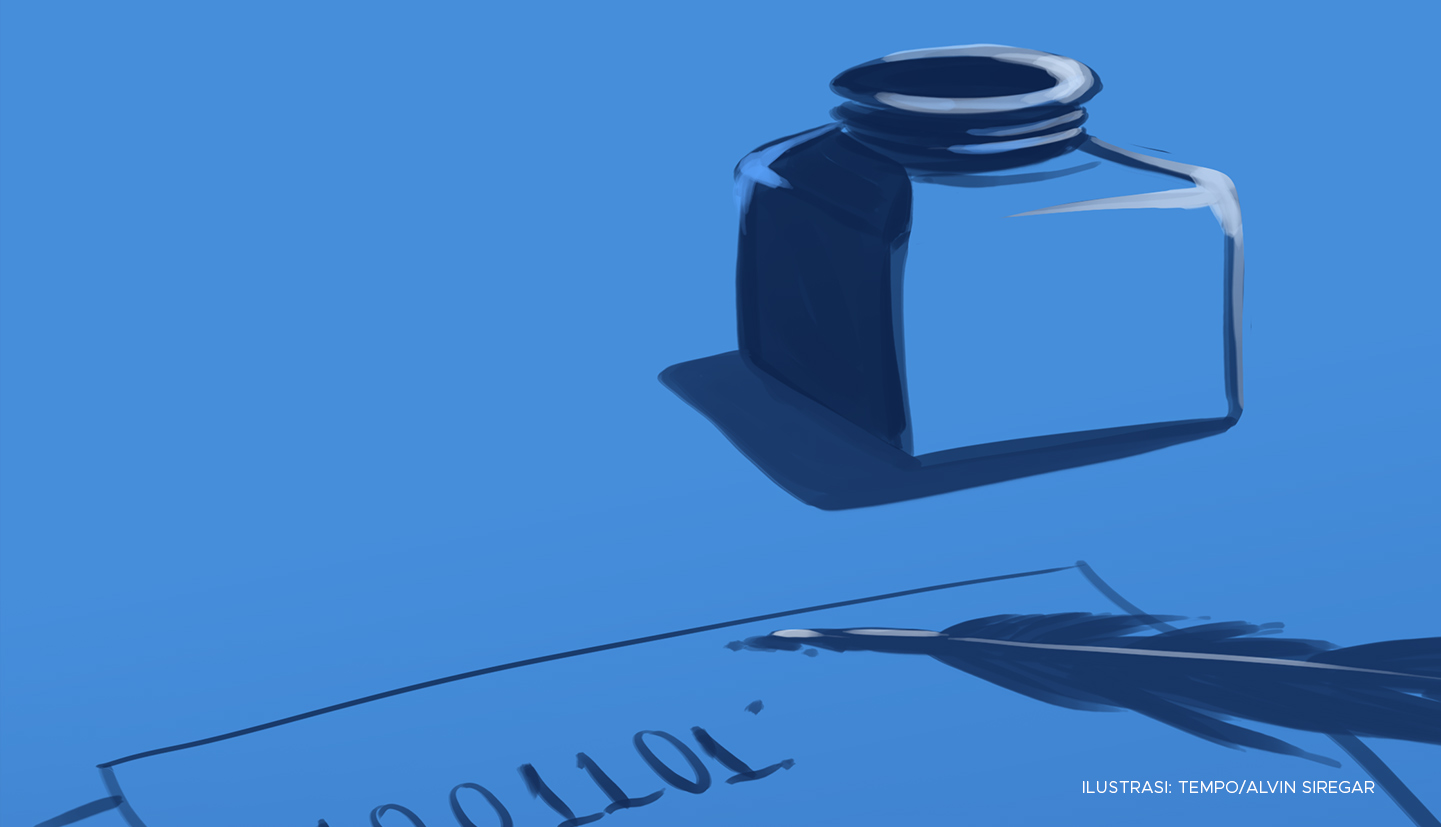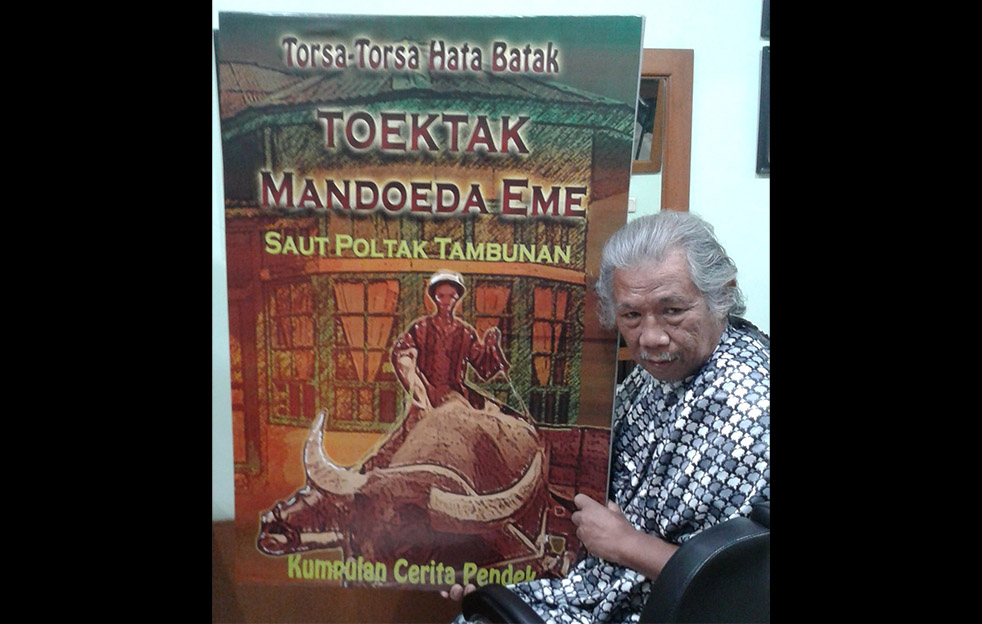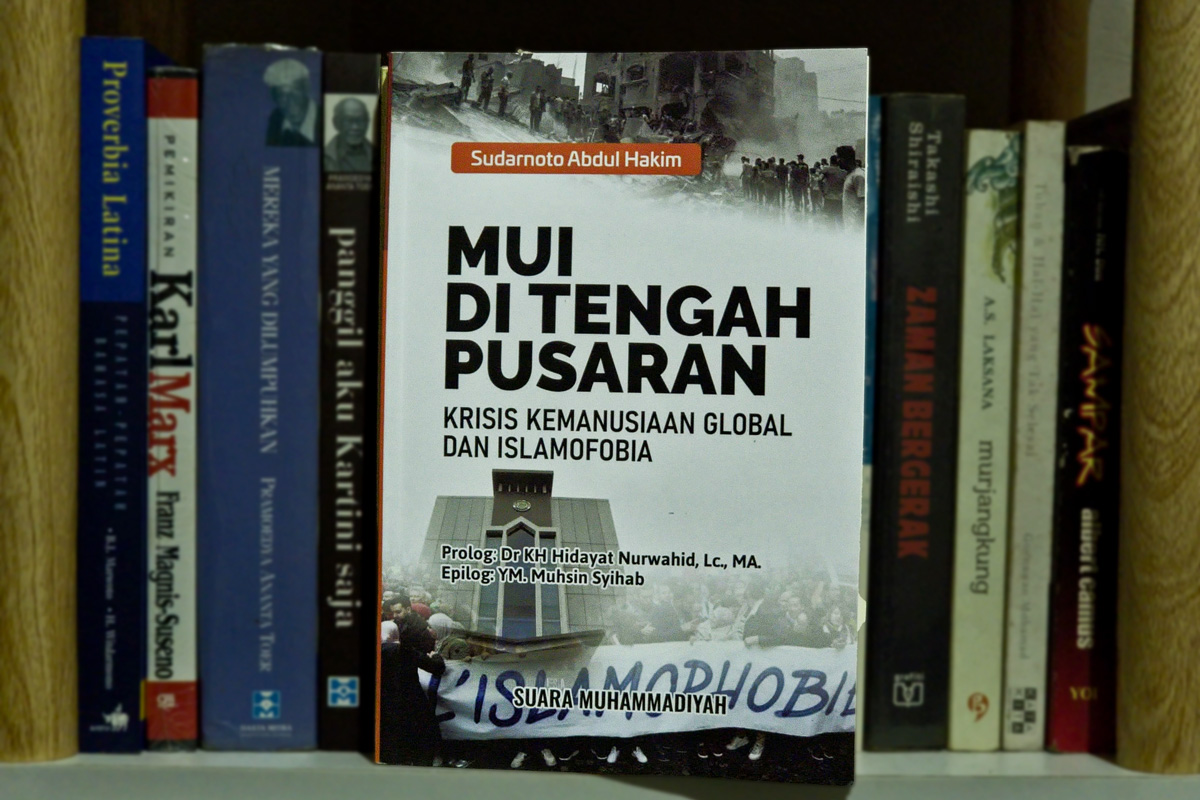Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Zaman digital hanya satu selaput tipis yang mengambang di atas lautan evolusi biologis.
Sastra dan kesenian modern mencoba berlaku tanpa pamrih, disinterested, mencoba berlaku setara dengan ilmu.
Zaman digital telah mempercepat kematian close reading, kritik sastra, liberal arts, dan comparative literature.
Sastrawan Nirwan Dewanto menyampaikan ceramah dalam forum Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) ke-13 di Muaro Jambi, Jambi, Kamis, 21 November 2024. Festival ini berlangsung pada 19-23 November 2024 dengan menggelar berbagai kegiatan dan menghadirkan sastrawan, seniman, pelaku budaya, peneliti, serta insan kampus dari dalam dan luar negeri. BWCF dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Ratu Convention Center, Jambi, Selasa, 19 November 2024. BWCF 2024, yang mengangkat tema Membaca Ulang Hubungan Muarajambi-Nalanda dan Arca-arca Sumatera, dipusatkan di Candi Kedaton, Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, Jambi. Berikut ini adalah esai utuh yang dilisankan dalam forum tersebut. Huruf kecil di awal beberapa alinea dalam tulisan ini adalah kesengajaan dari Nirwan. — Redaksi
Sebuah Pengakuan, Sebuah Percobaan
PIKIRAN saya sekarang, bila itu masih bisa disebut pikiran, tentang sastra di era digital, seperti akan saya paparkan dalam forum ini atas permintaan Anda, hampir saja menyerupai keserempakan dan keacakan datangnya “informasi” di linimasa Instagram saya—
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
tetapi ternyata metabolisme saya tetap berlaku sejalan dengan urutan hidup saya sejak saya dilahirkan di Surabaya sampai saya hadir di mimbar Muarajambi sekarang. Sehingga paparan saya ini menyatakan sejenis penyelamatan diri juga yang, saya bayangkan, masih memerlukan semacam logika yang bersifat linier.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baiklah, ternyata tidak banyak yang berubah, atau bahkan mungkin tidak ada yang berubah, dalam diri organisme-manusia yang secara biologis masih bernama Homo sapiens, sejak spesies ini muncul di muka bumi pada kurang-lebih 250 ribu tahun lalu.
Berubahnya kapasitas mental dan indrawi (yang tidak selalu progresif, tapi juga regresif), baik secara perlahan-lahan maupun secara “revolusioner”, sejak Revolusi Industri pada 250 tahun yang lampau hingga Revolusi Informatika pada hari ini, belum kuasa mengubah kita menjadi spesies yang lain atau memunculkan spesies Homo yang baru—
juga, sebenarnya tidak banyak yang berubah dalam segala hal yang menyangkut “pemikiran” kita, terutama menyangkut segala nilai yang menyangkut kemanusiawian kita. Misalnya saja bahwa kita tetap tidak bisa hidup tanpa akhirat, tanpa afterlife, tanpa Tuhan.
Itulah sebabnya si manusia tetap saja menjadi pusat di alam raya, yaitu bahwa dia tidak sanggup mencerna kemahaluasan alam semesta, bahwa bumi hanyalah lebih kecil daripada setitik debu di tengah miliaran galaksi di tengah kekosongan semesta.
Manusia tetap saja Homo deus, bukan karena dia menciptakan segalanya ex nihilo, melainkan karena dia menolak dirinya sebagai hasil dari proses paling evolusi biologi sejak organisme pertama muncul di bumi pada 600 juta tahun yang lalu. Bagaimana mungkin filsafat pascahumanisme bisa mengumumkan akhir sang manusia?
Namun, tentu saja, sudah terlalu banyak revolusi. Justru karena kita tidak menghendakinya. Segenap algoritma yang memudahkan hidup kita, yaitu sejak kita membeli makanan dan tiket kereta api hingga keisengan kita memeriksa unggahan di Instagram menjelang tidur malam hingga kesertaan kita dalam upaya raksasa untuk memusnahkan pandemi Covid-19, sudah satu-menyatu dengan digital panopticon yang sepintas lalu bersifat non-hegemonik.
Tentu saja yang saya maksudkan dengan revolusi di sini bukanlah perkara menggulingkan orde politik lama atau menghapus kelas borjuasi, melainkan bagaimana proses mengambil putusan bisa berlaku ribuan kali lebih segera bahkan tanpa timbangan pikiran sekalipun. Termasuk bila itu menimbulkan kematian atau penderitaan pihak lain.
Zaman digital hanya satu selaput tipis yang mengambang di atas lautan evolusi biologis sejak bumi terbentuk pada 4.500 juta tahun lampau. Namun demikian, saya mau mengatakan bahwa kesadaran yang mampu mengenali kuantitas dan kualitas proses evolusi ini bernama kesadaran ilmiah, yang juga hanya selaput mahatipis yang mudah sobek di atas lautan ketidaksadaran yang dibentuk oleh berbagai revolusi yang sudah saya sebut tadi.
Revolusi digital, yang bukan tunggal tapi jamak, bukan berurutan tapi serentak, niscayalah adalah kelanjutan dari tradisi keilmuan yang berlaku sejak Revolusi Kopernikan pada lima abad yang lalu—
tetapi bila buah-buah ilmu yang boleh bernama teknologi, industri, dan demokrasi bisa dihasratkan semua orang di dunia ini, maka perangai ilmiah, scientific temper, hanya dimiliki oleh segelintir kecil orang, katakan saja kaum ilmuwan. Bahasa ilmu berpisah dari komunikasi massa dan kebudayaan umum untuk menyingkapkan hukum-hukum alam dengan sebaik-baiknya.
Sastra dan kesenian modern yang mencoba berlaku tanpa pamrih, disinterested, mencoba berlaku setara dengan ilmu, misalnya saja dengan prinsip death of the author atau escape from personality, tidak pernah berhasil mencapai tujuan itu.
Bila perangai ilmiah tidak pernah merasuk ke dalam diri kita, sementara kehidupan kita dikuasai teknik dan teknologi, apakah artinya bahwa “modernisasi adalah hak segala bangsa” dan “semua penjajahan di dunia harus dihapuskan” (demikianlah bila saya boleh menggelincirkan frasa-frasa dari Pembukaan UUD 1945)?
Modernisasi tidak harus selalu berarti gerakan ke arah depan, tapi juga ke belakang. Progres yang kita kejar dengan bersusah payah sering kali mendamparkan kita ke dalam regresi, dan gerak mundur ke belakang ini justru lebih lancar pada zaman informatika kini.

Nirwan Dewanto (kanan) memberikan ceramah umum tentang Sastra di Era Digital pada The 13th Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) 2024 di halaman Candi Kedaton, Muarajambi, 21 November 2024. Dok.BWCF 2024
Dalam segala apa yang kita sebut kemajuan atau modernitas, masa lampau selalu kembali, baik kita hasratkan ataupun tidak. Demokrasi, misalnya, ialah bukan hanya pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum, tapi juga manipulasi atas berbagai arus primordial demi pemenangan kuasa politik.
Penyerahan diri kita ke dalam digital panopticon tidaklah disadari sebagai sebentuk penjajahan (yang lebih canggih, belum tentu lebih baik, daripada penjajahan lama) tapi tata kelola terbaru demi kemaslahatan bersama. Para pegiat lingkungan mempersalahkan “kapitalisme neoliberal” untuk kerusakan lingkungan dan bencana iklim, tapi problem penumpukan sampah dan limbah sesungguhnya adalah masalah pokok yang harus dipecahkan oleh pemerintah dan warga di wilayah yang bersangkutan.
Membicarakan sastra di era digital adalah juga membahas kelembaman si manusia pembuat sastra di tengah kelisanan di tahap ketiga. Bukan saja kita bertanya apakah ia, si pembuat sastra, masih makhluk spiritual-romantik yang menulis berdasarkan ilham ataukah ia sudah menjadi semacam mesin algoritma yang bisa menggunakan dataraya sastra.
Atau barangkali kita bertanya lebih sederhana lagi, misalnya apakah para penyair kita sekarang, di zaman ketika hampir seluruh jurnal sastra dari mancanegara bisa dibaca secara digital, punya keterampilan dan wawasan yang lebih baik daripada generasi Chairil Anwar. Barangkali jawabannya adalah tidak—
tetapi barangkali juga kita tidak perlu menjawab ya atau tidak. Sebab, sastra Indonesia yang ditulis pada hari ini mungkin adalah sastra yang dikerjakan tanpa sejarah sastra nasional. Dua generasi yang muncul sejak akhir abad lalu hingga kini, adalah mereka yang berkarya tanpa anxiety of influence (demikianlah bila saya boleh mengutip frasa tersebut dari Harold Bloom)—
bila pun mereka mencoba mengikuti jejak-jejak kaum pendahulu yang membangun sastra nasional itu, maka jalan tersebut segera terkubur dalam gelombang sastra dunia, segenap bacaan mereka atas karya-karya mutakhir dari mancanegara, meski yang disebut “sastra dunia” ini tidak lain daripada hasil tapisan Anglophonia—
lebih mudah bagi kita sekarang menoleh ke karya-karya mutakhir dari Jepun, Amerika Selatan, Turki, misalnya. Meski semua itu ternyata disodorkan, sebagian besar, melalui terjemahan Inggris. Situasi “buta-huruf nasional” makin membuat karya-karya sastra Indonesia dari masa kemarin makin tak tersentuh.
Saya segera menyadari bahwa situasi tanpa ingatan, tanpa masa lalu, tanpa sejarah, tanpa anxiety of influence, bukan hanya milik medan susastra nasional, tapi juga situasi hidup kita pada umumnya—
bila kita bicara tentang pemajuan Indonesia, misalnya, tentang bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen setahun, bagaimana kita bisa setara di antara bangsa-bangsa di dunia ini dan seterusnya, maka kita lupa kepada para bapa-ibu pendiri Indonesia, kepada visi mereka kenapa Republik Indonesia harus berdiri.
Kita bisa berbicara tentang generasi anak saya yang di kelas VI SD sudah fasih berbicara tentang identitas gender dan energi terbarukan tapi tidak perlu lagi tahu akan kekerasan berdarah pada 1965 dan 1998. Dan pada saat yang sama kita boleh tersadar bahwa, di sisi Indonesia yang lain, anak-anak di bawah umur mewajarkan kekerasan dan intoleransi melalui media sosial, terutama jika mereka tidak mendapatkan sekolah yang baik—
bila saya mendidik anak saya untuk mencintai buku, sastra, dan kesenian, sudah jelas saya percaya kepada landasan humanisme yang membuat anak saya berkembang menjadi manusia dewasa yang tercerahkan. Pada zaman digital ini, saya tergolong insan kuno yang percaya kepada model pendidikan yang bersifat “klasik”.
Karena pikiran saya yang purba ini, sastra bagi saya tidak pernah jauh-jauh amat dari makna yang dikandung asal katanya sendiri yang Sanskrit, yaitu bahwa sastra ialah tulisan atau wacana tertulis, tidak berbeda dengan literatur dalam bahasa Inggris.
Bahwa kemudian makna dan amalan sastra menyempit menjadi susastra atau high literature, ini semestinya menunjukkan bahwa ketinggian tersebut tidak berarti apa-apa selain daripada bahwa kaum pesastra bergulat belaka dengan kata dan bahasa, untuk mencapai apa yang belum dikatakan oleh komunikasi yang “biasa-biasa” saja, komunikasi yang mudah terjatuh ke dalam fasisme.
Yang su- atau tinggi tidak dengan sendirinya menjadi kekal abadi, tapi dipertandingkan dari waktu ke waktu. Sebab, situasi tanpa persaingan akan membuat karya-karya sastra diciptakan secara sewenang-wenang hanya untuk menjadi bagian dari polusi, termasuk polusi ragawi pada masa bencana iklim sekarang, yang belum diketahui di mana dan kapan ujungnya.
Namun harus diakui pula bahwa, dalam arus nasionalisme yang sempit, atau dalam situasi tanpa kontak dengan perkembangan mutakhir di aras internasional, amalan susastra bisa mematikan. Dalam sastra berbahasa Indonesia, esai adalah bentuk yang terbengkalai, sementara fiksi (termasuk puisi) terjerembap ke dalam “psikologisme” yang cenderung serba-gelap atau, sebaliknya, serba-menjelas-jelaskan.
Kaum sastrawan yang begitu saja percaya bahwa su- melekat ke dalam karya-karya mereka tidak sadar bahwa sastra ialah tulisan, atau bagian dari budaya tulisan. Mereka berupaya sampai ke ketinggian dengan jalan kelisanan, yakni tanpa pemeriksaan ke dalam diri sendiri melalui khazanah pustaka.
Saya berpendapat dan kembali menganjurkan ke forum ini bahwa menulis adalah semacam hasil sampingan dari membaca belaka. Menulis adalah hasil dari ketidakmampuan saya menguasai lautan bacaan di dunia ini, itulah sebabnya membaca adalah proses yang absurd dan tak pernah berhenti.
Tulisan saya hanyalah setitik air yang ditambahkan seperlunya ke samudra tersebut. Ya, seperlunya saja, sebagaimana seorang anak manusia boleh ada dan boleh tidak ada di tengah ketidakterbatasan jumlah individu Homo sapiens yang pernah ada dalam sejarah di bumi. Juga, sebagaimana sebuah planet bernama bumi ternyata lebih kecil daripada setitik debu di tengah miliaran galaksi di tengah kekosongan alam semesta.
Zaman digital telah melimpahi seorang manusia dengan ribuan algoritma yang memudahkan hidupnya, tapi ia tetaplah makhluk spiritual yang menggantikan ketidakmampuannya mengenali kemahaluasan alam semesta dan ketidakterbatasan evolusi biologis dengan kehadiran Tuhan atau akhirat.
Zaman informatika telah mendamparkan seorang anak manusia ke dalam digital panopticon dan sekaligus seperti menyadarkan ia bahwa kebebasannya menjadi lebih besar, termasuk dalam menentukan nasib tubuhnya sendiri dengan suntik hormonal untuk mengubah arah gendernya dan menyunting masa depan pribadinya melalui sebuah peta genetik.
Membicarakan sastra di era digital bukanlah sekadar bergirang hati bahwa sekarang kita bisa terhubung dengan berbagai tautan ke pasar sastra dunia atau bahwa kita bisa menulis puisi dengan bantuan sejenis mesin algoritma.

Budayawan, penyair, dan penulis, Nirwan Dewanto. Dok. TEMPO/Febri Angga Palguna
Tidak sedikit yang membuat kredo bahwa kreativitas sudah mati, bahwa kepribadian sudah mati, bahwa puisi bisa dibuat dengan sejenis mesin algoritma, misalnya dengan jalan menghancurkan khazanah persajakan terdahulu dan membuat pastiche dari puing-puingnya—
atau bahwa sang penyair sendiri sudah mati, atau harus dibunuh, sebab puisinya selama ini hanya menghuni ketinggian yang tak terjangkau, hanya dibaca oleh kalangan sendiri, tak membebaskan khalayak dari cangkang kebudayaan bawah, kebudayaan massa, untuk mampu bersuara sendiri—
dan berkatalah si mirip-pemberontak bahwa para penjaga pintu gerbang sudah terusir, “sudah tidak berlaku lagi” (sebab, bukankah sekarang zaman decentering di jalan Internet dan media sosial?), maka semua orang kini berhak menjadi penyair, dan menulis sajak-sajak yang biasa saja, “organik”, menghancurkan kanon sastra.
Apabila saya bisa membuka palang pintu masuk ke peron stasiun kereta api dengan facial recognition, tentu saja saya telah menyerahkan identitas harfiah saya kepada “pihak yang berwajib”, dan dengan itu pula saya menjadi tahanan yang bebas dalam sebuah jejaring digital panopticon—
namun tentu saja saya masih punya identitas yang lain, yang lebih dalam barangkali, identitas yang membuat saya takut kepada maut dan kemusnahan yang lain, identitas yang saya pertahankan dengan menulis puisi, atau hanya dengan membaca puisi Chairil Anwar, ficciones Jorge Luis Borges, atau esai Edward Osborne Wilson—
bukan hanya dua identitas yang menghuni diri saya, tetapi sekian banyak identitas, bisa saja tak berhingga jumlahnya, sebagian bisa saya kendalikan dan sebagian lagi tidak, sehingga saya pernah menyimpulkan, untuk sementara waktu, bahwa skizofrenia di zaman digital ialah penyakit terbaik yang saya miliki.
Namun dengan membiarkan diri saya terpecah-pecah demikian, saya telah menjadi sesuatu yang tanpa komitmen, yang bisa sangat sewenang-wenang di satu pihak dan menjadi korban yang tak berdaya di pihak yang lain, pada saat yang sama—
misalnya saja, saya tidak perlu bertanggung jawab jika puisi saya ternyata buruk, jika saya memperbanyak limbah ke lingkungan saya, jika saya menghasut orang lain untuk berbuat kekerasan, jika saya meloloskan seorang penjahat ke tampuk kekuasaan, jika kata-kata saya ternyata serupa dengan limbah yang menebalkan pemanasan global.
Perluasan makna dan amalan sastra cocok dengan skizofrenia saya, barangkali skizofrenia kita semua, yaitu bahwa karya-karya sastra bukan lagi untuk sebuah kanon sastra, dan bahwa apa yang bernama sastra, susastra, tidak lagi ditentukan oleh para penjaga pintu gerbang, bahwa sastra itu banyak, beraneka, dan masing-masing bersifat “kontekstual”—
yaitu bahwa sastra “borjuis”, sastra tinggi, sastra kanonik, sudah mati, dan kini berlakulah non-kreativitas, bahkan anti-kreativitas, di mana si penyair berlaku sebagai mesin atau sebaliknya, dan ini sejalan dengan proses decentering total yang berlaku di semesta Internet dan media sosial, di mana setiap orang mampu menjadi pusat nilai bagi puak digitalnya sendiri, di mana perkara jumlah likes dan followers ialah nilai tertinggi—
Zaman digital telah mempercepat kematian close reading, kritik sastra, liberal arts, dan comparative literature, baik di negeri-negeri yang “maju” maupun yang “pascakolonial”, dan kematian ini, konon, setara dengan demokratisasi di segala bidang, termasuk di ranah akademi—
muncullah pembacaan lebar, wide reading, cultural studies, yang bukan hanya pendekatan lintas-disiplin, yang menggerus kekunoan (dan kepusatan) humanisme dan humanities, tapi juga membebaskan apa yang pinggiran, yang subaltern, yang tak bisa bersuara, dan seterusnya—
muncullah pembacaan jauh, distant reading, yang dengan statistika dan mesin algoritma mampu membaca semua jenis sastra, tanpa membedakan apa yang rendah dan yang tinggi, dan dengan itu mampu menyingkap arus-arus sosial yang terlepas dari niat si pengarang untuk menjadi bagian dari perubahan sosial yang sesungguhnya.
Pembacaan lebar dan pembacaan jauh, yang di negeri-negeri sana bukan hanya titik jenuh humanities, tapi juga pertanda ke arah penebalan cangkang-cangkang identitas yang pada gilirannya, secara ironis, memenangkan “Trumpism”, ternyata di sini sangat cocok dengan kelisanan tahap kedua atau ketiga, dengan merosotnya mutu pendidikan, termasuk pendidikan tinggi—
cocok pula dengan situasi membangsa yang tidak pernah berhasil mengembangkan perpustakaan dan museum, dengan pragmatisme politik nasional yang tetap bersandar kepada “politik aliran”, dengan makin luasnya persekutuan antara kebudayaan massa dan semesta digital, dengan penyerasian antara “pasca-kebenaran” dan berbagai warisan primordial.

Redaktur Utama Kalam, Nirwan Dewanto (kanan) dan Zen Hae, dalam diskusi Kalam Kembali dan Peluncuran Kalamsastra.id di Salihara Arts Center, Pasar Minggu, Jakarta, 24 Februari 2024. TEMPO/ Nita Dian
Zaman digital telah menyebarkan hasrat kita untuk serba-tahu melalui berbagai hyperlink dan aplikasi, tak berhingga banyaknya, tapi pada saat yang sama kita, sebagai tahanan yang bebas di jejaring panopticon yang diciptakannya, kehilangan kemampuan untuk merasa tidak tahu, untuk tahu bahwa kita tidak tahu, artinya juga kehilangan kepekaan akan adanya ketimpangan—
misalnya, sebentar lagi kita akan punya drone yang mengantarkan paket ke pintu rumah dan “melihat” sekerumun manusia terbang ke Mars dan kembali lagi ke bumi, tapi kita alpa bahwa berbagai kota dan desa kita tak sanggup menangani limbah dan sampah, bahwa negara-negara di Afrika Barat sekarang hidup jauh lebih buruk daripada Indonesia pada 1960-an—
ketimpangan itu juga berlangsung dalam diri kita sendiri, misalnya bahwa kita bisa paham benar dengan perkembangan politik dan seni budaya mutakhir melalui WhatsApp dan Instagram, tapi tetap saja tak peduli dengan kinerja sel-sel dalam tubuh kita sendiri, dengan residu ganas yang tertimbun dalam tubuh kita sendiri.
Zaman digital bukan hanya belum mampu mengubah Homo sapiens menjadi spesies lain, tapi bahkan juga mengantarnya ke dalam regresi, misalnya saja dalam ranah yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat manusia, ranah yang bernama politik, misalnya saja bahwa di sebuah negeri yang “maju”, “Trumpism” bersekutu dengan “Muskism”—
Saya tidak menganjurkan pesimisme, tapi optimisme memang tidak banyak gunanya. Masalah saya di sini adalah bahwa saya tidak lagi bisa membanggakan skizofrenia saya. Dengan kata lain, saya harus menyatukan kembali diri saya yang terpecah-pecah, yaitu diri yang sewenang-wenang di satu pihak dan diri yang menjadi korban yang merasa sehat di pihak lain—
tanpa upaya penyatuan itu saya tidak punya komitmen sebagai warga umat manusia dan warga negara, bahkan sebagai warga dalam keluarga inti saya sendiri, bahkan pula saya tidak punya komitmen terhadap segala apa yang saya kerjakan, termasuk sastra dan kesenian—
Sastra adalah pelaksanaan seluruh algoritma alami yang terkandung oleh tubuh saya, bahasa saya, tradisi saya, khazanah warisan budaya sedunia. Kreativitas saya, bila itu masih boleh disebut kreativitas, adalah selisih diri saya dengan umat manusia, dengan para pendahulu saya di bidang yang sama, termasuk selisih genetis saya yang hanya sekitar tiga persen dengan simpanse, Pan troglodytes—
bila saya menderita anxiety of influence, itu bukan berarti saya mau menghuni kanon yang sudah dihuni oleh karya-karya para pendahulu saya, tapi karena saya mau jadi pembelajar seumur hidup yang kadang-kadang hanya merasa tahu namun segera sadar bahwa ketidaktahuan saya sungguh merajalela dalam diri saya—
sastra membuat saya menyadari kondisi saya, yaitu kondisi bahwa saya tidak-tahu atau belum-tahu, yaitu bahwa pengetahuan saya hanya sebatas kemampuan indra dan kognisi saya, pengetahuan yang tidak pernah berhasil menjangkau ujung alam semesta, kerja sel-sel dalam tubuh saya, titik nol dalam 4.500 juta tahun riwayat bumi, kegirangan pembuat batu-bata di Sriwijaya, dan seterusnya—
sastra ialah sebentuk atavisme yang radikal, yaitu bahwa ia seperti mengembalikan kita menjadi seperti si manusia pertama yang mencoba menamai dunia, menemukan kata pertama, ketika ia berupaya mengenali semesta yang menakutkannya sekaligus menakjubkannya, sebelum ia menemukan cara untuk menemukan (atau menemui) hukum-hukum alam—
tetapi, tentu saja, kondisi primitif itu tidak ada lagi, malah sebaliknya, dunia yang dihadapinya adalah yang sudah dikuasai ilmu dan dikerjai oleh teknologi, meski si manusia, karena ketakutannya akan kematian dan ketiadaan, tidak pernah mempunyai kesadaran ilmiah sepenuhnya—
sastra berada dalam tegangan ini, tarik-menarik antara dunia yang menjadi terang benderang oleh ilmu dan makhluk spiritual yang gentar kepada ilmu, antara kegandrungan si makhluk akan buah-buah ilmu yang memudahkan hidupnya dan kegentarannya pada dirinya sendiri sebagai organisme hasil proses evolusi biologi yang panjang—
sastra mengatakan kembali kondisi pra-ilmiah itu (yang kini menyaru dengan rias dan busana pascamodern), kegelapan yang belum disinari oleh ilmu, residu yang tertumpuk di bawah kesadaran akan progres, maka berupayalah ia, si anak manusia, kembali kepada kata pertama, yang tentu saja tidak ada lagi—
upaya ini di satu pihak adalah mengangkat kegelapan yang tak terjangkau oleh kesadaran ilmiah, kegelapan yang bila dibiarkan di dalam sana akan dimanipulasikan (dengan bantuan teknologi digital, antara lain) menjadi irasionalitas dan ketidakmerdekaan—
dan di lain pihak adalah upaya untuk melawan (dan mempermainkan) ideologi dan komunikasi massa (keduanya bisa sangat religius) yang begitu saja menggunakan bahasa umum dengan dalih untuk menegakkan kebenaran tertinggi—
Tentu saja apa dan bagaimana itu sastra bisa berubah dengan peralihan zaman, tapi saya akan mengelola sastra dalam pengertian yang wajar, jika bukan yang “kuno”, seperti halnya saya mempertahankan museum dan perpustakaan sebagai sumber-sumber refleksi dan pengetahuan, yang bisa sesekali berubah mirip window display yang riang dan menarik hati—
selaku pesastra, saya bisa memalsukan kepribadian saya (bukan berpura-pura membunuh diri dengan mesin algoritma dan anti-kreativitas) dan meminjam kepribadian orang lain untuk diri saya (bukan merasa berhasil mengamalkan lelaku escape from personality), sebab dengan itulah saya menyadari skizofrenia saya, penyakit yang harus saya sembuhkan—
saya bisa saja bercanda dengan pembacaan lebar dan pembacaan jauh, seperti halnya saya harus berlibur dari kerja di laboratorium saya, untuk segera menyadari bahwa saya harus kembali kepada pembacaan dekat, kepada upaya menjadi lebih melek-huruf di tahap yang berikutnya—
itulah yang saya sebut komitmen, yaitu bahwa saya, sebagaimana masyarakat saya, berupaya untuk tak terjerumus ke dalam situasi buta huruf paling canggih di semesta digital, ke dalam semacam sikap tinggi hati menganggap apa saja sebagai sastra dan kesenian—
namun dengan komitmen yang tak pernah sempurna itu, barangkali saya hanya menghasilkan “sastra” belaka, yang tidak pernah penting bagi sastra nasional dan sastra dunia, tapi, sayang sekali, dengan itu pula saya bisa rumangsa kapan saya harus tidak menulis, atau membuang tulisan saya, untuk tidak menebalkan polusi dan limbah ke dunia ini—
dan saya akan sekadar kembali sebagai satu individu dalam lautan Homo sapiens yang menebalkan selisih diri saya dengan mereka semua, dan pada saat yang sama saya berbuat berbagai hal lain, demi kesehatan bumi dan kesehatan masyarakat saya, misalnya menyetorkan limbah plastik dan kertas di terminal pengelolaan di Panggungharjo, Bantul, atau menyelenggarakan sebuah pameran besar seni rupa kontemporer di Surabaya.
Berpindah cepat dari Surabaya (di mana saya bermukim secara in transit dalam dua bulan terakhir ini) ke Sewon, Bantul (di mana saya menetap bersama keluarga saya) ke Muaro Jambi (di mana saya hadir di depan Anda sekalian sekarang) pada hari-hari terakhir ini, saya berupaya menyatukan diri saya yang gampang meletup-letup di dunia maya dan diri saya yang lain, yang lebih senyap dan “berhitung” dalam dunia sehari-hari.
Kembali ke sastra, tulisan, budaya tulisan, adalah menempuh regresi dengan sadar, mencapai titik permulaan yang lain di jalan menuju rasionalitas. Bukanlah saya mengancang kematian diri saya dalam semesta algoritma dan kecerdasan buatan, sebab sebagian diri saya telanjur hidup di kuburan digital, yang mengaduk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini adalah kuburan yang mengubah Homo sapiens menjadi Homo deus.
Surabaya-Muarajambi, 15-20 November 2024
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo