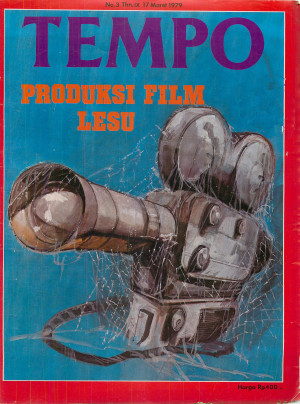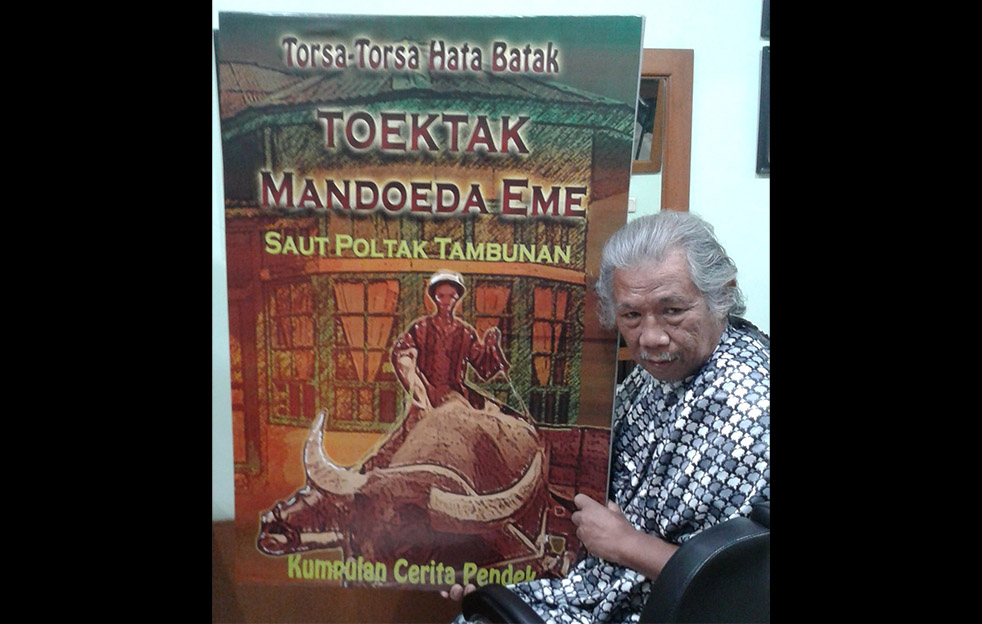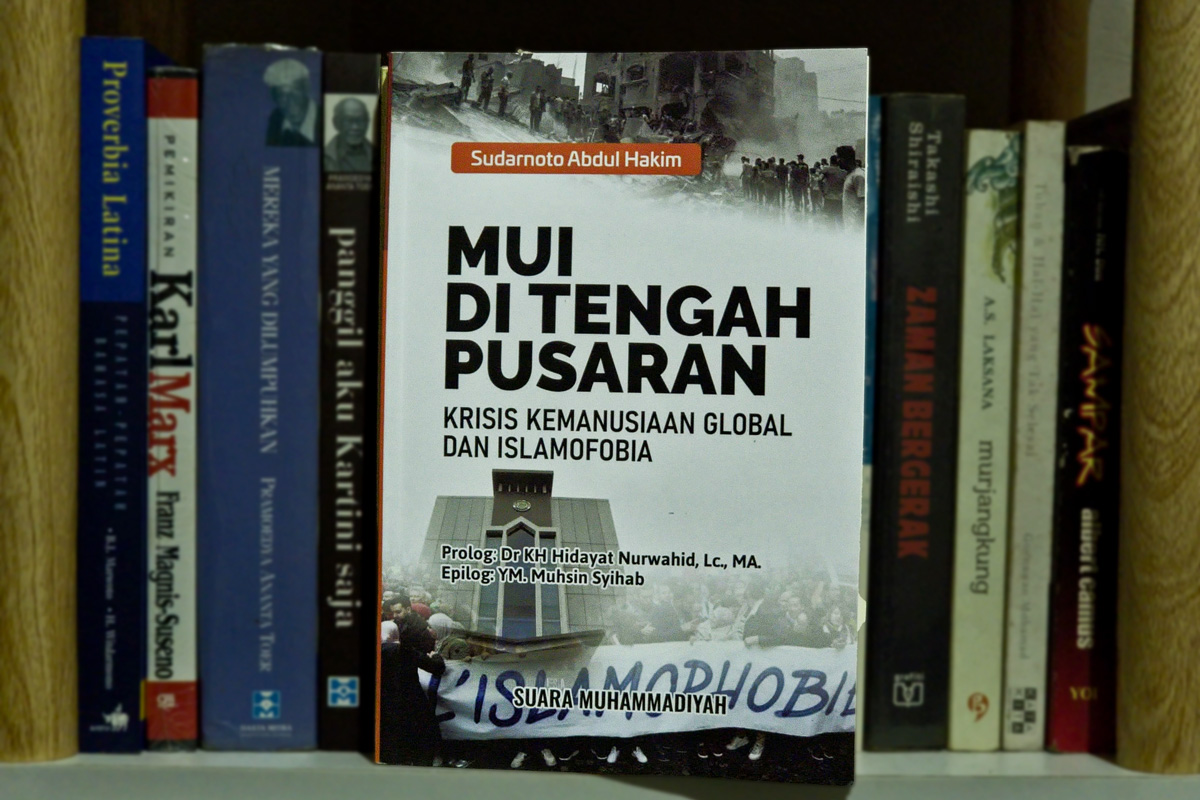WARUNG di Taman Ismail Marzuki setiap harinya ramai dengan
orang film. Ini pertanda yang jelas bahwa film lagi sepi -
seperti kata seorang seniman yang tiap harinya juga nongkrong di
situ. Sutradara Khairul Umam misalnya secara terbuka mengaku
telah menganggur selama 7 bulan. Sejumlah pemain pembantu
(figuran) yang biasanya ikut panen jika produksi lancar, kini
terlihat lesu di kursi-kursi warung tempat berkumpul para
seniman itu (lihat: Suka Duka).
Juga di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, dan di kantor-kantor
produser -- walaupun orang-orang yang hidupnya tergantung dari
produksi ada juga yang berkunjung ke tempat terakhir itu.
"Daripada nganggur di rumah. Siapa tahu ada produksi, dan kita
kebagian peran," kata salah seorang. Masih di Pusat Perfilman,
kelesuan terbukti jelas jika orang melongok kantor PT Romei
Indah Film. Perusahaan yang mengkhususkan diri menyewakan
alat-alat pembuatan film -- lampu, kamera, lensa -- kini bahkan
tidak bekerja setengah kapasitas. "Biasanya kita kelabakan
meladeni yermintaan," kata seorang pegawai.
Masa "kelabakan" yang disebut itu tentulah terjadi di
tahun-tahun 1977-1978. Menurut catatan Sinematek Indonesia,
sepanjang sejarah pembuatan film di negeri ini tahun tersebut
merupakan masa paling produktif. Antara Festival Film Indonesia
(FFI) 1977 di Jakarta dan FFI 1978 di Ujung Pandang, tercatat
134 film diproduksi di Indonesia. Catatan Departemen Penerangan
menunjukkan bahwa tahun sebelumnya, 1976, cuma 58 film nasional
yang diproduksi. Lonjakan yang amat menyolok ini juga merupakan
hal yang baru pertama kalinya terjadi.
Yang juga pertama kali keputusan Menteri Penerangan yang
mewajibkan para importir ikut membuat film. Justru karena
keputusan itulah jumlah film meningkat 100% lebih. Bintang film
yang lagi top, seperti Roy Marten atau Yatti Octavia, masa itu
pernah sekali kontrak 4 film. Beberapa di antara mereka bahkan
ada yang setiap bulannya rata-rata menyelesaikan 2 film.
Panen demikian tidak pula tanpa akibat sampingan. Produksi yang
mendadak naik membutuhkan banyak tenaga. "Tenaga setengah jadi,
mentah, masih mengkal, semua tersedot." Begitu Misbach Jusa
Biran, ketua Karyawan Film dan Televisi (KFT) pernah berkata.
Bukan cuma itu. Orang luar yang masih harus belajar ABC film pun
terserap masuk mengisi tempat-tempat kosong di dalam industri
yang mendadak bangkit itu. Maka terlihatlah betapa keanggotaan
KFT dan Parfi, persatuan para artis, bertambah dengan cepat.
Dunia film ramai. Honor artis menanjak. Sutradara yang dianggap
bisa bekerja cepat diborong para importir yang harus memproduksi
banyak film karena juga ingin memasukkan banyak film impor.
Tiba-tiba terjdi pergantian kabinet. Mashuri SH, Menpen yang
mewajibkan importir berproduksi, pergi dari Deppen. Setelah
beberapa bulan kosong, datang ke sana Menpen yang baru, Letjen
Ali Murtopo. Orang film tidak usah menanti lama untuk tahu ke
arah mana angin bertiup. Dua hari setelah dilantik, kepada TEMPO
Ali Murtopo menjelaskan: "Kondisi seperti ini saya tidak senang.
Karena di sini dititikberatkan segi ekonomis yang hanya bisa
dinikmati oleh produser . . . Jadi tidak boleh asal produksi,
asal banyak, tapi akibatnya merusak masyarakat."
Pernyataan Menpen Ali Murtopo itu menyentak orang film yang
lagi panen. Ke arah mana kita akan dibawa? Beberapa hari
kemudian, di tengah ramainya pesta film di FFI 1978 di Ujung
Pandang, Dirjen RTF, Sumadi, mengumumkan bahwa "produksi
nantinya tidak akan diikatkan lagi dengan imipor." Sungguh
bagai petir di siang bolong bagi orang film. Dari Ujung Pandang
mereka pulang dengan lesu. Mereka menanti realisasi ucapan
Sumadi dalam bentuk surat keputusan. "Keputusan itu baru muncul
bulan Nopember, tapi telah melesukan produksi sejak FFI Ujung
Pandang itulah," kata sutradara Bai Isbahi.
Cerita di kalangan orang film nampaknya cenderung membenarkan
keterangan Bai Isbahi itu. Konon, bahkan beberapa bintang yang
telah teken kontrak -- dan menerima uang panjar - begitu saja
dibatalkan kontraknya oleh sang produser karena pernyataan
Sumadi itu. "Soalnya yang getol produksi dan punya uang untuk
itu cuma para importir. Kalau mereka tidak wajib produksi lagi,
buat apa repot-repot," kata Sjuman Djaja. Dan Sjuman, yang
beberapa film terakhirnya diproduksi oleh importir, hingga hari
ini belum kedengaran rencananya bikin film lagi.
Ketika surat keputusan Menteri belum juga muncul, dan produksi
terhenti lantaran menanti kebijaksanaan baru, yang muncul, eh,
Kenop 15. "Produksi makin sulit karena bahan baku film yang
semuanya impor -- melonjak dengan hebat, sementara harga tanda
masuk bioskop tidak naik," kata produser dan sutradara Turino
Junaidi. Lima belas hari kemudian, 30 Nopember, yang
ditunggu-tunggu pun tiba.
Hari itu keluar Sk Menpen No. 224 ditandatangani Menpen Ali
Murtopo. Ucapan-Sumadi di Ujung Pandang kini menjadi aturan
resmi. Tapi keputusan baru itu bahkan lebih dari sekedar
menceraikan impor dari produksi. Lewat keputusan yang sama juga
diatur baha impor film boleh memasukkan 6 copy untuk setiap
judul. Sebelumnya cuma diizinkan 3 copy. Tidak heran kalau
keputusan ini disambut dengan pahit oleh kebanyakan orang film.
"Peraturan baru pemerintah itu sangat tidak bersahabat kepada
kita orang film," kata FES Tarigan, juru kamera.
Sembari menganggur, orang-orang film yang kini punya waktu
banyak itu mulai tampil dengan renungan, pendapat, bahkan saran.
Tidak jarang di antara mereka terjadi debat sengit mengenai
bagaimana cara mengatasi kelesuan yang ada. Sjuman Djaja dan
sutradara muda Djun Saptohadi menuding Sk 224 itu sebagai sumber
kelesuan. "Ibarat orang mau bunuh tikus dalam rumah, yang
dibakar rumahnya." Begitu perumpamaan yang dipakai Djun.
Akan halnya keputusan Mashuri "mengawinkan produksi dengan
impor," oleh banyak orang film dinilai cukup baik. "Paling tidak
membuka lapangan kerja dan memberi kesempatan melatih
ketrampilan," kata salah seorang di antara mereka. Mengenai
lahirnya film-film jelek akibat wajib produksi tersebut, dengan
mengeluh, Edward Pesta Sirait, sutradara, berkata: "Itu salah
kitalah orang film. Produser kan cuma punya uang, yang bikin
film kita ini. Kalau film jelek, kitalah yang salah."
Dan tampillah Asrul Sani. Bekas penyair yang kini jadi sutradara
itu nampak tidak terlalu kecewa dengan keadaan sekarang. Asrul
menilai "menurunnya jumlah produksi tidak mutlak berarti
merosotnya film kita." Argumentasi Asrul: "Dari 134 film buatan
tahun 1977-1978, 70% sebaiknya tidak perlu dibikin. Mutunya
jelek." Asrul juga menilai tidak adil wajib produksi di masa
kemarin itu. "Coba saja. Seorang importir yang menanam modal Rp
100 juta untuk sebuah film, akan mendapat insentif sama dengan
seorang produser yang cuma memproduksi film dengan modal Rp 40
juta."
Tidak setujukah Asrul dengan kebijaksanaan wajib produksi itu?
Ternyata bukan itu soalnya. Bersama dengan Sjuman dan Turino,
Asrul melihat manfaat kebijaksanaan yan lampau itu tapi harus
ada sistim kontrolnya," katanya. Kepada TEMPO, Sjuman menjeskan
bahwa ketidakadilan peraturan dulu itu -- sebagai yang diuraikan
Asrul -- dapat diatasi jika ada kontrol terhadap mutu film yang
dibuat para importir tersebut. "Aparat kontrol itu terdiri dari
tokoh masyarakat, orang, film dan pemerintah," begitu penjelasan
Sjuman. Kabarnya Mashuri sendiri sudah merencanakan sistim
kontrol ini. "Tapi ia keburu pindah ke Senayan," kata Sjuman
pula.
Karena tidak adanya kontrol itulah maka lahir film-film yang
"seharusnya tidak diproduksi." Bagi kalangan importir, justru
film-film bermutu rendah itulah yang merusak selera penonton dan
membuat para penonton menjauhi film Indonesia. Importir dan
pemilik bioskop seperti Rudi Lukito, misalnya, menyatakan film
rongsokan itu yang menjadi sebab kelesuan produksi film nasional
sekarang."Lah, kalau tidak ada yang nonton, uang tak terkumpul,
bagaimana mau produksi lagi, "begitu Rudi pernah berkata.
Laporan para wartawan TEMPO dari daerah juga menyebut menurunnya
jumlah penonton film nasional di wilayah mereka. Tapi
sumber-sumber yang dihubungi para wartawan TEMPO itu tidak
menyebut secara jelas sumber kelesuan itu: Kenop 15 atau mutu
film yang rendah.
Akan halnya masalah mutu, sebagian besar orang film mengakui
bahwa SK 224 ini bisa diharapkan berbuat sesuatu. Seperti kata
Rudi Lukito: "Sebab nanti ya orang membuat film secara
sungguh-sungguh dan tidak sekedar mengejar tah film impor."
Misbach Jusa Biran tidak seoptimis Rudi. Tapi ia toh "percaya
pada pemerintah yang tentu tidak tega melihat orang film lama
menganggur."
Bagaimana pemerintah menyatakan rasa tidak teganya terhadap
orang-orang film? Hingga hari ini belum diketahui. Tapi,
sehubungan dengan pernyataan Ali Murtopo bahwa film harus
bersifat "cultural educative," tanggal 21 Maret ini sebuah
seminar akan diorganisir oleh Deppen. "Dari berbagai kalangan
akan diminta sumbangan fikiran," kata Haji Djohardin, orang lama
Direktorat Film yang kini beredar kembali di Deppen.
Tapi ketika berbagai seminar dan lokakarya perfilman asyik
berlangsung-antara lain yang diadakan Angkatan 45 - masalah
izin memasukkan 6 copy bagi film impor itu memang mencemaskan.
"Dengan 3 copy saja kita kelabakan. Apalagi dengan 6 copy.
Pokoknya makin sempitlah pasaran film nasional," keluh Turino
Junaedi. Soekarno M. Noer, aktor dan produser, bahkan menyebut
6 copy plus tidak adanya wajib produksi bagi importir sebagai
sumber kelesuan film nasional sekarang. "Kita akan tetap
produksi. Itu pasti. Dari dulu juga begitu. Tapi akan diputar di
mana kalau bioskop sudah dipenuhi film impor?"
Bagaimana komentar para importir mengenai 6 copy itu? Marius
Nizart dari PT Suptan (importir film Mandarin) menyebut
kebijaksanaan itu sebagai "menguntungkan penonton." Alasannya?
"Mereka tidak perlu menanti lama lagi dan tak usah menyaksikan
film yang baret-baret akibat terlalu banyak diputar." Jiwat dari
PT Bola Dunia Film (importir film India) dengan terus terang
mengaku tidak bakal menebus 6 copy film yang diimpornya.
"Memasarkan 3 copy saja sulit, apa lagi 6."
Tapi kalau filmnya memang baik dan bisa menarik banyak penonton,
tentu "kesempatan itu kita pergunakan," kata Rudi yang nampak
sependapat dengan Jiwat. Tapi baik Rudi maupun Jiwat keduanya
juga sependapat, bahwa film impor yang baik sekarang sulit
didapat. "Selain harganya sudah amat mahal, pasaran dalam negeri
juga lesu -- harga tanda masuk tak bisa naik -- dan video tape
merajalela dengan cerita-cerita top tanpa sensor," kata Rudi.
Walhasil, kelesuan dan debat masih terus berlangsung dalam dan
di sekitar dunia film nasional, ketika FFI 1979 di Palembang
sudah berada di ambang pintu. Dengan produksi yang melorot
secara fantastis, bisa dipastikan bahwa pesta di Palembang tidak
bakal menarik bagi banyak orang film.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini