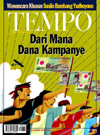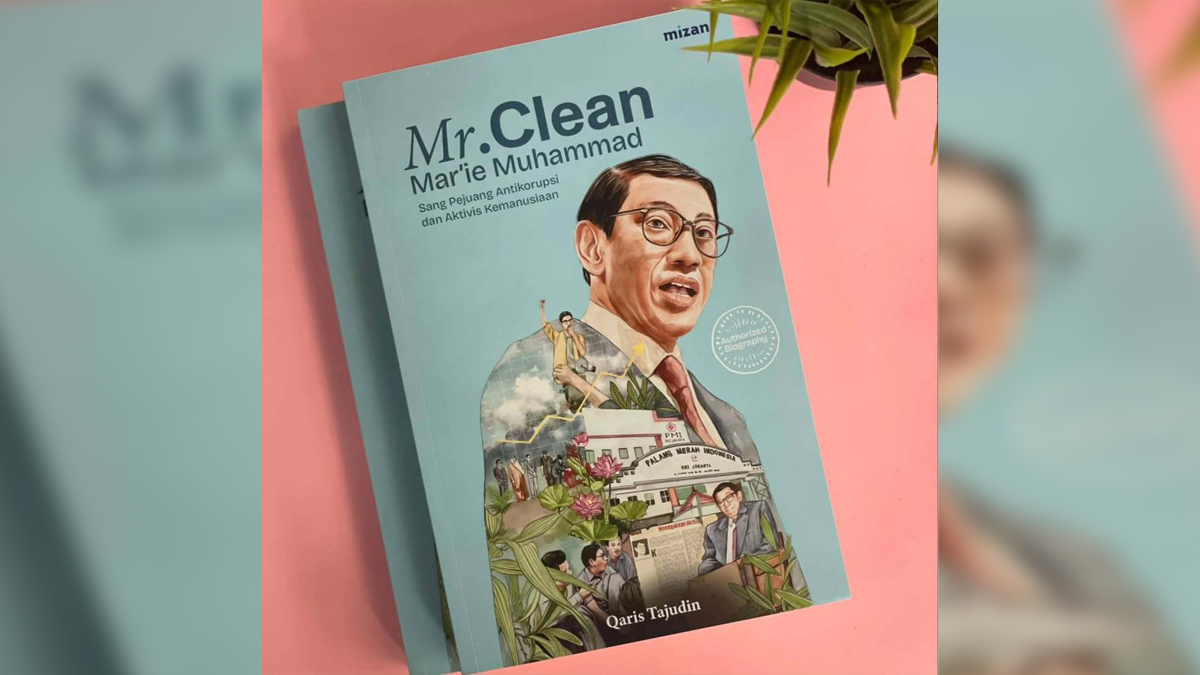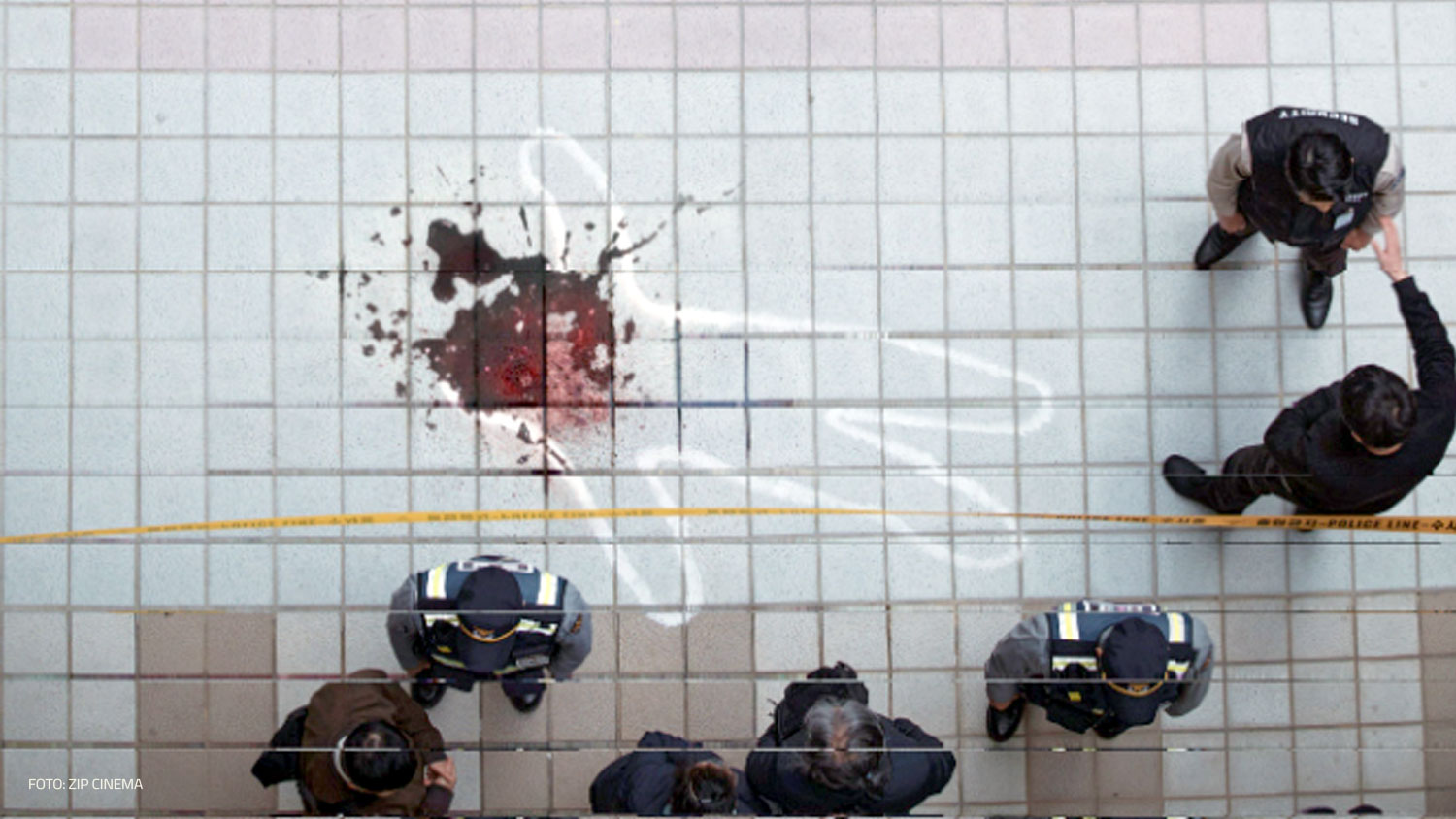Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sabtu dua pekan lalu, tatkala senja mulai merayap di Desa Sanur, debur ombak tak terdengar. Tertelan hiruk-pikuk lalu-lintas di sepanjang jalanan by pass dengan kecepatan tinggi. Suara-suara bising yang tak punya arti.
Petang merembang saat perupa Nyoman Erawan, 45 tahun, memulai repertoar Ciwayakali di pelataran Darga Galeri, Sanur. Erawan, bersama dramawan Agung Eksa Wijaya dan 8 personel komunitas para perupa dari desa Delod Tangluk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, duduk melingkar di pelataran. Sebuah gong besar sebagai instrumen sentral dibaringkan di depan Erawan.
Repertoar Erawan kali ini merupakan interpretasi dari sajak Ciwalakaci karya Sindhunata, S.J. Hari itu, di tempat yang sama, Sindhunata meluncurkan buku antologi puisinya yang bertajuk Air Kata-Kata. Selain itu, digelar pula pameran drawing para perupa Yogya dan Bali. Dalam pameran yang berlangsung hingga 10 Maret 2004 itu para perupa menggali gagasan kreatifnya dari karya sastra. Karya sastra menstimulasi makna, dan yang selanjutnya kita nikmati adalah keluasan dan perluasan makna.
Gong sudah dipukul oleh "tangan anganan" Erawan, ditingkah gumam puisi. Irama mantra meliuk-liuk dan serasa lekas merangsek ke dalam kalbu. Bermula dari ketukan jari pada gong, dilapis dengan pukulan, garukan, dan usapan, selanjutnya lahirlah aneka irama yang saling membelit. Sebuah gong—diberi efek lewat beberapa mikrofon—lantas mendiasporakan irama, jadi konserta. Bunyi murni yang berpadu dengan efek-efek bunyi pada sound system kemudian jadi irama liar yang saling berkutat.
Selanjutnya adalah kepiawaian permainan Erawan menjinakkan bunyi-bunyi liar itu menjadi harmoni. Manakala harmoni sudah mewujud, Erawan menghancurkannya lagi menjadi bunyi-bunyi liar tak beraturan. Begitu selalu. Erawan seperti tengah memainkan bunyi murni dan efek-efek bunyi pada gerak sentrifugal dan sentripetal, efek ke luar dan ke dalam dari gerak putaran sebuah lingkaran.
Adalah Erawan sendiri yang menciptakan "lingkaran irama" itu. Dan dia pula yang mengendalikan "tempo irama". Akibatnya, efek-efek bunyi lantas memetaforakan dirinya menjadi gerak bunyi dari sebuah titik pusat yang bergerak kian melebar ke tepian. Gerakannya sentrifugal. Sementara itu, bunyi murni yang semula keras lalu kian melembut bergerak secara sentripetal, dari tepian bunyi menuju titik pusat. Dua gerak bunyi itu adalah ibarat dua tokoh dalam pementasan drama, dan Nyoman Erawan memerankan keduanya. Erawan seolah sedang mementaskan "monolog bunyi".
Saat jeda, bunyi gong henti. Erawan mulai melumuri wajahnya dengan cat putih. Bermula dengan menoreh gambar tapak dara di atas kepalanya. Sebuah gambar yang bermakna religius dalam Hindu. Mantra puisi kembali terucap. Bunyi genta melapis irama mantra.
Bunyi puisi, bunyi genta, barangkali sama dengan bunyi hiruk-pikuk lalu-lintas. Namun, bagi yang mau masuk ke dalamnya, ada misteri makna yang akan ditemui. Misteri yang mesti digali dengan hati nurani. Misteri itu tak akan ditemui pada teks yang memang memiliki keterbatasan ungkap.
Lewat bunyi pada sajak Ciwalakaci itu, tampak jelas kegelisahan Sindhunata pada pemaknaan manunggaling kawula-Gusti. Simak bait akhir: waduh ora Gusti ora aku/ waduh ilang aku ilang Gusti/ Ciwalakaci, aku lan Gusti lebur dadi/ manunggaling cecak lan kopi/. Terjemahannya: waduh bukan Dia bukan aku/ waduh hilang aku hilang Dia/ Ciwalakaci, aku dan Dia lebur jadi/ bersatunya cecak dan kopi/ Semakin orang menggali makna manunggaling kawula lan Gusti, maka yang ditemui hanyalah cecak dan kopi.
Barangkali, bagi Sindhunata, Tuhan itu misteri yang tak mungkin ditemui jika kita menggali dengan rasionalitas semata. Dia, Tuhan, memang begitu dekat dengan realitas kehidupan kita. Sedekat cecak dan kopi. Hanya, kita acap alpa, dan mencari-Nya di nun.
Desah gelisah tentang misteri itu kian memuncak manakala para personel para rupa mulai meningkahi perpaduan bunyi itu dengan pukulan rebana. Dramawan Agung Eksa mulai bangkit dari duduknya. Ia membaca bait akhir dari sajak Ciwalakaci sembari melakukan gerakan-gerakan yang mirip pada tari Calonarang.
Sesekali ia tebarkan bedak yang diletakkan pada sebuah cawan di tengah lingkaran. Suasana mistis hadir kian kuat. Irama musik kian tinggi. Erawan menabuh gong dengan teknik yang kian bervariasi hingga memunculkan irama yang mirip dengan bunyi-bunyian purba. Kesan purba kian kuat ketika para personel para rupa melafalkan bunyi ha… dan hu… secara padu.
Sementara itu, rebana ditabuh dengan irama acak hingga mirip bunyi perkusi dari musik Afrika. Puncaknya, Agung merebahkan diri di tengah lingkaran. Suasana senyap. Pertunjukan usai. Klimaks dari pementasan itu mirip beberapa kesenian tradisional Bali yang digelar pada upacara keagamaan: trans. Tapi Agung tetap sadar, meski gerakan-gerakannya amat mirip orang yang sedang trans.
Di tangan seorang Erawan—komentar Sindhunata usai pementasan—yang mengeksplorasi sajak dengan media bunyi, kian tampak jelas betapa terbatasnya daya ungkap kata.
Sindhu tampaknya benar. Sebab, menurut pengakuan Erawan, kegelisahannya tak jauh berbeda dengan Sindhunata. "Maka, saya mensugesti sajak Ciwayalaci dengan terminologi kreatif saya menjadi Ciwayakali. Ini lebih merupakan kegelisahan saya pada Sang Ciwa di zaman Kali ini," tutur Erawan.
Begitulah Erawan—perupa yang cukup lama berkutat dengan seni rupa beragam dimensi—pada repertoar Ciwayakali seperti mengingatkan bahwa zaman Kali memang sudah berada di depan kita. Sementara itu, ketika Kali datang tanpa permisi, rakyat kecil pula yang menanggung akibatnya. Padahal, kalau dikaji secara mendalam, kehadiran Kali senantiasa datang dari ulah segelintir manusia yang bermahkotakan elite politik.
Hartanto, pengamat seni, tinggal di Bali
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo