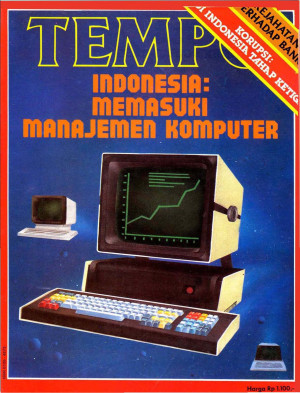RENCANA pembangunan Kantor Konsulat Jepang di Medan sejak dua
tahun lalu terbengkali. Tanah yang mereka beli, di Jalan Listrik
guna membangun kantor itu dan sudah mendapat sertifikat "hak
pakai", belakangan digugat pihak lain. Rehan boru Bangun merasa
memiliki sebagian dari tanah itu karena mempunyai sertifikat
"hak guna bangunan". Kasus sertifikat ganda yang memang banyak
terjadi itu kali ini menimpa badan perwakilan negara lain di
sini.
Konsulat Jepang yang menyewa kantor di Jalan Suryo 12, Medan,
sudah lama merencanakan pindah. Konsul Jenderal Hyosuke Yasui
merasa kantornya tidak layak lagi dibandingkan kantor konsulat
negara lain di Medan. Sebab itu pada 1979 konsulat membeli
sebidang tanah seluas 5.767 m2 di Jalan Listrik itu. "Kami
melihat letak tanah itu bagus untuk kantor dan rumah konsul,
karena itu kami menghubungi pemiliknya, Hasan Chandra," ujar
Yasui kepada TEMPO.
Begitulah, dengan harga Rp 367 juta, Hasan Chandra melepaskan
HGB-nya atas tanah itu. Setahun kemudian konsulat mendapatkan
sertifikat baru, yang biasa diberikan kepada perwakilan asing,
yaitu hak pakai. Persoalan muncul ketika konsulat memasang plang
di atas tanah itu: "Milik Konsulat Jepang". Seorang penduduk
yang merasa pemilik, Rehan, kaget, lalu menggugat haknya melalui
pengadilan.
Setelah beberapa kali sidang, awal Juli lalu pengadilan menolak
gugatan Rehan. Tapi sampai kini Konsulat Jepang belum bisa
memenuhi hasratnya untuk membangun kantor baru. Sebab, sampai
pekan lalu, melalui pengacaranya, Abdul Muthalib Sembiring Rehan
menyiapkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Medan. "Kami
harus sabar menunggu," kata Yasui.
Semula tanah sengketa itu milik Kodam II Bukir Barisan. Dua
puluh tahun lalu, tanah itu diserahkan Kodam kepada pimpinan CV
Rezeki, Marah Laut dan istrinya, Asmah boru Lubis. Pemberian itu
disertai sebuah syarat: mereka harus membangun sebuah bengkel di
situ. Untuk itu Marah Laut dan istrinya mengurus dua buah
sertifikat HGB. Akhir 1965 mereka mendapatkan sertifikat HGB
nomor 9 atas sebagian tanahnya dan sertifikat nomor 13 untuk
sisanya.
Tapi di atas tanah itu tidak dibangun bengkel sesual dengan
perjanjian dengan Kodam II. HGB nomor 9 malah mereka jual kepada
Rehan dan HGB nomor 13 kepada Salimin Bahadjadj pada sekitar
1960-an.
Karena adanya ingkar janji itulah Kodam II pada 1968 membatalkan
kembali perjanjian itu. Tanah itu kemudian diserahkan kepada
seorang pedagang, Hasan Chandra. Kodam II, yang waktu itu
dipimpin Brigjen Leo Lopulisa, juga meminta Menteri Dalam Negeri
membatalkan sertifikat HGB nomor 9 dan 13 atas nama CV Rezeki.
Pada 1971 Direktur Jenderal Agraria, Abdurahman membaalkan
kedua sertifikat itu, dan memberikan sertifikat HGB baru atas
nama Hasan Chandra dengan nomor 43. "Ternyata keputusan kami
terdahulu atas kedua sertifikat itu keliru," tulis Abdurahman
ketika memberikan keputusan.
Namun, rupanya, pembatalan itu tidak mempengaruhi pihak-pihak
yang membeli tanah itu dari CV Rezeki. Bahkan Salimin masih
sempat menjual tanah itu kepada Tongku Sagala, 1978, sementara
Rehan merasa tidak tahu-menahu adanya pembatalan itu. Setelah
tanah itu menjadi milik Konsulat Jepang, hanya Rehan yang
menggugat. Pemilik sebagian lainnya dari tanah itu, Tongku
Sagala, konon diberi ganti rugi oleh Hasan Chandra, sehingga
mengurungkan niatnya menggugat Konsulat Jepang.
Rehan tentu saja tidak bisa menerima putusan pengadilan. Sambil
meminta perpanjangan HGB nomor 9 itu -- yang akan berakhir 1985
-- Rehan meminta pengacaranya naik banding. "Di mana lagi letak
kekuatan hukum sebuah sertifikat?" dipertanyakan Abdul Muthali
Sembiring, yang merasa kepuusan ltu merugikan kliennya.
Ketua Majelis Hakim yang memutuskan perkara itu, S.M. Sudihardjo
merasa keputusannya benar. HGB nomor 9 itu, katanya, sudah
dibatalkan oleh DirekturJenderal Agraria sejak 1971. "Berarti
HGB di tangan Rehan itu dianggap tidak ada lagi," ujar
Sudihardjo. Pembatalan sebuah sertifikat atau sebuah akta yang
berkekuatan hukum, kata hakim itu lagi, bisa saja dilakukan.
"Jika terjadi kekeliruan," tambahnya.
Hakim itu membenarkan dalam kasus itu pihak Rehan -- sebagai
pembeli beriktikad baik -- menderita rugi. Tapi yang bisa
dituntut penggugat itu, katanya, kedua suami istri Marah Laut.
Repotnya, Marah Laut dan Asmah tidak ditemukan lagi alamatnya
sejak ia menandatangani pengembalian HGB-nya kepada Kodam II,
1968, dan setelah menjual semua tanah itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini