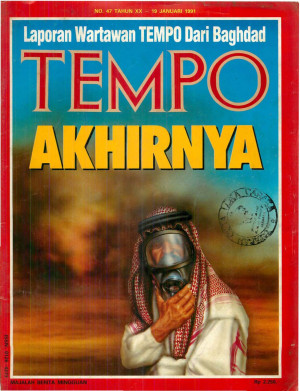H. JOHN NARO, 61 tahun, bekas Ketua Umum PPP, itu akhirnya menang berperkara. Rabu pekan lalu, Naro, lulusan FH UI yang pernah menjadi jaksa, itu berhasil memperkarakan tujuh orang ketua kelompok pengarap tanah yang diakui miliknya itu, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka masing-masing diganjar hukuman 2 bulan dalam masa percobaan 8 bulan karena dianggap telah menyerobot dan menguasai tanah itu secara tidak sah. Namun, tak berarti Wakil Ketua DPR/MPR itu bisa menguasai kembali tanah miliknya seluas 2,6 ha itu. Bahkan tanah yang terletak di wilayah Jakarta Barat, dan rencananya di atasnya akan dibangun hotel berbintang lima di atasnya itu, belum lama ini sertifikat HGB-nya dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bukan itu saja. Di atas lokasi sengketa yang terletak di sudut persimpangan jalan tol Jakarta-Tangerang dengan Jalan S. Parman itu, masih saja ada sejumlah penduduk. Jumlahnya, permukiman setingkat RW itu, 800 rumah milik 1.500 keluarga. Menurut Naro, mereka ini cuma penggarap yang tak kunjung mau meninggalkan tanahnya. Namun, di luar semua itu, ternyata batas-batas tanah itu - yang diakui milik Naro -- memang tak jelas. Maklum, tanah yang semula rawa dan berasal dari eigendom (hak milik Barat) itu merupakan bagian dari satu paket tanah seluas sekitar 9 ha. Pada 1966, tanah tersebut dihibahkan Bung Karno kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Rencananya, PB NU akan membangun gedung Islamic Centre dan Universitas NU di atas tanah itu. Untuk itu, tentu perlu izin membangun dan sertifikat tanah, termasuk pembebasannya. Namun, sampai Ketua PB NU Djamaluddin Malik meninggal dunia, pada 1970, sertifikat itu tak kunjung bisa diperoleh. Mungkin karena tanah itu masih terkena jalur hijau. Pada 1971, di masa Ketua PB NU Kiai Achmad Sjaichu, muncullah nama Eddy Tandyowidjojo. Eddy mengaku sanggup menyelesaikan urusan sertifikat dan menyediakan dananya. Cerita berikutnya malah menjadi simpang siur, karena ternyata, pada 3 April 1971, Eddy membeli tanah itu -- tercatat seluas 82.460 m2 -- dari PB NU. Eddy baru membayar Rp 130 juta -- 3/4 dari harga beli. Toh izin membangun dan sertifikat tak juga diperoleh. Tugas itu pun, di masa Ketua PB NU Kiai Idham Chalid, dilanjutkan Ketua NU Jakarta, Fachrurazi. Ternyata, pada Mei 1973, Fachrurazi malah menjual lagi tanah itu -- tertulis 96.000 meter persegi -- kepada Letkol. (Pol.) Markono Tisnawidjaja (kini almarhum). Waktu itu, Markono baru membayar Rp 80 juta (1/4 dari harga beli). Sebesar Rp 50 juta dari uang Markono itulah yang kemudian digunakan PB NU untuk menggantikan uang Eddy. Belakangan, seperti juga Eddy, baik Fachrurazi maupun Markono tetap tak bisa menyelesaikan tugasnya untuk memperoleh sertifikat itu. Sebab itu, Markono menagih kembali uangnya -- kabarnya, PB NU sudah membayar Rp 50 juta. Pada 1975, urusan tanah itu semakin tak jelas juntrungannya. Soalnya, Markono kemudian diadili dengan tuduhan menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli tanah tadi. Akibatnya, seperempat bagian dari tanah PB NU tersebut disita pengadilan. Belakangan, pada Mei 1985, MA menyatakan tanah itu dirampas untuk negara. Sementara itu, entah bagaimana prosesnya, pada 1976, Naro berhasil membuat Idham Chalid menjual seluas 4,7 ha dari tanah itu kepadanya, dengan harga Rp 165 juta. Seluas 2,1 ha dari tanah itu untuk jalan tol, sisanya (2,6 ha) menjadi milik Naro. Menurut bekas Sekjen PB NU, K.H. Yusuf Hasyim, sebenarnya Naro belum membereskan pembayaran itu. Namun, herannya, pada 1980, lewat proses hibah, Naro bisa memperoleh lagi sisa tanah PB NU, seluas 4,3 ha (seluas 2,5 ha menjadi milik Naro, sisanya untuk jalan tol). Naro bukan saja berhasil mendapatkan hampir seluruh tanah PB NU itu, pada Maret 1977, ia juga berhasil memperoleh izin membangun dari Gubernur DKI Jakarta. Bahkan dua tahun kemudian, Juli 1979, Naro bisa memperoleh sertifikat HGB atas tanah miliknya seluas 2,6 ha tadi. Untuk itu, Naro menyetor Rp 42 juta lebih ke kas negara dan memberikan ganti rugi pembebasan tanah kepada para penggarap. Rencana Naro, pada awal 1992, di atas tanah itu sudah berdiri hotel berbintang lima "Crown Plaza", yang bernilai Rp 116 milyar. Ternyata, rencana itu berantakan. Gara-garanya, putusan MA dalam kasus Markono, plus sulitnya menggusur para penggarap. Akhirnya, pada Februari 1990, Naro menggugat ahli waris Markono dan Oditurat Jenderal Tinggi ABRI. Ia menganggap kedua tergugat inilah yang membuat rencananya membangun hotel menjadi berantakan. Sementara gugatan berjalan, pada September 1990, malah Oditurat Jenderal yang memohon agar BPN membatalkan sertifikat HGB milik Naro. Sebab, kata sumber TEMPO, cara perolehan sertifikat tanah itu -- yang masih dalam status sita jaminan - tidak benar. Menurut sumber itu, sebenarnya PB NU hanya memberikan kuasa kepada Naro untuk menjual tanah tersebut. Selain itu, BPN tak mengetahui transaksi antara PB NU dan Eddy maupun Markono. Ternyata, pada 10 November 1990, BPN mengabulkan permohonan itu. Pembatalan sertifikat HGB Naro ini, antara lain, diiklankan lewat koran Pelita edisi 3 Januari 1991. "Proses penerbitannya memang keliru. Mungkin panitianya juga kurang teliti," kata Kepala BPN Sony Harsono. Dengan begitu, praktis tanah itu kembali menjadi tanah negara. Keruan saja Naro berang. Sertifikat itu, kata putra Naro, Hussein Naro, kan jelas-jelas diperoleh sesuai dengan prosedur. Lagi pula, "Bagaimana bisa sertifikat yang sedang dijadikan barang bukti dalam gugatan terhadap Oditurat dibatalkan?" ujar Hussein. Sebab itu, Naro akan menggugat BPN. Menurut Soni Harsono, boleh saja Naro menggugat instansinya. Yang jelas, katanya, kini riwayat tanah tersebut masih terus diteliti BPN. "Agar sertifikatnya bisa diterbitkan kembali dan diperuntukkan bagi pihak yang paling tepat," ujar Sony. Katib Am PB NU, K.H. Ma'ruf Amin, berharap status kepemilikan tanah itu dikembalikan pada keadaan semula, yakni milik PB NU. Sebab, katanya, semua kuasa ataupun transaksi yang terjadi atas tanah itu, selama ini, bukanlah atas nama PB NU. Tapi antara orang-orang NU saja, baik Eddy, Markono, maupun Naro. "Untuk tindakan hukum seperti itu kan harus ditandatangani paling tidak oleh empat orang: rais am, katib am, ketua umum, dan sekjen," kata Ma'ruf. Selain itu, segala proses jual-beli selama ini, ternyata, tak ada dokumennya di PB NU. Agaknya, kisah tanah Naro ini masih bakal panjang. Entah dari cerita yang mana BPN akan menyisirnya. Namun, kasus ini cukup menggambarkan perlunya administrasi pertanahan yang ketat dan seragam. Termasuk, tentunya, dokumentasi segala tindakan hukum yang menyangkut hak-hak tanah. Happy S. dan Nunik Iswardhani (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini