Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
UU TPKS sudah berlaku sejak 2022, tapi satu pun kasus kekerasan seksual divonis memakai aturan itu.
Aparatur hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim, kerap mengabaikan UU TPKS karena berbagai alasan.
Aparatur hukum masih memakai perspektif hubungan dalam menangani kasus kekerasan seksual.
PERINGATAN Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan yang jatuh pada 25 November-10 Desember menyisakan catatan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai penegakan hukum terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan masih belum maksimal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Nurani Perempuan Women Crisis Center (WCC) Rahmi Meri Yenti mengatakan satu masalah yang terlihat jelas adalah minimnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh aparatur hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Meri mengatakan sejak aturan itu berlaku hingga hari ini, belum ada putusan pengadilan menggunakan UU TPKS sebagai alat mengadili pelaku kekerasan seksual, walaupun beberapa penyidikan aparat kepolisian sudah menggunakannya. "Belum ada putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," katanya kepada Tempo pada Selasa, 10 Desember 2024.
Dari kepolisian, menurut Meri, sebenarnya sudah ada upaya menjerat pelaku dengan UU TPKS. Menurut catatan Nurani Perempuan WCC, lembaga swadaya masyarakat berbasis di Sumatera Barat, dari total 128 kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak 2022 di provinsi ini, 45 persen disidik dengan UU TPKS. Sisanya, penyidik memakai Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Kami terus mendorong kepolisian resor dan kepolisian sektor se-Sumatera Barat mau menggunakan pasal UU TPKS, tapi ada masalah di pengadilan lagi," ujarnya.

UU TPKS sebenarnya bisa mempermudah kerja aparat penegak hukum dalam mengungkap kekerasan seksual. Hal itu tak terlepas dari perluasan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 24 dan 25 undang-undang tersebut.
Pasal 24 ayat 2 memperluas alat bukti tindak pidana kekerasan seksual seperti yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut memasukkan keterangan korban sebagai salah satu bukti yang sah. Pasal 24 ayat 3 pun menyatakan surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater atau dokter spesialis kejiwaan bisa menjadi alat bukti yang sah.
Sementara Pasal 25 ayat 1 menyatakan hakim bisa memvonis terdakwa bersalah hanya berdasarkan keterangan saksi dan/atau korban plus salah satu bukti sah lain. Ayat 3 pasal tersebut pun menyatakan orang yang tak melihat atau mendengar langsung kekerasan seksual itu bisa menjadi saksi sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindakan tersebut.
Sulitnya menerapkan UU TPKS, menurut Meri, terjadi karena pemerintah belum mengeluarkan semua aturan turunannya. Dari tujuh aturan turunan, baru tiga yang sudah disahkan pemerintah, yakni Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Dari pengalaman Meri mendampingi kasus kekerasan seksual di Sumatera Barat, ia juga menyatakan aparatur hukum kerap menerapkan restorative justice untuk menyelesaikan kasus dugaan kekerasan seksual. Padahal, menurut dia, tindakan ini merugikan korban. Ia menyatakan penerapan keadilan restoratif sering mengabaikan upaya pemulihan. "Banyak yang lupa terhadap pemulihan korban jika kasusnya diselesaikan dengan restorative justice. Padahal trauma korban harus dipulihkan," ucapnya.
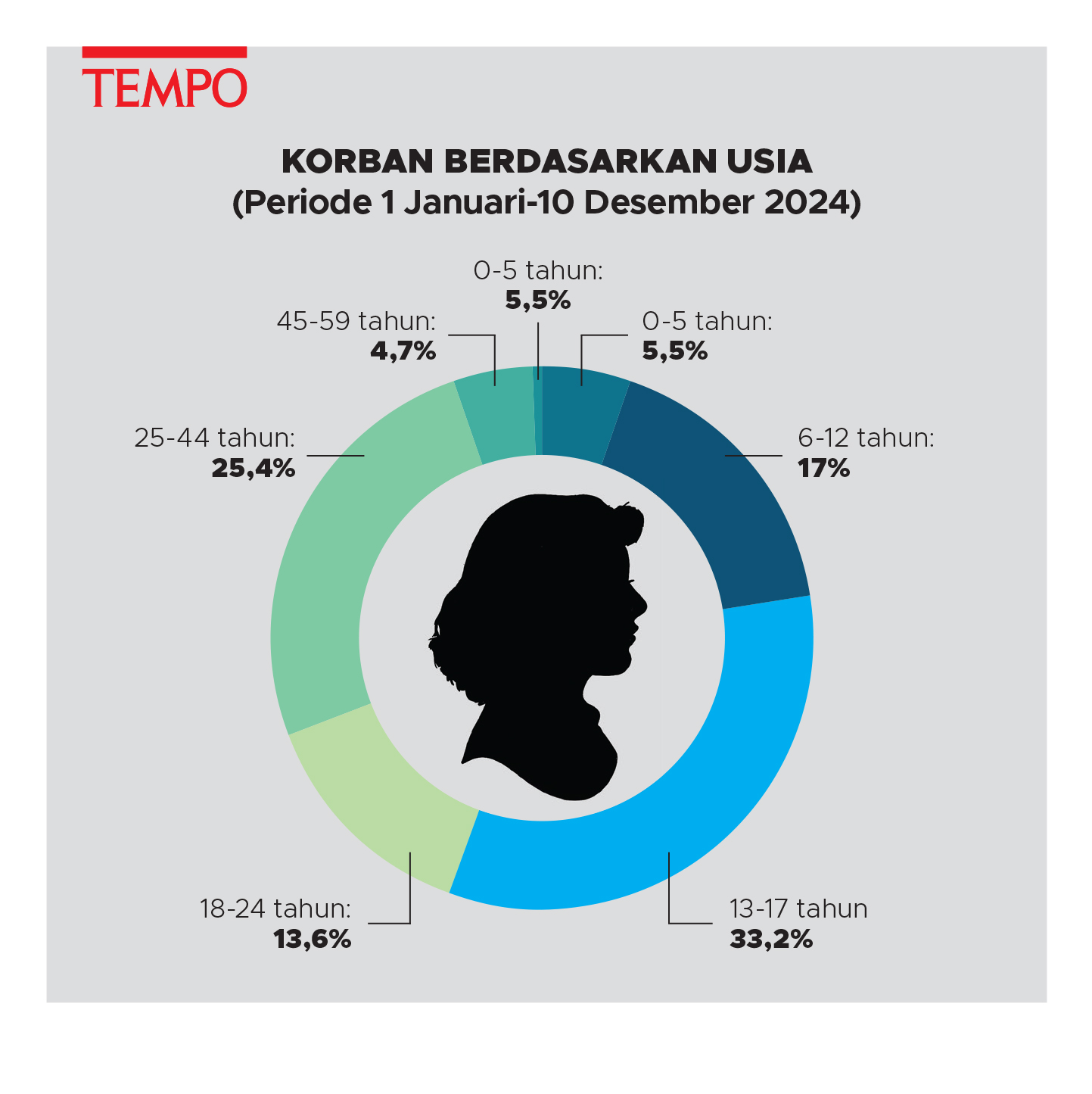
Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Theresia Iswarini menyatakan penerapan UU TPKS belum maksimal karena ada pandangan atau perspektif aparatur hukum yang keliru. Selama ini, menurut dia, aparat selalu melihat unsur kekerasan seksual dari motif suka sama suka atau paksaan. "Konsep dalam UU TPKS adalah relasi kuasa dan keberpihakan kepada korban, tidak melihat hubungan antara pria dan perempuan dengan asumsi suka sama suka," tuturnya.
Selain itu, menurut Theresia, aparatur hukum masih kerap merujuk KUHAP soal kesaksian untuk mengungkap kasus kekerasan seksual. Padahal, jika merujuk pada KUHAP, keterangan seseorang bisa dianggap sebagai kesaksian jika diperkuat dengan keterangan orang lain atau prinsip unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi).
Cara penyidikan tersebut bertentangan dengan UU TPKS yang memperbolehkan hanya kesaksian korban sendiri. "Kadang-kadang orang melakukan kekerasan seksual justru ketika keadaan sepi, tidak ada saksi. Jadi itulah problemnya," ujarnya.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur berpendapat aparat penegak hukum sulit menerapkan UU TPKS karena minimnya literasi. Isnur menilai banyak penegak hukum yang tak memahami UU TPKS. Bahkan, menurut dia, aparat penegak hukum kerap mengabaikan undang-undang terbaru, misalnya Undang-Undang Serikat Buruh dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Sebagai aparatur hukum, kata Isnur, seharusnya polisi, jaksa, dan hakim cepat beradaptasi dengan regulasi dan perkembangan baru. Hal itu sebagai bukti profesionalisme lembaga tersebut untuk memberikan keadilan hukum bagi masyarakat. "Yang mereka (aparat) tahu hanya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU ITE. Ini menjadi problem. Aparat tidak fokus, tidak update, seharusnya cepat dong beradaptasi," ucapnya.
Selain minimnya literasi, Isnur menyoroti kesiapan lembaga-lembaga pendamping sesuai dengan amanat UU TPKS. Dalam UU TPKS Pasal 24 dan 26, korban kekerasan seksual memerlukan surat keterangan dari psikolog klinis serta mendapat pendampingan dalam proses penyidikan hingga persidangan. "Nah, ini problem selanjutnya. Memang belum banyak daerah yang punya psikolog klinis dan lembaga yang bisa memberikan pendampingan. Di sini perlu ada pelibatan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan," tuturnya.

M. Fatahillah Akbar, dosen hukum pidana Universitas Gadjah Mada, mengusulkan semua lembaga penegak hukum membuat pelatihan khusus bagi para personelnya untuk memahami UU TPKS. Alasannya, dalam undang-undang baru pasti ada delik baru juga.
Selain itu, berdasarkan pantauan Fatahillah, terdapat sejumlah unsur yang rumit untuk diterapkan dalam UU TPKS. Dia mencontohkan ketentuan Pasal 6 soal merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Pasal tersebut, menurut dia, mirip Pasal 289 KUHP. Hanya, dalam Pasal 289 KUHP terdapat unsur memaksa orang lain melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.
Karena itu, Fatahillah mengimbuhkan, tak mengherankan aparat penegak hukum kerap memilih tidak menggunakan UU TPKS untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. "Sepanjang bisa pakai KUHP atau undang-undang lain, pada praktiknya penegak hukum memilih pasal yang mudah dibuktikan," ujarnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko tak merespon pertanyaan Tempo soal alasan banyak penyidik yang enggan menerapkan UU TPKS dalam kasus kekerasan seksual. Demikian juga dengan Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto.
Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan biasanya jaksa menyusun dakwaan berdasarkan berkas penyidikan yang diserahkan oleh polisi. "Ketika penyidik mempersangkakan pelaku sesuai UU TPKS, jaksa penuntut umum akan melakukan penelitian berkas perkara terhadap pemenuhan unsur-unsur sesuai pasal sangkaan dari penyidik," kata Harli singkat.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Fachri Hamzah berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Artikel ini telah mengalami perubahan pada Rabu, 11 Desember 2024 pukul 15.45 WIB dengan penambahan keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar dan upaya konfirmasi ke Polri dan Mahkamah Agung.






























