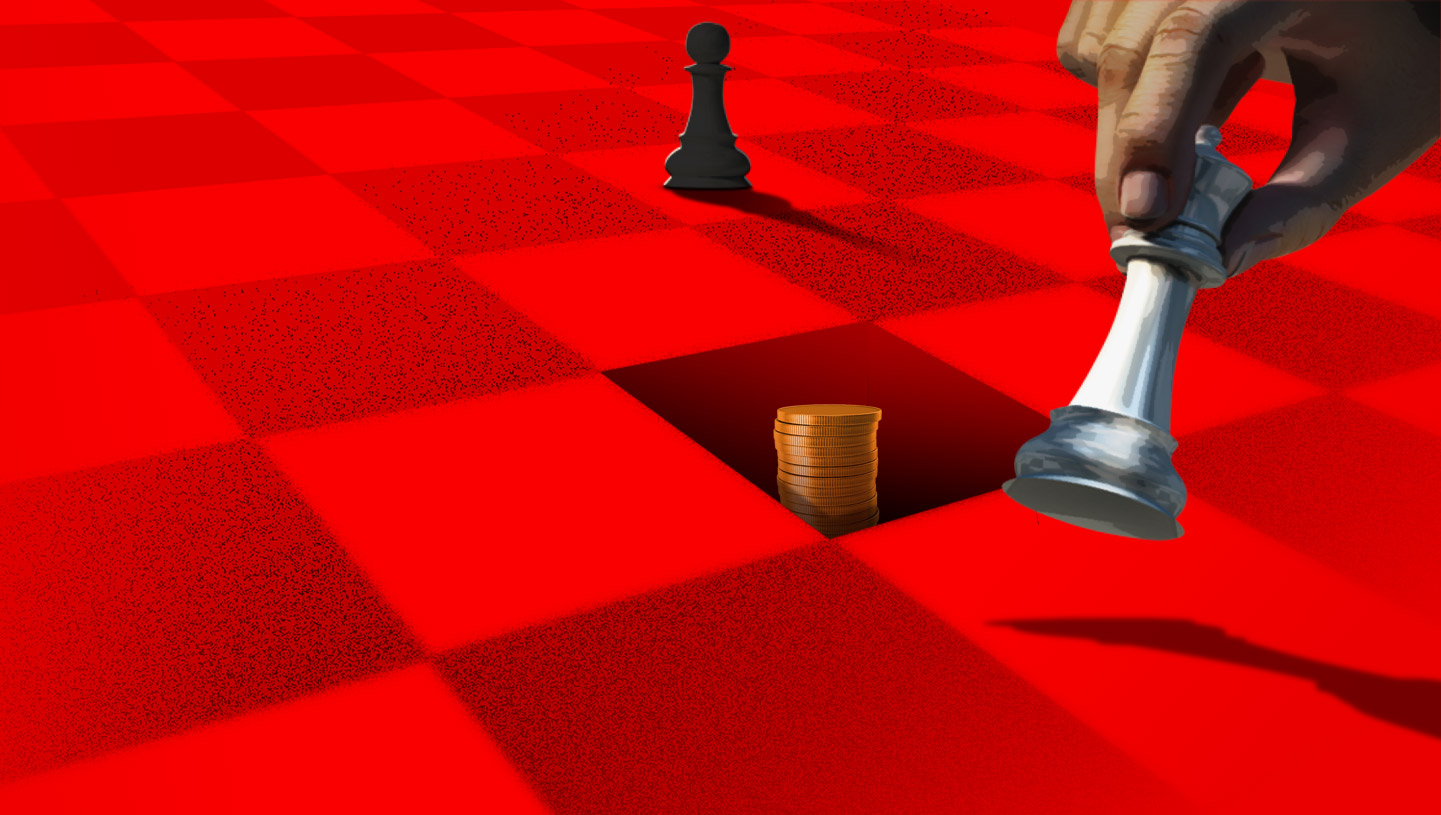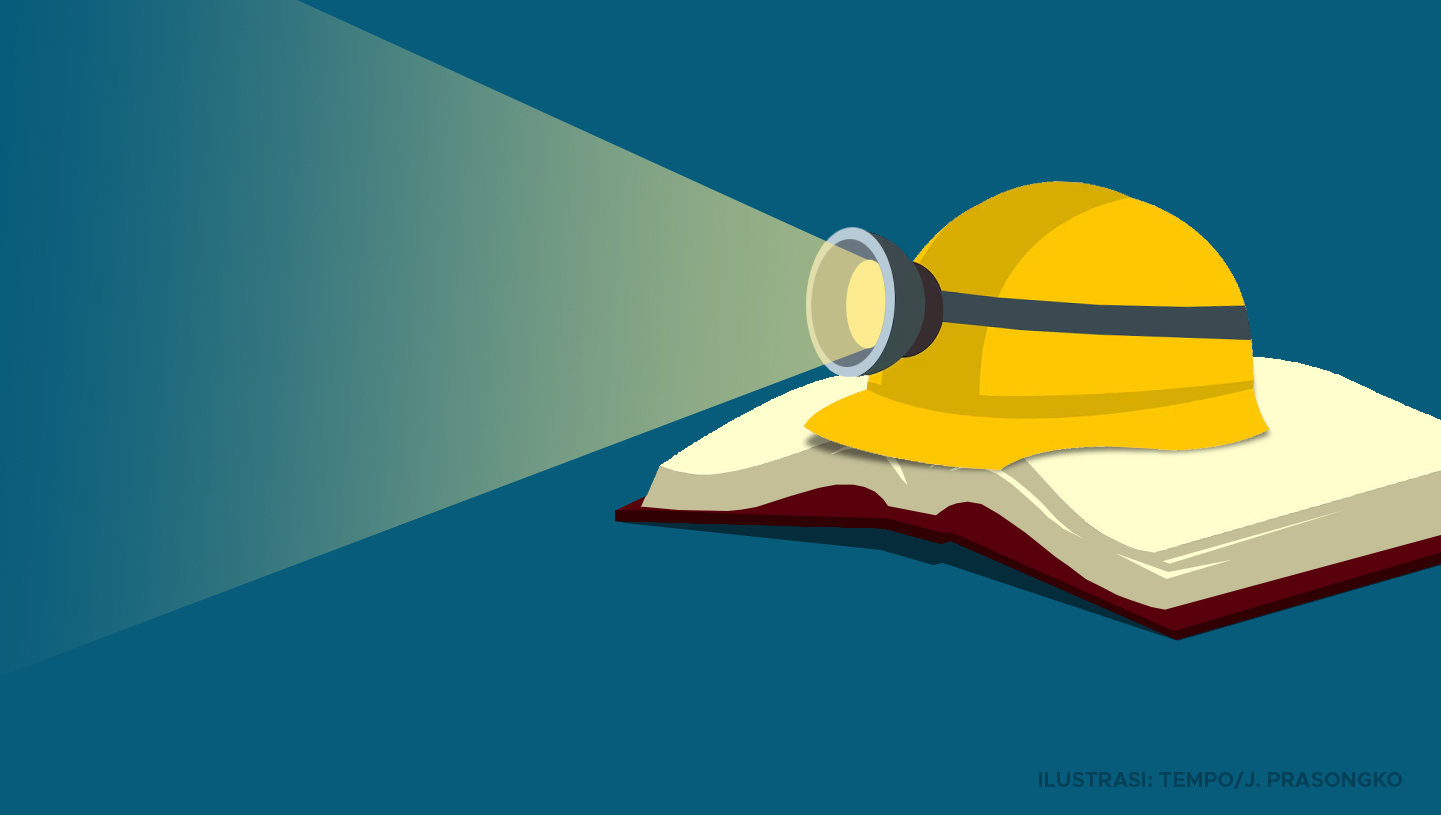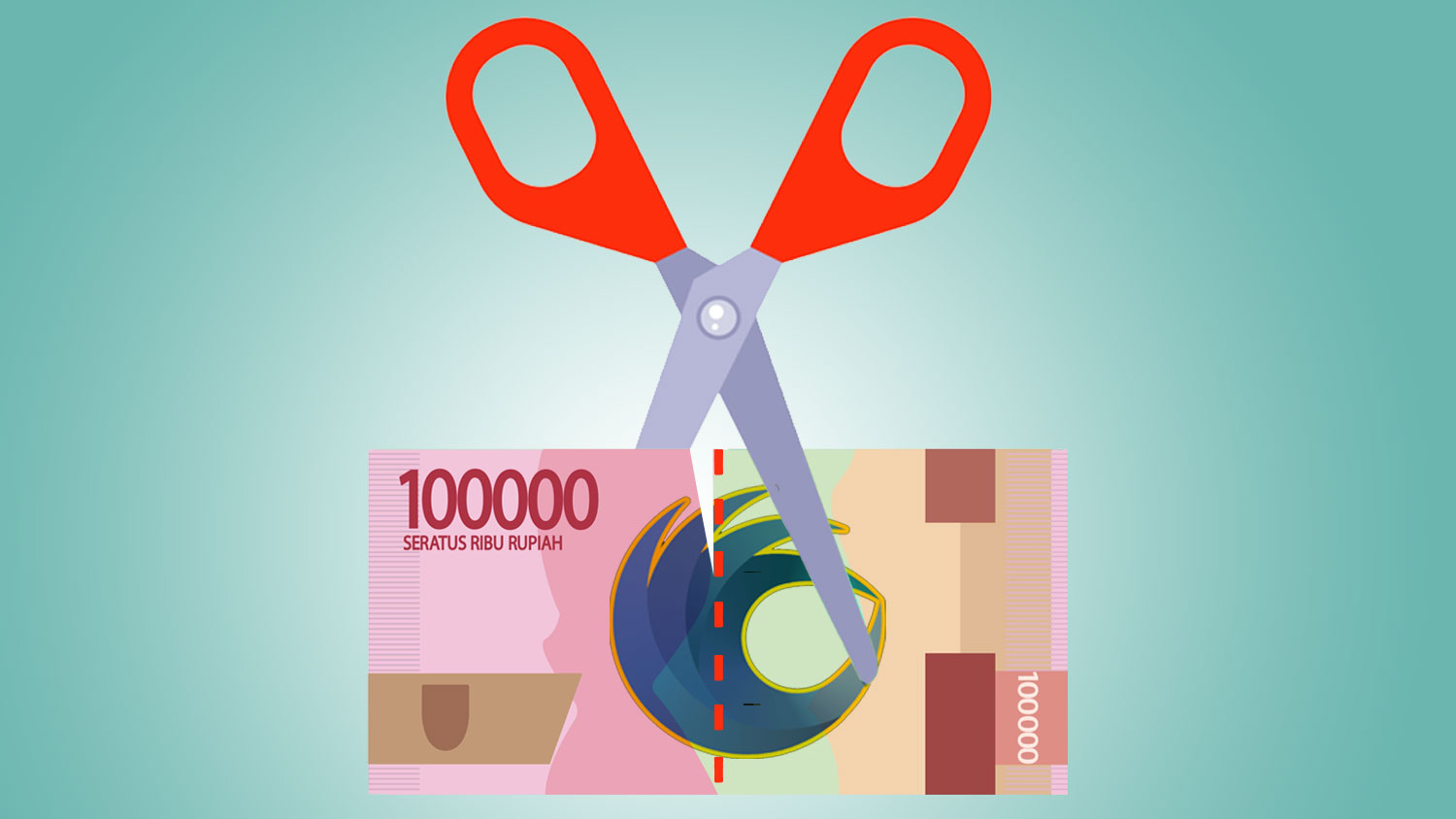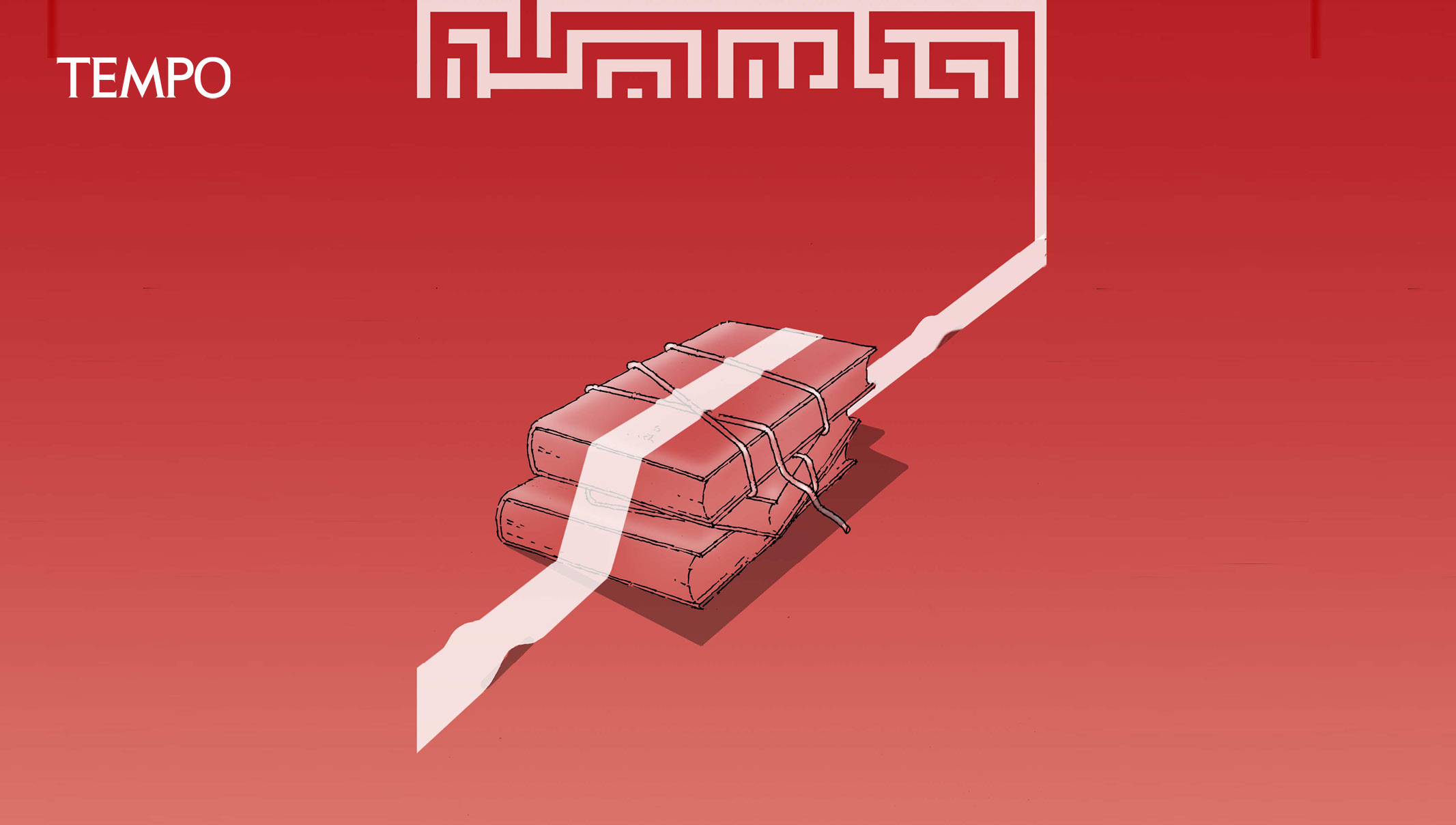Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yang dibicarakan sepatu. Ini di Jakarta, di awal abad ke-20. Persisnya: yang dibicarakan adalah sepatu, sekolah Eropa, murid-murid Belanda, murid-murid bukan Belanda, dan, di balik semua itu, kolonialisme.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Di sekolah menengah pertama MULO saya berpakaian seperti yang diwajibkan celana pendek, jas yang dikancingkan sampai leher tapi masih memakai sandal, belum sepatu. Itu tahun 1920, dan saya masih belum mengenakan sepatu. Saya tak punya sepatu. Hanya setelah hampir masuk HBS, sekolah menengah atas hampir semua siswanya Belanda totok, bukan seperti MULO, yang muridnya kebanyakan anak Indosaya jadi gugup. Tapi, ketika pelajaran berdansa mulai di HBS... saya sudah mulai bersepatu.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Percakapan dengan “Tuan Roeslan” ini direkam sejarawan Rudolf Mrazek dalam A Certain Age: Colonial Jakarta Through the Memories of Its Intellectuals (2010).
Mrazek selalu menulis dengan perspektif yang segar, dengan informasi yang menarik dan wawasan yang diam-diam dalam. Sejarah, dalam buku ini, seakan-akan rekaman yang melankolis tentang waktu yang dilampaui manusia bersama hal-hal yang banal.
Misalnya sepatu.
Mrazek tak menyebut sepatu selain sebagai pelindung kaki. Tapi saya ingin menambahkan: sepatu juga sebuah penanda ketegangan sosial, khususnya di Indonesia dalam kekuasaan “Hindia Belanda” sejak akhir abad ke-20. Ada orang-orang yang tak punya sepatu, ada yang berhak bersepatu, ada yang dilarang dan menolak mengenakan sepatu.
Ini thema klasik. Kostum dan kolonialisme adalah bagian cerita penindasan yang tak terpisahkan di Asia dan Afrika.
Sejak 1658, penguasa Belanda, waktu itu VOC, mengharuskan orang “bumiputra” berpakaian daerah. Mereka dilarang memakai kostum Eropa. Ketika ada sejumlah orang keturunan Cina mencoba, mereka dihukum. Aturan ini, demikian dikatakan, buat mempermudah “menangkap penjahat”.
Sejarah perlawanan lokal yang panjang sejak abad ke-17 membuat kekuasaan kolonial bersiap dengan mendeteksi apa yang di luar dirinya. Busana jadi alat paling langsung untuk itu.
Seorang sejarawan terkemuka dari Leiden, Henk Schulte Nordholt, menyusun Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia (1997) dari makalah beberapa peneliti. Dari buku ini kita tahu, ketika pakaian ditentukan, sebuah teknik penaklukan pun dimulai. Kees van Dijk menggambarkan murid-murid Jawa yang belajar di sekolah Belanda harus memakai pakaian Jawa dan bertelanjang kaki; sepatu adalah “tanda” Eropa. Bahkan di STOVIA, para mahasiswa kedokteran juga harus berpakaian daerah; hanya yang beragama Kristen boleh berpantalon, berjas, dan tentu saja met schoenen.
Tak mengherankan Raden Saleh mengalami kepahitan ini. Perupa tersohor ini kembali ke Hindia Belanda setelah bertahun-tahun di Eropa. Ia ingin mengenakan busana Eropa. Ini melanggar hukum. Ratu Belanda juga tak memberinya keistimewaanmeskipun yang ia inginkan cuma memakai pantalon, jas, dan mungkin boot marinir, yang modelnya sudah kedaluwarsa.
Saya kira ada orang-orang “bumiputra” yang akan menganggap Raden Saleh memperbudak diri. Bagi mereka, berpakaian tradisional seraya menampik kostum “Barat”adalah peneguhan identitas diri. Dalam Si Doel Anak Betawi oleh Aman Datuk Madjoindo (1932), engkong anak itu murka ketika si cucu datang di hari Lebaran dengan berpakaian padvinder: topi, celana pendek, sepatu. Si anak Bidara Cina dibentak dan harus datang mengenakan sarung dan kopiah....
Dengan menangis, sang cucu pun melepas kostum yang dibanggakannya. Tapi bagi Engkong, orang Betawi mesti “tetap betawi”. Yang semacam itu terjadi ketika gerakan Boedi Oetomo diambil alih arahnya oleh kalangan priayi tinggi Jawa yang bertopang kepada apa yang dianggap sebagai yang “asli”, dengan adagium Radjiman Wedyodiningrat bahwa “bangsa Jawa tetap jawa”.
Agaknya itu sebabnya kita mengenang Boedi Oetomo, pada tanggal kelahirannya, 20 Mei, dengan membayangkan wajah Wahidin Soedirohoesodo berbaju surjan dan blangkon seakan-akan “kebangkitan nasional” hanya terbatas pada apa yang dianggap “Jawa”.
Tidak, 20 Mei tak hanya itu. Dari kebangkitan 111 tahun yang lalu itu ada Tjipto Mangoenkoesoemo. Dalam Kongres Pertama “Jong Java” di tahun 1908, lulusan STOVIA itu menunjukkan perlawanannya menghadapi Radjiman dengan berdebat dalam bahasa Melayu, sementara lawannya berbahasa Jawa.
Dalam dasawarsa selanjutnya, getar perlawanan itu berlanjut. Doenia Bergerak, yang terbit di tahun 1914 dan tentu saja pemimpin redaksinya, Mas Marcoakan dikenang sebagai penentang keras ide “bangsa Jawa tetap jawa”. “Adat Majapahitan” harus ditolak. Kain, destar, dan blangkon hanya mempermudah penindasan. Jas, pantalon, dan dasi yang dipakai di depan para aristokrat dan pejabat kolonial akan menggedor mereka: ini bukan pakaian untuk menyembah. Maka, tulis Mas Marco, seorang bupati hilang lepas nyawanya ketika melihat seorang Jawa berpakaian Eropa, lengkap dengan sepatu di kakinya.
Memang ini bukan cerita pengganti sandal. Ini cerita ketika politik identitas diungkai dan ditunjukkan: di atas itu, di atas sol itu, ada politik ketaksetaraan.
Goenawan Mohamad