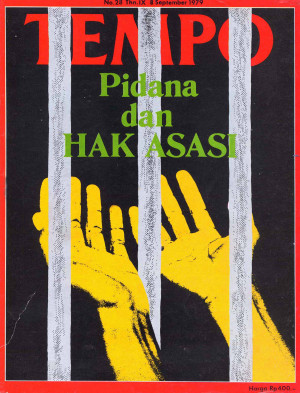JIKA berminat perihal kemungkinan-kemungkinan cara mati,
buka-bukalah bab tentang Saija dan Adinda yang tehor itu, dalam
Max Havelaar. Kepala distrik Parangkujang yang serakah telah
merampas kerbau Saija. Ayahnya melarikan diri dari Badur karena
tidak mampu membayar pajak tanah. Saija lalu mencoba mengadu
untung ke Betawi, dengan harapan bisa bekerja sebagai kacung
bendi. Dalam perjalanan dilamunkannya kematian dari pertemuan.
Lika-liku jiwa Saija, kedalaman cintanya pada Adinda,
disingkap-singkapkan Multatuli dengan perulangan sampai lima
kali: "Aku tak tahu di mana aku akan mati."
Saija tak ingin mati di samudera luas, tubuh terlempar ke air
dalam, ikan hiu berebutan datang. Ia tak ingin mati terbakar
seperti Pak Ansu, mayatnya ditimpa kepingan-kepingan kayu
berpijar. Saija ingin mati seperti orang kebanyakan di Badur,
dikafani, lalu ditanam dalam tanah. "Bila aku mati di Badur, dan
aku ditanam di luar desa, arah ke timur di kaki bukit dengan
rumputnya yang tinggi maka Adinda akan lewat di sana, tepi
sarungnya perlahan mengingsut mendesir rumput, .... Aku akan
mendengarnya."
Mbah Suratinem juga punya keinginan yang mirip tapi tanpa rona
romantis seperti itu. Hidupnya menjanda dan menggelandang di
kota, usia lebih 70 tahun, anak satu-satunya mati tertembak di
Maluku. idupnya terlantar. Pesannya pada cucunya, kalau mati
supaya dikubur di desanya. Walau miskin, ongkos sudah dia
sisihkan ala kadarnya. Dan itu, Insya Allah, akan dilaksanakan
cucunya yang miskin, yang selalu memberinya kehangatan.
Alasannya berkubur di sana, supaya gundukan tanah yang memendam
jasadnya tidak terlantar supaya ada yang mengunjungi dan
membersihkan pada bulan Ruwah dan Lebaran, supaya sesekali
mendapat taburan bunga kantil, mawar dan kenanga. Kalau dikubur
di kota jelas terlantar. Bukankah penanggungan terlantar pada
usia tua begini sudah lebih dari cukup?
Contoh mbah ini tidaklah umum. Dia sial kehilangan anak,
penopang hidup satu-satunya, dan yang tinggal cuma cucu yang
miskin. Kalau anaknya tidak mati muda dan kalau anaknya "jadi
orang", jalur hidupnya tentu lain. Bukankah untuk jaminan hari
tua, anak lebih kokoh dari emas dan Tabanas'? Selagi keadaan
ekonomi negara belum beres, tempat bergayut ialah anak, terlebih
pada ruas akhir kehidupan.
Pada masyarakat ini, orang tua dihormati dan dibantu sejauh
mungkin. Orang tua yang uur, reot dan keriput takkan dilayani
seperti perkutut yang gagal: dibanting ke tanah karena suaranya
tidak lagi hoorketekung tapi sudah merosot --hoorketekekkek,
hoorketekekkek . . . Sebab bukankah menurut Wulangreh,
penghormatan yang tinggi wajib diberikan kepada orang tua? Ayah
dan ibu wajib dihormati karena mereka yang "menjadi lantaran
manusia berada di dunia." Juga mertua, karena mereka yang
"memberi rasa sejati dan melanjutkan keturunan."
***
Why survive? (Mengapa masih hidup?) Demikian judul buku dr.
Butler (1975) yang menarik itu. Isinya perihal kehidupan lanjut
usia di Amerika Serikat yang merisaukan. Bab satu merangkum
permasalahannya dengan baik: tragedi mereka yang berusia lanjut.
Ternyata banyak yang terjerat kemiskinan setelah lanjut usia.
Jaminan Sosial (Socil Security) belum mampu mengikis habis
beban kemiskinan kelompok usia lanjut. Ukuran apa pun
dipakai--termasuk ukuran resmi pemerintah--jelas besar jumlah
mereka yang dijerat kemiskinan. Pada tahun 1970 seperempat dari
orang-orang tua itu tergolong miskin. Angka ini berobah pada
1972 karena kenaikan jaminan sosial. Namun, paling tidak 3
sampai 3,6 juta golongan tua di Amerika Serikat tetap tergolong
miskin.
Persoalan hidup mereka bisa datang mendadak, dalam berbagai
ujud. Mereka sering jadi sasaran empuk dari kejahatan, baik di
jalanan maupun di rumah. Karena pendengaran dan penglihatan
memburuk, mereka kerap jadi korban penipuan penjual ini penjual
itu dan juga pelbagai penjual jasa. Pintuputar berputar terlalu
cepat bagi mereka. Juga sering punya kesukaran fisik naik turun
tangga. Karena berjalan lemah dan lamban diteriaki pula oleh
sopir bis yang tak sabar.
Humanisme menjadi penghias etalase, kalau masyarakat membuat
keuntungan materi jadi takaran satu-satunya. Orang-orang jompo
telah membeberkan kegagalan peradaban kita. Habis manis sepah
dibuang. Demikian Simone de Beauvoir dari Perancis dalam bukunya
The Coming of Age (1973). Maka semuanya secara menyeluruh perlu
ditata kembali.
Pada tanggal 15 Agustus 1979, dua hari sebelum ulang tahun
kemerdekaan yang ke 34, koran memuat berita: "Pensiunan tua,
sasaran copet gaya baru." Diberitakan kakek Asikdari Banjaran
disikat dengan teknik salam-tempel di perempatan jalan di depan
gedung Kas Negara. Dengan menyalami dan merangkul secara akrab
digaet habis uang pensiunan sebanyak Rp 75.000.
Ibu Ica, pensiunan dari Cicalengka berusia 60 tahun, mengalami
nasib serupa. Setelah disalami dan dipeluk oleh pemuda berbaju
belang hitam, amblaslah semua uang pensiunan sebesar Rp 52.500.
Maka patutlah dipertanyakan: adakah ini sebuah pertanda?
Pertanda erosi. mulai menjamah sebuah nilai yang luhur?
Jawabannya mudah-mudahan "tidak". Jika "ya", alangkah pilunya.
Alangkah sedih bila dalam alam pembangunan ini seorang seniman
harus bertutur: "Aku tak ingin mati seperti pensiunan Pak Alit:
pulang dari Kas Negara disambar pemuda kekar, di bawah pohon
asam jasad dingin terkapar, darahnya membasahi rumput .... "
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini