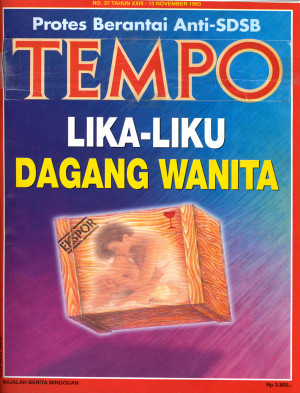Seperti yang diperkirakan, duet sipil-militer Harmoko dan Ary Mardjono terpilih menggantikan duet militer-sipil Wahono dan Rachmad Witoelar, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golongan Karya (Golkar) untuk periode 1993-1998. Pada masa seperti ini, pasti akan terjadi pergeseran kultur dan struktur dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Golkar, sebagai organisasi politik terbesar dan berpengaruh, memiliki peranan besar untuk menentukan luas-sempit atau maju- mundurnya pergeseran itu. Langkah antisipasi, mestinya, tercermin dalam program kerja pengurus baru itu. Sayangnya, itu terlewatkan diamati secara mendalam. Kita tenggelam di tengah pencalonan ketua umum baru dengan dikotomi sipil-militernya. Lebih bijaksana menunggu langkah nyata penjabaran program kerja pengurus baru itu ketimbang membuka kembali lembaran berita terdahulu yang memuat pernyataan pengurus tentang program kerjanya. Ganjalan pertama dan terberat, menghilangkan isu dikotomi sipil-militer yang masih melekat pada struktur kepengurusan barunya. Jika di DPP sekitar 95% anggota dari kalangan sipil, tapi tidak demikian dengan struktur di daerah. Lebih 75% Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) diisi oleh militer, baik melalui jalur A (ABRI) maupun Keluarga Besar ABRI (KBA). Adanya bargaining position itu menimbulkan kekhawatiran awam. Suatu saat, bisa timbul friksi antara kedua pihak tersebut. Itu menyebabkan ketidakselarasan, dan program kerja tidak akan sukses. Sebab, tidak ada kesatuan pandangan dalam gerak dan langkah organisasi. Buntutnya, Golkar tak mampu merespons secara baik perubahan kultur dan struktur yang terjadi. Keinginan Dewan Pembina menjadikan Golkar orpol dengan mayoritas tunggal pada Pemilihan Umum 1997 tinggal impian. Friksi antarkelompok yang terjadi di tubuh Golkar, secara tak langsung, akan mengganggu stabilitas nasional dan laju pembangunan. Inilah tantangan terberat bagi duet Harmoko-Ary Mardjono: menghilangkan (isu) dikotomi sipil-militer di tubuh Golkar dan menyelaraskan kembali pandangan, gerak, dan langkah Golkar dalam mewujudkan cita-citanya (kembali ke khitah 1964). Kewibawaan Dewan Pembina juga diperlukan untuk meleburkan perbedaan-perbedaan pandangan ataupun visi politik di antara kelompok-kelompok yang ada di tubuh Golkar, sehingga, pelaksanaan program kerja untuk merespons masa-masa transisi dan pergeseran-pergeseran kultur dan struktur sosial politik bangsa Indonesia berjalan mulus. Dan niat menjadikan Golkar sebagai lokomotif demokrasi (meminjam idealisme Adnan Buyung Nasution) bisa terwujud. SUNU WIDI PURWOKOMahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok-Jawa Barat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini