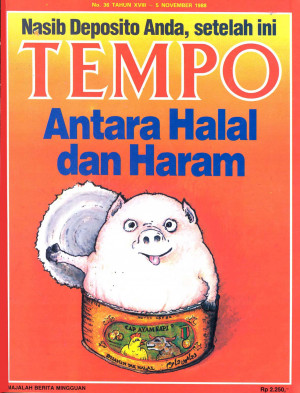SUATU ketika, Batara Narada berbahasa Melayu kepada Dewi Sinta. Memang aneh, terutama karena ini terjadi dalam Babad Kraton yang ditulis dalam bahasa Jawa di abad ke-18. Adakah niat lain di dalamnya, misalnya untuk menyindir? Kita tak tahu. Cuma disebut, Dewi Sinta kemudian bertanya, "Siapa yang bicara seperti orang Belanda itu?" Tak berarti hanya yang "seperti orang Belanda" yang berbahasa Melayu. Dalam beberapa naskah cerita Panji, yang ditulis di abad ke-18 ataupun sesudahnya, ada adegan ketika orang Jawa menggunakan bahasa "asing" itu. Prof. Purbatjaraka, yang menulis Tjerita Pandji Dalam Perbandingan, mengatakan, "Bagi orang Jawa, bahasa Melayu yang dipergunakan dalam pergaulan dengan orang asing kedengarannya gagah." Gagah? Dari sudut pandang lain, nampak bahwa pemakaian bahasa Melayu, di sela-sela dialog berbahasa Jawa, menunjukkan satu pertanda: ada yang tak akrab dalam komunikasi itu. Kini tentu agak lain keadaannya. Bahasa Indonesia mendadak dipergunakan ketika sang pembicara, yang semula berbahasa daerah, terlibat dalam suatu diskusi -- tentang ekonomi, misalnya. Ia memerlukan konsep-konsep, seperti "pertumbuhan", "pemasaran", atau "dana cair", yang belum berkembang dalam bahasa daerah. Tak berarti bahasa Indonesia telah jadi bahasa yang intim bagi kebanyakan kita. Penguasaan bahasa secara intim tak ditandai dengan penguasaan atas konsep-konsep, kata-kata abstrak. Ada seorang teman yang punya cara menguji sejauh mana seseorang menguasai sebuah bahasa. Ia tak mengujinya dengan menyuruh baca sebuah risalah filsafat. Ia mengujinya dengan meminta orang itu bercerita bagaimana membuat telur dadar. Untuk bisa bercerita bagaimana membuat telur dadar, kita harus tahu nama pelbagai bumbu dan alat dapur. Kita juga harus tahu bagaimana menyebut tiap tahap dalam proses kerja. Dengan kata lain kita harus menguasai kata-kata kongkret -- bagian dari hidup sehari-hari. Itulah tanda keakraban kita dengan sebuah bahasa. Sejauh ini, hubungan kita dengan bahasa Indonesia memang belum akrab benar. Dan ini sebenarnya menyedihkan, karena kita sudah mulai lupa akan bahasa daerah kita, sementara bahasa asing tak kita kuasai. Pada saat yang sama, suatu proses pemelaratan bahasa Indonesia sedang berlangsung di sekitar. Di sekolah, anak-anak belajar bahasa Indonesia, tetapi mereka tak pernah diajar berpidato, berdebat, menulis puisi tentang alam ataupun reportase tentang kehidupan. Mereka cuma disuruh menghafal: menghafal apa itu bunyi "diftong", menghafal definisi tata bahasa, menghafal nama penyair yang sajaknya tak pernah mereka baca. Di luar sekolah, proses pemelaratan bahasa mengambil pelbagai bentuk lain. Tiba-tiba saja kita kehilangan arti atau kehilangan kata. Tiba-tiba saja kita kacau. Contoh: Ambisi: kata ini semula hanya berarti "cita-cita besar". Satu proses pemiskinan terjadi: kata itu kini disatuartikan dengan "ambisius". Misalnya, "Dia itu orangnya ambisi." Dengan itu kita bukan saja kehilangan daya membedakan kata sifat dan kata bendanya. Kita juga akhirnya cuma punya satu kata untuk dua arti. Hal yang sama juga terjadi pada kata emosi. Kita juga mencampuradukkannya dengan pengertian "emosional". "Jangan emosi, Dik." Depdikbud: ini contoh bagaimana sebuah akronim dipaksakan. Akronim nampaknya memang sulit dihindarkan dari bahasa Indonesia, yang tiap katanya bersuku kata banyak. Kata berdikari, yang sebenarnya akronim seperti kata hansip, telah memperkaya kosakata Indonesia. Tapi Depdibud tidak. Ia hanya sekadar memenuhi ketentuan akronim yang dipakai di kalangan ABRI. Haruskah yang berlaku untuk kalangan ABRI pas dipakai untuk di luar itu? Haruskah DPR diubah jadi "Wanwara" dan RSUP jadi "rumkitumpus"? Kata Depdikbud bukan saja sulit diucapkan, tapi -- seperti kebanyakan akronim menyebabkan orang bisa lupa dan bingung akan arti semula kata itu. Dan kita ingat: PKI juga gemar akronim, misalnya "Politbiro" dan "Agitprop" -- belum lagi yang untuk memaki, misalnya "kabir" (kapitalis birokrat) dan "Manikebu" (Manifes Kebudayaan). Akronim seperti ini menggedor kesadaran kita hingga kita tak peduh lagi untuk mengenal kata-kata asalnya. Tegar: kata ini dimaksudkan untuk menerjemahkan apa yang dalam bahasa Inggris disebut rigid, "kaku dan tak luwes". Tapi kini ia disalahartikan hingga jadi seperti "teguh" atau "kukuh". Misalnya, "Pancasila harus tetap tegar." Kita telah kehilangan kata untuk arti rigid. Atau kita tak tahu bahwa kita telah mengacaukan "keteguhan" dengan "ketidakluwesan". Yang terjadi kemudian adalah suara gagap. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini