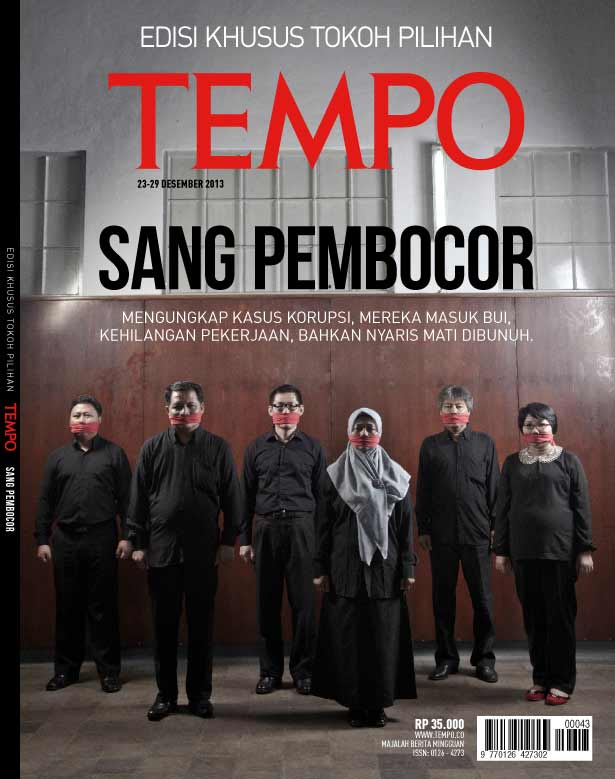Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Membaca sejarah, menyusun sejarah, adalah berkabung. Kita menyadari ada kematian. Kita menemui yang tak bisa lagi dihidupkan. Kita takziah ke dunia tokoh-tokoh yang tak ada lagi dan peristiwa yang tak bisa diulangi. Kita mencoba menghadirkannya kembali—tapi pada saat itu juga kita tahu, selalu ada yang luput. Bukan karena amnesia.
Sebuah riwayat—lihat film Soekarno, Lincoln, atau October: Ten Days That Shook the World—hadir di sebuah layar putih. Dengan kata lain, ia disusun dalam seraut bentuk. Bangunan naratif itu menghendaki awal dan akhir. Apa gerangan yang terjadi sebelum awal dan sesudah akhir itu? Sang penyusun cerita terpaksa menghilangkannya. Bentuk adalah reduksi yang meringkus dan meringkas data yang bertaburan, susup-menyusup, berubah terus, centang-perenang.
Bentuk itu, kisah sejarah itu, terbangun oleh kenangan, bukan oleh ingatan. Saya membedakan ingatan dari kenangan. Yang pertama rekaman pengalaman yang kita bayangkan tersimpan di sebuah ruang imajiner dengan label "masa lalu". Ingatan mudah ditata. Kenangan sebaliknya: ia tak tertata dalam ruang terpisah. Ia mengalir memasuki masa kini, bagian dari masa kini, mengubah secara kualitatif masa kini. Kenangan membikin masa lalu manunggal dengan semua masa. Waktu bukan ruang yang terkotak-kotak.
Tapi para penyusun kitab sejarah membuat arsitektur: cerita mereka terdiri atas bab demi bab, sebagaimana sebuah film terdiri atas adegan demi adegan. Keruwetan ditiadakan, bahkan dalam karya historiografis yang biasanya tak dianggap "modern". Seperti Syair Singapura Dimakan Api yang ditulis Abdullah bin Abdulkadir Munsyi di abad ke-19: cerita sejarah ini disampaikan dalam bentuk puisi, tapi bukan puisi yang ekspresif yang menyeruak acak-acakan dari jiwa yang terkena trauma. Syair itu dengan runut bercerita.
Dengan bentuk serunut itu, menulis sejarah adalah sebuah perkabungan resmi. Sering kali kita memerlukannya. Kita telah bersua dengan waktu dan kematian. Kita seakan-akan menyaksikan Kronos, dewa waktu dalam mithologi Yunani yang—seperti digambarkan dalam sebuah lukisan Goya—mengerkah anaknya yang hidup. Dan kita gentar.
Syahdan, di hadapan kita ada dua jalan. Pertama, jalan yang ditempuh Hegel. Filosof Jerman ini menampik Kronos. Ia mengukuhkan Zeus, "dewa politik"—Zeus yang mengendalikan arus waktu, Zeus yang menegakkan stabilitas, Zeus (penguasa di Olimpus) yang membentuk struktur dan menegaskan hukum-hukum yang abadi di atas bumi.
Jalan yang kedua: kita mengakui kematian, namun menolak Kronos dan sekaligus Zeus. Kita membangun sebuah narasi yang dekat dengan arus kehidupan yang tak abadi tapi berarti. Kita ingin merasakan geraknya, menyentuh dinginnya, menyimak pelbagai partikel yang membuat warna dan aromanya. Dengan hasrat itu kita bawa tokoh dan peristiwa yang sudah lewat ke tengah masa kini—dan novel, lakon, dan film sejarah pun diproduksi.
Dalam karya-karya itu, alur bergerak dalam "hari yang seakan-akan sekarang". Para pembaca Bumi Manusia dibawa ke masa kini Nyai Ontosoroh. Dalam bentuk lakon, seperti Sandyakalaning Majapahit Sanusi Pane, "hari yang seakan-akan sekarang" bahkan datang lebih langsung. Di pentas, sebagaimana di layar putih, para tokoh sejarah hadir di masa kini.
Para sejarawan akan menegaskan, itu bukan bagian historiografi. Tapi barangkali bisa didalihkan, sebuah novel (atau sebuah lakon, juga sebuah film) tetap penting karena ia menampik Hegel. Dari puncak menara filsafat, Hegel (juga Marx) memandang perjalanan hidup manusia dengan angkuh: aku bisa melihat sejarah secara lengkap, aku tahu apa awal dan ujungnya.
Novel menunjukkan bahwa hidup tak bisa disimpulkan dari menara tinggi. Para tokoh novel tumbuh dari kancah sejarah: mereka tak akan beroleh gambaran total riwayat mereka sendiri. Mereka melangkah, mereka berjuang, tapi selalu meraba-raba jalan. Biarpun mereka tampak di tengah "narasi besar"—misalnya dalam perjuangan kemerdekaan sebuah bangsa—hidup mereka adalah pelbagai narasi yang "kecil" dan "lokal". Yang mereka ketahui datang sepenuhnya dari praxis. Mereka adalah kerja, mereka berkreasi, berproduksi; mereka bukan makhluk teori.
Tentu teori tentang sejarah diperlukan. Dengan teori bisa kita rumuskan gejala dan kita perkirakan arah; dalam sebuah ikhtiar pembebasan, misalnya dalam melawan kolonialisme, teori punya peran strategis.
Namun sang pengusung teori akan salah bila ia membentuk apa yang digambarkan Michel de Certeau sebagai "kota panorama". Kota seperti itu tampil sebagai sebuah totalitas, tapi totalitas itu sebenarnya hanya anggitan seorang "dewa-pengintip"—kuasa yang hanya tertarik kepada keutuhan cerita besar sejarah. Maka diabaikanlah narasi kecil yang tak bisa dicocok-cocokkan oleh teori, dan disingkirkanlah apa yang tak terduga-duga. Di "kota panorama", berkuasa sikap yang tak mau menyentuh perilaku manusia sehari-hari.
Seakan-akan datang kematian yang lebih mendasar: yang sehari-hari telah tak lagi punya pesona.
Tapi kita masih punya alternatif. Kita masih bisa berjalan menyusuri kota seperti dalam sebuah novel, atau sebuah puisi, atau sebuah film yang mampu memulihkan pesona itu: sebuah jam tua di dinding, selembar kain warna saga di jemuran, sekilas senyuman dalam hujan. Seakan-akan mereka buat pertama kalinya muncul di dunia….
Kita akan selalu ketemu Kronos dan berkabung, tapi ada hal-hal sepele yang membahagiakan kita.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo