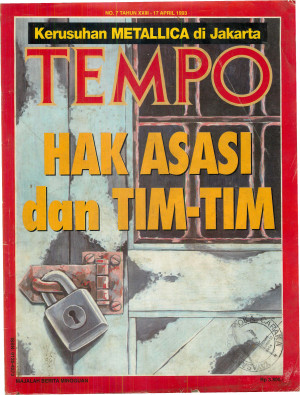BERLIN seperti dicakar sejarah. Berjalan dari Lapangan Marx- Engels Platz menyusuri bulevard Unter den Linden, menjelang musim semi 1993, kita akan merasakan di sekitar kita masa lampau berlapis-lapis mengendap. Di kanan kiri, deretan bangunan abad ke-18 dan ke-19 yang masih utuh dan sepi. Agak di sana, barisan konstruksi abad ke-20 yang ''sosialistis'', kaku dan wagu, yang sekarang kosong ditinggalkan. Berlin, terutama di sisi Timur, kini praktis menjadi seonggok monumen kenangan tentang kemegahan dan sekaligus kekalahan, keduanya dengan rasa nyeri sendiri-sendiri. Lalu apa jadinya nanti dengan kota ini, kota yang dulu pernah memaklumkan perang ke mana-mana tapi kalah, kota yang congkak dan kemudian luluh lantak dan kini harap-harap cemas ini? Orang Jerman mencoba memutuskan, tapi tak mudah. Memang, tembok yang dibangun dengan paksa oleh Uni Soviet itu sudah roboh. Benar, masa depan tengah disiapkan dengan gegap gempita. Tapi bagaimana memutuskan mau jadi apa kelak kota ini? Berlin bukan cuma sebuah tempat. Berlin adalah sebuah trauma. Agaknya inilah yang kian tajam terasa setelah Timur dan Barat bertaut. Tanpa tembok, tanpa batas yang ditegakkan oleh para penakluk Perang Dunia II, kedua sisi kota saling langsung bisa memelototkan mata. Kontras-kontras, yang dulu tersembunyi di balik dinding, kini jadi kehilangan tutup, mencolok, menyakitkan. Di sepanjang Kurfuerstenstrasse, di Barat, yang tampak adalah etalase gemerlapan: pameran pakaian dan parfum, restoran dan kegembiraan. Di sepanjang Unter den Linden, di sepanjang Alexanderplatz, di Timur, yang tampak adalah warna kusam. Tak mengherankan bila luka setelah perang terasa masih lebih amis di sini. Di tahun 1989, orang-orang Berlin Timur bersorak dan menari-nari setelah menggempur dinding yang mengepung mereka itu, bagaikan beratus ribu pesakitan yang lepas memberontak dari sekapan, mirip para tahanan yang akhirnya menenggak kebebasan di adegan akhir opera Beethoven. Segera menyusul itu, orang Jerman Timur pun memilih untuk segera bisa bersatu dengan Jerman Barat, dan Berlin tiba-tiba menjadi sebuah tanda yang paling spektakuler dalam sejarah tentang kekalahan sosialisme di hadapan kapitalisme. Dengan menggabungkan diri ke dalam sistem yang menang, mereka berharap akan ikut menang pula. Ternyata tidak. Kapitalisme bukanlah sebuah kenduri. Kapitalisme juga sederet tuntutan. Haetzel, seorang entrepreneur berumur 30 tahun berasal dari Barat, ingin membuka rumah makan di sisi Timur. Tetapi ia tak mudah merekrut 25 orang pelayan di sebuah negeri yang selama 40 tahun hidup dalam sistem komunisme. Bukan karena di sana, dalam semangat sama-rata-sama-rasa, tak ada pelayan restoran. Sebabnya lebih mendasar: dalam sebuah masyarakat yang diatur segalanya oleh birokrasi, orang hanya tahu caranya bagaimana melayani para birokrat dan para petinggi. Tanpa ekonomi pasar, tak banyak orang yang tahu perlunya melayani konsumen. Tak ada pedagang yang memikat pelanggan, tak ada pelayan yang tersenyum di pintu. Herr Haetzel akhirnya menunda pembukaan restorannya tahun depan.... Di Timur sementara itu kian banyak yang menganggur. Kapitalisme menghendaki itu. Ketika perusahaan-perusahaan negara berpindah tangan ke swasta, ribuan buruh harus dilepas. Ketika pabrik- pabrik kimia ala Jerman Timur ternyata menyebarkan polusi, sejumlah lapangan kerja terancam. ''Dulu, oleh pemerintah komunis, saya diberi tahu buruknya kapitalisme'', kata seorang penganggur, bekas karyawan hotel di sebuah gerbong kereta dari Postdam. ''Sekarang oleh kaum kapitalis saya lebih diberi tahu''. ''Kami, di Timur, kalah empat kali,'' kata seorang bekas hakim dari Berlin Timur yang tak boleh jadi hakim lagi. ''Yang pertama kalah dalam Perang Dunia ke-1. Yang kedua kalah dalam Perang Dunia ke-2. Yang ketiga kalah di hadapan sistem kapitalisme. Kini, yang keempat, kami kalah di dalam sistem kapitalisme.'' Suaranya tanpa emosi. Ia termasuk mereka yang sudah terbiasa menyerah kepada ketidakpedulian. Tak jauh dari sana, menyengat bau bacin air Sungai Spree yang mengalir di belakang Gedung Palast der Republik. Gedung yang dulu jadi pusat pemerintahan komunis itu juga lambang ketidakpedulian. Ia sedang hendak dihancurkan, walaupun baru berumur 20 tahun, karena ia selain buruk arsitekturnya juga dibangun dengan memakai banyak asbes. Pemerintah Kota Berlin kini menganggap itu membahayakan kesehatan, dan orang ramai bisa menyimpulkan bahwa ''istana'' itu sebuah hasil kekuasaan yang begitu rupa, hingga bisa berbuat apa saja kepada manusia, termasuk berbuat kebodohan. Palast der Republik: ia agaknya harus dilupakan, seperti sebuah kesedihan. Tapi Berlin bukan cuma sebuah kesedihan. Kota yang menanggungkan sejumlah perang dan sejumlah rezim dan sejumlah kebengisan adalah sebuah kota yang berharga. Hanya mereka yang mengenal trauma, mereka yang pernah dicakar sejarah, tahu benar bagaimana menerima kedahsyatan dan keterbatasan yang bernama manusia. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini