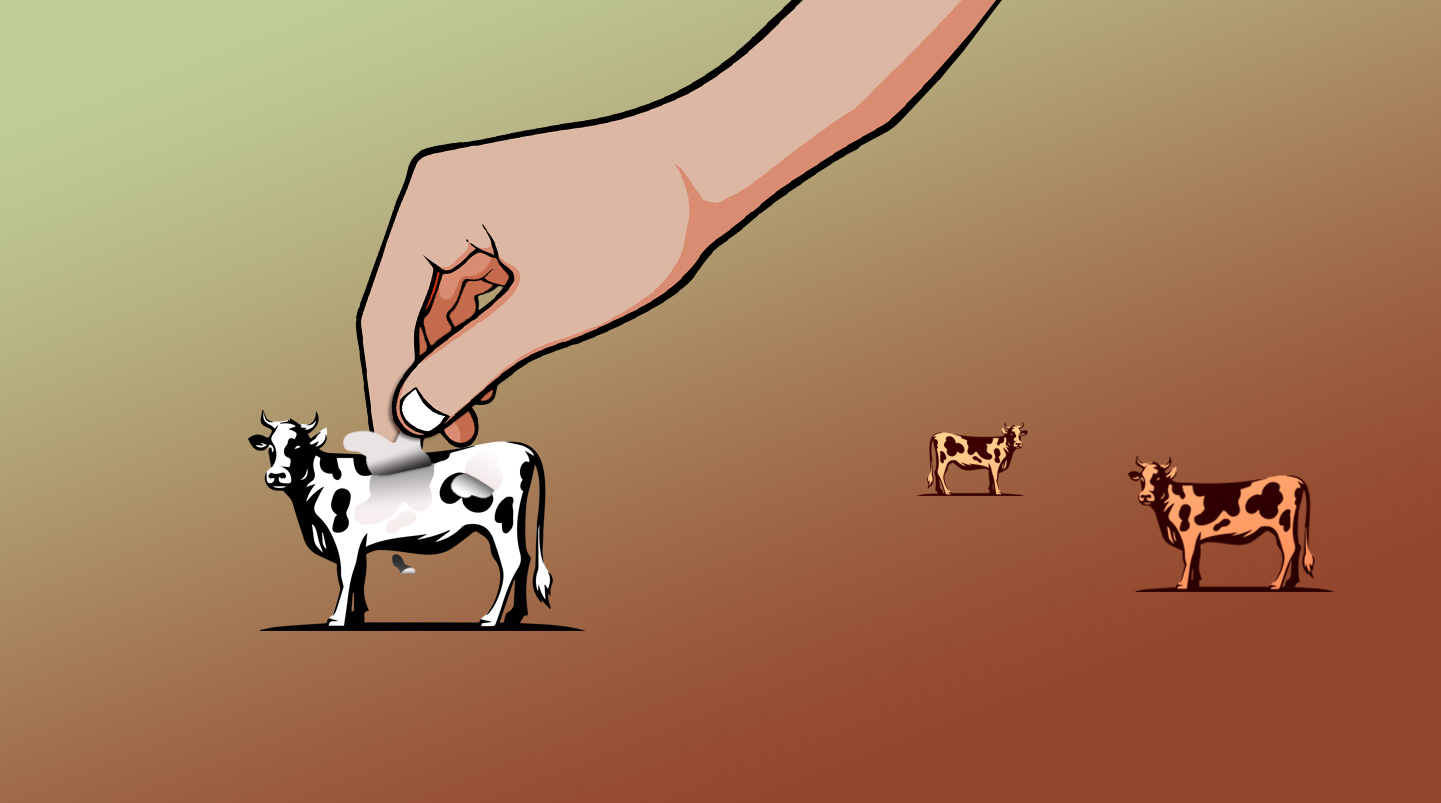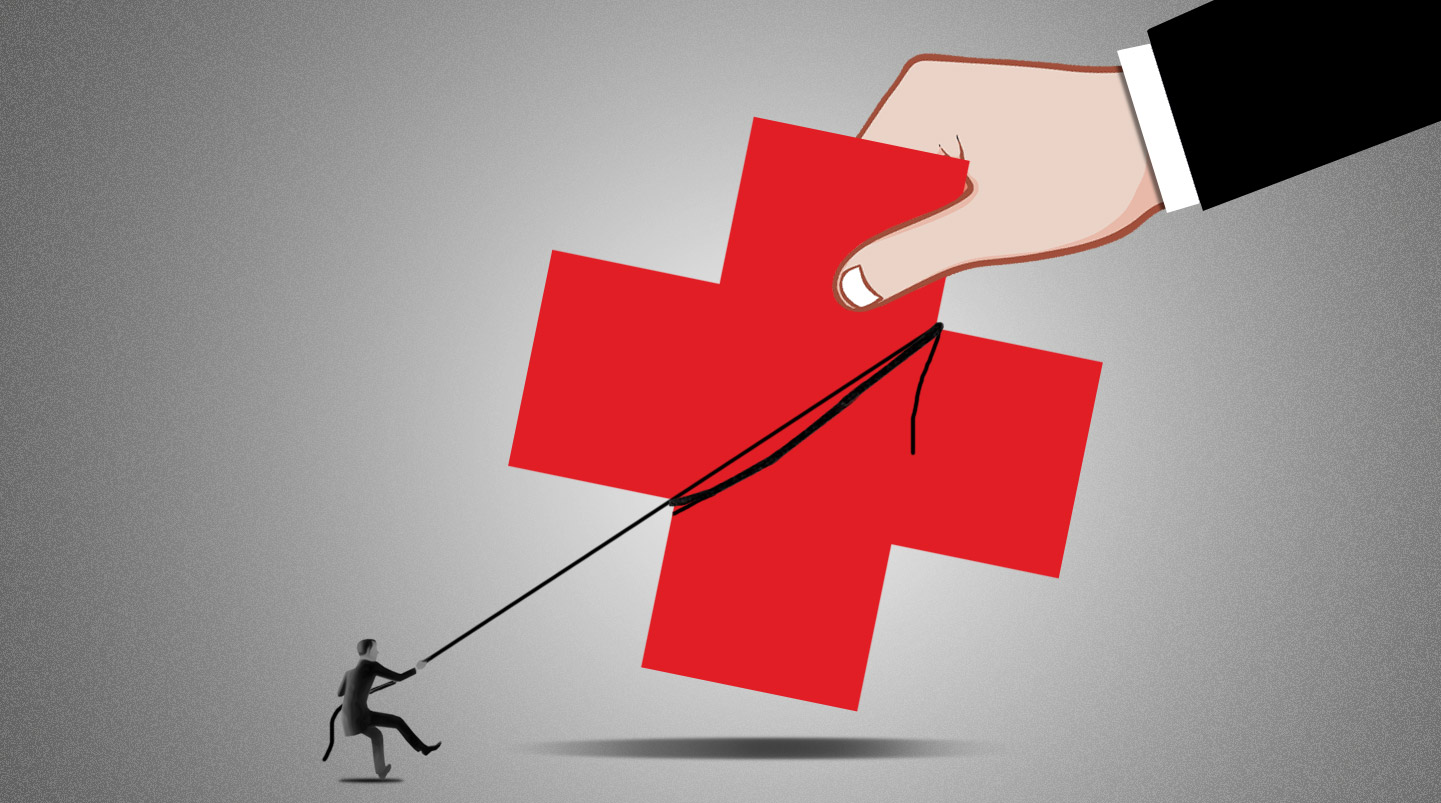Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak bulan Agustus lalu hingga kini, Indonesia sedang ramai dengan aksi seorang peretas (hacker) yang bernama Bjorka. Hacker Bjorka pada awal aksinya mengklaim sudah menjual 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar yang berisi nomor handphone warga Indonesia di forum breached.to. Aksi Bjorka berikutnya menyerang data-data pribadi para petinggi negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Terkait motif Bjorka pernah ia ungkapkan dalam unggahan akun twitternya @bjorkanism, yang kini sudah ditangguhkan. Ia mengungkapkan aksinya merupakan bagian dari balas dendam atas kekecewaan pada pemerintah Indonesia. Kekecewaan pada dirinya muncul karena di tahun 1965 teman baiknya yang berasal dari Indonesia tidak bisa balik karena kebijakan saat itu hingga akhirnya teman baiknya yang juga sudah merawat dirinya dari sejak lahir hingga meninggal dunia tahun lalu. Menurutnya, temannya itu adalah sosok yang sangat jenius dan berkeinginan untuk memperbaiki Indonesia melalui teknologi seperti layaknya sosok Habibie. Selain itu juga Bjorka mengaku ingin menunjukkan bahwa keamanan siber yang dimiliki Indonesia sangat lemah dan mudah dibobol dari berbagai pintu keamanan sibernya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Aksi Bjorka berhasil menciptakan teror di Indonesia. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga turut kuatir dan takut dengan keamanan datanya yang berbasis siber. Jika menelisik dari motif dan aksi yang dilakukan Bjoarka, Michael Blain dalam bukunya yang berjudul “The Sociology of Terrorism: Studies in Power, Subjection, and Victimage Ritual “ menjelaskan bahwa segala aksi teror dilatarbelakangi oleh kekerasan politik yang kemudian dimanifestasikan dalam sebuah gerakan politik. Ada visi-misi besar dalam gerakan politik tersebut, yaitu resistensi dan eksistensi diri atas kekerasan dan penindasan yang dialaminya. Hal ini semua dimulai dari kekerasan politik yang terjadi.
Menurut Blain kekerasan akan melahirkan kekerasan. Maka untuk itulah menurut Blain, terorisme didefinisikan sebagai akumulasi dari kekerasan politik oleh setiap kelompok yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik terhadap perlawanannya. Definisi ini dimaksudkan untuk mencakup spektrum mengenai taktik yang digunakan oleh suatu kelompok, negara, dan pemerintah serta gerakan politis lainnya, dalam hal ini Bjoarka melancarkan taktik gerakan politiknya melalui serangan keamanan siber di Indonesia.
Melalui sudut pandang pemikiran Foucault dan Kenneth Burke, Blain menggambarkan fondasi kekerasan politik yang berujung pada aksi radikal dan kemudian menikung pada aksi teror. Aksi teror yang dilakukan Bjorka tidak lepas karena adanya permasalahan pada mekanisme power, subjection, dan victimage ritual yang terjadi.
Bjorka Dalam Pusaran Dendam Power, Subjection, dan Victimage Ritual
Relasi aksi teror Bjoarka dan power ini tergambarkan dari kebijakan negara tahun 1965 saat itu terhadap perlakuan yang diterima oleh teman baiknya tersebut. Penggunaan power yang dilakukan aktor politik atau penguasa ini kemudian melahirkan nuansa sadomasokisme dan dramatisme. Power diolah sedemikian rupa oleh aktor politik atau penguasa, sehingga aktor politik atau penguasa berusaha untuk memuaskan keinginan sadomasokismenya di khalayak massa dengan melambangkan pembunuhan dan kematian sebagai syarat dan citra drama tragis, yaitu adanya pahlawan, penjahat dan korban. Penggunaan power demikian menurut Blain seperti yang pernah dilakukan oleh Adolf Hitler melalui Nazi yang dibentuknya. Penggunaan power oleh Hitler ini kemudian melahirkan sebuah tragedi kemanusiaan yang bernama Holocaust. Tragedi Holocaust merupakan bentuk dari power yang lekat dengan nuansa sadomasokisme dan dramatisme.
Maka untuk itu power yang dilanggengkan dengan nuansa sadomasokisme dan juga dramatisme memunculkan beberapa proposisi, yaitu: (1) aktor politik atau penguasa selalu berusaha untuk memuaskan keinginan sadomasokismenya di khalayak massa; (2) komunikasi yang dilakukan menyentuh sebuah kompleksitas alam bawah sadar, budaya, hukum, dan adanya kambing hitam; dan (3) aktor politik atau penguasa akan menggunakan dramatisme untuk mendapatkan identifikasi massa dengan tanda-tanda dan simbol-simbol otoritas dan kekuasaan mereka. Power sadomasokisme dan dramatisme yang melahirkan kekerasan politik pada akhirnya memunculkan benih radikalisme. Klimaks dari radikalisme yaitu terorisme.
Selain power, subjection turut andil dalam melahirkan aksi teror Bjoarka. Subjection merupakan bagian dari penyerahan diri terhadap orang lain atau kelompok sebagai individu atas nama ketertundukan. Subjection menjadi jembatan akumulasi kekerasan politik yang terjadi melalui power yang bernuansa sadomasokisme dan dramatisme. Efek dari power ini kemudian menjadi sebuah teknologi kuasa yang dimaksudkan untuk membentuk subjection atas subjek. Maka demikian power menjadi proses di mana subjek dijadikan sebagai “yang ditundukan”. Namun demikian dari momentum subjection ini, tidak membuat subjek menjadi patuh pada setiap kuasa yang berusaha untuk membentuknya. Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Foucault, bahwa dalam power akan memproduksi sebuah resistensi. Dari resistensi inilah “kebenaran baru” dihasilkan dari subjek yang melawan. Pada konteks disini, Bjoarka ingin melancarkan aksi terornya sebagai bentuk resistensi atas apa yang dialami oleh temannya, namun satu sisi ia ingin memberitahu kepada negara bahwa keamanan sibernya sangat mudah diretas.
Agar power dan subjection ini berjalan dengan baik, maka ia harus dikemas melalui victimage ritual. Victimage ritual merupakan strategi bertindak atas situasi sosial yang ada. Victimage ritual adalah strategi di mana salah satunya “tidak bisa kehilangan“, namun salah satunya lagi “mencoba untuk melawan dengan caranya sendiri “. Maka untuk itu harus mengembangkan strategi yang benar dan realistis. Pada posisi ini aktor politik atau penguasa menggunakan tindakan diskursif dengan menggunakan kata "tulus" tetapi harus “dihitung” sebagai tujuan politik mereka. Di sinilah kemudian para aktor politik atau penguasa menggunakan victimage ritual untuk memotivasi massa dalam aksi kekerasan kolektif melalui dramatisme victimage ritual sehingga menjadi sebuah perjuangan dramatis dari seorang pahlawan untuk melawan penjahat, baik melawan kejahatan, ketidakadilan, dan mempertahankan hubungan kekuasaaan.
Contoh victimage ritual, dapat kita lihat dari peristiwa invasi Amerika Serikat dengan sejumlah negara sekutunya ke Irak di tahun 2003. Ketika itu Irak masih dibawah kendali Saddam Hussein. Invansi Amerika Serikat dan sekutunya dikemas untuk menjadi “pahlawan” dunia dengan mencari senjata pemusnah massal di Irak. Namun rupanya senjata pemusnah massal tidak ditemukan di Irak, tetapi akhirnya tujuan invansi tersebut adalah penggulingan rezim Saddam Hussein dan adanya tujuan penguasaan minyak. Dari invansi ini kemudian lahirlah kelompok radikal seperti ISIS yang melakukan aksi terorisme. Dengan kata lain, victimage ritual dapat dilihat dari negara membuat kebijakan dengan mengkampanyekan bahwa kebijakan tersebut demi keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat, namun di satu sisi kebijakan tersebut melahirkan penindasan pada kelompok lain, sehingga melahirkan dendam pada kelompok tersebut kepada negara.
Bjorka dan Ketahanan Negara
Dari power, subjection, dan victimage ritual, Bjorka di satu sisi ingin melancarkan motif balas dendamnya dan di satu sisi ia ingin memberitahu kepada negara bahwa pintu keamanan sibernya mudah diretas. Sehingga aksi Bjoarka menjadi alarm peringatan bahwa negara harus memperkuat keamanan sibernya sebagai bagian dari ketahanan negara.
Kita ketahui bahwa pelaksanaan wilayah NKRI tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Sumber ancaman (source of threat) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan nasional” menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (internal threat) atau luar (external threat) tetapi juga ancaman azymuthal (mengglobal, tidak bisa dikategorikan dari dalam atau luar). Seirama dengan itu, watak ancaman (nature of threat) juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi internet, tetapi multidimensi.
Maka untuk itulah penting memperkuat geopolitik dan geostrategi sebagai bagian dari manajemen pertahanan negara, dan memperkuat keamanan siber nasional. Sebab di era masyarakat digital saat ini, potensi ancaman siber sangat tinggi, baik itu berupa malware, ransomware, phishing, dan Denial of Service (DDoS) dan penipuan online lainnya.
Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, ruang universitas, hingga ruang warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini, salah satunya kasus pembunuhan Brigadir J oleh Sambo.
Untuk itu masyarakat sambil melihat tontonan aksi Bjorka dan respon negara atas aksinya, harus tetap menjaga daya nalar kritis dalam mengawal proses penyelidikan kasus Sambo. Jangan sampai, fenomena aksi teror Bjoarka seperti asap panas segelas kopi yang menguap dan akhirnya kopi panas tadi menjadi dingin. Peter Kivisto dan Thomas Faist dalam bukunya “Citizenship: Discourse, Theory, and Transnational Prospects” (2007) mengatakan bahwa untuk meredupkan perdebatan suatu peristiwa dalam percakapan masyarakat, maka harus diciptakan percakapan baru. Bjoarka adalah warna cerita dari pekerjaan rumah negara, namun ia juga seperti ibarat wajah lama sudah tak keruan di kaca, sedang wajah baru belum jua jelas, kata Mochtar Lubis.