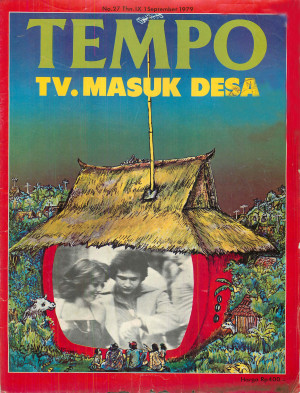BERAPA banyak dari kita masih suka dipanggil "bung"Agaknya tidak
banyak lagi.
Nampaknya orang sekarang lebih suka dipanggil "pak" "bapak",
"mas" atau munkin "abang". Padahal dulu alangkah pernah populer
panggllan itu. Di mana-mana panggilan "bung" itu terdengar. Dan
rasanya baik bagi yang memanggil maupun yang dipanggil kata itu
seakan ada semacam pengaruh ajaib. Begitu kata "bung" itu
diucapkan wajah yang cerah nampak selalu mengikuti kata itu.
Seakan ada semacam tali persaudaraan yang akrab yang langsung
terjalin antara yang memanggil dan yang dipanggil itu.
Kenapa begitu? Mungkin karena kata itu lahir bersama dengan
menaiknya suhu sentimen kebangsaan kita pada jaman pergerakan.
Pada waktu kita membutuhkan suatu suasana solider dan akrab
antara sesama bangsa "inlander".
Tanyakanlah kepada mereka yang mengalami jaman itu. Jaman orang
keranjingan memakai peci dan memakai segala baju yang berbau
pribumi. Sarung, celana batik, jas tutup lurik aan sebagainya
lagi. Jaman "swadeshi"--untuk mengikuti gerakan yang dianjurkan
oleh Gandhi di India itu. Yakni suatu gerakan yang antara lain
menganjurkan untuk hanya memakai hasil buatan negeri sendiri.
Juga jaman di mana Indonesia-Raya belum dinyanyikan "Indonesia
Raya merdeka, merdeka" tetapi "Indonees, Indonees mulia, mulia
... "
Di tengah suasana begitulah, saya kira, muncul "bung". Yakni
satu kata panggilan yang agaknya dapat mewakili sentimen
kebangsaan, persaudaraan dan solidaritas. Satu kata panggilan
pendek yang sekaligus dimaksudkan untuk dapat meloncati tembok
"segan-menyegani", nkuh-pakewuh, sebagai akibat tingkat
perbedaan ieodal maupun kolonial. Kata yang bisa menggantikan
"tuan", "ndoro", "meneer" dan sebagainya itu.
Maka waktu pemimpin-pemimpin pergerakan menganjurkan rakyat
untuk memanggil mereka dengan "bung" saja menjangkitlah wabah
itu. Maka orang tidak lagi memanggii Ir. Soekarno tapi Bung
Karno, bukan Drs. Moh. Hatta tapi Bung Hatta, Bung Syahrir dan
bung, bung lainnya lagi. Di sekolah-sekolah menengah para
pelajar yang bersemangat kebangsaan (secara sembunyi) saling
menyapa dengan bung. Seorang pelajar yang mondok di rumah kami
bahkan minta kepada pacarnya untuk berhenti memanggilnya "sehat"
tetapi "bung".
Di jaman Jepang, kecuali untuk Bung Karno dan Bung Hatta, bung
lenyap sebentar dari peredaran umum. Hanya di antara mereka yang
bergerak di bawah tanah saja, saya kira, panggilan bung masih
berlaku. Bung Adam, bung Chairul, bung Syahrir, bung Badio, bung
Wikana dan sebagainya lagi. Tetapi di antara para pelajar
sekolah menengah tidak terlalu banyak lagi "bung" kedengaran.
Baru pada waktu revolusi pecah, bung jadi berkumandang lagi. Di
Jakarta, di Surabaya, di Yogya, di mana-mana. Di Surabaya lahir
seorang orator baru yang bernama Bung Tomo yang kemudian disusul
dengan berpuluh bung-bung pemimpin baru di mana-mana.
Waktu itu adalah juga waktunya orang senang terlibat dalam debat
dan diskusi terbuka. Tentang politik melawan Belanda, tentang
Linggardjati, tentang Renville, tentang Sayap Kiri, tentang
Persatuan Perjuangan, tentang Front Demokrasi Rakyat, tentang
apa saja.
Itulah suasana suhu sentimen kebangsaan naik dengan
sqadijadinya. Pekik merdeka yang hampir tidak hentinya
diteriakkan di mana-mana, di sepanjang Malioboro yang
remang-remang tetapi ramai dengan penduduk "kiblik" yang
hilir-mudik itu, di front, di garis depan di pinggir-pinggir
garis demarkasi.
Itulah semua satu suasana yang agaknya subur lagi buat
kembalinya kata bung sebagai alat-penyapa yang paling cocok dan
enak. Merdeka, bung! Mau ke mana bung, sini, dong, bung, Iho,
kok gitu to, bung . . . Ismail Maruki, komponis kita itu, juga
tidak ketinggalan melempar senandung baru: Mari, bung, mari ke
mari, Jakarta menanti-nanti. . .
Dan pada waktu akhirnya kemerdekaan kita menangkan? Bagaimana
dengan nasib "bung" kita? Wah, berangsur jadi mlempem lagi. Buat
mereka, terutama para pemimpin politik, yang sudah terlanjur
memiliki kata "bung" sebagai semacam "kata majemuk", semacam
trade mark bagi nama mereka, "bung" yang menempel di depan nama
mereka sudah jadi cap yang abadi. Tetapi "bung" sebagai
panggilan, baik yang akrab maupun yang basa-basi, sungguh jadi
pudar kembali.
Bahkan mereka yang pada jaman revolusi merasa sudah terbiasa
dipanggil bung oleh teman-teman dan bawahannya sekarang merasa
kikuk dan risih telinganya mendengar kata "bung" dilempar
kepadanya. Kok kayak panggil pelayan restoran saja, gerutu
seorang kepala jawatan. Berangsur-angsur orang agaknya lebih
senang dipanggil "bapak".
Akhirnya '.'bung" mengalami satu hari naas waktu Bung Karno
lebih suka dipanggil "bapak" dalam percakapan tidak resmi dan. .
. Paduka Yang Mulia Presiden bagi upacara resmi. Maka seluruh
anggota kabinet 100 menteri pun mengikuti jejak itu. Bahkan D.N.
Aidit--yang juga anggota kabinet--dalam pelariannya waktu
mendarat di lapangan terbang Adisucipto konon masih disapa oleh
protokol lokal dengan: Yang Mulia . . .
***
Mengapa "bung" mengalami nasib begitu?
Mungkin karena "bung" adalah kata yang diciptakan oleh suasana.
Atau tepatnya oleh kebutuhan akan suasana. Pada waktu negeri
kita membutuhkan satu suasana solidaritas nasional yang hangat
dan akrab yang dalam kenaikan suhunya bisa menjadi suasana
"revolusioner" itu. Tetapi begitu kebutuhan akan suasana ini
pudar, melembaga dalam berbagai kotak dan atribut-kotak, "bung"
ini jadi binatang yang aneh. Kotak-kotak beserta
penghuni-penghuninya itu sang pemenang revolusi-- tiba-tiba
melihat "bung" tidak secantik dulu lagi. "Bung" pun jadi
dikotakkan juga dalam tempatnya sendiri. Maka sang kepala
jawatan menggerutu: kok kayak panggil pelayan restoran saja...
Tapi dalam jaman pembangunan seperti sekarang ini tidakkah kita
membutuhkan satu suasana "solidaritas nasional" lagi? Suasana
"duduk sama rendah berdiri sama tinggi" lagi? Suasana yang tempo
hari sesungguhnya telah dicitra dengan baik oleh jenderal Yoga
Sugama - yang sayang tidak keburu populer sebagai "pemerataan
keprihatinan" itu!
Bukankah dalam satu keadaan di mana kita secara simultan
ditantang oleh inflasi yang mau membesar lagi, masalah sumber
pangan dan sumber alam yang terus rawan, masalah pendidikan dan
lapangan pekerjaan -- dua kembar siam yang belum juga
terpecahkan dengan memuaskan, kependudukan yang belum sepenuhnya
terkendalikan, benar-benar dibutuhkan sikap prihatin yang merata
di antara kita?
Dalam keadaan begitu bukankah suasana hng.dan rabnya
persaudaraan akan membantu membangun solidaritas-nasional itu?
Dan "bung" mungkin akan menjadi tiangsangga yang pentlng untuk
pembangunan suasana yang demikian itu.
Ingat jaman 'Indonees, Indonees mulia, mulia, mulia . . . "
Ingat waktu Bung Karno dan Bung Hatta dan bungbung yang lain
masih bung-bung kita yang benar? Bagaimana kalau tidak hanya
kepada Bung Adam kita panggil "bung" sekarang? Juga Bung Harto,
Bung Widjojo, Bung Yusuf?
Sehingga tidak perlu kita ikut berhiba dengan ciptaan Ismail
Marzuki yang lain: Buuuung di mana engkau berada, bertahun
lamanya kita berpisah . . .
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini