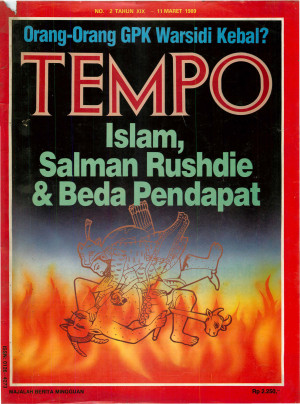"BUNUH!" kata titah itu. Dan kita ingat akan kematian Trunajaya. Ia datang sebagai orang yang kalah ke Keraton Kartasura. Amangkurat II menyambut. Tapi raja bekas teman seperjuangannya itu juga sudah siap menghukumnya. "Ayo, para bupati !" Dan bebeberapa belas keris menikam, dan Trunajaya roboh di balairung itu, dan perutnya dibelah, dan hatinya dicabik-cabik, dan setiap yang hadir menelan sepotong kecil cabikan itu. Lalu kepalanya dipenggal. Darah menggelimang di wajah itu, ketika kepala Trunajaya diletakkan di ambang pintu keputren, agar setiap putri bisa menginjaknya. "Bunuh!" Dan kita ingat akan kematian Damiens, yang dihukum mati di awal Maret 1757 di Place de Greve, Paris. Ia diletakkan di pancang. Lalu dagignya direnggutkan: dari dadanya, dari lengannya, dari pahanya, dari betisnya -- dengan sepasang sepit besi yang dipanaskan -- dan, kemudian, ke bekas luka itu, dituangkan timah cair minyak yang mendidih, damar yang menyala, lilin yang dicampur belerang. Bahkan kemudikan enam ekor kuda dikerahkan untuk menarik lengan dan pahanya agar patah. Ketika prosedur hukuman ini gagal, para algojo pun memotong anggota tubuh hukuman itu, satu demi satu. Sistematis. "Bunuh!" titah pengadilan. Damiens menjerit. Apa ada yang hendak dikatakan, tanya petugas pengadilan ketika laki-laki yang malang itu dalam rasa sakit yang sangat. "Ampun, ya Tuhan, ampun!" -- itu saja yang diucapkannya. Dan kita tak pernah tahu adakah ia diampuni. Kita hanya percaya. mungkin berharap, bahwa Tuhan (Maha Pengasih, bukan?) tak akan merestui keganasan ,di Place de Greve itu. Atau di mana saja. Tapi barangkali memang benar bahwa, seperti dikatakan oleh seorang pengarang yang sedih, sejarah adalag "otobiografi seorang gila". Tak ada aturan , rasanya, malah mungkin penuh kengerian. Kekerasan tidak mulai, dan tidak berhenti di abad ke-18. Dulu kita dengar bagaimana pasukan Assyria menaklukkan sebuah negeri: kepalaorang-orang yang kalah disulah oleh yang menang, atau mata mereka dicongkel, para wanitanya diperkosa, dan anak-anaknya diperbudak. Kini juga kita dengar bagaimana anak dan ibu dibakar hidup-hidup, tahanan diinjak injak, dan orang tak bersalah diledakkan di udara. Apalagi kini kekerasan punya banyak dalih. Bahkan tuntutan yang adil. Jean Paul Sartre memberi pengantar buat risalah Franz Fanon tentang perlunya kekerasan dalam pembebasan sebuah bangsa: "Menembak roboh seorang Eropa berarti membunuh dua ekor burung dengan sebutir batu: untuk menghancurkan sang penindas dan orang yang ditindasnya sekaligus." Dengan kata lain pembunuhan terhadap si penindas juga berarti pembebasan jiwa bagi si tertindas. Saya tak bisa menyalahkan Sartre. Bahkan kadang asyik juga menyaksikan bagaimana kekerasan-untuk-keadilan macam itu diagungkan dan diberi warna-warni: kisah Bima di medan Perang Kuru, kisah Bruce Lee di layar film. Tetapi kemudian, siapakah "si penindas"? Seorang Rahwana adalah sosok yang kongkret, juga seorang Caesar. Tetapi kemudian zaman memperkenalkan pengertian -pengertian baru. Si penindas adalah sebuah "sistem", bukan orang, demikian kata sebagian ahli teori revolusi. Si penindas adalah "neokolonialisme" atau yang semacam itu -- pokoknya bukan Si Fulan atau Si Badu. Maka, siapa yang harus ditemhak roboh? Di zaman ini nampaknya manusia kian mampu merubah musuh yang konkret jadi lawan yang abstrak. Selama 20 tahun terakhir -- dengan perkecualian di sana-sini -- praktis tak ada lagi Trunajaya yang dicincang di balairung dan Damiens yang dibantai di Place de Greve. Pembalasan tak lagi diarahkan ke badan. Maka, tulis Michel Foucault,sejenis tragedi berakhir, dan pertunjukan macam lain muncul sandiwara bayang-bayang seperti wayang, suara-suara tanpa wajah, satuan-satuan yang tak teraba. Hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menyiksa tubuh, melainkan untuk mereformasi "jiwa". Dan aparat pelaksana hukuman, kata Foucault, "kata harus menggigit realitas yang tak berjasad ini." Ada yang melegakan. Kita tak harus lagi melihat darah yang muncrat. Tapi toh kekerasan tak berakhir, dan "realitas yang tak berjasad" yang disebut Foucault akhirnya toh tak terbatas hanya pada jiwa seorang penjahat. Ke dalam katagori "jiwa" itu, kemudian termasuk juga milik kita di luar penjara. Dan itu terjadi ketika sejumlah orang, dengan seonggok kekuasaan, mulai melihat bahwa jiwa kita pun -- manusia yang bebas ini -- adalah jiwa yang perlu dipermak. Maka, kita pun melihat kekerasan lain-lain: otak kita dicuci, agar bisa diisi dengan apa yang mereka maui. Kemauan kita mutlak. Ayuh, taat, seru mereka, jangan gelisah dengan bertanya. Dan "bunuh!" Tubuh kita mungkin mati mungkin tidak. Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang tak lagi bergerak.Goenawan Mohammad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini