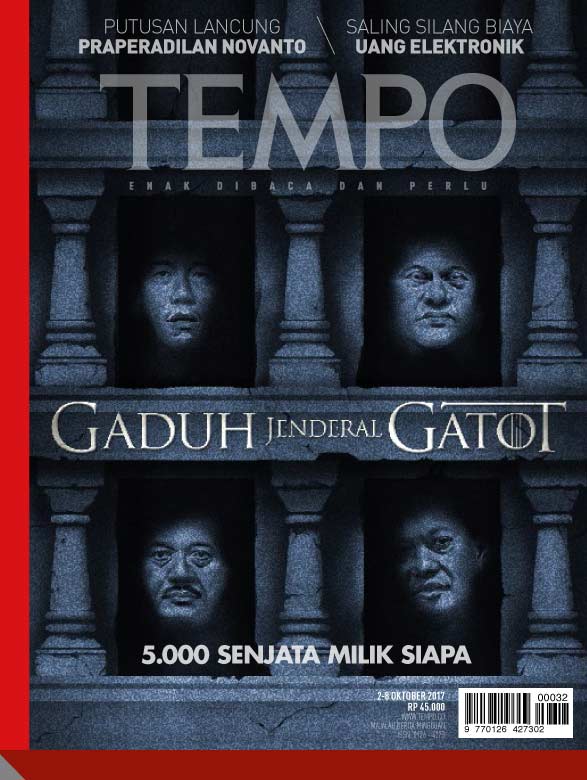Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pukul 00.15, 10 November 1989, di Berlin sebuah republik runtuh sebuah tembok runtuh. Republik Demokrasi Jerman, atau "Jerman Timur", dengan cepat ditiup sejarah ke masa lalu. Diiringi pekik gembira ribuan penduduk.
Pada pukul 23.45, setelah sorak-sorai itu, terdengar suara berdentang-dentang. Ramai-ramai penghuni Berlin Timur pakai kapak, palu, dan entah apa lagi menghantam tembok yang mengungkung kota: tirai keras sepanjang 156 kilometer yang didirikan Partai Komunis di tahun 1961.
Tengah malam itu rakyat menjadikan diri Mauerspechte, burung pelatuk yang mencucuki tembok, menghancurkannya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya, setahun kemudian, bangunan muram itu punah.
Sepanjang hari dan malam itulah pernyataan mereka yang paling dahsyat dan mengejutkan: mereka tolak pemerintahan yang menyebut diri "demokratis" dan partai yang menyebut diri pembawa suara pekerja.
Mereka sudah lama tak berdaya. Tembok itu, yang didirikan dengan perintah penguasa Uni Soviet, Khrushchev, begitu kuat dan ketat dijaga. Lebih dari 5.000 orang mencoba lepas, dan 239 tewas, sebagian besar ditembak. Tiap malam, di sepanjang "jalur maut", Todesstreifen, lampu sorot mencorong bersama derap sepatu Volkspolizei ("Polisi Rakyat") dan Kampfgruppen der Arbeiterklasse ("Grup Tempur Kelas Buruh") yang siap senjata.
Siang sedih di tempat ini. Di malam hari
Lampu sorot mencari jejak:
Mencari suara teriak
Yang bukan karena takut di tengah mimpi
Itu bagian sajak Joseph Brodsky, penyair Rusia yang hijrah ke Amerika, tentang Tembok itu: dinding yang dibangun Ivan, tulis Brodsky, dan tempat Hans mati….
Tapi musim dingin itu, pemerintahan partai komunis angkat tangan, tak lagi didukung kekuatan Uni Soviet seperti sejak 1945. Rakyat pun menerobos batas.
Tembok yang jebol itu menandai banyak hal yang seram dalam abad ke-20: pemisahan Jerman, Tiongkok, Vietnam, Korea- ya, "Perang Dingin". Meskipun tak seluruhnya dingin: inilah konflik panjang di semua tempat antara kekuatan pro-komunis dan anti-komunis, dalam perang ideologi, perang spionase, perang gerilya, sabotase, dan ancaman thermonuklir yang sudah disiapkan. Dalam kata-kata Nehru, pemimpin India yang ingin menengahi ketegangan itu, kedua belah pihak dirundung ketakutan.
Tembok Berlin juga tanda "ketakutan" itu- dan akhirnya, sebuah kesia-siaan.
Di sana pernah tergurat grafiti:
Viele kleine Leute die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt veränderen- ribuan orang kecil di ribuan tempat kecil melakukan ribuan hal kecil yang dapat mengubah wajah dunia.
Benar sekali.
Di tahun 1966, bersama Régis, seorang teman Prancis, saya turun dari Brussels di peron yang agak gelap di Friedrichstraße, stasiun di Berlin Timur yang dibuka untuk kereta api dari Barat. Dalam liburan ini Régis ditemui dua teman perempuan dari Universitas Humboldt yang kemudian menemani kami berkeliling. Mereka sangat membanggakan sebuah gedung tempat Louis Armstrong mengadakan konser jazz dalam kunjungannya ke Jerman Timur setahun sebelumnya. Jazz bukan musik "realisme sosialis", tapi tak haram: ia produk industri budaya kapitalis, tapi ia musik orang Hitam yang tertindas. Dan suara parau "Satchmo", tiupan trompetnya, senyum luasnya, membuat orang Berlin merasa, di antara Tembok, "it is a wonderful world".
Tapi di kereta kembali ke Belgia, Régis membuka sepucuk pesan kecil yang diselipkan Ingrid dalam novel Stefan Zweig yang ia berikan sebagai cendera mata. Régis bacakan untuk saya. Seingat saya: "Satchmo menyatakan, ia tak tertarik Tembok Berlin. Ia lebih tertarik pengunjung konser. Tapi bukankah musiknya tambah berarti justru karena Tembok itu mengungkung kami- yang hanya bisa dengarkan musik yang diatur Partai?"
Kemudian hari Régis bercerita, Ingrid aktif menyelenggarakan konser rock di sebuah gereja- sebagai aksi perlawanan. Ia tentu bukan satu-satunya burung pelatuk yang bunyinya membangunkan rakyat di antara batas yang dipaksakan itu.
Pekan ini saya berbicara dengan Teguh Ostenrik, perupa ternama itu, yang pernah tinggal di Berlin Barat dan bersekolah di Hochschule der Künste: ia tak hendak melupakan Tembok yang hadir dalam hidupnya selama 10 tahun. Melihat Tembok itu pertama kali di tahun 1972, katanya, sama seperti pertama kali melihat salju. Aufgeregt. Dari sisi barat ia bisa leluasa dengan dinding itu: membuat grafiti, piknik, bikin sate. Tapi ia sering menyeberang ke Timur dan tahu, batas itu harus ditembus.
Ketika Tembok itu runtuh, ia pun kembali ke Berlin dan membeli puing-puingnya. Ia simpan bongkah-bongkah semen itu selama 27 tahun dan akhirnya ia jadikan sebuah monumen di Taman Kalijodo: "Menembus Batas".
Batas pemisah itu, yang tak mau dilihat Louis Armstrong tapi dialaminya sebagai minoritas Hitam yang ditampik, kini dilihat Teguh di sekitarnya. Di Jerman Timur dulu politbiro Partai Komunis mengukuhkannya; di Indonesia: para pengkhotbah kebencian.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo