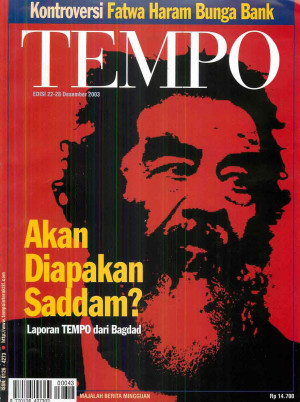Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INGGRIS, pada akhir 1935. Sebuah buku terbit dengan judul The General Theory of Employment, Interest and Money. Penulisnya John Maynard Keynes. Buku itu segera saja disambut orang. Terjadi perang opini pada waktu itu. Opini terbentang dari satu kutub—Cambridge, sarang tempat Keynes menghasilkan mahakarya ini—sampai ke kutub lain, yang beranggapan bahwa revolusi Keynesian sebetulnya tak terjadi, dan argumen Keynes sebenarnya sejalan dengan teori klasik yang dimodifikasi. Yang menarik, bahkan kritikus yang paling tajam terhadap Keynes pun mengakui: Keynes punya argumen yang sah. Dan memang, dengan resep Keynes, dunia keluar dari depresi besar. Tentu tak sesederhana itu. Tapi setidaknya resep Keynes memang telah menjawab depresi besar. Saya jadi teringat kepada buku tua yang kering dan teknis itu, ketika membicarakan calon presiden 2004 dan program ekonomi beberapa partai peserta pemilu. Pertanyaannya: apakah akan muncul sebuah General Theory baru lewat presiden dan program partai-partai ini? Apakah akan ada sebuah resep yang menyelesaikan soal ekonomi kita dan membawa kita pada sebuah "dunia baru"? Sebuah dunia yang tak pernah kita tahu, tapi dipercaya ada: Indonesia yang adil makmur.
Lalu orang, dengan putus asa dan naif, masuk dalam ilusi zaman keemasan Orde Baru. Sebenarnya jika kita mau adil, kita harus bicara dua hal tentang Orde Baru: periode pertumbuhan ekonomi 7 persen dan periode yang membawa negeri ini dalam krisis ekonomi. Keduanya terjadi dalam masa Orde Baru yang sama. Lalu kenapa kita hanya mau mengingat masa pertumbuhan yang tinggi. Ironis, karena ini menunjukkan betapa pendeknya ingatan kita. Sejarah adalah sebuah proses yang kontinu, bukan sesuatu yang discrete atau terputus. Karena itu, jika orang bicara mengenai krisis ekonomi yang terjadi saat ini, kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah kontinuasi sejarah. Krisis terjadi juga karena pelbagai kesalahan yang juga dibuat oleh rezim Soeharto—sesuatu yang seperti dirindukan saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang paling buruk dalam sejarah dan penjarahan justru terjadi pada periode transisi Soeharto ke Habibie pada 1998. Ketika kita bicara tentang korupsi yang buruk saat ini, kita juga perlu sadar bahwa tak ada yang berubah secara signifikan sejak era Soeharto dulu, hanya mungkin beberapa aktor baru dari partai politik. Dengan kata lain, sebuah era yang sebenarnya tak berbeda banyak dengan situasi pada hari ini. Ironis, begitu mudah amnesia sejarah terjadi. Tapi kita juga harus mencatat rezim yang mengaku dirinya "reformis" memang tak juga membawa perbaikan yang signifikan. Pemulihan ekonomi masih amat tersendat.
Barangkali naif atau mungkin sebuah ilusi bila mengatakan dengan presiden yang baru yang baik, pertumbuhan ekonomi akan melompat dari 3 persen menjadi 7 persen. Untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen dibutuhkan rasio investasi per PDB 28-35 persen. Saat ini rasio investasi terhadap PDB diperkirakan sekitar 22 persen. Dengan kondisi ini, sulit diharapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.
Pertanyaannya adalah apakah presiden terpilih dengan kabinet barunya akan mampu meningkatkan rasio investasi terhadap PDB menjadi sekitar 30 persen, seperti kondisi sebelum krisis. Kenaikan investasi membutuhkan perbaikan dalam institusi, dan perbaikan dalam institusi bukan kerja satu malam. Karena itu, mungkin menjadi naif jika kita berargumen dengan presiden yang baik, ekonomi segera pulih. Simak saja gambaran berikut ini: sepanjang tahun 2004, praktis kita tak bisa mengharapkan investasi baru yang signifikan karena investor akan memilih menunggu hasil pemilu. Presiden terpilih akan membentuk kabinetnya pada sekitar Oktober 2004. Setelah itu, pasar akan menjajaki kemampuan dan kapasitas presiden serta kabinet baru mungkin untuk selama enam bulan. Artinya, jika toh mereka menganggap bahwa pemerintah baru ini kredibel, investor asing baru akan masuk ke Indonesia pada semester kedua 2005.
Dampak dari investasi yang masuk terhadap sektor produksi memiliki tenggang waktu karena pabrik harus dibangun, output harus diciptakan. Karena itu, mungkin dampaknya baru akan terasa pada akhir 2006. Artinya, dengan presiden dan kabinet yang kredibel sekalipun, kita baru bisa bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 2007-2008. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tak akan tercapai segera, lalu apa yang bisa harapkan dari presiden terpilih tahun depan? Saya kira pertanyaan ini adalah pertanyaan yang valid. Pemulihan ekonomi tak akan segera terjadi, namun tanpa dasar yang baik, pemulihan ekonomi tak akan pernah terjadi.
Coba saja kita simak, bagaimana dampak dari stabilitas makroekonomi pada investasi. Kebijakan ekonomi yang hati-hati pada akhir tahun 1998 baru menunjukkan hasilnya pada sekitar tahun 2000, tatkala pertumbuhan investasi mengalami peningkatan signifikan. Gonjang-ganjing politik yang terjadi tahun 2001 mengganggu proses ini lagi. Dan kebijakan makroekonomi yang hati-hati baru mulai diterapkan kembali pada tahun 2002, dan baru pada bulan setelah triwulan pertama 2003, misalnya, lembaga rating dunia meningkatkan peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan arus modal portofolio masuk ke negeri ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa stabilitas makro adalah prasyarat utama.
Kemudian, stabilitas makro ini harus diperluas dengan perbaikan dalam institusi. Restrukturisasi sektor keuangan dan perbaikan dalam supervisi perbankan, misalnya, menjadi prasyarat lain yang harus dipenuhi. Apa yang terjadi pada Bank BNI dan BRI menunjukkan bahwa proses restrukturisasi perbankan di bank pemerintah praktis tak mengalami kemajuan yang signifikan. Apa yang terjadi dalam pengawasan di BNI dan BRI hanyalah miniatur dari buruknya dan gagalnya institusi di Indonesia. Karena itu saya melihat, mereka yang bisa menyediakan perbaikan dalam institusi inilah yang akan membawa dampak bagi perbaikan ekonomi. Memang efeknya tak akan terasa langsung dan pertumbuhan ekonomi tak akan melompat seketika dari 3 persen menjadi 7 persen, tetapi presiden terpilih punya peluang memberikan fondasi kepada perbaikan dalam institusi. Satu isu yang amat krusial buat pertumbuhan yang berkelanjutan.
Soal lain, yang juga amat krusial di negeri ini, adalah buruknya kualitas kebutuhan pokok dan infrastruktur. Laporan Bank Dunia, misalnya, menunjukkan tingkat elektrifikasi masih sedikit di atas 50 persen, fasilitas kesehatan dan pendidikan juga amat terbatas dan semakin buruk. Sedangkan di pihak lain, alokasi APBN dan APBD lebih berorientasi kepada pengeluaran rutin. Tanpa perbaikan dalam kebutuhan pokok dan infrastruktur, persoalan kesejahteraan rakyat akan tetap diabaikan, dan presiden terpilih tak memberikan hal baru bagi negeri ini. Dalam soal pendidikan dan kesehatan kita memang tak tumbuh secara signifikan. Sebagai contoh: penduduk dengan akses untuk sumber air yang lebih baik di kota relatif tak berubah bahkan mengalami penurunan dari 92 persen pada tahun 1990 menjadi 90 persen, walau untuk desa mengalami peningkatan dari 62 persen (1990) menjadi 69 persen (2000). Selain itu baru 55 persen penduduk yang memiliki akses kepada kesehatan yang baik. Pembangunan infrastruktur juga memberikan ruang bagi penyerapan lapangan kerja, sesuatu yang amat krusial bagi negeri ini. Saya melihat bahwa kebutuhan pokok dan lapangan kerja merupakan prioritas yang amat penting.
Indonesia adalah sebuah negeri yang "surplus" dalam kebijakan ekonomi di atas kertas dan "defisit" dalam implementasi. Saya kira kita bisa melihat bahwa di atas kertas kebijakan ekonomi cukup baik, namun sayangnya ada soal besar dalam implementasinya. Soal besar yang kita hadapi adalah soal koordinasi. Di sinilah kepemimpinan dari seorang presiden menjadi penting. Tanpa itu, negara akan menjadi NGO terbesar dalam arti Non-Governing Organization atau menjadi pemerintah yang tidak memerintah. Sayangnya kita tak dapat melakukan pengujian empiris terhadap calon presiden yang ada. Karena itu mungkin baik nanti jika kita menilai, kebijakan ekonomi yang paling mungkin diimplementasi adalah kebijakan yang "realistis" dan menghindar dari pelbagai retorika. Berbagai kebijakan populis yang sekadar berusaha mencari popularitas atau dukungan dapat membawa negeri ini ke jurang yang semakin dalam. Semakin besar retorika yang disampaikan, semakin kecil kemungkinan diimplementasi. Kebijakan ekonomi yang dirancang haruslah lebih didasarkan pada "kemampuan" dan bukan sekadar "keinginan". Kita harus membedakan mana yang mimpi di malam hari dan mana yang mimpi di siang hari. Karena itu ada satu hal penting yang perlu dicatat baik-baik oleh para calon presiden: bagaimana menyadarkan masyarakat dari ilusi bahwa seolah-olah dengan pemilu segala persoalan akan segera selesai. Pemilu hanyalah sebuah langkah untuk memberikan fondasi bagi pemulihan ekonomi. Karena itu mungkin baik bila calon presiden dan partai-partai ini menyadarkan masyarakat: tidak ada penyelesaian yang instant. Pemilu bisa saja menjadi sebuah batu loncatan, tapi ia bukan jawaban seluruh persoalan ekonomi. Krisis global tak akan selesai dengan satu penyelesaian parsial. Barangkali kita perlu mendekonstruksi ilusi itu. Termasuk ilusi mengharap munculnya sebuah General Theory ala Keynes lewat program partai, yang dapat segera menyelesaikan krisis ini secara instant. Tapi kita punya harapan, presiden terpilih dapat memberikan fondasi bagi perbaikan institusi yang sampai saat ini rusak—bila kita tak mau menyebutnya amat korup.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo