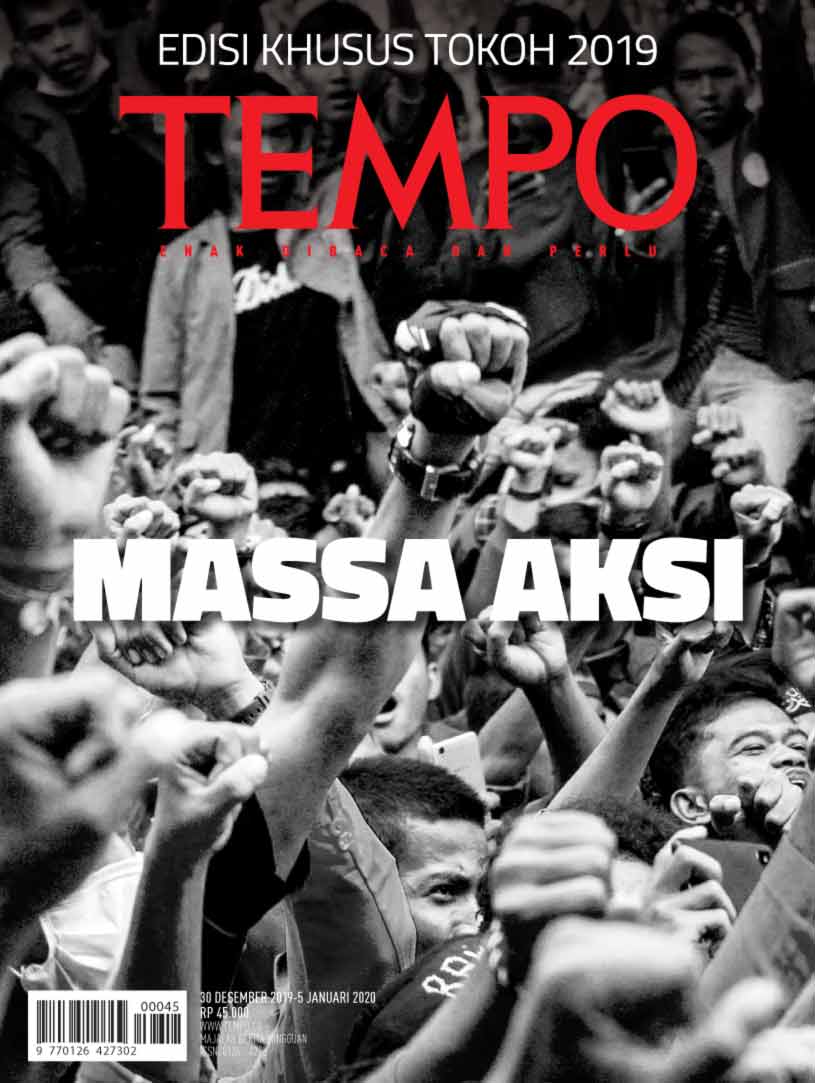Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ujung kaki Buddha yang melepuh, atau bengkak, atau samar dan berubah: deretan lukisan itu menyebut nama “Buddha yang tidur”, meskipun telapak di kanvas-kanvas itu memberi kesan Buddha yang berjalan jauh. Dan tak hanya jauh, tapi juga tak dibatasi asal tak terkungkung arah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dengan rangkaian karya itu Ugo Untoro, dalam pameran tunggalnya di Galeri Nasional hari-hari ini, memperkenalkan sosok yang seperti digambarkan tokoh Buddhisme Tiongkok abad ke-9, Linji Yixuan: seseorang dengan menyimak dharma, hadir “tanpa bentuk, tanpa sifat, tanpa akar, tanpa dasar; ia tak tinggal di satu tempat tertentu, namun hidup sehidup-hidupnya”.
Dengan kata lain, Buddha yang dibawakan Ugo adalah Buddha yang melangkah di bawah, dalam debu, perlahan-lahan, mudah dilupakan. Ia bukan Buddha dalam identitas yang utuh, bukan Buddha sebagai subyek yang koheren, yang dengan mata nyalang menyadari “aku”-nya dan menguasai dunia. Ia Buddha yang tidur, kata Ugo.
Buddha dalam lukisan Ugo Untoro adalah Buddha yang tak bisa dibunuh.
Linji terkenal dengan ucapannya, “Jika kau bertemu dengan seorang buddha, bunuhlah buddha itu.” Dengan kata-kata yang mengejutkan itu Linji sebenarnya menolak mereduksi apa yang misterius dalam pengalaman kita jadi sekadar problem yang bisa dirumuskan dalam konsep. Dengan kalimat tadi Linji hendak menegaskan: “buddha” tak bisa diringkas jadi identitas, dalam sebuah konsep tentang apa itu “buddha”, sebagaimana manusia seutuhnya tak bisa dilihat datar dan permanen dalam KTP. Pada saat ia jadi identitas, pada saat ia jadi konsep atau doktrin tentang yang suci dan tak tepermanai, ia harus dihabisi. Sebab ia jadi berhala.
Mungkin tanpa disadari, kanvas-kanvas Ugo melihat Buddha sebagaimana Linji: sebuah pandangan ikonoklastik, yang menolak Buddha seperti yang dibangun di Kuil Wat Pho di Bangkok: terbujur miring, berwibawa, sepanjang 14 meter, raksasa berkilau keemasan yang membisu. Seorang ikonoklas tak hendak menyembah sang suci yang digantikan arca, yang dibuat kedap perkasa—dan mandek—oleh lembaga agama dan politik. Dengan kata lain, dibuat selesai.
Bagi saya, yang berkesan dari kanvas-kanvas Ugo adalah serangkai karya yang belum selesai. Lukisan-lukisan itu tak hendak memberat, monumental, berbobot, serius dengan makna dan pesan.
Dalam hal ini, mereka jujur. Kanvas-kanvas itu pengakuan bahwa karya seni tak bisa memenuhi janjinya buat mengungkapkan “kebenaran” dan mengkomunikasikan “kebenaran”. Adorno menyebutnya konstitutiven Unzulänglichkeit: ada sifat tak memadai dalam karya seni, tapi sifat itulah yang menjadikannya.
Sebab itu lahir tafsir. Di kanvas Affandi, dengan goresan cat yang beringas dan gemas, dengan warna yang tumpang-tindih, kita, mungkin samar-samar, melihat sebuah bentuk—sebuah jukung nelayan. Jika kita tanya apa makna jukung itu, jika kita bahas mengapa jukung itu seperti melonjak-lonjak, kita harus memberi interpretasi. Dalam arti tertentu, karya itu “dihentikan”, digantikan kata-kata.
Tapi penafsiran itu tak pernah final.
Pada umumnya, berdasar tradisi yang melihat setiap imaji adalah lambang—seperti ketika menatap burung garuda lambang Negara—orang mengira karya seni adalah “bentuk” yang mengandung “isi”. Seperti sebuah jambu bol: di dalam warna, tekstur, dan raut bulat itu, ada daging dan bijinya. Tapi Roland Barthes punya perumpamaan yang lebih baik untuk seni rupa dewasa ini: sebuah karya seni ibarat sebutir bawang. Di bawah lapisan demi lapisan kulitnya, tak ada inti, tak ada daging. Lapisan-lapisan itu saja yang meliputi dan jadi bentuknya. Tak ada isi.
Bagi mereka yang menghendaki seni sebagai alat komunikasi, sebagai pembawa pesan, “tak ada isi” adalah cacat, bahkan kesalahan—bukan keadaan yang tak selesai yang justru membuat sebuah karya hadir sebagai proses kreatif. Bagi mereka yang menganggap “isi” terpisah dari “bentuk”, bahkan dalam dikotomi itu “isi” lebih luhur ketimbang “bentuk”, seni rupa yang tak ada isi, “tak selesai” itu semacam dosa sosial.
Hitler orang macam itu (dan ia tak sendiri). Ia membenci seni yang tak selesai. Ia anggap “bobrok” kanvas macam karya Georg Grosz dan Otto Dix, yang menampilkan sosok manusia yang tak lengkap, tak sempurna, tak rapi seperti barisan tentara Nazi yang penuh disiplin. Bukan tauladan yang “benar”. Kementerian “Pencerahan Masyarakat dan Propaganda” menyita 5.238 buah karya seni rupa Ekspresionisme Jerman dan juga dari Picasso, Chagall, dan Kandinsky. Mereka dipamerkan dalam ruang-ruang yang kurang cahaya dan sempit. Inilah “Pameran Seni Rupa Bobrok” (entartete Kunst) yang, kata Hitler, “menghina perasaan Jerman”.
Di tempat lain, sebuah pameran yang dinyatakan mencerminkan “jati diri” Jerman digelar. Lebih megah, tentu. Yang hendak dipertontonkan adalah sesuatu yang agung, luhur, kekal. Seni rupa Nazi hendak mendirikan berhala.
Kita tahu, setelah Hitler jatuh, berhala itu tak berharga.
Mereka yang ingin membangun tata kekuasaan dan keyakinan (ideologi sekuler ataupun agama) jadi konstruksi yang beku dan dipuja bak berhala perlu baca satu kutipan dari Sutra Vajra Prajna Paramita. “Beginilah kita memandang hal-ihwal dunia: seperti mimpi, gelembung udara, ilusi, bayang-bayang, seperti bintang jatuh, tetes embun, dan kilat petir.”
Seperti telapak kaki Buddha di debu.
GOENAWAN MOHAMAD
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo