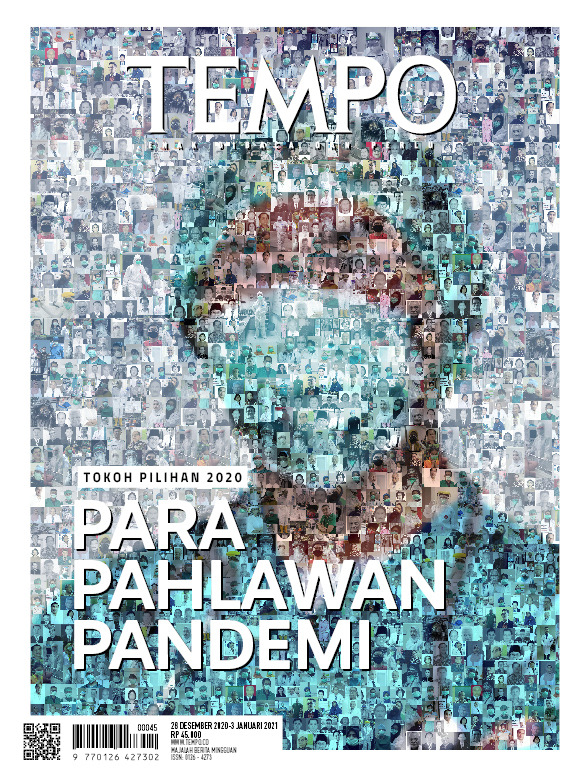Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI masa banyak kematian, di masa ketika rumah sakit penuh dan orang dihantui virus, kita sering lupa: sebenarnya ada yang lain. Sebenarnya kita tetap bisa merasakan yang lain—masih bisa menatap sekitar kita seperti Sapardi Djoko Damono: dengan cinta yang sederhana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada seorang perupa yang melukis burung-burung. Ia ingat di masa kecilnya tiap pagi sepasang branjangan hinggap di dahan kedondong di sebelah rumah. Ia selalu dengar suara “tik-cek-tir” mereka di antara cuitan lain. Tak ada yang istimewa. Tapi kali ini, ketika ia cari warna yang cocok di antara deretan cat minyak untuk melukis bulu burung itu, ia tiba-tiba seperti melihat buat pertama kalinya alur cokelat yang aneh di sela putih: rapat, halus, antara tertata dan tak terduga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Ajaib”, katanya dalam hati.
Dan ia ingin menghadirkan yang “ajaib” itu di kanvasnya.
Itu tak berarti ia berniat meniru dan menghadirkan kembali di kanvasnya bentuk dan warna benda-benda yang dilihatnya. Bagaimana meniru dan merepresentasi “yang ajaib” dengan cat minyak pada kanvas?
Yang “ajaib” tak terumuskan: ia adalah penampakan, atau pesona, yang datang intens ke pancaindra, deras dan tak tertampung. Kita silau. Kita tak dapat melihatnya penuh. Di saat itulah kita bertemu dengan “fenomena yang melimpah”, phénomènes saturées, kata Jean-Luc Marion.
Pelukis kita, karena ia peka, terbuka kepada yang melimpah itu. Mungkin fenomen itu, yang tersaji, yang di luar rencananya itu, adalah “inspirasi”. Dalam perumpamaan Marion, kanvas, cat, dan sang perupa sekaligus ibarat prisma. Prisma menerima cahaya putih dan menyerapnya, menghentikannya, sampai tak tampak—kemudian mengurainya dalam satu spektrum warna, dan menjadikannya kasatmata.
Itu momen “pemberian”, donation, kata Marion. Jika kita terjemahkan kata itu ke bahasa kebatinan Jawa, “pinaringan”, kita bisa tahu ada konotasi religius dalam pilihan kata itu.
Marion memang pemikir Katolik Prancis yang mempertautkan fenomenologi dengan theologi—dan sebab itu, di zaman ini, kontroversial. Paus Fransiskus Oktober yang lalu menganugerahinya “Penghargaan Ratzinger” atas sumbangannya di bidang theologi. Tapi para pemikir menggugatnya karena melewati klaim fenomenologi. Marion dianggap memasukkan sesuatu yang adanya hanya diyakini mereka yang, seperti Marion, beriman.
Tapi mungkin Marion tak melihat hubungannya dengan yang ilahi sebagai hanya soal percaya kepada Tuhan. Hubungannya lebih berupa pengakuan akan kasih—dan kasih, meskipun sebagai “cinta dengan cara sederhana”, lebih dahsyat ketimbang iman. Dengan dan dalam kasih, bahkan yang banal sekalipun menerima sentuhan yang kekal dan tak terhingga: bulu branjangan, sepatu kotor yang dilukis Van Gogh, bunyi gelas yang dibesut dalam musik Tony Prabowo. Dan itu memungkinkan kita memandang keanekaragaman dunia tak dibentuk batas-batas.
“Orang-orang berbicara tentang segala yang tumbuh, yang ditanam maupun liar, seolah mengenal mereka lebih daripada pokok-pokok itu sendiri mengenal dingin dan matahari, ataupun hangat bumi. Namun binatang tidak menghafal pohon-pohon karena namanya, seperti seekor induk atau sepasang tidak mengenal tetasannya atau susuannya dengan nama. Mereka mengenal tanpa batas.”
Paragraf itu saya temukan dalam novel Saman Ayu Utami, yang bagi saya berbicara dengan pas dan puitis tentang fenomena yang melimpah—yang bukan hanya dari pengalaman religius seorang Katolik. Sebab dalam pengalaman seorang sufi seperti Ibn Arabi, “Tak ada yang berjalan dalam semesta ini tanpa berjalan sebagai utusan (rasûl) dengan pesan.” Sufi dari Spanyol itu menambahkan, dalam al-Futūḥāt al-Makkiyya: “Bahkan cacing, dalam gerak mereka, bergegas dengan pesan bagi orang yang memahaminya.”
Jika kita membuka diri, yang “ajaib” menghadirkan misteri yang tak habis-habisnya, mengelak dari analisis. Dalam diri mereka bertaut yang tampak dan yang tersembunyi.
Saya kira Heidegger, pendahulu Marion, tak jauh dari pengalaman seperti itu. Saya bayangkan filosof Jerman itu di Hutan Hitam di Freibourg. Di luar pondoknya, sehabis mendangir tanah di kebun, ia sejenak tertegun menyaksikan daun-daun elma disentuh matahari. Tiap pagi sebenarnya ia melihat itu—fenomen yang biasa saja—tapi sesaat itu ia terpesona. Saat itu dia bersua dengan yang “melimpah”.
Ia takjub—dan agaknya filsafat Heidegger, terutama dalam perkembangannya yang kemudian di pertengahan abad ke-20—bertolak dari ketakjuban. Baginya, hidup selalu dalam das Geviert, “empat-selipat”: bersama bumi, langit, makhluk yang fana, dan isi dunia di mana tersirat isyarat yang-ilahi.
Lihat kendi itu. Seseorang membuatnya dari tanah liat. Tapi ada yang bukan dari tanah: ruang kosong di tengahnya—sesuatu yang tak kasatmata. Di sana air mendapatkan tempat, dan air itulah yang membuat kendi itu diraut untuk menyelamatkan kita dari haus. Ketika air tercurah, kendi itu (dengan kata lain: tanah liat, karya tangan, zat segar di ruang kosong) memberi. Heidegger menyebutnya das Geschenk des Gusses, “pemberian dari curahan”. Di saat itu bumi dan angkasa tinggal bersama yang-tak-abadi dan yang bersifat “ilahi”. Dalam sebuah kendi.
Pemberian itu tak ternilai. Di hari Natal atau bukan, di masa banyak kematian dan kecemasan, ia seakan-akan membuat dunia sekali lagi dilahirkan.
GOENAWAN MOHAMAD
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo