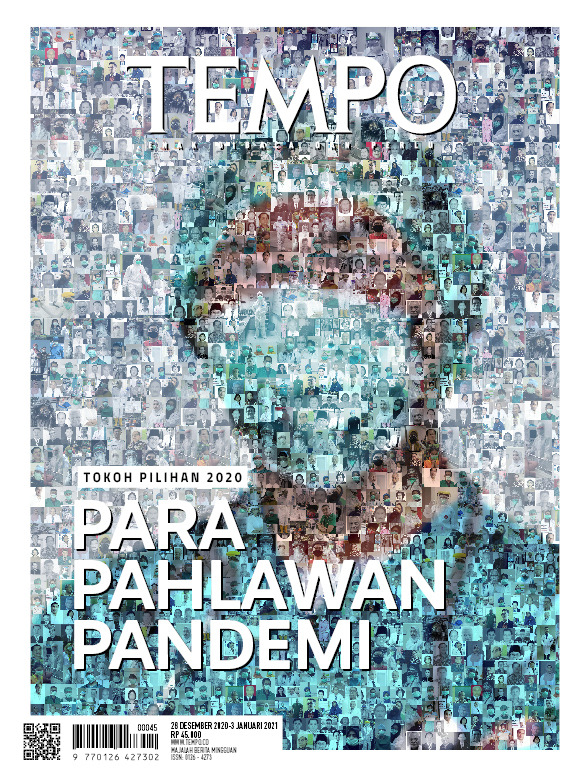Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ahmad Hamidi*
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“LABEL ‘forensik’ dalam linguistik terkadang... ya gitu, deh. Padahal ujung-ujungnya ya menggunakan kacamata analisis wacana dan pragmatik pula,” demikian celetuk seorang mutualan—orang yang mengikuti akun media sosial orang lain dan orang lain tersebut mengikuti balik akun yang bersangkutan—saya di media sosial. Di lain kesempatan, dia nyeletuk lagi, “Gimmick ilmu itu adalah ketika demi cari nama, ilmuwan berkoar-koar ilmunya sebagai ilmu baru, dikasih nama tertentu agar terlihat keren dan meyakinkan para pemula.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saya dapat menebak arah kedua celetukan mutualan saya itu. Apa gunanya memperanak-pinakkan linguistik (ilmu bahasa) yang sudah bejibun cabangnya kalau pada akhirnya ilmu lama juga yang bakal dipakai? Barangkali ia bukan satu-satunya orang yang sangsi akan kedudukan linguistik forensik di antara cabang linguistik lain.
Secara etimologis, kata yang dipermasalahkan oleh mutualan saya itu berasal dari bahasa Latin, forēns(is), yang menurut Oxford Dictionary bermakna “in open court, public”—sepadan dengan forum yang bermakna “what is out of doors”. Kamus yang sama mendefinisikan forensik sebagai “connected with the scientific tests used by the police when trying to solve a crime”. Inilah titik temu lekatan forensik pada terminologi “linguistik forensik”.
Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI) terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan forensik secara lebih spesifik; merujuk pada disiplin ilmu tertentu: kedokteran (“cabang ilmu yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum”) dan bedah (“ilmu yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan”). Karena kita mengenal disiplin forensik lain, seperti psikologi forensik, antropologi forensik, digital forensik, dan forensik pada judul tulisan ini, dalam pemutakhiran berikutnya, definisi versi KBBI patut direvisi.
Secara historis, setidaknya sampai 1968, istilah linguistik forensik belum pernah digunakan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jan Svartvik, profesor linguistik berkebangsaan Swedia, melalui publikasinya, The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics, tentang penyelidikan ulang pernyataan tersangka dalam kasus pembunuhan yang “dilakukan” oleh Timothy J. Evans (Coulthard & Johnson, 2017). Karya monumental Svartvik itu, di kemudian hari, disepakati sebagai penanda waktu kelahiran linguistik forensik.
Di Indonesia, usia linguistik forensik jauh lebih muda. Sekalipun peran ahli bahasa dalam penyidikan dan persidangan sudah dimulai sejak dulu, istilah ini mulai disebut-sebut tidak lama setelah disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya dalam persengketaan antara Prita Mulyasari dan Rumah Sakit Omni Internasional. Pembicaraan tentang linguistik forensik “meledak” lagi, kali ini dalam radius yang lebih luas, manakala mantan Gubernur DKI Jakarta tersandung kasus penistaan agama. Makin ke sini, publikasi ilmiah yang mengatasnamakan kajian linguistik forensik makin menjamur.
Linguistik forensik merupakan ilmu terapan di bidang linguistik (applied linguistics)—sebagaimana ilmu terapan lain yang lebih dulu dikenal, seperti penerjemahan (translation) dan pengajaran bahasa (language teaching). Istilah “linguistik forensik” menonjolkan linguistik sebagai pusat perhatian, sekalipun wilayah kajiannya berada dalam irisan antara ilmu linguistik dan ilmu hukum. Prinsip kerjanya, Olsson (2008) mengatakan, pengetahuan dan teori linguistik diaplikasikan demi kepentingan penegakan keadilan. Sekalipun demikian, sebagai landasan berpikir, doktrin atau paradigma hukum tertentu diperlukan dalam kerja-kerja linguistik forensik—sebagai perbandingan, mahasiswa di fakultas hukum secara formal tidak mengenal linguistik forensik, mereka hanya diajari perancangan (instrumen) hukum (legal drafting).
Konsep seperti itulah yang sesungguhnya diemban linguistik forensik sebagai nama cabang ilmu. Linguistik forensik adalah, meminjam terminologi Kripke (1980), rigid designators. Dalam gagasan semiotika struktural Saussure (1916) tentang signifié et signifiant (penanda dan petanda), linguistik forensik merupakan “penanda” bagi konsep kognitif yang ditandainya (“petanda”).
Obyek kajian ini terbatas pada tanda bahasa dalam ranah hukum—tidak seluas obyek kajian hukum, memang. Unsur “dalam ranah hukum” penting ditekankan untuk membedakannya dengan bahasa hukum (legal language). Kalau dikatakan bahasa hukum saja, ini terlalu sempit. Bahasa hukum seolah-olah hanya merujuk pada jenis laras bahasa, seperti bahasa dalam undang-undang—yang acap kali dianggap rumit dipahami itu, padahal tindak kejahatan yang direpresentasikan melalui bahasa juga obyek kajian linguistik forensik.
Sebagian pakar menganggap linguistik forensik sebatas ancangan (approach), yang secara kategoritatif tentu tidak berkohiponim dengan, misalnya, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, atau pragmatik. Deretan ilmu yang terakhir disebutkan itu justru merupakan pisau analisis yang digunakan dalam kerja-kerja linguistik forensik, sebagaimana juga terjadi pada, misalnya, linguistik lanskap (Landry & Bourhis, 1997) dan linguistik antropologis (Foley, 1997). Jadi tidak ada hubungan logis antara linguistik forensik sebagai “nama cabang ilmu” dan “agar terlihat keren dan meyakinkan para pemula”. Ada kebutuhan substansial di balik itu.
Sebenarnya, selain forensic linguistics, ada nama lain yang dikenal atas cabang ilmu ini, yaitu legal linguistics. Pada kenyataannya, forensic linguistics lebih massal digunakan. Barangkali ini pula alasan linguis Indonesia memperkenalkan pungutan linguistik forensik, sementara Badan Bahasa sempat mempopulerkan forensik kebahasaan. Selagi konvensional, itu bukan masalah. Bukankah bahasa, termasuk nama, adalah tentang konvensi?
Di balik tembang abadi “hukum diartikulasikan melalui bahasa”, ada kejahatan berbahasa yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terlepas apa pun namanya, bidang ini umpama gelanggang yang begitu lapang bagi para linguis untuk memposisikan diri lebih ke tengah dalam dinamika sosial-politik Indonesia di masa depan.
*) ALUMNUS PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA, MENYUSUN TESIS BERJUDUL “ANALISIS PRAGMATIK TUTURAN BERMUATAN TINDAK PIDANA: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo