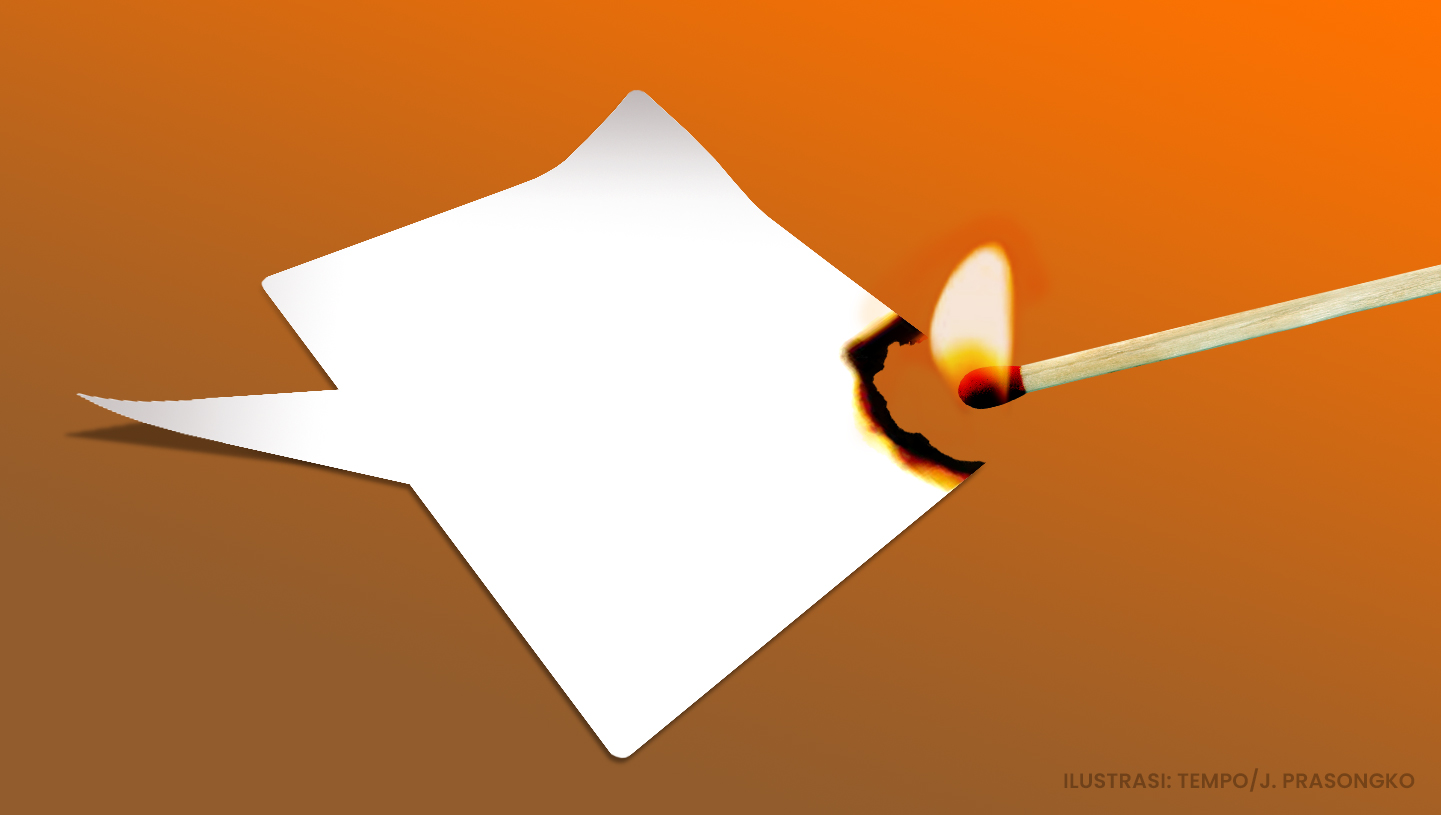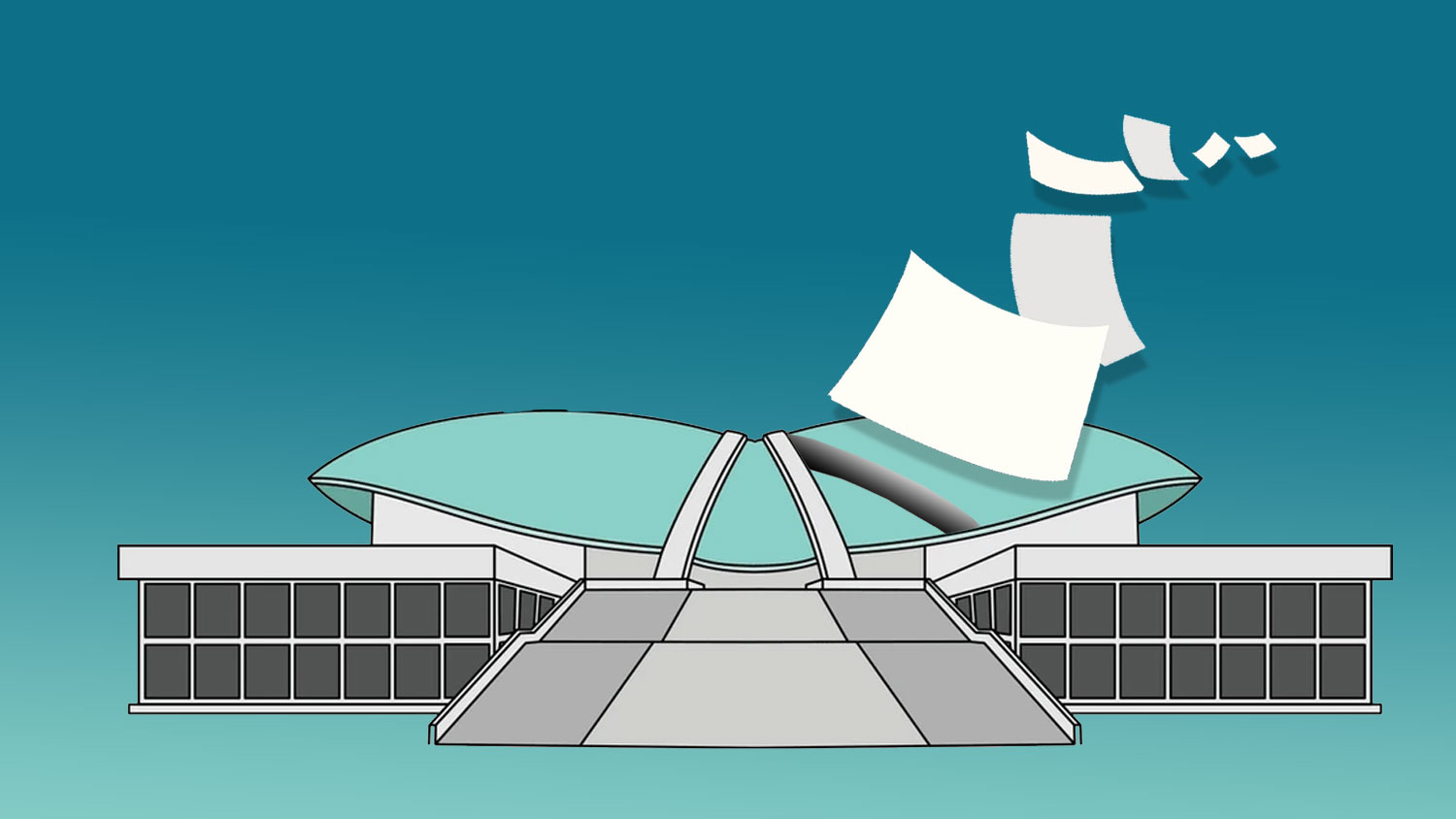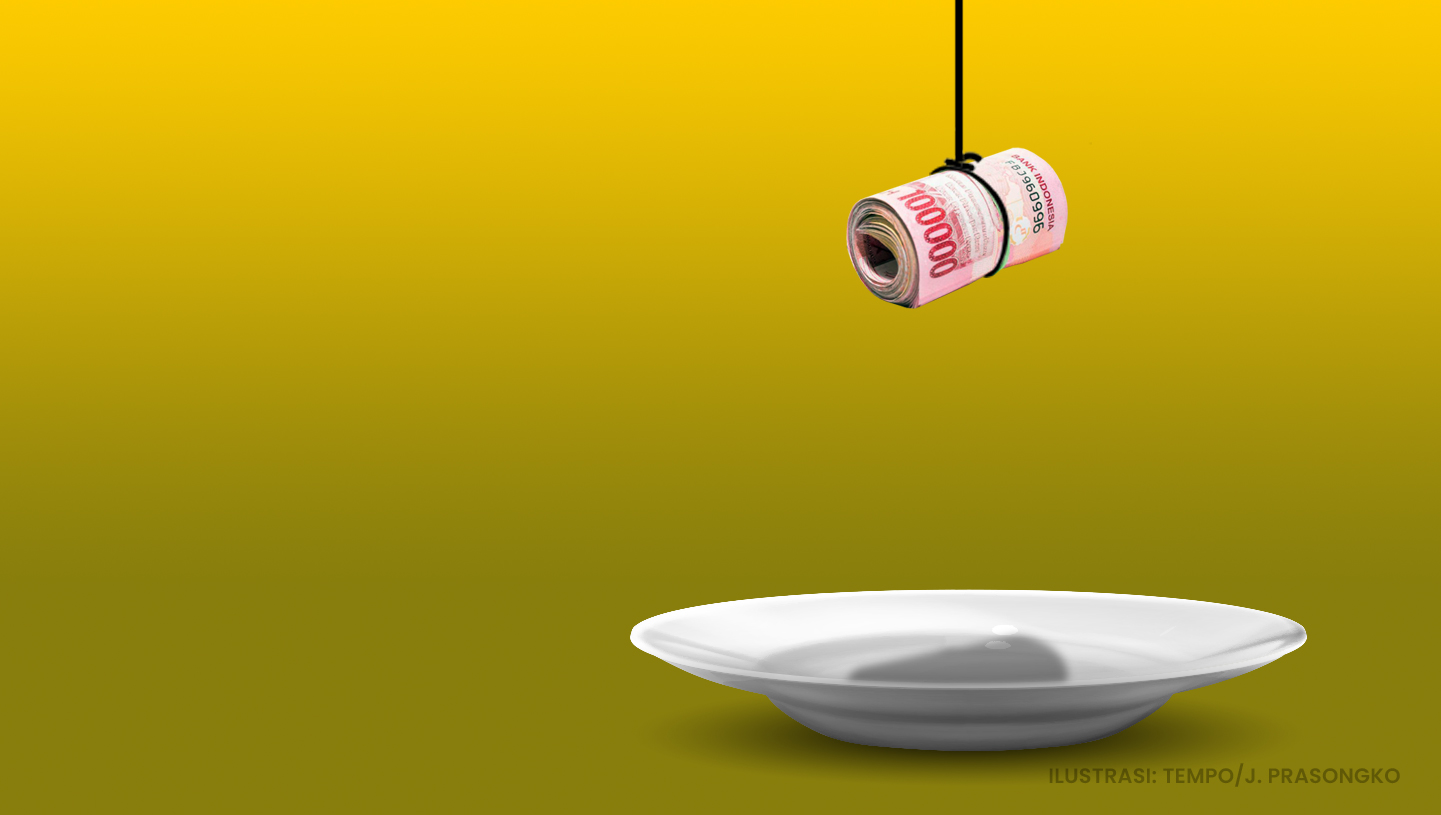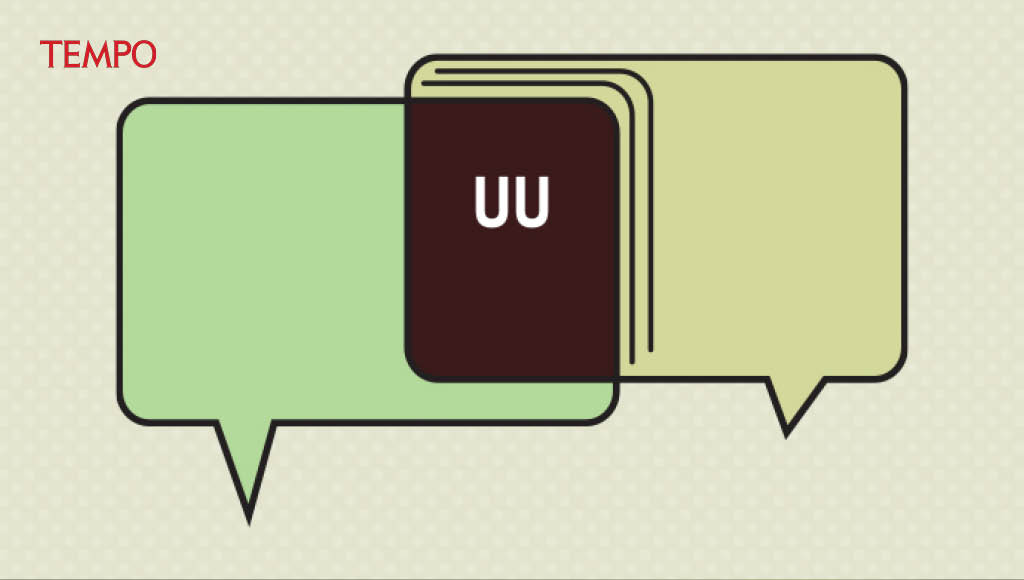Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SALAH satu ilusi sejarah adalah perbatasan. Di Amerika Barat Daya, suku Pima, penduduk asli, punya sepatah kata yang menyeramkan, oimeddam: penyakit yang berkelana—wabah yang melampaui perbatasan mana pun.
Sebuah dongeng Pima bercerita:
Seorang asing, jangkung, bertopi hitam, muncul di dusun itu. Seorang penduduk bertanya, “Tuan datang dari mana?”
“Dari jauh,” jawab orang asing itu. “Melintasi Lautan Timur.”
“Apa yang Tuan bawa?”
“Aku bawa kematian. Napasku membuat anak-anak mengeriput dan mati seperti tanaman muda di salju musim semi. Aku bawa kehancuran. Tak peduli betapa cantik seorang perempuan, sekali ia menatapku, wajahnya akan berubah jadi buruk seperti Maut. Dan buat laki-laki, aku tak cuma membawa ajal, tapi juga musnahnya anak dan istri mereka.”
Umur oimeddam mungkin setua sejarah, sejak manusia berhimpun, bepergian, menyeberangi batas, berdagang, berperang, bergaul. Dongeng di atas mengisyaratkan bahwa Maut bukan barang baru, tapi selamanya asing. Penyakit yang menakutkan itu bukan dari kampung sebelah. Ia menerobos tapal batas mana saja dan mencabut ribuan nyawa.
Orang di Eropa punya catatan tentang “Sampar Justinian” di abad ke-6. Ketika di Konstantinopel berkuasa Maharaja Justinianus, penyakit pes membunuh 40 persen penghuni kota yang kini disebut Istanbul itu. Sebelum wabah itu reda di tahun 750, separuh penduduk Eropa habis.
Di abad ke-14, wabah kedua datang, disebut “Maut Hitam”. Jumlah korbannya hampir sebanyak jumlah orang mati dalam Perang Dunia II.
Buku John Kelly, The Great Mortality, mengisahkan dengan menarik dan rinci—agak terlalu rinci—sampar raksasa itu.
Umum disebutkan, epidemi itu bermula di Caffa, di Semenanjung Krimea di pantai utara Laut Hitam. Kini ia bernama Feodosiya, kota kecil yang sekarang diperebutkan Ukraina dan Rusia. Menjelang pertengahan abad ke-14, pengelana Maroko terkenal, Ibnu Batutah, berkunjung ke sana dan melihatnya sebagai “kota megah di sepanjang pantai”, dengan “pelabuhan yang menakjubkan”.
Sejak tahun 1230, Semenanjung Krimea berada di bawah kekuasaan Mongol—pecahan kesekian dari imperium yang didirikan Jenghis Khan—yang berhasil menerobos Eropa. Caffa mendapat posisi berbeda: para saudagar Genoa mendapat konsesi di kota itu untuk berniaga bebas. Caffa pun menjadi bandar perdagangan internasional yang penting, juga pasar budak yang besar, yang dihuni berbagai bangsa. Jika kita baca penuturan Ibnu Batutah—yang di sana menemui kelompok sufi yang berbeda-beda—di Caffa ada kehidupan yang damai di antara penduduk.
Orang Mongol, yang berkuasa di Krimea, sejak tahun 1200-an umumnya muslim. Öz Beg, sultan mereka (disebut “Khan”), masuk Islam sejak menjadi pangeran pelarian setelah ayahnya dibunuh. Ketika merebut kembali takhta, Öz Beg menganjurkan rakyatnya jadi muslim. Tapi ia bersikap baik kepada orang Kristen. Kepadanya Paus Yohanes XXII mengirim surat berterima kasih. Öz Beg membalas dengan jaminan yang lebih kuat: ia akan menghukum mati siapa saja yang “mengutuk dan menyalahkan” penganut Yesus itu.
Tapi berkali-kali terjadi: agama-agama tak bisa dilepaskan dan melepaskan diri dari perilaku pemeluknya. Mereka hidup dengan perbatasan dan permusuhan. Di tahun 1343, Kota Tana diguncang konflik antara penduduk muslim dan orang Genoa yang Kristen. Seorang muslim tewas.
Takut akan pembalasan, orang-orang Genoa melarikan diri ke Caffa. Ketika Janiberg, yang setahun sebelumnya menggantikan ayahnya, Öz Beg, mengirim tim untuk menangkap yang bersalah, penduduk Caffa membangkang. Murka, Janiberg memerintahkan kota itu dikepung. Caffa melawan. Lewat jalur laut datang makanan, obat-obatan, dan bala bantuan dari Italia. Janiberg mundur.
Ketika kemudian pasukannya mengepung Caffa lagi, ia digagalkan kekuatan yang lain: wabah pes, yang bergerak pelan melampaui Sungai Don dan Volga, masuk ke Krimea, dan membinasakan pelbagai kota dan permukiman. Tentara Mongol yang bersiap di perbukitan di atas Caffa terkena.
Pasukan Janiberg berantakan. Tapi cerita tak berhenti di sini. Gabriel de Mussis, seorang notaris Italia, melukiskan satu kejadian spektakuler: Janiberg bertitah agar bangkai-bangkai pasukannya yang terkena pes dipasang di mesin pelontar dan ditembakkan melintasi tembok Caffa.
“Segera tumpukan bangkai prajurit Tartar yang membusuk itu mencemari udara dan meracuni persediaan air. Baunya meringsek kota.... Nyaris hanya satu dari beberapa ribu orang yang bisa melarikan diri.... Satu orang terjangkiti wabah akan menularkannya ke banyak orang lain, di tempat lain....”
Benarkah ini penggunaan senjata biologis pertama dalam sejarah?
Caffa memang dihabisi pes; kota jadi kosong dan bangkai jadi najis di tiap sudut. Tapi The Great Mortality menyebut penjelasan lain. Ole Benedictow, sejarawan Norwegia yang dikenal dengan penelitiannya tentang “Maut Hitam”, menyimpulkan: tikus pembawa pes itu—tanpa dibantu Janiberg—“menemukan jalan masuk melalui celah-celah tembok di antara pintu gerbang”.
Dari Caffa pes menjalar ke seluruh Eropa, seperti ketika ia bermula dari Asia Tengah. Garis pemisah pun hilang—juga antara tikus dan manusia. Tapi sejarah selalu melahirkan tapal batas sebagai tempat berlindung. Kini kita belum tahu, sekian abad setelah “Maut Hitam”, adakah bencana sedunia membuat manusia makin saling bersimpati, atau saling curiga.
GOENAWAN MOHAMAD
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo