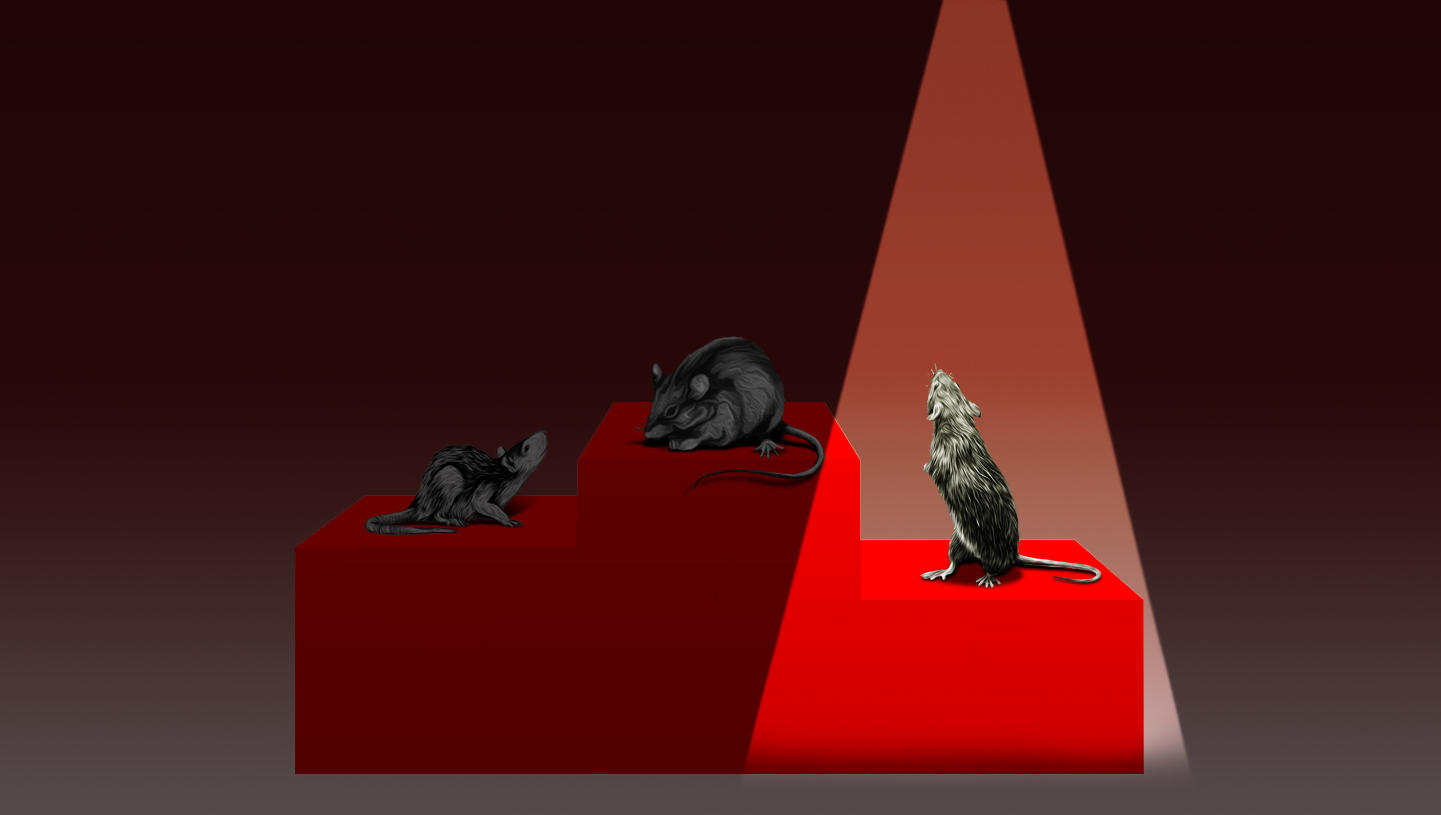Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Eko endarmoko *
Pernah sekali waktu akal sehat Anda terusik oleh klausa "mencemarkan nama baik"?
Saya pernah, apalagi dalam beberapa tahun belakangan. Omong-omong soal cemar, akan sampailah kita nanti pada satu titik saat kita agak gelagapan, tidak tahu lagi apa ini soal logika-dan-tata bahasa atau perkara tata susila, moralitas. Saya mulai saja dari aspek sintaksis dan semantika, mengingat ruang ini adalah kolom bahasa, bukan forum tempat membincangkan budi pekerti apalagi agama.
Cemar, bahasa, moralitas. Tiap kata punya kodrat sendiri dan punya makna unik. Seperti sidik jari manusia yang tak memiliki kembar sempurna, tak ada dua kata atau lebih yang persis sama. Kodrat kata cemar menjadi wadah tempat menampung segala hal yang berkenaan dengan najis, kurang-lebih setara dengan kotor, mesum. Dan sifat-sifat itu dalam cemar tidak hanya bertaut dengan barang, benda-benda (dekil, kotor, kumuh, mesum, atau butek, keruh), tapi bisa juga menunjuk ke lisan, perkataan (cabul, carut), juga perbuatan (dursila, jangak) atau malah ke akhlak: tunamoral. Raden Anudiningrat mengusir anak perempuannya yang bunting sebelum nikah karena ia anggap telah mencemarkan nama baik darah biru wangsanya.
Turunan dari kata itu, mencemarkan, berarti menjadikan cemar (segala apa yang sebelumnya tidak atau belum tercemar). Penutur bahasa Indonesia tidak memerlukan nalar yang canggih demi memahami pernyataan selugas itu. Tidak bisa, atau paling tidak janggal, apabila mencemarkan kita kenakan pada sesuatu yang sudah kotor. Itu boleh kita namai menentang kodrat, menghina akal sehat, pamer kedunguan—secara penuh, paripurna. Mencemarkan sesuatu yang sudah kotor tak bisa lain berarti membuat sesuatu jadi lebih kotor.
Orang, atau bisa juga lembaga, lancung yang gerah dan tak terima dituding-tuding, sebut saja P (penjahat), lalu berbalik menuntut penuding, kita namai dia M (yang mencemarkan), dengan dalih pencemaran nama baik, kadang bagi saya menggelikan (dalam arti baik lucu maupun bikin jijik). Bayangkan saja ia, yang suka membawa-bawa penasihat hukum, berkelit sembari sembunyi di balik asas praduga tak bersalah, sebuah prinsip yang menurut Profesor J.E. Sahetapy hanya berlaku di dalam ruang pengadilan (lihat http://www.kompasiana.com/dadyandela/presumption-of-innocence). Perilaku itu mirip tindakan penyair atau penulis kacangan yang menyuruk di balik licentia poetica. Setelah menumbuk-numbuk kaidah bahasa yang ia buta terhadapnya, lantang berkata: itulah kebebasan penulis!
Kasus seperti pemakaian kata cemar tidak sendirian dalam praktek kita berbahasa. Contoh lain yang paling dekat adalah membersihkan sampah. Seperti mencemarkan nama baik, tak ada salah pada bangun membersihkan sampah secara gramatika, tata kata. Tapi tata makna adalah soal yang sama sekali berbeda. Di tataran maknalah kita dapat saksikan orang bodoh tengah membersihkan sampah, sementara orang yang tidak bodoh membersihkan jalanan (atau sungai, atau ruangan) dari sampah.
Izinkan sekarang saya mengajak Anda melihat sedikit lebih jauh dimensi lain makna yang keluar dari artefak bahasa, katakanlah semacam metabahasa. Baju, tembok, burung emprit, benda-benda bukan manusia tak bakal bereaksi manakala dicemarkan—sekalipun sampai berulang kali. Tapi tidak P. Ia jadi berang, sebab menurut dia M telah mencemarkan nama baiknya, sedangkan M tidak merasa begitu karena sejauh yang ia tahu, kiprah P tidak membuktikan kehadiran sebuah nama baik. Sekian informasi tentang P yang M serap (baca, dengar, lihat) cukup menjadi alasan M menilai P tidak punya nama baik. P dan M bersimpang paham di klausa mencemarkan nama baik. Di mata M, mencemarkan nama baik P tak lain dari contradictio in terminis. Bagaimana bisa mencemarkan nama yang sudah cemar?
Pengertian nama baik sudah ditangkap berbeda oleh kedua pihak yang bertikai itu. Pada M kita melihat bahwa pengertian, definisi, makna (cemar dan nama baik) meloncat keluar dari rumusan kamus, mencelat dari teks. Ia menggelandang ke konteks, dunia nyata, demi mengumpulkan sejumlah fragmen buat menegaskan dirinya. Dari sudut M, perbuatan P menilap uang negara, menjegal lawan politik secara kasar, menjiplak karya orang lain—itulah cemar, bukan nama baik. Sebaliknya, P dapat meremukkan pengertian yang sudah terbangun tadi begitu bisa ia buktikan bahwa fragmen-fragmen tadi tidak benar. Perbantahan soal di luar teks itu sering amat liat dan keras. Dan di ujungnya menggantung pertanyaan: Di mana batas makna?
Di situ linguistik struktural jelas lumpuh, tak kuasa memberi penjelasan yang memadai mengenai pokok soal. Bagi saya, mengingat bahasa adalah perkara konvensi dan hukum di dalamnya lebih dekat ke kode etik, saya kira batas tersebut terletak pada asas kepatutan. Tetapi P rupanya siap dengan gugatan baru: apakah patut itu? Patut menurut siapa? Siapa bisa bersaksi? Di sini sudah masuklah kita ke ranah linguistik pragmatik—sebuah subdisiplin ilmu bahasa yang barangkali dapat kita harapkan menjelaskan bopeng bahasa kebangsaan kita di semua tataran. l
*) Penyusun Tesamoko: Tesaurus Bahasa Indonesia Edisi Kedua
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo