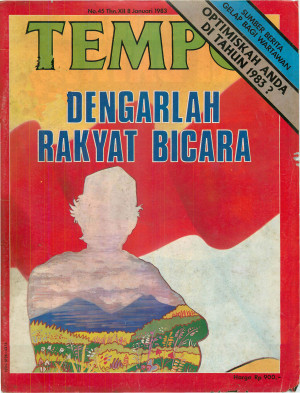KIPAS angin itu sial sekali. Sial lantaran dikirim penciptanya
ke Indonesia, bukan ke negeri lainnya yang lebih menghargai
kipas angin. Lalu riwayatnya pun menjadi bukti nyata, betapa
peliknya bagi orang Indonesia membangun negerinya,
memodernisasikan bangsanya.
Entah sudah berapa lamanya dia mati, menjadi bangkai tidak ada
yang mengetahui. Juga tidak diketahui riwayat kematiannya.
Apakah sebab musababnya voltase yang meninggi pada suatu hari
yang naas lalu ada yang putus dalam tubuh kipas angin itu?
Ataukah lebih sepele, ada soal kecil tak beres pada stop-kontak?
Wallahualam.
Namun cerita kematiannya tidak berakhir di situ. Bukan sembarang
kematian. Memilukan bahwa bukan cuma kerangkengnya yang dikrom
indah itu yang hilang, tapi bangkainya pun dicabik-cabik orang.
Dari keempat daun baling-baling yang biasanya mengipas-ngipas
udara itu, tak satu pun selamat. Semuanya patah-patah
mengerikan, seolah-olah bangkai yang terkutuk.
Dan jelas orang Jepang yang membikinnya tidak bisa membayangkan
nasibnya jadi begitu -- konyol dan mati muda. Di Jepang tidak
ada kipas angin sesial itu.
Lima dari delapan kipas angin yang ada sudah mati, dengan status
bangkai yang aneka ragam. Masih ada bangkai yang utuh, tapi
semua kerangkengnya sudah amblas. Entah untuk apa digunakan
manusia, sulit ditebak.
Tiga masih hidup, tapi dua tidak bisa berputar-putar
menggelengkan kepala. Tidak bisa lagi mengedarkan udara ke
segenap penjuru. Sampai saat ini, cuma satu yang selamat yang
dapat berfungsi dengan semestinya.
Ketika mereka baru tiba di Indonesia, begitu banyak kepala yang
kagum menengadah melihat mereka, pada perjalanan perdana yang
amat mengesankan. Angin yang mereka sebarkan sempurna sekali
sehingga pembesar dan wartawan Ibukota tidak putusnya
memuji-muji. Ketika itu mereka merupakan lambang modernisasi.
Karena itu sukar dibayangkau bahwa kipas angin itu akhirnya
mati muda, lalu dipenggal-penggal tangan orang Indonesia yang
terkenal halus.
***
'Wanita dipotong-potong . . . dipotong menjadi tiga belas . . .
wanita dipotong-potong, dimasukkan ke dalam karung . . . " Anak
muda itu menyerukan berita utama koranuya yang kaya peristiwa
dan foto perihal Ibukota. Wajahnya kalem tidak menunjukkan
perasaan. Tujuannya mencari sesuap nasi, tidak lebih. Di
sela-sela manusia yang berjejal dan berkeringat dia menyelinap.
Lalu suaranya sayup-sayup mengulangi berita utama: "Wanita
dipotong-potong, dimasukkan ke dalam karung . . . "
"Mangga mangga .... empat go pek, ... empat go pek." Tidak
jelas mengapa go pek, mengapa tidak "lima ratus rupiah". Toh
semua calon pembeli orang Indonesia. Mungkin maksudnya supaya
ada kelucuan sedikit di dalam ruang yang panas pengap itu. Dan
fisiknya kuat sekali. Dijajakannya mangga sekeranjang di
sela-sela manusia yang begitu berjejal.
Di jalan yang sempit itu hilir mudik pelbagai penjaja, tiada
hentinya, diiringi suara, nada dan gerak aneka ragam. Ada rokok
ada berbagai minum dalam botol, ada berbagai makanan dalam
plastik (termasuk tahu dan nangka), ada berbagai bacaan, ada
buku teka-teki silang lengkap dengan spidolnya.
Pengemis buta enam orang, seperti susul-menyusul, lima
laki-laki, satu perempuan. Masing-masing punya gaya khas: dua
pertama dituntun oleh anak belasan tahun, yang lainnya jalan
sendiri. Semuanya minta dibelaskasihani dan mendoakan panjang
umur dan berlimpah rezeki. Amat mengagumkan bagaimana mereka
yang buta itu dengan cekatan pindah dari gerbong yang
terguncang-guncang ke gerbong yang terguncang-guncang lainnya
lantaran kereta api melaju dengan kecepatan tinggi.
Di antara mereka yang mencari sesuap nasi di tengah-tengah
manusia yang berkucur keringat itu, penjual kolonyet yang paling
kocak. Mukanya bundar, mudah tersenyum, kedua pipinya berlesung
pipit. Di atas kepalanya bertengger topi baret abu-abu. Badannya
gemuk dan penampilannya tipikal untuk tampang extrovert yang
periang tapi sensitif. "Kolonyet, kolonyet, seratus, seratus . .
. Kolonyet membikin cakep . . . tanggung cakep." Sesudah
bergurau sebentar dengan seorang pembeli, suaranya menggema
lagi: Panasnya sudah kayak gini . . . keringat sudah
membahayakan . . . ini dia kolonyet bikin segar . . bikin
cakep."
* * * *
-- Sudah berapa tahun umur gerbong ini Pak?
-- Tidak tahu persis, tapi jelas masih relatif baru. Mungkin
berumur sekitar enam tahun. Paling lama delapan tahun.
-- Berguna sekali kereta api Jabotabek ini. Boleh dibilang
sukses.
-- Berguna sih berguna. Tapi pemeliharaan gerbongnya ini perlu
disesalkan. Nah, kita berjejal dan berkeringat begini. Di atas
kita kipas angin tidak jalan, malah sudah dipenggal pula. Sadis.
(Mereka lalu membicarakan kerusakan lainnya dalam gerbong.
Bantal-bantal tempat duduk sudah rusak. Dalam jajaran mereka dua
bantal tempat duduk sudah amblas, tinggal metalnya untuk
diduduki. Rak mungil tempat sampah di bawah meja sudah lenyap,
tinggal bekas-bekas sekrup).
-- Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, kesalahan kita
semua.
-- Memang tidak, tapi ini menampakkan suatu masalah yang
mendasar. Masalah hubungan kita dengan benda-benda. Bukan cuma
masalah pemeliharaan, tapi masalah kecintaan kita terhadap
benda-benda. Kita cintai benda-benda itu sebagai simbol, simbol
modernisasi, simbol kemajuan. Ada seremoni, ritual dan
petuah-petuah. Ketika kemudian dia menampakkan diri sebagai
benda biasa, gerbong, bangunan kakus, kipas angin atau mesin
fotokopi, dia menjadi tak terurus. Kita pun sibuk dengan
simbol-simbol yang baru. Tanpa kecintaan yang mendasar kepada
benda-benda, tanpa peningkatan penguasaan terhadap alam
kebendaan, modernisasi cuma slogan.
-- Itu seperti pendapat Niels Mulder.
-- Dalam hal ini saya setuju dengan dia. Bicara tentang
pembangunan, kita harus bicara tentang hubungan kita dengan
benda-benda. Kita harus mencintai benda-benda itu dalam arti
yang sesungguhnya. Dan selalu ingin tahu tentang sifat-sifatnya,
sehingga makin lama makin menguasai alam kebendaan.
-- Betul juga. Contohnya begitu banyak. Tidak usah jauh-jauh,
lihat saja di muka kantor Bappenas, di Taman Suropati. Beberapa
tempat duduk dari semen sudah berpatahan. Di tengah lapangan ada
patung jerapah, ada kerbau, ada gajah. Semuanya jadi "makhluk"
cacat, kupingnyalah, ekornyalah, tanduknyalah, gadingnyalah.
(Pembicaraan mereka berhenti ketika kereta api Jabotabek
mendekati stasiun Depok Baru. Bersama beberapa penumpang lainnya
di gerbong itu, mereka siap-siap turun).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini